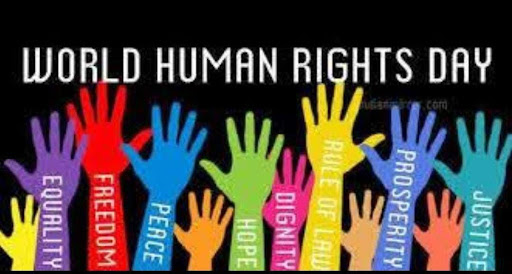“The human rights discourse remains, in order to be such, mythology without mythos. It cannot exist or endure outside the webs of impassioned commitment and networks of critical solidarity, whether on behalf, or at the behest, of dominant or subaltern classes, each claiming ownership of a transformative vision of political possibility.”
Upendra Baxi (The Future of Human Rights).
Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilakukan dengan pendekatan preskriptif dan deskriptif. Pakar hukum India Upendra Baxi dalam sebuah wawancara dengan pemikir hukum dari Jerman Werner Gephart mengangkat sebuah kebijaksanaan dari salah satu teks sakral dalam agama Hindu (Rig Veda 1.89.1) yang mengatakan: “Let noble thoughts come to us from all directions” (biarkanlah pengetahuan datang dari segala penjuru) (Baxi, 2013).
Dari jalur pendekatan preskriptif, gagasan tentang HAM diciptakan berdasarkan konseptualisasi idealisme tentang agensi manusia. Seperti layaknya seorang arsitek yang mendesain bangunan rumah susun di Paris (Bertho, 2014), ide-ide dari slogan Liberté, Égalité, dan Fraternité mengejawantah menjadi cetak biru dari hunian kelas pekerja yang menjadi tulang punggung perekonomian Prancis. Manusia diasumsikan membutuhkan sederet daftar kelayakan untuk dapat menghuni tempat tinggal, dan semuanya dimulai dari meja gambar dan pemikiran seorang arsitek (Taylor & Levine, 2025).
Sebaliknya, pendekatan deskriptif dipraktikkan dengan metode Sokratik yang mulai dari ketidaktahuan dan sampai pada sebuah konstruksi pengetahuan yang ajeg. Baxi adalah pengkaji HAM dari perspektif juridis, dan ia dalam praktiknya memilih untuk masuk dan mendengarkan.
Setelah belajar hukum di bawah bimbingan Hans Kelsen, Baxi banyak terlibat dalam berbagai upaya advokasi mereka yang tertindas di bawah kebijakan diskriminasi ras apartheid-termasuk di Australia dalam kaitannya dengan penduduk pertama yang diberi label “aborigin”.
Dalam pembelaannya terhadap kaum marjinal tertindas di Rajashtan, India, Baxi menuturkan, saat mereka meminta bantuannya, Baxi mulai dengan pendekatan dari dimensi religius tentang tugas manusia untuk melawan penderitaan (suffering) sebagai fondasi pembelaannya (Baxi, 2013).
Penderitaan sebagai Titik Sentral HAM
Bertolak dari sudut pandang religius, Baxi mengatakan, penderitaan dapat dipandang bukan sebagai kenyataan fatalistik yang hanya bisa diterima begitu saja, tetapi sebaliknya, sebagai lawan yang harus dihadapi.
Baxi sendiri membagi HAM menjadi enam ragam: ethical imperatives (tuntutan etik), grammar of governance (tata bahasa pemerintahan), languages of global governance (bahasa tata kelola global), insurrectionary praxis (bagian dari tindakan reaktif terhadap kekuasaan), juridical production (produk dari aktivitas yuridis), dan “culture” (bentuk kebudayaan) (Baxi, 2008:12-22).
Dengan titik pijak tersebut, menurut Baxi, HAM tidak pernah sama persis dari satu kejadian ke yang lain. Keenam “wujud” HAM ini menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah konsep yang cair yang sifatnya sangat kontekstual.
Filsuf politik Achille Mbembe bahkan tergolong pesimistik saat menyiratkan bahwa HAM dapat menjadi dampak atau ekses dari kebijakan yang disebutnya nekropolitik: “The ultimate expression of sovereignty resides, to a large degree, in the power and the capacity to dictate who may live and who must die. Hence, to kill or to allow to live constitutes the limits of sovereignty, its principal attributes” (Ekspresi tertinggi dari kedaulatan, dalam kadar yang besar, terletak pada kuasa dan kapasitas untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Oleh sebab itu, membunuh atau membiarkan hidup merupakan batas-batas utama yang menandai atribut pokok kedaulatan) (Mbembe, 2020:66).
Pemikiran Mbembe ini, ada di koridor yang sama dengan poin kedua dan ketiga HAM dari Baxi: bahwa berbagai bentuk kebijakan yang relatif superfisial (permukaan) menjadi ajang pembuktian seberapa inklusif hukum di suatu negara terhadap HAM. Peristiwa pemilihan umum, keanggotaan di dewan perwakilan, dan semacamnya dijadikan indikator HAM tanpa menyentuh persoalan yang lebih substantif.
Sebagai ilustrasi, keterwakilan sebuah provinsi di dewan perwakilan dianggap sebagai simbol dari jaminan HAM terhadap suku-suku terasing. Namun demikian, bentuk perwakilan seperti ini sebenarnya mensyaratkan kebijakan-kebijakan substansial yang menuntut perbaikan kondisi dan kualitas hidup mereka. Misalnya, dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ilustrasi lainnya, tidak cukup HAM dianggap sebagai gramatika inklusivitas keadilan bila lembaga peradilan menutup mata terhadap sulitnya warga negara berpenghasilan rendah untuk diperlakukan adil dalam proses hukum.
Dimensi HAM yang Semakin Divergen
Baxi dalam pemikirannya menyayangkan pola pikir Barat yang menurutnya terlalu “Euroamersian-sentris” – hanya dijangkarkan konsep HAM yang ada di Amerika dan Eropa.
Selanjutnya, bahkan konstruksi teoretik tentang HAM seolah menegasi sejarah kekerasan yang ada di masyarakat Barat. Terakhir, menurut Baxi, ada ketimpangan antara yang dicita-citakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia dengan gejolak konseptual yang memajumundurkan gerak pencapaian manusia dalam menjamin implementasi HAM (Baxi, 2009:22-24).
Berbagai perkembangan terbaru dalam bidang ilmu dan teknologi justru sangat sulit diikuti oleh berbagai negara yang terbeban dari sisi konsep HAM. Kejahatan siber (cybercrime) dan berbagai praktik rekonstruksi kode genetik (misalnya dalam rekayasa jenis kelamin bayi, pengguguran bayi dengan cacat bawaan) sebagai dampak dari pemetaan genomik manusia (human genome project) seolah ada di luar payung hukum yang berbicara tentang HAM.
Pengkaji HAM Frantz Fanon (1963) memberikan catatan, di wilayah bekas kolonial selalu ada persoalan oposisi biner pendatang (settlers) dan penduduk asli (natives). Menurut Fanon, sejarah menunjukkan bahwa pendatang seolah-olah merasa lebih tahu tentang situasi dan kondisi geografis dan berbagai hal lainnya daripada penduduk asli, dan kemudian memberikan redefinisi tentang HAM secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kompleksnya enam dimensi HAM seperti yang dijelaskan oleh Baxi.
Ekspansi ala “white man burden” (beban peradaban ada di pundak orang kulit putih) seolah menjadi justifikasi untuk menentukan ramuan teoretik dan juridis seperti apa HAM yang paling “ideal”. Kondisi paradoksikal seperti disposisi kulit hitam di Amerika Serikat yang tidak pernah sepenuhnya melebur adalah contoh ironi hasil ambiguitas gagasan HAM yang diajukan Barat.
Pengkaji pascakolonial, Boaventura de Sousa Santos (2018) bahkan menilai, pemikiran Barat tentang HAM didasarkan pada fondasi epistemik yang sangat “ghaib” (abyssal), yang dimulai dengan asumsi sederhana: bahwa selain Barat tidak ada manusia lain (noneksisten). Dampaknya, bagi dunia Barat (oksidental) perlakuan apapun terhadap dunia non-Barat menjadi sangat semena-mena. Tolak ukur sepihak ini membunuh pengetahuan-atau epistemisida dalam istilah Santos. Sederhananya, seturut cara berpikir abyssal-manusia bebas menentukan kriteria apapun tanpa mempertimbangkan unsur sejarah atau tradisi yang diwariskan turun-temurun.
Dunia seolah dimulai dari “kertas kosong peradaban” yang bebas diubah begitu saja. Konflik di Afrika dan Timur Tengah adalah contoh ekses kalutnya pemikiran sepihak seperti ini, yang dengan acak menarik garis batas geografis tanpa mempertimbangkan elemen apapun, termasuk manusia yang tinggal di dalamnya.
Penegakan HAM sebagai Perjuangan Melawan Kejahatan
Menyikapi HAM sebagai sebuah perjuangan melawan “yang jahat”, seperti yang digagas Upendra Baxi memang berdimensi religius. Sikap seperti ini mungkin lebih relevan untuk menghadapi kompleks dan carut-marutnya persoalan HAM yang berlapis-lapis. Kasus Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (Writ Petition No. 2135 Tahun 1982) yang diputus pada 16 Desember 1983 adalah contoh betapa abainya kepekaan terhadap HAM di wilayah pascakolonial.
Di kasus tersebut, pekerja tambang diperlakukan seperti budak dan diikat dalam lingkungan kerja yang sangat buruk. Pemerintah India pada waktu itu seolah abai dan tidak berinisiatif untuk memeriksa situasi pekerja yang diperlakukan sangat tidak manusiawi. Setelah petisi diajukan, Mahkamah Agung India memerintahkan pembebasan para pekerja dan merehabilitasi hak-hak mereka.
Singkatnya, eksplorasi kritis terhadap HAM melalui perspektif seperti yang diajukan Baxi, Mbembe, Fanon, dan Santos menunjukkan, persoalan HAM tidak pernah dapat dipahami secara monolitik atau universal. Sebaliknya, HAM adalah sebuah medan “tarung” yang senantiasa membutuhkan pemaknaan ulang dalam berbagai konteks historis, sosial, politik, dan kultural.
Pendekatan preskriptif yang cenderung abstrak dan idealistis, sebagaimana arsitek yang menggambar “konsep ideal” tentang hunian yang layak, tidak akan pernah memadai tanpa didampingi oleh pendekatan deskriptif yang turun langsung ke realitas lapangan yang kaya dengan sejarah dan tradisi. Masa depan HAM terletak pada kemampuan kita untuk secara terbuka menerima berbagai sudut pandang menghormati keberagaman epistemik, termasuk dari dimensi religius.