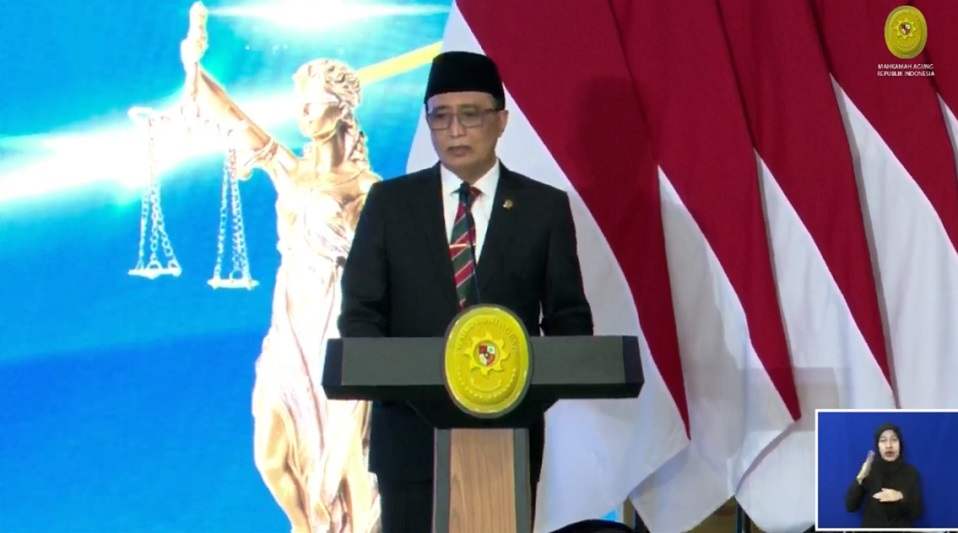Bayangkan seorang hakim yang duduk gelisah di ruang kerjanya menjelang tengah malam. Di hadapannya terbentang berkas kasus pencurian ringan dengan terdakwa seorang ibu yang mencuri susu formula untuk bayinya yang kelaparan.
Undang-undang dengan jelas menetapkan hukuman pada setiap perbuatan yang terbukti. Namun, hati kecilnya berbisik bahwa keadilan sejati membutuhkan pertimbangan lebih dari sekadar penerapan hukum secara kaku. Di sinilah konsep judicial restraint dan kemungkinan untuk melampaui doktrin tersebut menjadi pertanyaan mendasar dalam sistem peradilan.
Memahami Judicial Restraint dalam Konteks Indonesia
Judicial restraint atau pengekangan yudisial, adalah doktrin yang mendorong hakim untuk membatasi perannya sebagai penafsir hukum, bukan pembuat hukum. Di Indonesia, doktrin ini implisit dalam sistem hukum yang menganut civil law, di mana kodifikasi peraturan menjadi panduan utama (Marzuki, Peter Mahmud. 2008). Hakim Indonesia diharapkan menerapkan undang-undang sebagaimana tertulis, mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Dalam praktiknya, judicial restraint di Indonesia paling tampak dalam penerapan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur batas waktu hukuman (masa penahanan dan lama hukuman) serta jumlah/besaran hukuman. Beberapa undang-undang tidak hanya menetapkan batas maksimum pidana, tetapi juga batas minimum, UU Narkotika misalnya, menetapkan sistem pengancaman pidana secara kategoris dengan batas minimum dan maksimum. Sehingga idealnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman di luar batasan ini, inilah esensi dari pengekangan yudisial (Moeljatno. 2018).
Secara regulastif, sistem hukum Indonesia memang telah menetapkan batasan yang tegas dalam beberapa aspek:
1. Batasan Waktu: KUHAP mengatur batas waktu penahanan, mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan kasasi. Misalnya, penahanan oleh penyidik dibatasi maksimal 20 hari, dapat diperpanjang 40 hari. Secara keseluruhan, seseorang dapat ditahan hingga 400 hari sebelum hukuman final.
2. Jumlah Hukuman: Sudah banyak undang-undang pidana khusus yang menetapkan batas minimum dan maksimum untuk berbagai tindak pidana. Kasus narkotika dan perlindungan anak, misalnya, memiliki hukuman minimum khusus yang sebenarnya tidak boleh dilanggar hakim.
3. Ne Bis In Idem: Prinsip yang melarang seseorang diadili dua kali untuk perkara yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP.
Pembatasan-pembatasan ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan. Namun, dalam praktiknya, batasan ini kadang justru menjadi dilema ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan keadilan substantif (Sidharta, Bernard Arief. 2013).
Kapan Hakim Dapat Melampaui Judicial Restraint?
Pertanyaan menggelitik: Apakah hakim harus selalu terikat pada batasan-batasan kaku? Sistem hukum Indonesia, meski tegas, sejatinya membuka beberapa celah di mana hakim dapat-bahkan mungkin harus-melampaui pengekangan yudisial, dalam pandangan penulis beberapa kondisinya antara lain:
1. Ketika Terjadi Kekosongan Hukum
Indonesia mengakui bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur (Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009). Dalam kasus rechts vacuum (kekosongan hukum), hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini memberi ruang untuk judicial activism dalam bentuk penemuan hukum (rechtsvinding) (Mertokusumo, Sudikno. 2010).
Di Amerika Serikat, kasus Brown v. Board of Education (1954) menjadi contoh klasik ketika Mahkamah Agung melangkahi preseden yang mapan untuk mengakhiri segregasi rasial di sekolah umum. Di Indonesia, putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 tentang perbuatan zina dan LGBT menunjukkan bagaimana hakim konstitusi menolak untuk melampaui batas meski ada desakan publik.
2. Dalam Penerapan Konsep Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif (restorative justice) memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek di luar ketentuan formal hukum. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya, memberi kewenangan untuk menerapkan diversi-penyelesaian di luar jalur formal-untuk kasus anak.
Selain itu dalam kasus pencurian ringan, Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2012 telah menyesuaikan batas nilai kerugian, memungkinkan hakim untuk memperlakukan pencurian kecil dengan lebih proporsional dibandingkan ketentuan yang sudah usang dalam KUHP.
Terakhir, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan kebijakan khusus mengenai hal tersebut yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut pada hakikat membuka peluang bagi hakim untuk melampaui batas dari aturan-aturan dengan mengedepankan konsep keadilan restoratif.
3. Ketika Kepastian Hukum Bertentangan dengan Keadilan
Gustav Radbruch, filsuf hukum Jerman, mengajarkan bahwa hukum harus menyeimbangkan tiga nilai: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika terjadi konflik antara kepastian dengan keadilan, hakim Indonesia memiliki ruang untuk memilih keadilan.
Dalam kasus Fidelis Arie (2017), seorang pria yang menanam ganja untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit langka syringomyelia, hakim tetap menerapkan UU Narkotika dengan menjatuhkannya hukuman delapan bulan penjara meski motifnya adalah kemanusiaan.
Kasus ini menggambarkan ketegangan antara penerapan judicial restraint dan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat luas. Bandingkan dengan perkembangan di beberapa negara bagian Amerika Serikat dan Kanada yang telah mengizinkan penggunaan ganja untuk keperluan medis, menunjukkan bagaimana sistem Common Law lebih adaptif terhadap perubahan nilai-nilai sosial. (Elkins, Chris dan Samanta Brooks. 2022).
4. Melalui Mekanisme Dissenting Opinion
Sejak UU No. 48 Tahun 2009, Indonesia mengakui dissenting opinion dalam putusan hakim. Ini membuka ruang bagi hakim untuk mengekspresikan perbedaan pendapat dengan mayoritas, yang lambat laun dapat mempengaruhi perkembangan hukum. Di Amerika Serikat, dissenting opinion Hakim Holmes dalam Lochner v. New York (1905) akhirnya menjadi pendapat mayoritas beberapa dekade kemudian (Richard A. Posner, 2010).
Berjalan di Atas Tali Tipis: Bahaya Melampaui Batas
Perlu dicatat bahwa melampaui judicial restraint bukanlah tanpa risiko. Dalam tradisi civil law yang dianut Indonesia, aktivisme yudisial yang berlebihan dapat:
1. Mengancam prinsip pemisahan kekuasaan, menggeser hakim dari penerapan hukum menjadi legislator
2. Mengurangi kepastian hukum yang menjadi fondasi negara hukum
3. Menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum
4. Kasus Akil Mochtar, mantan Ketua MK yang terjerat korupsi, menjadi pengingat bahwa tanpa batasan yang jelas, kekuasaan yudisial dapat disalahgunakan.
5. Meskipun demikian, sebagai perbandingan, pada negara-negara yang mengatur secara fleksibel batas-batas tersebut utamanya negara-negara pada sistem Common Law di negara-negara Anglo-Saxon memberi ruang lebih luas bagi hakim untuk menciptakan hukum melalui preseden. Di Amerika Serikat, doktrin judicial review yang dikembangkan dalam Marbury v. Madison (1803) bahkan tidak tertulis dalam konstitusi. (Adriaan Bedner,.2013).
Pelonggaran batas atas ketentuan yang diterapkan hakim sebenarnya tidak selamanya bergantung pada sistem hukumnya, Jerman misalnya, meski menganut civil law, tetap mengembangkan konsep Richter Recht (hukum yang dibuat hakim) untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang. Indonesia, dengan karakteristik uniknya, dapat belajar dari keseimbangan dinamis ini.
Menuju Peradilan yang Bijaksana
Judicial restraint tetap menjadi panduan penting bagi hakim Indonesia, terutama dalam menerapkan batasan waktu dan jumlah hukuman. Namun, sistem hukum yang hidup membutuhkan fleksibilitas untuk menghadapi kompleksitas dan keunikan setiap perkara.
Hakim Indonesia perlu mengembangkan "kebijaksanaan yudisial"-kemampuan untuk mengetahui kapan harus taat pada batasan formal dan kapan harus melampaui batasan tersebut demi keadilan substantif. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam konsep hukum progresifnya, "Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya." (Satjipto. Rahardjo, 2009)
Dalam dilema hakim yang kita bayangkan di awal, jawaban mungkin tidak selalu hitam putih. Yang pasti, keberanian untuk melampaui batasan formal ketika diperlukan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang fundamental, adalah bagian tak terpisahkan dari evolusi sistem peradilan yang matang dan berkeadilan.