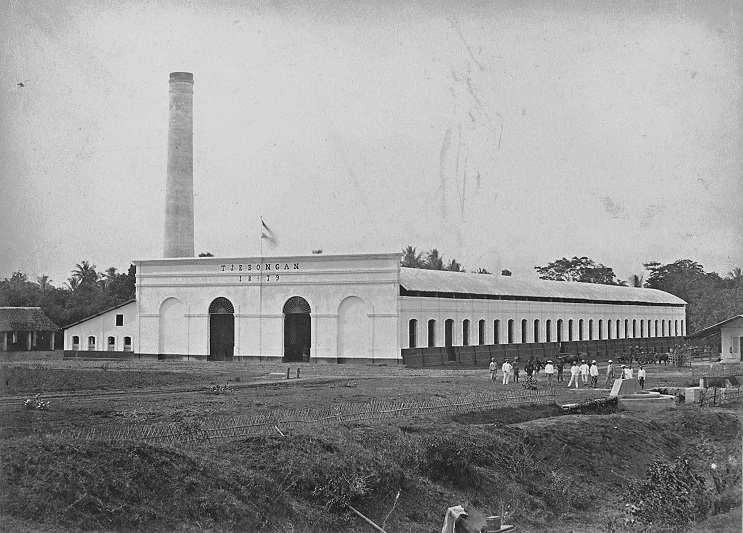“The Natural Liberty of Man is to be free from any superior Power on Earth, and not to be under the Will or legislative Authority of Man, but to have only the Law of Nature for his Rule.”
John Locke; Second Treatise of Government.
Pemikiran John Locke menjadi salah satu fondasi penting dari jurisprudensi tentang hak-hak kepemilikan pribadi. Menurut Locke, hak-hak pribadi bahkan mendahului institusi politik (prapolitis). Kepemilikan dibangun di atas konstruksi kemanusiaan yang sifatnya asali dan alami (state of nature).
Dalam kondisi sedemikian, yang menjadi relevan adalah hukum alam (the law of nature). Kepemilikan yang berada pada wilayah semacam ini adalah hak-hak alami (natural rights).
Selain hak untuk memiliki (the rights to own property), lanjut Locke, hak untuk hidup dan berkebebasan adalah hak yang tidak dapat dipindahtangankan maupun dilepaskan (unalienable). Argumen Locke ini dapat dijadikan dasar bahwa tindakan mengambil nyawa diri sendiri pun tidak dapat dibenarkan (Sandel, 2005).
Dasar dari pemikiran yang digagas Locke di Bab 2 dari Second Treatise of Government (1690:5) adalah: “For men being all the workmanship of one omnipotent, and infinitely wise maker: all the servants of one sovereign master, sent into the world by his order, and about his business, they are his property, whose workmanship they are, made to last during his, not one anothers pleasure”
Karena manusia adalah ciptaan dari satu pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, maka mereka adalah milik-Nya, sebagai hasil karya-Nya, yang diciptakan untuk hidup berdasarkan kehendak-Nya, bukan menurut kehendak manusia.
Hak-hak yang tidak dapat dipindahtangankan sifat, hanya dapat dipergunakan oleh agensi yang memiliki hak tersebut, tetapi tidak dapat diberikan (non-transferrable) pada siapapun, termasuk pada institusi politis seperti negara. Dengan kata lain, menurut Locke, negara pun tidak berhak untuk mengambil nyawa seseorang.
Oleh karena itu, kepemilikan pun bersumber dari hak-hak alami tersebut, seperti yang dikatakan Locke, “Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided, and left it in, he hath mixed his labour with, and joyned to it something that is his own, and thereby makes it his property” (Dengan demikian, apa pun yang diambil seseorang dari keadaan alamiahnya sebagaimana telah disediakan oleh Alam, lalu ia campurkan dengan kerja atau upayanya sendiri, maka ia telah menyatukannya dengan sesuatu yang menjadi miliknya, sehingga menjadikannya sebagai hak kepemilikannya); Locke, 1690:15.
Bekerja (labour) adalah aktivitas yang mengesahkan kepemilikan seseorang atas sesuatu yang sebelumnya adalah wilayah tidak berkepemilikan (the common).
Kepemilikan dan Dilema Sosial
Michael Sandel (2005) mengatakan, konsep kepemilikan (property rights) yang diajukan Locke dapat memiliki konsekuensi serius. Contoh yang diajukan Sandel adalah obat untuk penyakit kritis, seperti Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Penyakit yang sekarang sudah dapat diobati ini, membutuhkan biaya riset yang sangat besar, dan semua itu adalah upaya dari perusahaan farmasi dengan dukungan modal yang sangat besar pula.
Korporasi, lanjut Sandel, berada di wilayah kondisi asali (state of nature) aktual, karena tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikan ratusan negara di atas permukaan Planet Bumi.
Pemerintah Amerika Serikat punya kekuatan untuk bernegosiasi dengan raksasa farmasi, namun, tukas Sandel, pemerintah negara yang lebih lemah seperti Afrika Selatan, tempat prevalensi AIDS yang cukup tinggi di dunia, tidak punya posisi tawar yang cukup untuk meminta keringanan harga obat AIDS.
Pada kondisi tertentu, hak-hak alami yang tanpa kendali bisa menjelma menjadi sebuah bentuk kekerasan yang jauh dari konsep keadilan. Bahkan Locke sendiri mengatakan, “And one may destroy a man who makes war upon him, or has discovered an enmity to his being, for the same reason, that he may kill a wolf or a lion; because such men are not under the ties of the common law of reason, have no other rule, but that of force and violence, and so may be treated as beasts of prey, those dangerous and noxious creatures, that will be sure to destroy him, whenever he falls into their power” (Dan seseorang dapat membinasakan orang lain yang memeranginya atau yang menunjukkan permusuhan terhadap keberadaannya, dengan alasan yang sama seperti ia dapat membunuh seekor serigala atau singa; karena orang-orang semacam itu tidak terikat pada hukum umum akal budi, tidak mengenal aturan lain selain kekuatan dan kekerasan, sehingga mereka boleh diperlakukan seperti binatang buas, makhluk-makhluk berbahaya dan merusak yang pasti akan menghancurkannya kapan pun ia jatuh ke dalam kekuasaan mereka); Locke, 1690:10.
Ini berarti bahwa atas nama kepemilikan, apapun bisa dilakukan untuk mempertahankannya, dan dalam kondisi asali tidak ada tolak ukur apapun. Kondisi asali pada akhirnya akan berujung pada situasi yang dikuatirkan Thomas Hobbes: bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua) yang hanya dapat diselesaikan dengan adanya negara sebagai “Leviathan” (Hobbes, 1651).
Untuk menyelesaikan dilema ini, Locke memperkenalkan argumen lanjutannya, saat ia mengatakan: “’Tis true, governments cannot be supported without great charge, and ’tis fit every one who enjoys his share of the protection, should pay out of his estate his proportion for the maintenance of it. But still it must be with his own consent, i.e. the consent of the majority, giving it either by themselves, or their representatives chosen by them” (Memang benar bahwa pemerintahan tidak dapat berjalan tanpa biaya besar, dan sudah sewajarnya setiap orang yang menikmati perlindungan darinya turut membayar dari hartanya sesuai proporsi untuk membiayai pemeliharaan pemerintahan tersebut. Namun, pembayaran tersebut harus tetap berdasarkan persetujuannya sendiri, yaitu persetujuan dari suara mayoritas, baik diberikan secara langsung maupun melalui perwakilan yang telah mereka pilih sendiri).
Aspek Kolonialisme dalam Pemikiran Locke
Ada persoalan mendasar dari pemikiran Locke, yaitu peluang hak kepemilikan menjadi fondasi yang melampaui elemen-elemen lain yang penting dalam hidup manusia.
Bagi Sandel (2005), Locke tidak sepenuhnya tulus dalam mengalirkan argumennya, terutama karena Locke adalah bagian dari intrumen kolonialisasi Benua Amerika di masa-masa awalnya.
Ini berarti, pemikiran Locke adalah sebuah desain intelektual untuk mendukung ekspansi geopolitik monarki Inggris pada saat itu. Lebih lanjut Sandel (2014) menegaskan bahwa ada kemungkinan garis pemikiran Locke, yang dapat berlanjut pada Libertarianisme, akhirnya mengubah ekonomi pasar (market economy) menjadi masyarakat pasar (market society).
Contoh yang diambil Sandel adalah penjara di Santa Barbara (Amerika Serikat) yang selnya bisa ditingkatkan fasilitasnya (upgrade) selama tahanan bersedia membayar secara resmi kepada pihak pengelola penjara.
Di Universitas Oxford, dalam sebuah ceramah Sandel (2016) menceritakan tentang gagasan yang senada dengan pemikiran Locke, yang berasal dari Adam Smith. Bagi Smith, penting untuk mengubah pola remunerasi dosen dari gaji tetap menjadi honor per pertemuan yang dikaitkan dengan jumlah peserta kuliah.
Mekanisme yang mirip dengan mekanisme pasar ini menjadi sangat relevan dengan kecenderungan masyarakat pasar yang dikuatirkan Sandel. Lebih lanjut Sandel (2018) mengatakan, prinsip Liberalisme yang mengambangkan nilai-nilai yang sebenarnya sulit dicapai lewat konsensus.
Karakter konsensualis seperti yang diangkat Locke dalam Second Treatise of Government memberi ruang pada sisi transaksionalistik dari segala sendi kehidupan, dan tidak terkecuali hukum.
Dengan demikian, meskipun pemikiran Locke tentang hak kepemilikan pribadi memberikan dasar yang kuat bagi prinsip-prinsip demokrasi modern, kebebasan individu, dan keadilan berbasis konsensus, konsep ini tidak sepenuhnya bebas dari paradoks dan kontradiksi. Sebagaimana ditunjukkan Sandel, konsekuensi logis dari pandangan Locke dapat membawa kita pada masyarakat yang mereduksi seluruh aspek kehidupan menjadi transaksi ekonomi.
Oleh karena itu, tantangan terbesar yang muncul dari gagasan Locke adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara penghormatan terhadap hak-hak alami individu dengan kebutuhan akan regulasi kolektif demi terwujudnya keadilan sosial.
Kajian jurisprudensi kontemporer pun akhirnya dituntut untuk melampaui perspektif individualistik dan memandang hukum sebagai instrumen yang tidak hanya melindungi hak, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan dan kesejahteraan dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat.