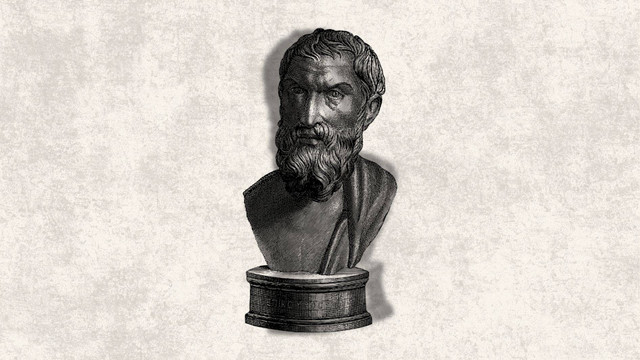“The Agricultural Revolution made the future far more important than it had ever been before.” – Yuval Noah Harari dalam Sapiens, Vintage (112)
Kelaparan sejatinya adalah persoalan biologis dalam tubuh manusia. Parameternya sangat jelas, secara fisiologis rasa lapar muncul saat jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengelola aktivitas selular seseorang tidak sebanding dengan energi yang tersedia dalam bentuk makanan. Pengkaji neurosains John Young dalam mengatakan bahwa secara biologis masalah kelaparan (hunger) berkaitan dengan jumlah kalori yang dideteksi oleh usus yang selanjutnya mengirimkan sinyal ke otak.
Kisaran yang dibutuhkan untuk bertahan hidup (tanpa mengalami kerusakan organ-organ) menurut standar World Health Organization (WHO) adalah di kisaran 1.500 hingga 2.000 kalori minimum. Dengan kata lain, kelaparan terjadi saat angka minimum ini tidak dipenuhi. Namun demikian, fokus ulasan ini adalah tentang bencana kelaparan. Pertanyaan yang sangat mendasar tentang bencana kelaparan dan eradikasinya dapat dirumuskan sebagai berikut: Mungkinkah bencana tersebut dihapuskan dihapuskan?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengingat beberapa hal. Pertama, bencana kelaparan bukan persoalan yang sifatnya personal, tetapi komunal atau bahkan global. Kedua, bencana kelaparan perlu dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan wabah yang sifatnya endemik. Ketiga, bencana kelaparan sebagai sebuah konsep yang ambigu perlu diklarifikasi ulang sebagai kerawanan pangan (food insecurity).
Bila bencana kelaparan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat personal, maka istilah “bencana” tidaklah tepat. Dengan kata lain, sebuah bencana mesti berdimensi sosial. Bila bencana kelaparan tidak dilihat sebagai penyakit menular (patologis), urgensi untuk mengatasinya tidak akan masuk dalam skala prioritas pengambil kebijakan di tingkat negara. Bila bencana kelaparan tidak dijelaskan secara spesifik sebagai kerawanan pangan, maka tidak akan ada solusi yang terukur untuk memitigasi tipe bencana semacam ini.
Kerawanan Pangan sebagai Distorsi Struktur Sosial
Bencana kerawan pangan adalah sebuah gejala (fenomenon) yang dekat dengan pertanian. Sebelum era revolusi pertanian dimulai, sekitar 10.000 tahun sebelum masehi manusia hidup sebagai pemburu dan peramu. Filsuf berlatar belakang sejarawan Yuval Noah Harari memperkirakan jumlah kelompok pemburu dan peramu sekitar 5 hingga 8 juta orang, dan setiap kelompok menghidupi wilayah yang luasnya mencakup puluhan hingga ratusan kilometer persegi.
Tipe institusi sosial seperti ini tidak mengenal istilah kerawanan pangan, karena persediaan makanan multimodalitas mereka dijamin oleh berbagai medan yang meliputi bukit, lembah, hutan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, saat manusia mulai bercocok tanam, situasinya berbeda. Manusia mulai hidup di satu wilayah yang ukurannya hanya puluhan atau ratusan meter persegi; bahkan petani hidup di satu tempat yang ukurannya beberapa meter persegi, catat Harari.
Kerawanan pangan terjadi saat wilayah yang diandalkan untuk menyediakan makanan mengalami kegagalan panen. Singkatnya, bagi Harari kerawanan pangan adalah konsekuensi logis dari pilihan hidup manusia sebagai masyarakat bertani. Pilihan ini bersifat satu arah, sebagaimana yang dikatakan Harari: “Farming enabled populations to increase so radically and rapidly that no complex agricultural society could ever sustain itself if it returned to hunting and gathering”. Dengan kata lain, saat kelompok pemburu dan peramu menjadi masyarakat agrikultur, kerawanan pangan adalah dampak negatif yang bersifat inheren dengan praktik bercocok tanam.
Karena pertanian dan kerawanan pangan tidak dapat dipisahkan, cara terbaik untuk memperkuat ketahanan pangan adalah dengan memperbaiki sistem pertanian secara keseluruhan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Sederhananya, bila budaya agrikultur dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu, mestinya sistem pertanian sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan untuk mencegah kerawanan pangan. Metode bercocok tanam tentu saja sudah mengalami perbaikan yang sangat signifikan.
Teknologi pertanian paling mutakhir sudah mempergunakan robot untuk memetik buah yang sangat rentan seperti stroberi, menembak gulma dengan laser, mendeteksi kadar air dengan sensor nirkabel di akar dan pesawat nirawak (drone). Dengan demikian, saat teknologi menjadi motor penggerak dari metode pertanian modern, dampak negatif kerawanan pangan bisa dikendalikan dan bahkan diselesaikan.
Aspek Patologis Kerawanan Pangan
Pendapat bahwa perkembangan teknologi berhasil mengatasi masalah kerawanan pangan didukung oleh Harari. Dalam karya seminalnya Sapiens, Harari mengatakan bahwa kekurangan pangan, perang, dan penyakit adalah tiga hal yang telah berhasil diselesaikan oleh manusia. Di sini Harari menempatkan masalah kerawanan pangan pada koridor yang sama dengan penyakit. Harari lebih lanjut menegaskan bahwa ada perubahan paradigmatik bencana ini, dari kekurangan menjadi kelebihan (ekses). Bencana kelaparan telah berubah menjadi bencana obesitas, dengan dampak ekonomi dan sosial yang sama beratnya.
Secara statistik, jumlah orang yang meninggal karena komplikasi penyakit yang disebabkan oleh obesitas jauh melampaui jumlah manusia yang tewas karena bencana kelaparan. Namun demikian, penstudi James Vernon mencatat bahwa kerawanan pangan ini masih menjadi ancaman serius di abad ke-21. Vernon membandingkannya dengan aksi terorisme 11 September 2001 yang menimbulkan korban 2.973 orang. Di saat yang sama, di seluruh dunia sekitar 35 ribu orang tewas karena kelaparan.
Juga bertolak belakang dengan Harari, pengkaji Robert Albritton menengarai bahwa kerawanan pangan masih terjadi karena persoalan sistem. Menurut Albritton sistem produksi dan distribusi didesain untuk selalu menyisakan celah kekurangan persediaan makanan dengan tujuan untuk mengendalikan harga pasar. Albritton mencatat: “In its very constitution private property always implies a power relation between an owner and non-owner, and in the case of pure capitalism all means of production are private property owned exclusively by capitalists.” Pertanian modern bersifat privat, dan dengan demikian akan selalu bersifat eksklusif, betapapun surplus hasil produksinya. Bila upaya kapitalistik ini dilakukan oleh negara (state capitalism), celah-celah dalam kebijakan sebuah negara masih memungkinkan terjadinya kerawanan pangan.
Harari dalam Homo Deus mencatat bahwa komodifikasi sektor pertanian berjalan seiring dengan pengurangan ongkos produksi dan pemaksimalan profit, bahkan jika itu berarti degradasi hasil pertanian berupa materi karsinogenik (penyebab kanker) di produk-produk hasil bumi berikut produk olahannya karena pestisida dan materi sejenisnya, atau kehancuran lingkungan yang berakibat serius pada krisis iklim saat ini. Singkatnya, persoalan kelaparan bukan lagi permasalahan sesederhana perbandingan jumlah panen dengan permintaan pasar. Campur tangan kartel, kepentingan politik, dan praktik bisnis yang tidak etis menjadi penyebab utama latennya bencana kelaparan.
Mencari Solusi Persoalan Kerawanan Pangan
Mengatasi masalah kerawanan pangan bisa menjadi sangat kompleks, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Langkah pertama adalah dengan menenuhi jumlah kalori minimum. Pengelolaan makanan sisa yang diakibatkan preferensi jalur distribusi yang kenyataannya bersifat estetis (tampilan produk), atau standar industri tertentu (misalnya perhotelan) yang mengakibatkan makanan terbuang hanya karena tidak memenuhi kriteria tamu hotel berbintang bisa dihindari dengan regulasi langsung dari organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi oleh kebijakan pemerintah.
Melihat bencana kelaparan sebagai penyakit regional (endemi) dapat menjadi dasar untuk meminimalisasi praktik bisnis yang tidak efisien semacam ini. Langkah berikutnya adalah menghindari pertanian menjadi komoditas yang eksklusif dengan menerapkan kebijakan agroekologis. Dalam bunga rampai analisis Transitioning to Zero Hunger, peneliti Delwendé Innocent Kiba mengatakan bahwa langkah terbaik adalah dengan mengembalikan potensi lokal pertanian dalam bentuk agroforestrasi dan agrobiodiversitas.
Menghutankan pekarangan dengan berbagai tanaman adalah langkah nyata yang sudah berhasil dibuktikan di beberapa negara di Afrika Barat dan juga Srilanka. Mempercayakan pertanian semata hanya ke sektor privat atau pengelola tertentu rentan dengan persoalan kepentingan ekonomi atau politik yang bisa membahayakan ketahanan pangan masyarakat. Terakhir, prediksi Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa 670 juta orang masih rentan bencana kelaparan di tahun 2030 menunjukkan bahwa bahkan di tahun 2025 ini persoalan kelaparan masih jauh dari selesai.
Ancaman kerawanan pangan masih nyata. Indonesia dengan kebijakan bantuan sosialnya mungkin menjadi solusi temporal, namun langkah yang lebih permanen diperlukan. Kebijakan yang diambil pemerintah Malawi dapat menjadi contoh. Teknologi modifikasi genetik jagung yang dapat tumbuh di tempat yang sangat sempit (seperti pekarangan yang sangat kecil) dengan perawatan minimum ternyata bisa mengatasi masalah kelaparan, jauh lebih efektif daripada bantuan sosial langsung atau impor bahan pangan (Sarah Levy:2005).
Dengan demikian, teknologi tetap memegang peranan penting dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. Menerapkan ketiga langkah ini adalah sebuah langkah progresif dalam perjuangan tanpa henti untuk mengeradikasi kerawanan pangan.