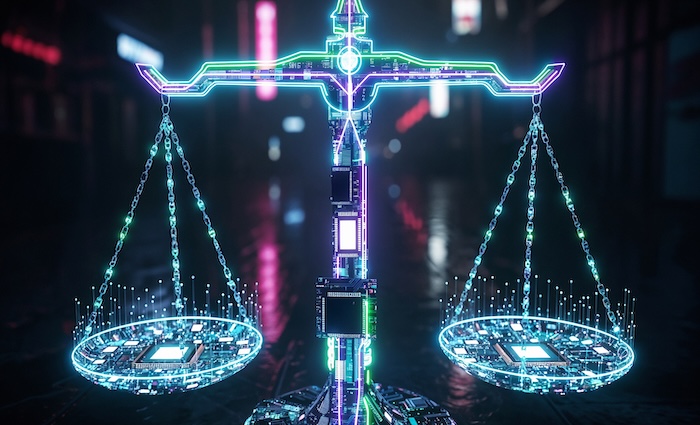“If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things.”
René Descartes (Principles of Philosophy).
Untuk mengetahui seberapa signifikan dampak teknologi kecerdasan buatan (AI) terhadap peradaban manusia, termasuk di dalamnya terhadap fondasi dari tatanan hukum dan ilmu hukum, negarawan dan begawan politik Henry Kissinger beserta dua pakar komputasi, Eric Schmidt (Google) dan Daniel Huttenlocher (Massachusetts Institute of Technology–MIT), menawarkan sebuah refleksi pemikiran yang dapat kita pergunakan sebagai bahan renungan sebelum melangkah lebih jauh dalam kajian-kajian filsafat hukum tentang AI dan kompleksitas dampaknya terhadap kehidupan manusia.
Kissinger, Schmidt, dan Huttenlocher, ketiganya berangkat dari pemikiran filsuf filsafat modern, René Descartes.
Descartes meletakkan teorinya pada rasionalitas manusia sebagai esensi dasar dari kemanusiaan. Berbeda dengan pemikiran Immanuel Kant, bagi Descartes pikiran (res cogitans) tidak terikat dengan organ tubuh (res extensa) manapun, termasuk otak. Pikiran adalah sebuah entitas independen yang tidak memerlukan induk (host) permanen.
Gagasan Descartes ini dikenal dengan istilah Dualisme, sebagai sisi berseberangan dari teori Monisme. Ujaran terkenal dari Descartes, “cogito ergo sum” (saya berpikir maka saya ada) memberi penekanan pada superioritas pikiran yang, dalam istilah Kant, sangat otonom. Cara berpikir yang diperkenalkan Descartes ini, diilhami dari pengamatannya pada otomaton, benda mekanis yang ada di taman istana Versailles.
Konsep res cogitans yang digagas oleh Descartes menggema kembali saat kita memikirkan tentang pengaruh AI terhadap sendi kehidupan manusia di Abad ke-21 ini. Kissinger, Schmidt, dan Huttenlocher (2021:16) mengatakan bahwa: “The Advent of AI obliges us to confront whether there is a form of logic that humans have not achieved or cannot achieve, exploring aspects of reality we have never known and may never directly known” (Munculnya kecerdasan buatan memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan apakah ada bentuk logika yang belum atau tidak dapat dicapai oleh manusia, serta menjelajahi aspek-aspek realitas yang belum pernah kita ketahui dan mungkin tidak akan pernah kita ketahui secara langsung).
Pertanyaan ini dapat kita uji secara langsung pada pemikiran Descartes, dengan mengajukan argumen berikut: “jika berpikir adalah hakikat manusia, dan jika mesin dapat berpikir seperti manusia, mesin memiliki res cogitans.”
Res Cogitans dan Persoalan Berpikir pada Mesin Agentik
Uji argumen Descartes mengarah pada persoalan baru: definisi tentang berpikir seperti manusia. Masalah ini terlihat sepele, namun Kissinger et al. mengingatkan bahwa mengesampingkan atau tidak memprioritaskan dampak perkembangan teknologi dan membahasnya secara mendalam adalah sebuah kesalahan.
Mereka mengatakan: “AI promises to transform all realms of human experience. And the core of its transformation will ultimately occur at the philosophical level, transforming how humans understand reality and our role within it” (Namun, kecerdasan buatan menjanjikan transformasi di seluruh dimensi pengalaman manusia. Inti dari transformasi ini pada akhirnya akan terjadi pada tingkat filosofis, yang mengubah cara manusia memahami realitas serta peran kita di dalamnya) (Kissinger et al, 2021:17).
AI agentik (agentic AI) adalah perkembangan lanjutan dari AI generatif yang kita kenal sekarang dalam bentuk ChatGPT dari OpenAI dan berbagai kecerdasan generatif lainnya.
Dalam sistem AI agentik, ada dua kecerdasan artifisial yang bekerja. AI yang pertama akan bertindak sebagai pengambil keputusan (agent), dan AI berikutnya bertugas untuk mencari, memeriksa, dan mengolah data (query).
Sejauh ini, ada dua sistem pencari utama, RAG (Retrieval-Augmented Generative) dan CAG (Cache-Augmented Generative). Berbeda dengan Large Language Models (LLMs) yang seperti GPT 4, Gemini, dan Llama, AI agentik bekerja secara mandiri dan bahkan memiliki kemampuan untuk menolak memberikan jawaban apabila analisis yang diperoleh dirasa tidak memadai atau tidak cukup kredibel (IBM, 2024).
Bila ini kita kembalikan ke kata “cogito” (res cogitans), maka AI agentik telah memenuhi prasyarat berpikir untuk dapat disebut setara dengan manusia. Descartes sendiri tidak memberikan deskripsi lebih lanjut tentang definisi berpikir.
Bagi Descartes, tindakan berpikir sepenuhnya otonom dan khas manusia. Di masa Descartes hidup di Prancis, menyakiti hewan tidak termasuk perbuatan yang tidak manusiawi karena hewan tidak berbeda dengan benda mati. Seandainya Descartes hidup di masa sekarang, maka ia sudah pasti akan memberi label “manusia” pada AI agentik, terlebih, karena bagi Descartes seperti yang dipaparkannya dalam Regulae, pengetahuan diwakili oleh aktivitas-aktivitas berikut ini: (1) imajinasi, (2) persepsi sensorik (sense-perception) and (3) memori (Decyk, 2000:448).
Menautkan kemampuan berpikir hanya pada tiga kualitas tersebut berarti menyepakati eksistensi kesadaran manusia pada benda, karena AI agentik memenuhi ketiganya, sementara LLMs dapat melakukan tiga syarat yang diminta Descartes. Tentang imajinasi, AI dapat mencipta (generate), meskipun prompt atau kata-kata yang diberikan terbatas.
Tentang memori, baik AI LLMs dan agentik memiliki kapasitas data latihan (token) yang sangat besar: sekitar 13 kilometer tumpukan buku kamus tebal yang masing-masing memuat 600.000 kata.
Persepsi sensorik adalah ciri yang tidak dapat dipenuhi oleh LLMs, tetapi dapat dilakukan dengan mudah oleh AI agentik. Mobil otomatis yang tidak memerlukan pengemudi (self-driving vehicle) adalah contoh dari penerapan AI agentik pada aplikasi sehari-hari.
Kendaraan semacam ini memindai situasi di jalanan secara langsung dan menerjemahkannya dalam bentuk tindakan tanpa perlu meminta otorisasi manusia untuk mengambil keputusan. AI agentik hanya akan berkonsultasi dengan RAG dan CAG sebagai bahan pertimbangan, sehingga manusia tidak lagi ada dalam sistem (“humans out of the loop”).
Dilemma Res Cogitans dalam Hukum di Era AI Agentik
Mengandaikan mesin yang dapat mengambil keputusan secara mandiri pada hakikatnya mensyaratkan perubahan yang fundamental dalam sistem hukum. Persoalannya mungkin terlihat sederhana, namun seperti yang diingatkan oleh Kissinger et al. (2021:15), “While the advancement of AI may be inevitable, its ultimate destination is not. […] Attempts to halt its development will merely cede the future to the element of humanity courageous enough to face the implications of its own inventiveness” (Meskipun kemajuan kecerdasan buatan mungkin tak terhindarkan, arah akhirnya bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan. […] Upaya untuk menghentikan pengembangannya hanya akan menyerahkan masa depan kepada bagian dari umat manusia yang cukup berani untuk menghadapi implikasi dari daya cipta mereka sendiri).
AI agentik yang seturut garis pemikiran Descartes memiliki “res cogitans”, mau tidak mau menuntut perubahan fundamental dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan.
Sebagai ilustrasi, secara hipotetik dapat dibayangkan sebuah situasi saat produsen mobil tanpa pengendara menjual kendaraannya ke konsumen. Bila terjadi kecelakaan yang merengut nyawa manusia, pertanyaan yang sangat mendasar adalah siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban.
Dengan penalaran hukum sekarang, kita mungkin menjawab bahwa produsen mobil yang harus bertanggung jawab. Namun demikian, jika dalam proses produksi AI bertindak independen dari pemrogramnya dan dalam menjalankan kendaraan AI sama sekali tidak melibatkan manusia dalam pengambilan keputusannya, maka persoalannya tidak akan pernah sederhana. Ini berarti bila teknologi ini akan segera diluncurkan ke pasaran di tahun 2030-an, hanya ada waktu sekitar lima tahun untuk memeriksa dan melakukan penyesuaian terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pemikir Jean-François Bonnefon (2021:33) mengatakan, persoalan paling besar dari “moralitas mesin” adalah pilihan yang akan diambilnya (social dilemma): apakah sang mesin akan menjadi liberalis (termasuk proto-libertarian & libertarian) atau utilitarian.
Sederhananya, apakah mesin akan memilih untuk menyelamatkan hanya penumpang saja (liberalis), atau orang di jalan (utilitarian). Dalam situasi seperti ini, merancang hukum tidak lagi sesederhana memberi pertimbangan hanya pada eksistensi res cogitans sebagaimana yang digariskan oleh Descartes.
Dilema ini tidak akan muncul dalam bila dalam kendaraan tidak ada orang atau di jalanan tidak ada siapapun. Namun, bila situasi kecelakaan terjadi di sebuah jalan besar padat di Jakarta dengan penumpang puluhan orang, persoalan akan menjadi sangat kompleks.
Dengan demikian, perkembangan AI agentik tidak hanya menantang ulang batas antara manusia dan mesin, tetapi juga menuntut kita untuk meninjau kembali fondasi-fondasi filosofis dan normatif dari sistem hukum yang selama ini diasumsikan beroperasi atas dasar agensi manusia semata.
Ketika entitas nonmanusia seperti AI mulai menunjukkan kapasitas berpikir, mengambil keputusan, bahkan menjalankan tanggung jawab secara otonom, maka konstruksi-kontruksi hukum seperti tanggung jawab, niat (mens rea), dan kehendak bebas (free will) tidak lagi dapat didefinisikan secara sempit. Filsafat hukum di era AI agentik harus bergerak melampaui dikotomi tradisional antara manusia dan mesin, dan mulai merumuskan suatu kerangka etik-normatif yang inklusif terhadap entitas berpikir nonmanusia, sembari tetap menjaga nilai-nilai keadilan, keselamatan publik, dan martabat manusia.
Tantangan ke depan bukan hanya bagaimana menciptakan hukum yang relevan di tengah percepatan teknologi, tetapi juga bagaimana menjaga agar hukum tetap menjadi ruang etik yang mampu menampung kompleksitas zaman-termasuk keberadaan res cogitans dalam bentuk baru yang tak pernah dibayangkan oleh Descartes.