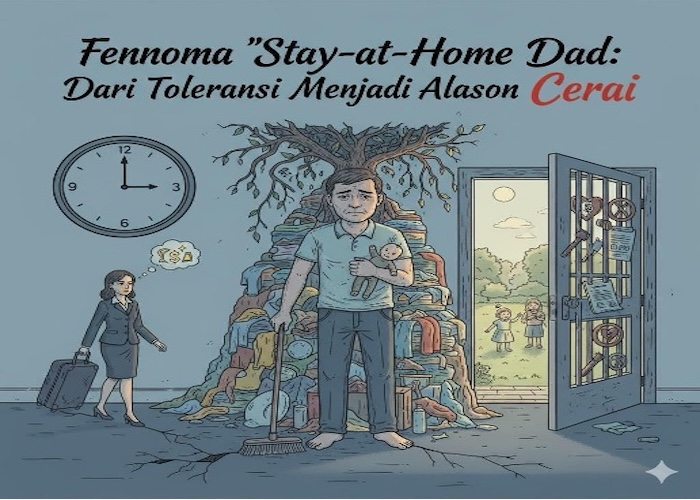“The extended family, consisting of three or more generations living together or in close proximity, often functions as a single economic and social unit in many societies. It provides economies of scale in production, mutual support in childcare and eldercare, and a network for the transmission of property and social status.”
George Peter Murdock (Social Structure).
Berkeluarga dan berketurunan boleh jadi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi manusia saat ini. Secara demografis, pertumbuhan populasi global sekitar kurang dari satu persen pada 2020. Ini berarti, di 2086 penduduk dunia akan mengalami pertumbuhan negatif, bergerak turun dari 10,43 miliar jiwa (Roser & Ritchie, 2022).
Tren tersebut, tidak dapat diasosiasikan dengan beralihnya ciri paterfamilias (laki-laki sebagai pencari nafkah) ke karakter yang lebih egalitarian (saat siapapun bisa menjadi sumber penghasilan). Data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan, dengan meningkatnya partisipasi kerja perempuan (female labour-force participation) dari 49% (1980) ke 64% (2020), angka perceraian turun 10% di tahun yang 2020 (OECD, 2024).
Hukum bekerja untuk dan dikelola oleh manusia. Masa depan hukum mau tidak mau ditentukan oleh keberadaan spesies ini sebagai alasan eksistensialnya (reason d’être).
Bagi pakar yurisprudensi Inggris Henry Maine, keluarga yang dibentuk melalui lembaga perkawinan adalah fondasi dari institusi sosial di tingkat mikro, yang bergeser fungsinya dari “peran” (status) menjadi “perjanjian” (contract) (Feaver, 1969).
Dengan berkeluarga, keberadaan anak diatur oleh negara. Tujuannya adalah untuk melindungi dan mengayomi generasi penerus sebuah bangsa. Namun demikian, keluarga modern tidak lagi menjadi jangkar regenerasi warga negara. Alasan ekonomi tentang mahalnya biaya untuk membesarkan anak menjadi salah satu argumen yang menjelaskan perkawinan niranak (childless marriage). Lebih dari 28% pasangan semacam ini di Amerika mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan finansial dalam mengasuh dan membesarkan keturunan (Pew Research Center, 2024), apalagi untuk memiliki anak lebih dari satu (OECD, 2024).
Berkeluarga Natural dan Kultural
Filsuf hukum Prancis, Jean Carbonnier, memberi penekanan penting hukum yang berkembang lentur (plasticité du droit) mengikuti dinamika sosial. Anak sebagai pihak yang diampu oleh orang tua (non-sujets de droit) sebelum menjadi subjek hukum (personnalité juridique) dibangun lewat keluarga yang terus mengalami perkembangan kontekstual (Carbonnier, 2001:279-280).
Terkait itu, sosiolog dan ekolog Urie Bronfenbrenner menggagas teori sistem bioekologis yang terdiri dari empat lapisan: mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. Teori ini dapat dipergunakan untuk menjelaskan perubahan struktur keluarga di abad ini (Bronfenbrenner, 1995). Sederhananya, interaksi paling lekat dari seorang anak ditemui dalam mikrosistem, seperti orangtua, teman, dan guru. Tolak ukurnya adalah seberapa dekat dampak langsung dari relasi tersebut terhadapnya.
Interaksi lapis kedua adalah relasi antarmikrosistem, yang disebut mesosistem. Ini dapat dilihat dari kedekatan orang tua dengan guru, dengan teman dekat sang anak, atau teman dengan guru di sekolah. Di tingkat ini dampak yang dirasakan tidak langsung, namun demikian, keharmonisan mesosistem sangat memengaruhi relasi mikronya.
Berikutnya adalah situasi eksosistem yang terjadi antara orang tua dengan tempat kerja mereka, entah lembaga swasta atau pemerintah. Dampaknya mungkin tidak langsung dirasakan oleh sang anak, tetapi pada orang tua. Di tahapan makrosistem, faktor-faktor budaya dan ideologi berpengaruh pada relasi eksosistemnya. Ini dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh kebijakan negara, misalnya, pada perlindungan dan kesejahteraan karyawan.
Individualisme liberalis dan libertarian yang berkembang di Barat (misalnya lewat pemikiran John Rawls dan Robert Nozick) memang memberi penekanan pada anak sebagai elemen singular pada keluarga inti (nuclear family). Sebaliknya, konsep keluarga besar (extended family) yang lebih dominan di masyarakat praindustrial dan masih sangat kuat di Timur memiliki dampak dan konsekuensi berbeda. Dari sisi antropologis, kekeluargaan pada hakikatnya memiliki jaring interaksi yang lebih luas (Murdock, 1965).
Sosiolog Talcott Parsons menjelaskan bagaimana keluarga besar bisa berdampak fungsional (Parsons, 1964). Fungsi ekonomi, misalnya, bisa dilakukan secara multidimensional, atau dengan kata lain, ada berbagai peran profesional yang bisa dilakoni seorang anggota keluarga.
Komunitarianisme dan Keluarga
Rumah adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia mungkin terlihat sebagai sebuah “beban” dari perspektif ekonomi dan politik yang cenderung liberalis, tetapi dari sudut pandang komunitarian, justru peluang. Kecenderungan individualisme di berbagai sektor memunculkan kesenjangan yang mengutubkan yang terkaya dengan termiskin. Masyarakat (community) memiliki kekuatan untuk bisa menjadi pihak pengimbang dari kekuasaan.
Michael Sandel, misalnya, mengkritik keras privilese korporasi yang menghasilkan sebuah sistem ekonomi tertutup yang tidak menyentuh siapapun yang tidak berafilisasi dengan perusahaan (Sandel, 2012). Kesejahteraan tidak akan menetes ke bawah (trickle down) karena tidak ada ruang interaksi, misalnya, antara Bill Gates dengan Microsoftnya dan masyarakat.
Sekalipun ada upaya dari Gates untuk bersikap filantropik dengan berbagai sumbangan dari Bill & Melinda Gates Foundation, kita tidak dapat menafikan langkah tersebut memiliki dampak dari sisi reduksi pajak. Motif tersembunyi (ulterior) orang-orang terkaya bisa kita selalu pertanyakan.
Sistem “jaring pengaman komunitarian” yang ada di Indonesia atau negara-negara Asia lainnya berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat, misalnya, sebelum era industri dimulai. Parsons mengatakan, “The American family is perhaps best characterized as an ‘open, multilineal, conjugal system” (keluarga [besar] di Amerika mungkin dideskripsikan sebagai keluarga yang terbuka, tumpang tindih, dan diikat oleh elemen perkawinan) (Parsons, 1964:179).
Hal itu, berbeda dengan keluarga besar di Indonesia yang diikat oleh kekerabatan dan marga, hubungan seperti ini lebih mudah retak atau diretakkan oleh perubahan zaman. Pada masyarakat yang sudah tidak lagi mengandalkan sumber penghidupan dari bercocok-tanam, jaring pengikat yang ada lebih gampang putus atau terputus oleh dinamika sosial kehidupan urban.
Rumah adat yang ada di berbagai suku di Indonesia menjadi simbol kesatuan yang mengikat kuat dan tidak getas oleh perubahan jaman. Kehidupan urban tidak menjadi penghalang dari kuatnya ikatan kekerabatan (kinship) yang akhirnya berperan sebagai jaring pengaman yang masih memiliki peran fungsional.
Hukum yang Mengikuti Dinamika Keluarga Komunitarian
Bila hukum di Indonesia dibesarkan dalam kultur intelektual yang lebih memberi penekanan pada keluarga inti sebagai elemen singular yang terpisah, atau sengaja dipisahkan dari ekso atau makrosistemnya, maka ada persoalan penting yang perlu dikaji oleh para iuris.
Sebagaimana yang digagas Carbonnier saat melihat perubahan struktur keluarga di Prancis, hukum di Indonesia juga perlu melihat karakter keluarga besar (extended family) sebagai elemen yang tidak dapat dinafikan begitu saja. Realitas sosial di lapangan menunjukkan bahwa keluarga besar masih memegang peranan penting, baik sebagai unit sosial maupun ekonomi, terutama dalam konteks masyarakat adat dan komunitas tradisional ketika pengelolaan hutan atau tanah adat dilakukan secara komunal.
Benturan sering terjadi ketika hukum formal menuntut adanya dokumen resmi sebagai syarat pengakuan hak, sedangkan praktik budaya dan adat lebih mengutamakan relasi sosial dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Hal ini menimbulkan ketegangan antara hukum positif dan realitas sosial yang dinamis, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang mampu mengakomodasi kompleksitas semacam ini tanpa mengabaikan sisi keadilan.
Salah satu benturan antara praktik budaya yang sudah berlaku turun-temurun dengan hukum positif adalah masalah keberadaan dokumen pendukung resmi. Kasus Kerajaan Negeri Johor v Adong bin Kuwau & Others (1993) dapat menjadi ilustrasi menarik untuk melihat. Di kasus ini, pengadilan di Malaysia memberikan hak kepada suku Temuan untuk mengelola tanah mereka di Negara Bagian Johor, sekalipun mereka tidak memiliki sertipikat kepemilikan tanah.
Pemerintah di negara bagian bermaksud mengembangkan wilayah ini tanpa memberikan ganti rugi atau bahkan melibatkan mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku (due process), karena penduduk asli dianggap tidak memiliki hak dan tidak bisa membuktikan klaim mereka. Dasar putusan pengadilan adalah hak tanah adat diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara itu.
Dengan demikian, hukum harus mampu berjalan beriringan dengan realitas sosial tempat ia hidup, berkembang, dan dipraktikkan. Ketika keluarga besar di Indonesia masih menunjukkan peran fungsionalnya secara kuat, baik sebagai jaring pengaman sosial maupun kultural, maka hukum tidak dapat serta-merta mengadopsi konsep keluarga yang cenderung individualistis tanpa kajian kontekstual yang mendalam.
Keluarga bukan hanya sekadar konstruksi biologis, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai komunitarian yang melekat kuat dalam sejarah bangsa ini. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi para iuris adalah menciptakan dan mengembangkan kerangka hukum yang menghormati dinamika keluarga, sembari tetap memberikan ruang bagi perlindungan dan keadilan individu di dalamnya. Hanya dengan pendekatan semacam ini, hukum dapat menjalankan peran sejatinya sebagai instrumen keadilan sosial yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.