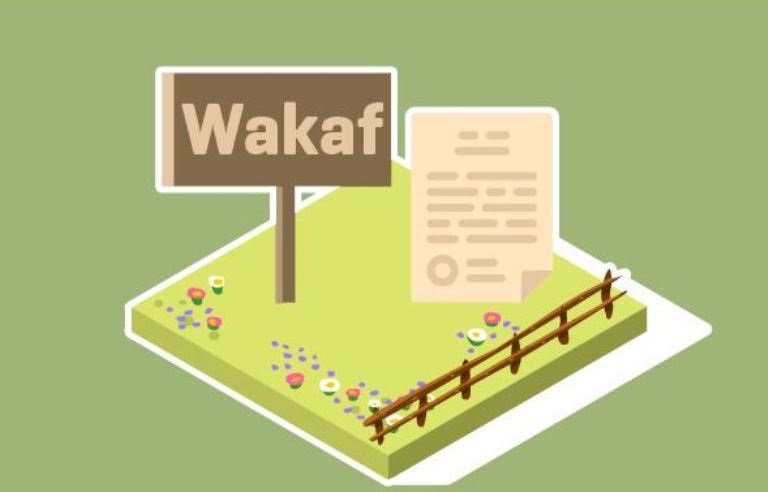Wakaf dan hibah sejatinya merupakan bentuk mulia dari kedermawanan. Namun tak jarang, niat baik itu justru berakhir di meja hijau. Perkara sengketa wakaf dan hibah semakin meningkat, baik karena persoalan waris, perubahan niat, atau ketidaktahuan prosedur hukum.
Wakaf menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meski keduanya berbeda, keduanya sama-sama berkaitan dengan peralihan kepemilikan yang sifatnya sukarela. Masalah muncul ketika ahli waris atau pihak ketiga mempertanyakan keabsahan atau maksud dari perbuatan hukum tersebut.
Seringkali niat wakif (pemberi wakaf) atau pemberi hibah tidak dituangkan dengan jelas dalam akta autentik, atau dilakukan secara lisan saja. Dalam kondisi ini, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk menelusuri kebenaran niat, bukti, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hakim harus jeli dalam membedakan niat filantropi murni dengan potensi manipulasi atau konflik kepentingan antarpihak.
Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi memegang peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan atas sengketa seperti ini. Melalui pembinaan teknis kepada para hakim, MA diharapkan mampu meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani perkara-perkara yang bernuansa keagamaan, sosial, dan etika, seperti wakaf dan hibah.
Di masa depan, diperlukan sosialisasi lebih luas mengenai pentingnya pencatatan resmi dalam perbuatan wakaf dan hibah. Masyarakat juga perlu memahami bahwa niat baik harus ditopang oleh proses hukum yang benar agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Dengan dukungan Mahkamah Agung, para hakim di tingkat pertama dapat menegakkan keadilan yang berpihak pada kepastian hukum sekaligus menjaga nilai luhur dari semangat filantropi.