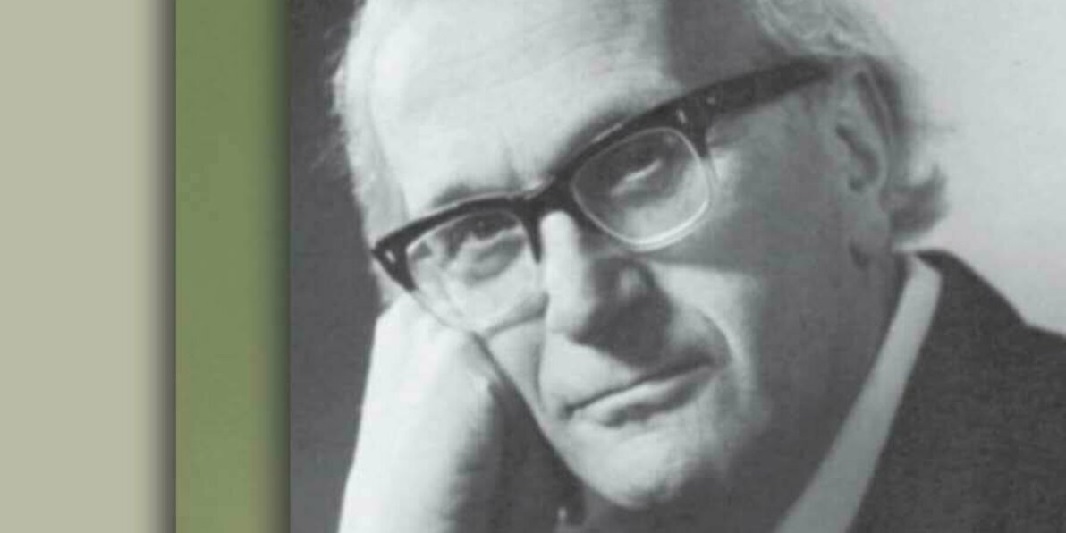“Through the word, which is already a presence made of absence, absence itself comes to be named.”
Jacques Lacan (Écrits: A Selection).
Memahami hukum hanya sebagai fenomena teks kerap menemui benturan, terutama dalam kaitannya dengan relevansinya dalam ruang hidup manusia yang jamak. Dari perspektif antropologi hukum, kita dapat membahas secara diskursif dengan mempergunakan pisau bedah yang ditawarkan pengkaji Sora Han (2022) yang mencoba mencari titik temu untuk memaknai teks-teks hukum dari perspektif distranslasi (distranslation).
Bertolak belakang dengan pendekatan konvensional yang melihat hukum sebagai perpanjangan dari yang hadir (presence), Han mengajukan konsep ketidakhadiran (absence) dari filsafat Timur sebagai alternatif pendekatan metodik yang dapat membantu untuk menangkap kompleksitas ruang hidup manusia yang biasanya gagal ditangkap dari perspektif konvensional.
Berbagai mekanisme kerja yang umum dalam budaya di Timur, seperti kaligrafi, pengobatan, meditasi aktif, menyimpan potensi untuk digali lebih jauh.
Praktik yang bersifat somatik dan afektif semacam ini, cenderung luput dari diskursus hukum yang terlalu formalistik. Secara prinsip, eksistensi hukum modern melihat manusia dengan tubuhnya sebagai beban (res extensa), dan bukan sebagai peluang.
Pendekatan antropologis dari tradisi yang berkembang di Timur justru melihat sisi sebaliknya. Tubuh manusia dilihat sebagai kemungkinan dan potensi. Dengan mengubah cara pandang seperti ini, persoalan konstruksi hukum bukan hanya masalah substansi yang akan dituliskan, tetapi apa yang “dihirup, dihidupi, dan dijalani dengan penuh tanggung jawab.”
Di sini, pemikiran Han dapat diiriskan dengan gagasan psikoanalisis dari Jacques Lacan tentang “yang Lain” (atau Liyan-istilah yang diperkenalkan oleh budayawan Goenawan Mohamad).
Bagi Lacan, hukum berada di wilayah “Liyan Luas” (the “Big Other”-le grand Autre), yang membentuk makna secara keseluruhan. Hukum adalah pembentuk jati diri manusia, karena lewat berbagai peraturan dan perundang-undangan manusia dibentuk.
Berikutnya, Lacan memperkenalkan “liyan sempit” (the little other-le petit autre), yang tidak lain adalah lingkungan terdekat yang membentuk diri seseorang. Keluarga, sahabat, kolega, dan lingkar kerabat adalah contoh dari liyan sempit semacam ini (Lacan, 1966 & 1973).
Interaksi antara kedua Liyan inilah yang membentuk diri, yang bekerja dalam bentuk bahasa. Bahasa Liyan Luas dan Liyan sempit terus bergerak mengasah pribadi seseorang. Dengan kata lain, subjek hukum adalah terjemahan (translasi) dari geliat tersebut. Han (2025) mengkritik proses translasi ini, dan sebaliknya memperkenalkan gagasan tentang distranslasi.
Distranslasi Subjek Hukum
Persis seperti air bergerak dari bejana yang penuh ke yang kosong, demikian hukum menggerakkan diri seseorang. Gerak ini dalam istilah Lacan disebabkan oleh kehilangan (manque). Namun, perspektif ini dimodifikasi secara radikal oleh Sora Han.
Alih-alih melihat manque semata sebagai kekurangan yang menyakitkan, Han membacanya sebagai ruang kemungkinan: tempat di mana hukum tidak sekadar mereproduksi kekuasaan simbolik, melainkan dapat ditranslasikan-ulang melalui pengalaman tubuh sehari-hari.
Dalam konteks ini, kasus City of Grants Pass v. Johnson 603 US 520 (2024) menjadi ilustrasi yang cukup konkret. Mahkamah Agung Amerika Serikat menguatkan kebijakan yang mengkriminalisasi tindakan tidur di ruang publik, sekalipun bagi mereka yang tidak memiliki alternatif tempat tinggal (tunawisma).
Dengan mengambil titik berat pada tindakan di ruang-ruang publik, dan bukan kondisi riil subjek hukum, putusan ini menunjukkan bagaimana hukum formal dapat menempatkan mereka dalam situasi sulit. Inilah titik di mana filsafat hukum sebenarnya perlu membuka diri terhadap kebertubuhan dan pengalaman-pengalaman serupa yang tidak sepenuhnya dapat direkam oleh bahasa normatif-yuridis.
Han menempatkan ketidakhadiran bukan sebagai celah untuk diisi oleh ancaman yang sifatnya legal, tetapi sebagai ruang temu untuk memahami keadilan dari luar tekstualitas dan masuk ke dalam kehidupan yang nyata dihidupi. Di sini letak distranslasi yang diajukan Han, terutama yang berakaitan dengan penderitaan yang dialami kaum tunawisma tersebut:
“Grief becomes unsolvable when the lack […] is not identified and grieved”(penderitaan tidak akan bisa diselesaikan bila tidak dipahami dan dialami lewat empati) (Han, 2022:xii). Dalam budaya di Indonesia, tidur di masjid atau langgar bagi mereka yang sedang bepergian yang tidak memiliki tempat tinggal, menunjukkan empati dari masyarakat yang melihat hukum sebagai distranslasi, dan bukan hanya translasi.
Esensi dari distranslasi juga dapat kita temukan di argumen yang diangkat oleh penelitian Anatoly Khazarov (1994) berjudul Nomads and the Outside World, yang berbicara tentang esensi dari kehidupan kaum nomaden.
Mereka adalah elemen-elemen yang tidak mendapatkan ruang lewat modernisasi saat berhadapan dengan privatisasi lahan, sekalipun secara de facto, komunitas-komunitas semacam ini sebenarnya memiliki keterikatan budaya, ekonomi, dan juga ekologis yang erat dengan wilayah-wilayah yang sebenarnya “diikat” dalam jejaring sosial lentur oleh orang-orang nomadik ini.
Khazarov mengatakan: “The negative effects of land privatization are most evident when participation in this process and its rewards are not balanced or commensurate, and when the number of dispossessed and displaced persons are proportionally high” (Dampak negatif dari privatisasi lahan paling nyata terlihat ketika partisipasi dalam proses ini dan hasil yang diperoleh tidak seimbang atau tidak sepadan, serta ketika jumlah orang yang kehilangan hak atas tanah dan mengalami pengusiran secara proporsional sangat tinggi) (Khazarov, 1994).
Performativitas dan Distranslasi Subjek Hukum
Konsekuensi dari sulitnya hukum konvensional untuk menemukan kosa kata tepat untuk menggambarkan pengalaman riil manusia juga dapat kita lihat dalam temuan dari antropolog Anna Jayne Kimmel (2023).
Kimmel menyoroti seberapa sulit manusia melihat bahwa kebebasan berpendapat, dan kebebasan untuk menghidupi pendapat, berasal dari tindakan (performativitas) tubuh yang sama. Konsekuensinya, berbagai kebiasaan masyarakat yang dilakukan dalam kerangka tradisi malah mendapat reaksi diskriminatif, sekalipun kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan mendapatkan ruang yang berbeda (Kimmel, 2025).
Kita dapat melihat bahwa eksklusi kaum nomaden dapat diperangkap secara slippery slope untuk mengalihgunakan lahan pertanian pada investasi dari luar negeri, seperti yang terjadi di Republik Demokratik Kongo; negara ini melepas 4% total wilayahnya (Buchholz, 2022) pada negara lain. Contoh lainnya dapat kita lihat dari penelitian antropolog Daniel G. Bates (1971) tentang komunitas Yörük di Turki.
Menurut Bates, interaksi yang selaras antara praktik masyarakat menetap dan berpindah adalah sebuah bentuk keseimbangan-sebuah relasi timbal balik yang menciptakan jejaring sosial serta ekonomi kompleks dan dilakukan dari generasi ke generasi.
Dari temuan Bates: “The Yorük migratory schedule is adapted to the agricultural cycles of the various villages, not because it is the optimum for grazing, or because it coincides with other productive requirements of the Yorük. It is a political adjustment” (Jadwal migrasi Yorük disesuaikan dengan siklus pertanian dari berbagai desa, bukan karena itu adalah pilihan terbaik untuk penggembalaan, atau karena bertepatan dengan kebutuhan produktif lain dari pihak Yorük. Ini adalah sebuah penyesuaian politis) (Bates, 1971:226).
Bila hukum akan dipergunakan untuk mengayomi komunitas-komunitas seperti Yörük ini, maka para iuris perlu untuk membuka diri pada kemungkinan distranslasi: sebuah pendekatan sensorik-indrawi atau yang dikenal dalam filsafat sebagai aesthesis.
Dalam metode ini, konstruksi tidak hanya cukup mempertimbangkan elemen yang sifatnya verbal argumentatif, tetapi juga kebertubuhan eksperiensialnya. Para hakim perlu, misalnya melihat kenyataan bahwa dokter di Swiss meresepkan terapi kunjungan ke museum karya seni sebagai bagian dari pengobatan (Reuters, 2025).
Kebijakan seperti ini adalah contoh adaptasi dunia medis terhadap aspek aesthesis yang ada dalam prinsip distranslasi.
Dengan demikian, melalui gagasan distranslasi, performativitas tubuh, dan pemaknaan hukum dalam ruang hidup, hukum tidak dapat dipahami semata sebagai teks beku, melainkan sebagai praktik menubuh, ritmik, dan relasional.
Ketika hukum mengabaikan kebertubuhan diri manusia, risikonya adalah penguatan eksklusi dan pengerasan struktural. Pendekatan distranslasi Sora Han membuka kemungkinan terhadap pemikiran hukum yang responsif terhadap kehadiran dan perasaan-singkatnya terhadap elemen aesthesis.
Dalam konteks ini, studi atas kehidupan komunitas nomaden menegaskan pentingnya memahami hukum sebagai bagian dari jaringan sosial dan spasial hidup, yang menuntut pendekatan interdisipliner dan multisensorik.