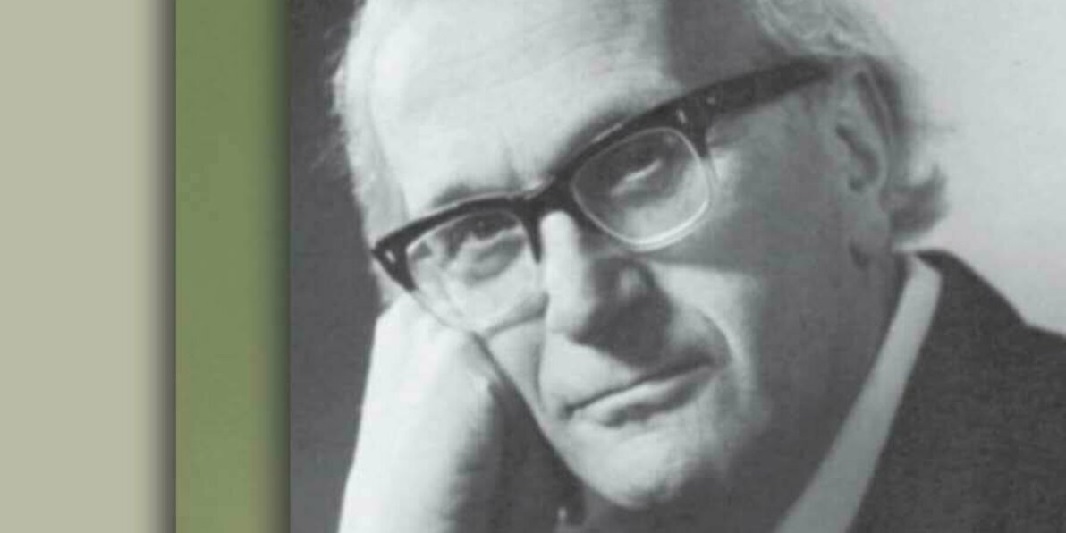“The attempt to interpret ideologies such as democracy, Marxism, or psychoanalysis as ‘secular religions’ is not only mistaken but dangerous, as it replaces analytical clarity with theological confusion.”
Hans Kelsen (Secular Religion: A Polemic Against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, Science and Politics as “New Religions”).
Hingga seperempat abad pertama di era yang pesat dengan teknologi informasi, kajian sosiologi hukum masih dihadapkan pada pertanyaan tentang relevansi agama dalam dinamika pembangunan dan pertumbuhan (development) sebuah negara.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, posisi agama memiliki tempat khusus dalam tatanan normatif dan kultural. Namun demikian, dalam kerangka analisis filsafat hukum, penting untuk melihat bagaimana negara-negara dengan tradisi sekular mendefinisikan dan memosisikan agama dalam konstitusi serta sistem perundang-undangan mereka.
Salah satu pemikir hukum yang kritis terhadap hubungan antara agama dan negara adalah Hans Kelsen. Dalam pendekatan positivisme legalnya, Kelsen menekankan pentingnya membedakan secara ketat antara tatanan hukum (law) dan sistem nilai atau keyakinan (morality atau religion).
Baginya, dalam negara sekular, agama adalah bagian dari wilayah privat, bukan bagian dari sumber legitimasi hukum negara. Sistem hukum yang positif, menurut Kelsen, harus bersifat bebas nilai (value-free) dan berdiri otonom dari doktrin-doktrin teologis (Kelsen, 1967).
Namun demikian, pemisahan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap keberadaan agama dalam kehidupan sosial. Justru Kelsen, secara normatif, berusaha menjaga agar hukum tidak diserap oleh kekuasaan moral atau dogma yang dapat mengancam prinsip netralitas dan universalitas hukum.
Dalam hal ini, posisi Kelsen berbeda secara tajam dengan Carl Schmitt, yang menganggap konsep-konsep hukum modern sebagai sekularisasi dari istilah-istilah teologis. Jika Schmitt mengafirmasi adanya fondasi metafisis dalam kedaulatan, Kelsen justru membebaskan hukum dari premis metafisis semacam itu (Kelsen, 2012).
Dalam konteks Indonesia, pemikiran Kelsen tidak serta merta menafikan pentingnya agama dalam masyarakat. Akan tetapi, ia memberi kita kerangka analitis yang tajam untuk memisahkan antara agama sebagai ekspresi keyakinan personal dengan hukum sebagai sistem normatif publik.
Pandangan ini menjadi penting terutama ketika kita memasuki era baru di mana pertanyaan tentang dasar legitimasi hukum, kebebasan beragama, dan netralitas negara terhadap nilai-nilai partikular semakin kompleks.
Religiositas sebagai Sebuah Bentuk Relasi Personal
Kritik terbesar Kelsen ditujukan pada Schmitt, yang memang memiliki riwayat yang problematis sehubungan dengan keterlibatannya di gerakan fasis Jerman. Menurut Schmitt, seorang iuris dan profesor di bidang hukum, semua infrastruktur yang ada di dalam agama pada dasarnya dapat diadaptasi dengan mudah ke dalam struktur negara modern.
Dengan kata lain, agama adalah sebuah bentuk upaya pencarian (inquiry) yang sifatnya rasional; dan dengan demikian, agama tidak berbeda dengan sains atau upaya-upaya lain yang mempergunakan rasio manusia (Schmitt, 1922).
Agama, bagi Schmitt, adalah bentuk embrionik dari sains. Bahkan aspek divinitas dalam agama dapat diterjemahkan dengan mudah menjadi penguasa. Pemikiran Schmitt ini mencoba mereduksi peran spiritual dari agama-agama dan meletakkannya murni dalam kerangka instrumental.
Menurut Kelsen, disposisi semacam itu rancu dan ambigu. Rasionalitas agama bukanlah rasionalitas saintifik. Tidaklah tepat untuk mendudukkan agama sebagai sains dalam bentuk baru. Menurut Kelsen, yang paling tepat adalah untuk mengembalikan agama sebagai bentuk yang mungkin dikategorikan sebagai irasional menurut sains (karena kesulitan dalam upaya pembuktian kebenaran korespondensi), namun tidak mengecualikannya dari sebuah konstruksi mental yang ditujukan untuk pengalaman spiritual (Kelsen, 2012).
Ini berarti, Kelsen menarik agama (religion) ke wilayah religiositas. Distingsi yang diberikan Kelsen menjadi sangat relevan saat negara menghadapi situasi yang cenderung heterogen dan multidimensional.
Penelitian dari Pew Research Center terhadap Government Restriction Index (GRI 2024) dan Social Hostilities Index (SHI 2024) menunjukkan, lepas dari upaya pembatasan terhadap agama di dalam suatu negara, agama tetap bersifat resilien (PEW, 2025:10). Karakter ini menjadi catatan penting yang dapat disandingkan dengan pemikiran Kelsen. Ini berarti ada perbedaan yang cukup mendasar dari agama yang diklaim oleh Schmitt sebagai bentuk lain dari fenomena sosial saintifik biasa, dengan agama sebagai pengalaman spiritual yang sangat personal.
Bahkan, beberapa studi menunjukkan agama masih sangat kuat berakar dalam tradisi sekularisasi yang sudah berlangsung berabad-abad (Rickless, 2019:458).
Penstudi fenomena religius Tudor-Cosmin Ciocan mengeklaim, agama dan budaya membentuk sebuah ikatan khas yang disebutnya sebagai simbiosis adaptif.
Menurut Ciocan, “Drawing on the metaphor of biological symbiosis, where distinct organisms engage in a mutually adaptive relationship, this framework explores how religions and cultures undergo a process of mutual influence, negotiation, and transformation in a manner akin to biological organisms adapting to new ecological niches” (Dengan menggunakan metafora simbiosis biologis-di mana organisme yang berbeda terlibat dalam hubungan adaptif yang saling menguntungkan-kerangka ini mengeksplorasi bagaimana agama dan budaya mengalami proses saling memengaruhi, bernegosiasi, dan bertransformasi dengan cara yang menyerupai organisme biologis yang menyesuaikan diri dengan ceruk ekologi yang baru) (Ciocan, 2024:149).
Melihat resiliensi agama dalam budaya, pertanyaan terbesar terhadap peran pasif agama dalam hukum yang diangkat oleh Kelsen menjadi bahan perdebatan yang cukup beralasan.
Meninjau Kembali Peran Religiositas dalam Pembentukan Hukum
Kelsen seolah melepaskan, dalam istilah Kartesian, res cogitans dari res extensa agama. Religiositas dilihat oleh Kelsen sebagai “jiwa” dari “tubuh” struktur sebuah agama.
Pandangan ini cukup problematis jika diterapkan di tipe masyarakat yang masih mengiriskan peran praktis dan praksis agama dalam kehidupan sehari-hari dengan keberadaannya sebagai bentuk formasi spiritual.
Dengan kata lain, saat agama tidak hanya bersifat teologis, namun juga sosiologis, maka gagasan Kelsen sulit untuk diterapkan tanpa mengakibatkan dampak yang cukup serius dalam kehidupan beragama.
Daniela Bifulco (2016) memberi penekanan bahwa agama (religion) berbeda dengan keyakinan (belief). Dalam garis pemikiran Bifulco, Kelsen membuat agama dan keyakinan menjadi rancu dan ambigu yang berdampak dalam kehidupan sosial.
Di Amerika Serikat, kita dapat melihat kasus Thomas v. Dewan Penilai Indiana pada 1981, saat Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan catatan tentang modifikasi prilaku (behaviour modification) sebagai beban (burden) atas sebuah keyakinan.
Hakim Agung Warren Burger mengatakan: “Where the state conditions receipt of an important benefit upon conduct proscribed by a religious faith, or where it denies such a benefit because of conduct mandated by religious belief, thereby putting substantial pressure on an adherent to modify his behavior and to violate his beliefs, a burden upon religion exists” (Bahwa apabila suatu ketentuan negara mensyaratkan pemberian suatu manfaat yang esensial berdasarkan tindakan yang bertentangan dengan ajaran atau larangan agama tertentu, atau apabila negara menolak pemberian manfaat tersebut karena adanya tindakan yang diwajibkan oleh keyakinan agama, sehingga menimbulkan tekanan yang nyata dan substansial terhadap penganut agama tersebut untuk mengubah perilakunya dan bertindak bertentangan dengan keyakinannya, maka ketentuan demikian dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama sebagaimana dilindungi oleh prinsip hak asasi manusia dan konstitusi) (Thomas v. Review Board of the Indiana Employment Security Division, 450 U.S. 707 (1981): 718).
Dengan demikian, yang tidak dilihat Kelsen adalah aspek perilaku dari keberagamaan seseorang yang sulit dilepaskan begitu saja. Dinamika hubungan antara agama dan hukum tidak dapat direduksi semata pada dikotomi antara wilayah publik dan privat sebagaimana dirumuskan dalam positivisme hukum Hans Kelsen.
Meskipun pemisahan yang diajukan Kelsen memiliki nilai penting dalam menjaga netralitas hukum terhadap nilai partikular, realitas sosial dan historis menunjukkan, agama dalam bentuk religiositas personal maupun ekspresi kolektifnya, terus menjadi elemen signifikan dalam pembentukan norma dan legitimasi.
Resiliensi agama dalam masyarakat sekular, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Pew maupun pandangan Ciocan, membuktikan bahwa agama bukan entitas pasif yang tunduk pada struktur negara, melainkan aktor budaya yang adaptif dan transformatif.
Kerangka filsafat hukum kontemporer, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap cara negara memosisikan agama, bukan hanya sebagai fenomena sosial, tetapi sebagai bagian penting dalam penciptaan hukum yang memiliki konsekuensi genting terhadap tatanan kehidupan bernegara.