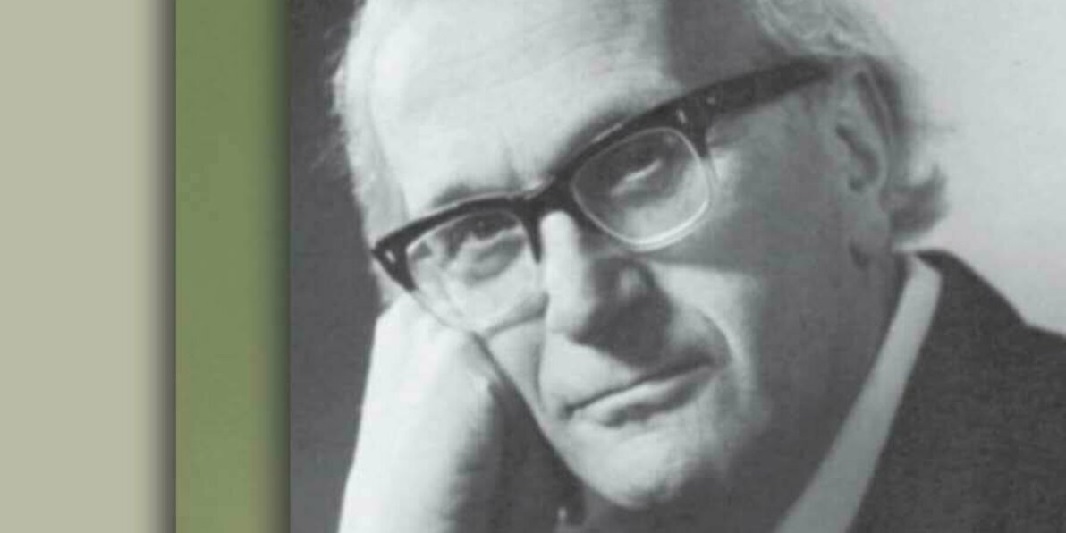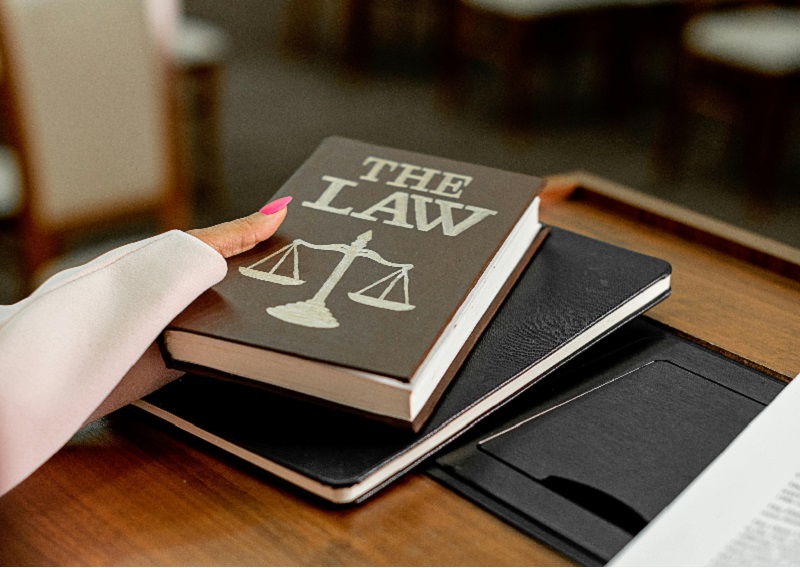“What more is required for a legal system is that its rules should be generally obeyed, and that officials should accept the rule of recognition from the internal point of view.”
H.L.A. Hart (The Concept of Law).
Melihat hakikat hukum sebagai fenomenon efemeral (sementara) adalah disposisi yang problematis. Setidaknya itu yang dapat kita angkat bila mencoba melihat hukum dalam kerangka desain besar yang ditujukan untuk memandu negara dari dermaga kemerdekaan hingga ke pelabuhan masa keemasan yang dituju.
Meminjam kosa kata positivisme legal, efemeralitas justru bertolak belakang dengan keberadaan aturan dan undang-undang dalam sejarah manusia. Filsuf Thomas Aquinas, yang menjadi sandaran dari pemikir naturalisme, menggagas bahwa yang abadi (eternal) adalah yang terbaik yang dapat digapai oleh manusia (Aquinas, 2008).
Klaim Aquinas membawa konsekuensi bahwa alasan keberadaan peraturan dan perundang-undangan adalah, untuk menjamin keberlangsungan mekanisme kebaikan yang bekerja secara impersonal di alam semesta.
Disposisi positivisme legal persis menyasar asumsi para naturalis, terutama sejak keragu-raguan (dubium) menjadi tema sentral dari semangat saintifik yang dimulai sejak filsafat modern.
Mereka menengarai, ada kerancuan berpikir untuk menilai hasil dari titik mulainya. Sebagai analogi, kita tidak mungkin mengetahui pemenang lomba maraton hanya dengan melihat pelari mana yang paling cepat melesat dari garis start. Ada begitu banyak kemungkinan yang akan terjadi selama 42 kilometer. Bahkan siapa sang juara lomba tetap tidak bisa ditentukan di lima menit terakhir sekalipun.
Satu-satunya cara untuk menentukan pemenang adalah dengan melihat peserta yang pertama kali menyentuh garis akhir. Demikian pula, dalam Modernitas, setiap kemunculan gejala tidak bisa diasumsikan tetap tidak berubah. Ada berbagai kondisi yang dapat mengubah hasil akhir sebuah kejadian (Hume, 2007).
Ini berarti, asumsi para naturalis terlalu prematur: keabadian tidak berkaitan dengan desain besar semesta yang sifatnya kontingen (tidak dapat ditentukan). Justru konsistensi cetak biru tatanan hukum dapat dimulai dengan memeriksa hakikat keberadaan aturan itu sendiri. Bagi filsuf hukum John Austin, saat hukum disekularkan, perintah religius menjadi sangat manusiawi (Austin, 1832).
Dengan demikian, hukum adalah pengejawantahan dari perintah (command). Ilustrasi dari prinsip ini dapat kita lihat saat seorang mandor memerintah buruh harian (yang terpaksa bekerja hanya di hari itu saja) untuk memindahkan tumpukan karung semen di sebuah tempat konstruksi. Tuntutan verbal koersif yang diucapkan mandor (dengan ancaman upah, misalnya) hanya berlaku di tempat, waktu, dan konteks tertentu. Setelah jam kerja selesai, selesai pulalah masa berlaku perintahnya.
Hukum dan Perubahan Sosial
Apa yang dalam kerangka naturalis tidak berubah, secara saintifik tidak pernah terjadi. Konsep tetap bersifat perseptif, artinya sangat bergantung pada anggapan yang merupakan hasil kerja otak. Sehingga dalam kerangka ilmu-ilmu alam, tidak ada yang benar-benar abadi.
Sebagai ilustrasi, dari disiplin biologi sebagian besar sel dalam tubuh manusia mengalami penggantian selama masa hidupnya. Ini berarti bahwa subjek hukum adalah definisi yang kontekstual, karena hanya desain kode genetik manusia (ADN-Asam Deoksiribo Nukleat) yang sama persis dari awal hingga akhir.
Analogi lainnya, bayangkan bila sebuah mobil diganti bagiannya sama persis satu demi satu sampai tidak ada lagi satupun bagian lama (dari saat pembelian) yang tersisa. Karena semua elemennya diganti serupa dengan desain awalnya, mobilnya terkesan “sama”.
Namun demikian, dalam kenyataannya kita memiliki mobil “baru”. Seturut analogi ini, secara legal nomor rangkanya pun sudah berbeda, sehingga mobil tersebut semestinya tidak lagi dapat mempergunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebelumnya.
Manusia memang bukan kendaraan, namun analogi di atas setidaknya memberi gambaran bahwa dengan perubahan biologisnya, manusia pasti berubah cara pikirnya. Kedewasaan berpikir seseorang terkait langsung dengan pertumbuhan neo-korteksnya.
Bagian otak tersebut, akan selesai berkembang dari usia 20 hingga 30 tahun. Dengan perubahan sel-sel dalam tubuh manusia, berubah pula cara pikirnya (Li Wang et al., 2025).
Fenomena “pubertas” dalam diri manusia erat kaitannya dengan perubahan dalam tahap selularnya. Lingkungan sosial tempat manusia hidup juga berubah setiap saat. Perubahan sikap dari anggota masyarakat akan mengubah tatanan sosial. Nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah institusi sosial akan terus mengalami penyesuaian dan modifikasi.
Penekanan Austin terhadap perintah sebagai alasan eksistensial hukum menurut H.L.A. Hart tidak tepat, sekalipun ia melihatnya sebagai sesuatu yang umum, persisten, efektif, delegatif, dan berdaulat (Hart, 1961:21-25).
Ada banyak ragam hukum yang berkembang dalam sejarah manusia yang tidak masuk dalam definisi Austin. Hukum berasal dari adat istiadat, berfungsi sebagai pengisi celah aturan dalam transisi kekuasaan (power-conferring laws), bersifat mengikat pembuatnya sendiri, dan bisa sangat kompleks dan rumit sehingga berada di luar kemampuan pihak-pihak yang mempromulgasikan atau mengesahkannya. Keempat jenis hukum ini tidak masuk dalam definisi yang diberikan oleh Austin (Hart, 1961).
Oleh karena itu, kelemahan Austin adalah ketidakmampuannya untuk memberikan argumentasi eksistensi hukum yang sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari di dalam masyarakat yang terus berubah. Kekurangan Austin adalah tidak menyiapkan instrumen untuk menyesuaikan peraturan atau perundang-undangan sesuai dengan perubahan sosial.
Tarik-Menarik Legalitas dan Moralitas
Perubahan sosial cenderung berjalan begitu subtil, sehingga perbedaan kelihatan mencolok di suatu era menjadi kebiasaan di era lain. Hart mengatakan, “The only mode of change in the rules known to such a society will be the slow process of growth whereby courses of conduct once thought optional become first habitual or usual, and then obligatory; and the converse process of decay when deviations once severely dealt with are first tolerated and then pass unnoticed” (satu-satunya cara perubahan terhadap aturan-aturan dalam masyarakat adalah proses penerimaan perlahan, ketika kebiasaan yang sebelumnya opsional lambat laun menjadi kebiasaan, dan kemudian menjadi kewajiban; serta proses kebalikannya, yaitu regresif, ketika penyimpangan yang sebelumnya dikenai sanksi keras, mulai ditoleransi, dan akhirnya diterima begitu saja) (Hart, 1961:92). Tugas para iuris adalah untuk mengawal proses ini, dan sedapat mungkin meminimalisasi dampaknya.
Pengkaji Hart, Jeffrey Kaplan (2021), menunjukkan bagaimana kasus McFall v Shimp (1978) menjadi argumen kuat dari pemikiran Hart bahwa benturan antara legalitas dan moralitas, dapat dikurangi lewat pemahaman ulang tentang hakikat hukum. Di kasus tersebut, Mcfall meminta Shimp (keponakannya) untuk mendonorkan sum-sum tulang belakangnya.
Shimp menolak dan Mcfall menempuh jalur hukum. Hakim John P. Flaherty, Jr. mengatakan: “For a society which respects the rights of its citizens, to even entertain the notion that one individual could be forced to undergo an intrusion of his body for the benefit of another, would to some extent sanction the decline of individual freedom and hence violate the very fabric of our free society” (Bagi masyarakat yang menghormati hak-hak warganya, dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa seseorang dapat dipaksa untuk mengintervensi tubuhnya demi kepentingan orang lain, paksaan semacam ini pada dasarnya sebentuk pembiaran serta kemunduran akan kebebasan individu, dan dengan demikian merupakan serangan terhadap sendi-sendi kebernegaraan yang dijunjung) (Court Ruling McFall v. Shimp, 10 Pa. D. & C.3d 90, 1978).
Menurut Kaplan, keputusan hakim untuk menolak memaksa Shimp mendonorkan bagian tubuhnya adalah contoh tuntutan moral yang tidak memiliki fondasi legal yang relevan, karena putusan ini juga mengayomi otoritas Shimp akan organ miliknya (Kaplan, 2021).
Mungkin di periode tertentu dalam sejarah manusia, tindakan semacam ini dianggap sebagai kewajiban. Namun di Abad ke-20, konteksnya menjadi berbeda. Di sinilah menurut Hart peran secondary law-instrumen legal yang memungkinkan penyesuaian hukum dengan situasi dan kondisi aktual.
Namun demikian, argumentasi Hart ini sebenarnya belum menyelesaikan persoalan mendasar yang diwariskan naturalisme. Mendesain hukum untuk masyarakat yang terus berubah memang membutuhkan refleksi ulang atas yang nyata terjadi (“is”) dan yang seharusnya terjadi (“ought”).
Upaya menghindari benturan keras seperti yang kita lihat di pemikiran Austin dapat diredakan dengan pendekatan Hart. Namun bila pemisahan ini menjadi terlalu jauh, maka yang terjadi adalah hukum yang tercerabut dari akarnya-manusia itu sendiri. Bila ini terjadi, maka aturan atau undang-undang menjadi sangat relatif; bergerak terlalu jauh dari misi utamanya untuk menegakkan keadilan.