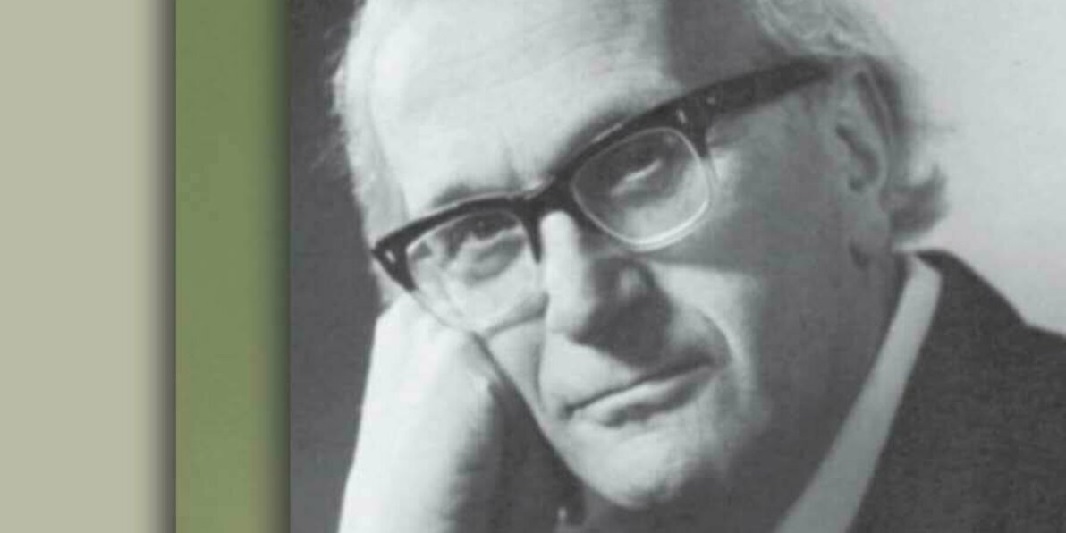“The aim of modern constitutions is not to make citizens constantly involved in government, but to guarantee them the independence of private life.”
Benjamin Constant (The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns).
Benjamin Constant, seorang pemikir di bidang filsafat termasuk filsafat hukum dan seorang liberalis, berada dalam garis argumentasi yang mirip dengan John Locke, yang sekalipun berada di koridor liberalisme, dapat dikategorikan sebagai proto-libertarian.
Constant memberi titik tekan pada kedaulatan diri seseorang sebagai individu yang bebas untuk menentukan kehidupan pribadinya. Sederhananya, menurut Constant, manusia memegang penuh kendali atas dirinya dan untuk itulah, sejalan dengan Locke, tugas negara adalah untuk memberi ruang pada aktualisasi diri. Constant memang tidak memberi porsi pada negara minimalis atau bahkan ultra minimalis. Satu poin penting dari Constant adalah persoalan kejujuran atau integritas.
Di satu sisi pemikiran Constant sejalan dengan apa yang digariskan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, kebebasan sejati manusia dapat dicapai saat seseorang mengoptimalkan rasionalitasnya. Bagi Kant, menjadi bebas berarti memiliki pilihan untuk menjadi rasional.
Namun, Kant tidak mengesampingkan kewajiban sebagai bagian dari menjadi bebas. Tugas paling fundamental dan paling luhur dari menjadi manusia adalah menjunjung tinggi rasio sebagai hakim terakhir dari tindakan dan bukan gejolak atau dinamika dari persepsi yang bias dan terlalu subjektif.
Menjadi objektif secara moral bagi Kant adalah, mencoba merangkum berbagai gejala dengan pisau bedah akal budi, atau yang dikenal dengan istilah metode sintetik apriori.
Ini berbeda, menurut Kant, dengan asumsi liberalisme sebagai proto-libertarian, utilitariansme, libertarianisme, karena pendekatan moral yang dipilih oleh mazhab argumentasi ini adalah analitik aposteriori, atau melakukan telaah empirik atas berbagai evaluasi etik yang akhirnya terperangkap dalam bias observasi atau keterbatasan infrastruktur perseptif untuk memberikan penilaian etis.
Moralitas bukan persoalan empirik, karena hanya dengan mengkaji yang sepatutnya dilakukan (Kant mempergunakan istilah “ought”), yang dilakukan (Kant menyebutnya “is”) menjadi sebuah tindakan etis. Untuk memeriksa prinsip ini, Kant mencoba menerapkan gagasannya untuk memeriksa perbuatan “berbohong demi kebaikan” (dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “white lies”).
Tentang Prinsip Manusia sebagai Tolak Ukur Nilai
Constant dan Kant menempuh jalur yang berbeda tentang disposisi rasionalitas untuk menghadapi kondisi ekstrim. Contoh paling seminal yang dipergunakan Kant adalah tentang berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang, yang menjadi tema sentral dari berbagai diskursus tentang moral dalam berbagai platform budaya populer.
Supremasi akal budi mestinya, menurut Kant, bisa mengatasi dilema yang terjadi saat ada diskrepansi antara yang terjadi dan yang semestinya terjadi. Kant menyajikan sebuah eksperimen mental (thought experiment) tentang pemilik rumah yang harus berbohong untuk menyelamatkan seorang teman yang diburu oleh seorang pembunuh.
Tuan rumah, menurut Kant, tidak bisa mengatakan bahwa ia tidak tahu tempat sang teman bersembunyi, sekalipun sebenarnya orang yang ia mau lindungi tepat berada di rumahnya.
Sekalipun kebohongan (dengan tidak mengungkap persembunyian teman) dilakukan untuk melindungi orang tersebut (karena diburu seorang pembunuh), bagi Kant tindakan tersebut tetaplah sebuah kebohongan karena rasa takut melampaui tuntutan moralnya untuk tetap rasional.
Kant mengajukan sebuah alternatif, yaitu keputusan untuk terbebas dari rasa takut yang dilakukan bersamaan dengan menjunjung tinggi rasio sebagai langkah yang lebih tepat daripada berbohong. Dalam pemikiran Kant, yang lebih tepat adalah pemilik rumah semestinya mengatakan bahwa ia tidak dengan persis mengetahui di mana temannya bersembunyi (karena memang ia tidak mungkin mengetahui secara pasti lokasi persembunyian sang teman) dari pada menyangkal keberadaannya kepada sang pembunuh.
Menggunakan rasio untuk menjelaskan keterbatasan akal budi jauh lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang memang keliru, karena bagi Kant tindakan tersebut mengkhianati akal budi.
Namun demikian, Constant tidak sepakat dengan argumen yang diajukan Kant: “The feeling of right and wrong is quicker, more certain, more infallible than all reasoning”-Perasaan tentang yang benar dan yang salah lebih cepat ditemukan, lebih pasti, dan lebih meyakinkan daripada semua konstruksi argumen akal budi. (Constant, 1797).
Rasionalitas manusia, bagi Constant, adalah sebuah wilayah yang terbatas, dan keterbatasan ini menjadi petunjuk bahwa hati nurani harus mengambil alih peran serta mengesampingkan rasio.
Kembali ke contoh kasus di atas, menurut Constant, situasi genting dan dilemmatis semacam itu menuntut sang tuan rumah untuk melakukan apa pun demi menyelamatkan nyawa temannya. Menyangkal keberadaan orang yang diburu oleh seorang pembunuh merupakan tindakan moral yang tepat pada konteks yang sesuai.
Dengan kata lain, sejalan dengan pemikiran Constant, saat keputusan rasional tidak dapat diambil, maka diri manusia harus menjadi ukuran. Ini berarti supremasi akal budi tidak serta-merta mengandaikan bahwa manusia hanya bersifat manusiawi ketika ia bertindak secara rasional. Dalam bahasa logika argumentasi, bila rasio adalah syarat cukup (sufficient) menurut Kant, maka menurut Constant akal budi berhenti pada batas syarat perlu (necessary).
Tatanan Hukum dan Supremasi Akal Budi
Sistem hukum di negara modern adalah ejawantahan dari supremasi rasio dalam mencari keadilan. Menurut perspektif Jeremy Bentham atau John Stuart Mill, rasio yang dipergunakan bersifat heteronom mutlak.
Sementara itu, bagi Locke dan Constant, rasio bersifat heteronom dominan dan otonom terbatas. Adapun menurut Robert Nozick, rasio cenderung heteronom terbatas dan otonom dominan. Kant, sebaliknya, mengasumsikan rasio sebagai otonom mutlak. Cara mempergunakan instrumen rasional dalam otak manusia menentukan bagaimana arus kanonisasi berbagai praktik kehidupan sehari-hari menjadi peraturan dan perundang-undangan.
Negara yang paternalis cenderung memberi berbagai batasan terhadap rentang tindakan moral. Bila individu menjadi elemen sentral penyelenggaraan negara, batasan moral menjadi sangat negosiatif dan kontekstual. Namun bila otonomi akal budi Kant diterapkan, proses hukum menjadi sangat sulit dan problematis-bahkan mustahil untuk diterapkan-sebagaimana yang ditengarai oleh Constant.
Namun demikian, pemikiran Kant bukan tanpa pengaruh yang cukup kuat. Paham liberalisme, utilitarianisme, dan libertarianisme memiliki ekses yang tidak dapat dianggap sepele. Sekali lagi, Kant mencoba mencari sebuah jangkar yang universal yang dapat menegakkan kemanusiaan manusia yang sangat manusiawi, yang tidak diombang-ambingkan oleh partikularitas ruang hidup manusia yang sifatnya spasio-temporal, bergantung pada ruang dan waktu.
Dengan kata lain, dalam Kant, orang biasa menjadi penting bukan karena negara menganggapnya penting, atau sebaliknya, orang biasa menjadi tidak penting karena tidak seberpengaruh individu-individu tertentu dengan kekuasaan yang cukup signifikan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan.
Masalahnya, secara saintifik manusia memang tidak pernah 100% rasional, sehingga mempergunakan prinsip dasar Imperatif Kategoris Kant (bahwa manusia bukanlah alat untuk mencapai sesuatu tetapi tujuan dari tindakan apapun) menjadi sangat problematis.
Daniel Kahneman, seorang filsuf yang banyak mengkaji masalah sistem berpikir manusia, dan juga peraih hadiah nobel, mengatakan, manusia memiliki sistem berpikir yang berbeda, yang secara umum disebut sebagai Sistem 1 dan Sistem 2 (Kahneman, 2011).
Dari kedua sistem tersebut, yang rasional murni adalah Sistem 2, sedangkan Sistem 1 bergantung pada keseimbangan hormonal. Sistem 1 juga berkaitan dengan perubahan persepsi mental yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, lingkungan, atau bahkan pengalaman masa kecil dan bentukan budaya (Kahneman et al., 2021).
Pada akhirnya, argumentasi dari Kant dan Constant memberikan implikasi bahwa kejujuran dan integritas adalah sistem nilai yang tidak bergantung pada supremasi rasio atau pertimbangan hati nurani. Kant mengingatkan kita pentingnya universalitas akal budi sebagai pijakan moral, sementara Constant menekankan bahwa konteks insani menuntut kelenturan etis yang sering kali melampaui nalar murni.
Dalam filsafat hukum, kedua pendekatan ini memperlihatkan betapa kompleksnya menciptakan sistem yang adil bagi manusia yang tidak sepenuhnya rasional namun tetap membutuhkan pijakan moral yang kokoh. Sebuah tatanan hukum yang baik perlu mampu menjaga titik keseimbangan antara “ought” dan “is”, dan juga membuka ruang pada kemanusiaan yang penuh dinamika, agar hukum tidak sekadar membatasi perilaku, melainkan menjadi wadah yang memelihara martabat dan otonomi manusia.