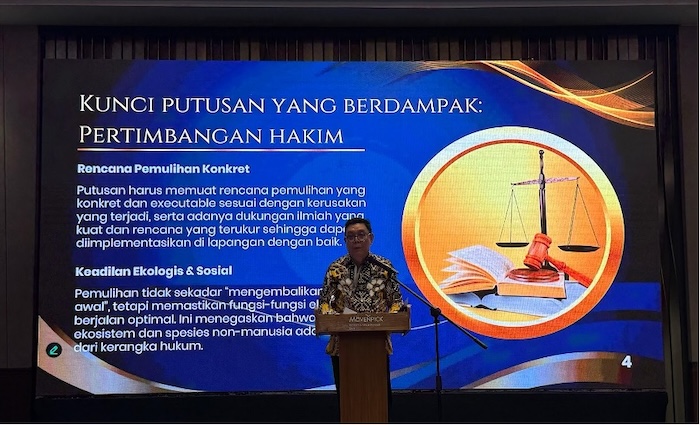Penegakan hukum dalam bidang kehutanan di Papua memiliki kompleksitas tersendiri, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
Perdasus tersebut, merupakan bentuk konkret pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang memberikan ruang legal kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan berdasarkan hak ulayat dan kearifan lokal mereka. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum atas tindak pidana kehutanan di Papua kerap mengalami benturan antara regulasi lokal dan nasional.
Perdasus No. 21 Tahun 2008 memposisikan hutan adat sebagai bagian dari wilayah masyarakat hukum adat, bukan sebagai hutan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perbedaan definisi ini berdampak langsung pada orientasi penegakan hukum. Sering kali, aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan nasional yang menganggap pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat sebagai pelanggaran hukum, terutama ketika tidak terdapat izin resmi dari instansi kehutanan pusat.
Berbicara konteks sistem peradilan pidana (criminal justice system), penegakan hukum kehutanan idealnya harus mempertimbangkan keberadaan dan kekhususan hukum adat. Namun hingga kini, sinkronisasi antara Perdasus dan regulasi kehutanan nasional belum optimal. Akibatnya, masyarakat adat Papua berada dalam situasi hukum yang rawan dikriminalisasi, meskipun mereka telah menjalankan pengelolaan hutan sesuai Perdasus dan nilai-nilai adat.
Sebagaimana masalah utama dalam penegakan hukum di Papua adalah tumpang tindih norma hukum. Di satu sisi, Perdasus 21/2008 secara tegas mengakui hak kelola masyarakat hukum adat atas hutan ulayat. Di sisi lain, Undang-Undang Kehutanan dan peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Kehutanan masih mensyaratkan izin formal berbasis struktur negara. Ketika aparat penegak hukum tidak memahami atau tidak mengakui kekuatan hukum Perdasus, maka tindakan hukum yang dilakukan dapat bersifat diskriminatif.
Banyak kasus pembalakan liar (illegal logging) yang sebenarnya bukan dilakukan oleh masyarakat adat, tetapi oleh korporasi besar atau oknum tertentu yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan. Ironisnya, masyarakat adat justru sering menjadi korban ketidaktegasan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum menyentuh akar persoalan: ketimpangan akses, konflik kewenangan, dan minimnya perlindungan terhadap hak adat.
Penegakan hukum yang ideal seharusnya bertumpu pada tiga unsur utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun di Papua sendiri aspek keadilan menjadi sangat penting. Tidak semua bentuk pemanfaatan hasil hutan harus diukur dengan legalitas formal yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Otonomi khusus Papua, melalui Perdasus, justru mengajarkan bahwa hukum harus adaptif terhadap keragaman sosial-budaya dan hak historis masyarakat adat.
Oleh karenanya, langkah strategis yang perlu diambil adalah melakukan harmonisasi antara Perdasus No. 21 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nasional. Harmonisasi ini tidak sekadar menyatukan norma hukum, tetapi juga menyelaraskan pendekatan dalam praktik penegakan hukum. Pemerintah pusat perlu secara aktif mengakui keberlakuan Perdasus sebagai lex specialis dalam konteks otonomi daerah. Ini berarti, dalam perkara kehutanan yang melibatkan masyarakat adat Papua, aparat penegak hukum harus menjadikan Perdasus sebagai acuan utama.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah penguatan kapasitas penegak hukum di daerah, untuk memahami karakteristik hukum adat Papua. Tanpa pemahaman yang mendalam, aparat akan terus menggunakan pendekatan positivistik yang kaku, dan mengabaikan nilai-nilai lokal yang justru memiliki potensi besar dalam pelestarian hutan.
Dalam paradigma hukum progresif, seperti yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menerapkan teks undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan konteks sosial, keadilan substantif, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Merujuk pada Perdasus 21/2008 justru menjadi jembatan penting antara hukum nasional dan kebutuhan lokal masyarakat Papua.
Sebagai pembanding, pendekatan restorative justice bisa menjadi solusi alternatif dalam menangani pelanggaran kehutanan oleh masyarakat adat. Restorative justice memungkinkan terjadinya dialog, pemulihan, dan penyelesaian berbasis adat yang menghindarkan kriminalisasi dan fragmentasi sosial. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menghasilkan vonis, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Hutan Papua adalah salah satu paru-paru dunia. Menjaganya berarti menjaga keberlanjutan lingkungan global. Namun, pelestarian hutan tidak bisa dipisahkan dari perlindungan terhadap masyarakat adat sebagai penjaga utama ekosistem. Oleh karena itu, penegakan hukum kehutanan di Papua harus dijalankan bukan dengan pendekatan kekuasaan semata, melainkan dengan pendekatan empati, dialog, dan penghormatan terhadap kearifan lokal.
Kesimpulannya, Perdasus No. 21 Tahun 2008 bukan sekadar produk hukum daerah, tetapi simbol pengakuan terhadap eksistensi hukum adat Papua. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan harus menjadikan Perdasus ini sebagai landasan utama, bukan sebagai pelengkap. Harmonisasi regulasi, edukasi aparat penegak hukum, serta pendekatan berbasis keadilan sosial harus menjadi agenda bersama dalam membangun sistem hukum kehutanan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi masyarakat Papua.
Sumber
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135.
- Indonesia. (2008). Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua.