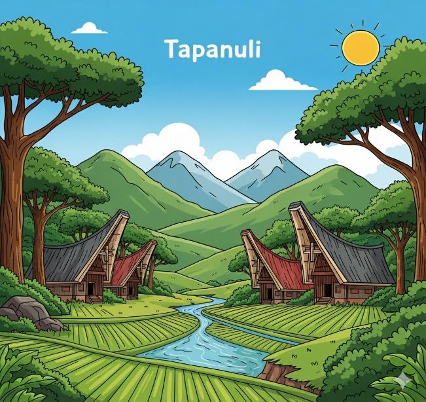Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 329 K/Sip/1957, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 1958, adalah contoh penting yang menunjukkan pengakuan dan penerapan hukum adat, dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait kepemilikan tanah.
Putusan ini menyoroti bagaimana hak ulayat (hak komunal) dan peran Kepala Persekutuan Kampung di wilayah Tapanuli Selatan diakui dan dihormati oleh negara.
“Kadaluwarsa” penguasaan tanah menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 329 K/Sip/1957, tanggal 24 September 1958 dengan Kaidah Hukum : “Atas izin Kepala Persekutuan Kampung didaerah Tapanuli Selatan, seorang warga memperoleh sebidang tanah secara merimba, namun ternyata kemudian selama lebih dari 5 (lima) tahun, orang yang berhak atas tanah tersebut membiarkan dan menterlantarkannya tidak diurusi dan juga tidak dikerjakan untuk berkebun/bersawah. Dengan fakta yang terbukti tersebut, menurut hukum adat, dapat dianggap/menimbulkan persangkaan; yang berhak telah melepaskan haknya atas tanah tersebut dan Kepala Persekutuan berhak memberikan tanah tersebut kepada warga lainnya.”
Pokok-pokok Putusan
Putusan ini, didasarkan pada sebuah kasus di mana seorang warga memperoleh sebidang tanah dengan cara "merimba" (membuka lahan) atas izin dari Kepala Persekutuan Kampung setempat.
Namun, setelah mendapatkannya, ia menelantarkan tanah tersebut, selama lebih dari lima tahun tanpa diurus atau dikerjakan, baik untuk berkebun maupun bersawah.
Kaidah hukum yang ditegakkan dalam putusan ini adalah, bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, perbuatan menelantarkan tanah oleh pemiliknya dapat menimbulkan persangkaan bahwa ia telah melepaskan haknya atas tanah tersebut.
Implikasi dan Kaidah Hukum
Implikasi dari putusan ini sangat signifikan, yaitu:
- Pengakuan Hukum Adat: MA secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai sumber hukum yang sah dan relevan dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama di daerah-daerah di mana hukum adat memiliki peran dominan.
- Peran Kepala Persekutuan Kampung: Putusan ini mengukuhkan wewenang Kepala Persekutuan Kampung untuk mengatur dan mengalokasikan tanah adat, termasuk hak untuk menarik kembali tanah yang ditelantarkan dan memberikannya kepada warga lain yang lebih produktif.
- Kadaluwarsa Penguasaan Tanah: Meskipun tidak secara harfiah menggunakan istilah "Kadaluwarsa" (verjaring) dalam pengertian hukum perdata modern, putusan ini menerapkan prinsip yang serupa. Yaitu, kelalaian dalam menguasai dan mengelola tanah selama periode waktu tertentu dapat mengakibatkan hilangnya hak atas tanah tersebut. Prinsip ini berbeda dengan verjaring dalam hukum barat yang biasanya mengacu pada batas waktu untuk menuntut suatu hak. Dalam konteks adat, ini lebih berkaitan dengan kewajiban moral dan komunal untuk memanfaatkan tanah demi kesejahteraan bersama.
- Perlindungan Fungsional: Putusan ini melindungi fungsi sosial dan produktif dari tanah, memastikan bahwa lahan tidak dibiarkan terlantar, melainkan dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga persekutuan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA).
Relevansi dengan Hukum Tanah Nasional
Yurisprudensi ini menjadi landasan penting bagi putusan-putusan selanjutnya yang mengakui hukum adat dan hak-hak masyarakat adat.
Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, negara melalui lembaga peradilannya telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional.
Putusan ini menjadi salah satu bukti bahwa pluralisme hukum (keberadaan lebih dari satu sistem hukum) diakui dalam praktik peradilan Indonesia, jauh sebelum UUPA secara resmi mengakui keberadaan hak ulayat, hal ini menunjukkan bahwa Hukum Adat dapat menjadi dasar dan landasan bagi penerapan Hukum Nasional seperti dalam Pasal 6 UUPA: Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pasal ini berbunyi: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.". Pasal 27 (untuk Hak Milik) menyatakan bahwa hak milik dapat hapus karena ditelantarkan.
Kemudian, Pasal 34 (untuk Hak Guna Usaha) dan Pasal 40 (untuk Hak Guna Bangunan) juga menyebutkan, bahwa hak-hak tersebut dapat hapus karena tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan.
Kaidah hukum dalam yurisprudensi ini, yang menyatakan bahwa penelantaran tanah selama lebih dari lima tahun, dapat dianggap sebagai pelepasan hak oleh pemiliknya, adalah cerminan dari prinsip hukum adat yang kemudian diakomodasi dan dilembagakan secara resmi dalam UUPA melalui pasal-pasal di atas.
UUPA menjadikan prinsip "tanah yang tidak produktif dapat dicabut haknya" sebagai aturan tertulis dalam hukum agraria nasional.
Jadi, meskipun UUPA lahir beberapa tahun setelah putusan tersebut, semangat dan substansi hukumnya sangat terinspirasi dari praktik-praktik hukum adat yang sudah berlaku, seperti yang tercermin dalam yurisprudensi tersebut.
Ini adalah pasal fundamental dalam UUPA yang menegaskan bahwa kepemilikan tanah di Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan memiliki tanggung jawab sosial.
Tanah harus dimanfaatkan demi kepentingan pemilik dan juga kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, tanah tidak boleh dibiarkan telantar dan tidak produktif karena hal itu bertentangan dengan prinsip fungsi sosial ini.
Secara ringkas, Putusan MA No. 329 K/Sip/1957 menunjukkan, bahwa pengabaian atau penelantaran tanah oleh pemiliknya, dalam konteks hukum adat Tapanuli, dapat diinterpretasikan sebagai pelepasan hak atas tanah tersebut, sehingga Kepala Persekutuan Kampung berhak untuk mengalokasikan ulang tanah kepada warga lain.