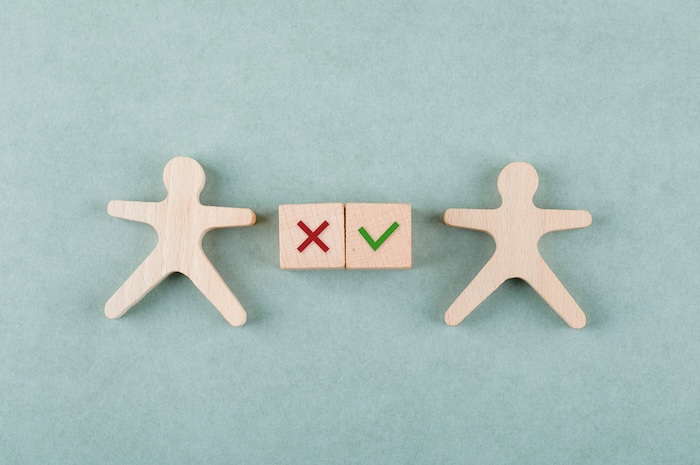“The demands of justice also naturally increase with the friendship, since both involve the same people and are of equal extent. It is more dreadful, for example, to defraud a comrade than a fellow citizen.” – Aristotle (Nicomachean Ethics).
Maestro Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, atau yang biasa dikenal dengan Michaelangelo, tidak pernah lelah berhadapan dengan bongkahan marmer yang ditambang di Carrara, daerah pegunungan Alpen Apuan, tidak jauh dari kota Toscana.
Dari tambang ke studio sang seniman, bongkahan-bongkahan marmer bianco duro, jenis yang paling keras dari varian marmer bianco lainnya, menempuh perjalanan sekitar 165 kilometer dalam waktu tiga bulan melewati laut dan sungai hingga ke Firenze.
Michaelangelo tidak hanya menunggu marmer Carrara sampai ke kediamannya, ia pergi ke lokasi ekstraksi hanya untuk memastikan bahwa kualitas material yang ia terima sempurna tanpa cacat (Scigliano, 2005). Michaelangelo tidak pernah kompromi dengan mutu, karya termashurnya David di sudut kota Firenze memakan waktu proses pengerjaan total selama hampir setengah abad untuk mencapai kesempurnaan (Coonin, 2014).
Filsuf yang menjadi jangkar pemikiran filsafat Barat, Aristoteles, meminjamkan instrumen ontologi (Aristoteles, terj. Makin, 2006; Cohen, 2025) yang dapat kita pergunakan untuk memaknai kerja Michaelangelo.
Bagi Aristoteles, marmer bianco duro dari Carrara adalah dunamis, yang memiliki potensi sebagai causa materialis. Tangan, pikiran, dan stamina Michaelangelo berperan sebagai causa effisiens, yang terlibat dalam tahapan kinēsis, sebuah proses panjang dan melelahkan untuk berinteraksi dengan gambaran desain sosok David sebagai causa formalis yang ada dalam kepala sang seniman.
Akhirnya, karya ini selesai sebagai causa finalis, yang bertahan berabad-abad sebagai entelechia, dan menginspirasi banyak orang dari jaman Renesans Tinggi (High Renaissance) di abad ke-16 hingga sekarang. Semua tahapan ini harus dijalani tanpa kecuali, karena bila tidak, marmer tersebut hanya akan berakhir sebagai bahan bangunan biasa.
Tidak Ada yang Instan secara Aristotelian
Ketujuh konsep Aristotelian ini pada dasarnya menjelaskan tahapan demi tahapan dari upaya dan kerja keras menjadi hasil. Kayu ulin yang bagus, misalnya, memiliki potensi untuk menjadi meja berkelas: potensi ini disebut dunamis oleh Aristoteles.
Balok kayu ulin tersebut adalah bahan baku yang menyebabkan seluruh proses dimulai, atau causa materialis (penyebab material). Namun untuk membuat meja, tukang kayu harus memiliki desain dan bekerja keras.
Desain menyebabkan bentuk, atau causa formalis (penyebab bentuk), dan kerja keras menghasilkan meja, atau causa effisiens (penyebab aktivitas). Dalam mengelola causa formalis dan causa effisiens, sang tukang kayu harus bergerak, kinēsis.
Semua upaya tukang kayu mesti diarahkan pada tujuan atau telos, sehingga titik finalnya adalah entelecheia, yang berasal dari “en-telos-echein” atau memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hasil akhirnya, meja yang elegan dan bermutu tinggi adalah penyebab selesainya keseluruhan proses atau causa finalis (Beere, 2009).
Bagi Aristoteles, tidak ada yang instan dalam dunia ini, semuanya adalah proses. Bahkan kebahagiaan utama bagi Aristoteles, eudamonia, adalah untuk mereka yang bekerja keras (Aristoteles, terj. Crisp, 2000).
Jenjang karier pun, memiliki ketujuh elemen ontologis yang kita telah lihat di atas. Seorang hakim sebelum masa formatifnya adalah seperti marmer Carrara yang dipergunakan oleh Michaelangelo, sebagai dunamis atau potentia dalam bahasa Latinnya.
Potentia ini membutuhkan kerja keras (causa effisiens) dan prosedur yang jelas (causa formalis). Tahap kinesis bisa juga diartikan sebagai proses saat hakim berupaya dengan kedua causa tersebut. Berbagai tahap pengangkatan yang diterima sang hakim adalah tahapan-tahapan entelecheia sebagai causa finalis dari kerja kerasnya.
Nepotisme (nepotism) atau Kroniisme (cronyism) yang memengaruhi posisi tertentu secara Aristotelian adalah retasan terhadap mata rantai tahapan tersebut, karena sang hakim tidak akan pernah mencapai entelecheia penuh dari substansi dunamis yang seharusnya ia wujudkan. Setiap tahap yang ia lalui bukan sekadar prosedur administratif, tetapi gerak progresif menuju telos jabatannya untuk menegakkan keadilan.
Dengan demikian, setiap jalan pintas yang diciptakan oleh Nepotisme atau kolusi bukan hanya cacat etis, tetapi juga cacat ontologis, karena mendistorsi hakikat profesi kehakiman itu sendiri (bandingkan Kronman, 1995).
Favoritisme dan Potong Kompas Jalur Prosedural
Baik Nepotisme dan Kroniisme berada di wilayah Favoritisme. Sederhananya, keputusan favoritis tidak memeriksa kelayakan apapun sebelum mengambil keputusan.
Dalam sebuah kumpulan tulisan, Robert G. Jones (2012:3) mengangkat beberapa definisi Nepotisme, salah satunya berbunyi: “the bestowal of patronage by reason of relationship regardless of merit” (“memberikan disposisi patronase atas dasar hubungan, tanpa memedulikan layak tidaknya seseorang”).
Dalam naskah yang sama, pakar-pakar lain mencoba menelisik bahaya Nepotisme bagi kelangsungan sebuah lembaga. Bagi Paul M. Muchinsky, nepotisme menghambat pertumbuhan organisasi. Bagi Marcus W. Dickson, Levi R. G. Nieminen, dan Benjamin J. Biermeier-Hanson, Nepotisme akan masuk dalam perangkap inkompetensi sebagai faktor yang diabaikan dalam merekrut pegawai selanjutnya.
Bagi Thomas E. Becker, nepotisme merusak tatanan kepercayaan. Bagi Aline Masuda dan Michelle Visio, Nepotisme menjadi ladang sumber konflik. Bagi Guillermo Wated dan Juan I. Sanchez, Nepotisme menjadi membuat korupsi menjadi sesuatu yang lumrah (Jones, 2012). Singkatnya, Nepotisme hanya akan mengakselerasi proses destruktif yang terjadi dalam sebuah lembaga.
Kroniisme, adalah bentuk lain dari Favoritisme yang juga tidak melihat kelayakan sebagai sebuah elemen fundamental dalam pengambilan keputusan menentukan siapa yang akan memegang posisi tertentu dalam organisasi.
Ekonom Randall G. Holcombe dan Andrea M. Castillo mencatat bahwa “Cronyism is a system in which people we call ‘cronies’ receive benefits from personal connections that are not available to others who are outside that group” (Kroniisme adalah suatu sistem di mana orang-orang yang kita sebut ‘kroni’ menerima keuntungan dari hubungan personal yang tidak tersedia bagi mereka yang berada di luar kelompok tersebut) (Holcombe & Castillo, 2013:8).
Salah satu dampak penting lain yang disorot oleh Holcombe dan Castillo adalah bagaimana produktivitas yang semestinya menjadi elemen penting dalam aktivitas ekonomi digantikan oleh berbagai koneksi yang cenderung bersifat politis (Holcombe & Castillo, 2013).
Dengan kata lain, keduanya mengingatkan bahwa sisi produktif sebuah negara akan tergerus, atau mungkin digantikan oleh lobi-lobi intensif yang kontra-produktif dengan gerak pembangunan sebuah negara, sebagaimana yang terjadi di Mesir (Smierciak, 2022).
Jalan Licin Perangkap Favoritisme
Kroniisme memang tidak sampai ke permukaan sebagai sebuah kasus, namun sembulan-sembulan yang terjadi menunjukkan bahwa berbagai ekses dari Favoritisme memang kontra-produktif terhadap ketahanan sebuah lembaga dan aktivitas ekonomi baik dalam skala mikro maupun makro.
Dalam perkara G.R. No. 205172, Herminio T. Disini v Republic of the Philippines, yang diputus oleh Mahkamah Agung Filipina di Manila pada 15 Juni 2021, Presidential Commission on Good Government (PCGG) menggugat Disini atas dugaan akumulasi kekayaan secara tidak sah melalui kedekatannya sebagai kroni Presiden Marcos, khususnya dalam komisi sekitar 50,6 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan kira-kira Rp810 miliar, yang diterimanya dari kontrak pembangunan PLTN Bataan, Central Luzon, dan diberikan kepada Westinghouse dan Burns and Roe.
Mahkamah Agung Filipina menetapkan bahwa Disini wajib membayar ganti rugi penggunaan relasi politiknya untuk keuntungan pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap integritas publik (Supreme Court of the Philippines, 2021).
Dengan demikian, beragam contoh yang telah dibahas menunjukkan bahwa proses yang sehat, baik dalam profesi maupun organisasi, selalu menuntut disiplin, ketelitian, dan penghormatan terhadap tahapan yang wajar.
Setiap bentuk pengabaian prosedur yang semestinya dalam pengambilan keputusan penting, termasuk Favoritisme dalam berbagai wujudnya, pada akhirnya merusak jalinan proses itu sendiri, mengikis standar, melemahkan kepercayaan, dan menurunkan mutu hasil.
Ketika kelayakan tidak lagi menjadi dasar penilaian, maka institusi apa pun, entah yang bergerak dalam pelayanan publik, pendidikan, maupun ekonomi, kehilangan arah dan gagal membentuk kualitas terbaik dari potensi yang sesungguhnya tersedia.
Hanya melalui komitmen pada prosedur yang adil, kerja keras yang konsisten, dan penghargaan terhadap integritas proses, sebuah lembaga dapat menjaga ketahanan, efektivitas, serta martabat yang melekat pada tujuan keberadaannya.