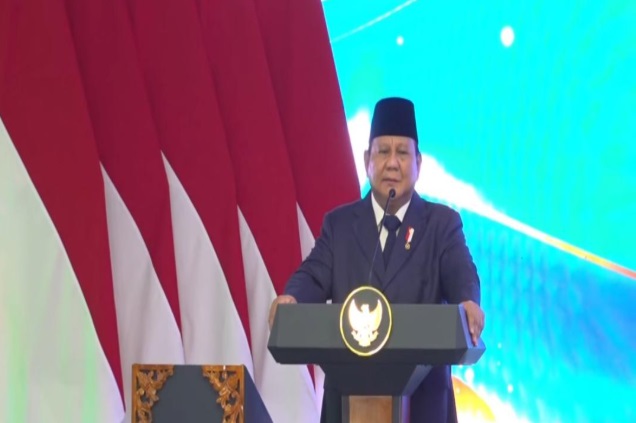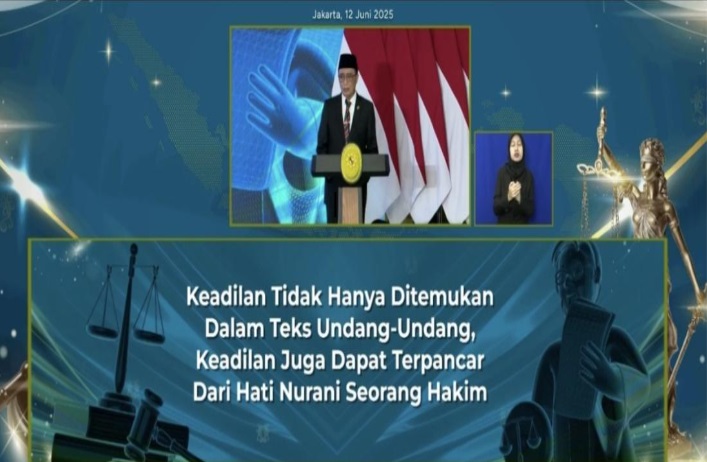Pelantikan pejabat pengadilan merupakan momen penting dalam sistem hukum yang idealnya mencerminkan integritas dan independensi lembaga peradilan. Namun, dalam praktiknya, pelantikan ini kerap diiringi budaya simbolik berupa pemberian karangan bunga dari berbagai pihak, termasuk yang berasal dari luar institusi peradilan.
Artikel ini mengkaji praktik tersebut dari perspektif pendekatan semiotika. di mana berdasarkan pendekatan tersebut ditemukan bahwa karangan bunga tidak netral secara makna, melainkan membentuk narasi sosial tentang jejaring, dukungan, dan kedekatan, yang berisiko mencederai persepsi publik atas imparsialitas pengadilan. Sangat diperlukan program Reformasi peradilan yang menyentuh aspek simbolik ini sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik secara menyeluruh.
Kritik Terhadap Budaya Karangan Bunga dalam perspektif Semiotika
Pelantikan pejabat pengadilan, baik hakim, ketua, panitera, maupun pejabat struktural lainnya, adalah peristiwa kelembagaan yang sarat makna. Di dalamnya terkandung pengukuhan atas tanggung jawab etik dan hukum, serta harapan publik terhadap independensi lembaga peradilan.
Namun, pelantikan ini sering kali berlangsung dalam kemeriahan simbolik, salah satunya melalui tradisi pemberian karangan bunga dari berbagai pihak.
Praktik ini memang tampak remeh, namun sebenarnya menyimpan persoalan yang layak dikaji secara serius. Ketika karangan bunga berasal dari aktor eksternal seperti advokat, pelaku usaha, atau pejabat eksekutif, maka batas antara simbol sosial dan potensi konflik kepentingan menjadi kabur. Dalam konteks negara hukum, simbol pun memproduksi makna. Tulisan ini mengupas fenomena tersebut melalui pendekatan etika kelembagaan dan semiotika budaya.
Dalam perspektif semiotika, karangan bunga bukan sekadar objek fisik, melainkan tanda (sign) yang mengandung makna. Barthes mengembangkan teori tentang mitos dan sistem semiotika dua tingkat, di mana tanda tidak hanya memiliki makna denotatif tetapi juga makna konotatif yang lebih dalam dan sering kali tidak disadari.
Eco (Roland Barthes,1972) menekankan, tanda tidak hanya memiliki makna statis, tetapi juga dinamis yang bergantung pada konteks budaya dan interpretasi (Umberto Eco, 1976).
Barthes selanjutnya menjelaskan, tanda dapat mengalami transformasi makna menjadi mitos ketika masyarakat secara kolektif menerima makna konotatif sebagai sesuatu yang natural dan given atau sesuatu yang dianggap telah ada/terberi (Roland Barthes, 1972).
Dalam konteks karangan bunga, pada perkembangannya telah terjadi naturalisasi makna bahwa jumlah dan kemegahan karangan bunga mencerminkan tingkat pengaruh dan kekuasaan pejabat yang dilantik. Mitos ini kemudian memengaruhi cara masyarakat memandang institusi pengadilan dan pejabatnya.
Perkembangan makna konotatif dari simbolisme karangan bunga sendiri jika dilihat pada rutinitas yang bisa dikatakan selalu ada dalam pelantikan pejabat pengadilan pada dasarnya telah mengarah pada transformasi tanda yang awalnya sederhana menjadi mitos, di mana jumlah karangan bunga senantiasa dikonotasikan sebagai indikator seberapa "penting" seorang pejabat pengadilan.
Persepsi ini menegaskan bagaimana karangan bunga telah menjadi apa yang disebut Baudrillard sebagai simulacra. Di mana, tanda tidak lagi merepresentasikan realitas tetapi justru menciptakan hiperrealitas (Bourdieu, Pierre, 1984).
Pada perkembangannya, praktik simbolisme karangan bunga bahkan menunjukkan bagaimana praktik ini telah berevolusi dari ekspresi selamat sederhana menjadi sistem tanda kompleks yang merepresentasikan jaringan sosial dan relasi kuasa.
Transformasi makna ini, menciptakan mitos tentang status dan pengaruh yang sebenarnya dikhawatirkan secara semiotik dapat berimplikasi pada salah satu makna yang seharusnya melekat pada simbol pengadilan itu sendiri yakni independensi. Apalagi dalam sistem demokrasi, lembaga peradilan dituntut untuk menjaga judicial independence dan institutional impartiality. Bukan hanya bebas dari pengaruh substantif, tetapi juga dari simbol-simbol yang menimbulkan persepsi bias (Mulgan, 2000).
Karangan Bunga sebagai Simbol Sosial
Karangan bunga dalam pelantikan pejabat adalah simbol yang terbaca publik sebagai bentuk ucapan selamat. Namun dalam konteks kekuasaan yudikatif, ucapan tersebut tidak bisa dilepaskan dari potensi relasi personal dan kepentingan profesional. Hadirnya karangan bunga dari advokat, pejabat pemerintah, atau pelaku usaha menimbulkan persepsi tentang eksistensi relasi di luar relasi hukum yang netral.
Hal tersebut menjadikan pemberian karangan bunga pada pelantikan pejabat pengadilan sebenarnya telah menciptakan dilema etis yang signifikan. Di satu sisi, praktik ini dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap pejabat yang baru dilantik.
Di sisi lain, pemberian simbol material ini, khususnya bila berasal dari pihak-pihak yang potensial menjadi pencari keadilan di kemudian hari, dapat menciptakan kesan adanya hubungan khusus yang berpotensi mengganggu objektivitas pejabat pengadilan.
Ascarya (2021) mengungkapkan, pemberian karangan bunga ini merepresentasikan "jejaring relasional" yang dapat dipersepsikan sebagai upaya mengikat pejabat pengadilan dalam jejaring patronase. Persepsi ini, meski tidak selalu mencerminkan realitas, sebenarnya sangat mungkin dapat merusak citra lembaga peradilan sebagai institusi yang independen dan imparsial.
Secara semiotik, pada makna yang lain, karangan bunga memang dapat diartikan sebagai penanda yang membawa petanda berupa apresiasi. Namun, melalui proses mitologisasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ia berubah menjadi mitos sosial-yakni, simbol dukungan, jejaring, atau bahkan “penandaan teritorial” atas kekuasaan simbolik. Dalam pelantikan pejabat pengadilan, hal ini dapat membentuk citra bahwa jabatan tersebut telah “diwarnai” oleh aktor-aktor tertentu.
Budaya simbolik ini berisiko mencederai prinsip etik. Meskipun tidak ada pelanggaran hukum eksplisit, simbol-simbol tersebut membentuk persepsi publik yang meragukan netralitas pejabat yang baru dilantik. Persepsi ini krusial karena kepercayaan terhadap peradilan dibangun tidak hanya dari putusan hukum, tetapi juga dari kesan publik terhadap proses internal lembaga.
Apalagi dalam perspektif sosiologi hukum legitimasi lembaga peradilan tidak hanya bergantung pada legalitas formal, tetapi juga pada persepsi publik terhadap integritas dan independensi para pejabat peradilan. Dengan demikian, praktik yang secara potensial merusak persepsi tersebut dapat berdampak negatif terhadap efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan.
Alternatif Konstruktif dari Sudut Pandang Semiotika
Merujuk pada permasalahan yang telah diidentifikasi, ada beberapa solusi yang dapat diusulkan dari perspektif semiotika seperti dengan melakukan dekonstruksi mitos dan rekontekstualisasi tanda. Mengikuti pemikiran Barthes tentang demitologisasi (Roland Barthes, 1968), diperlukan upaya sistematis untuk membongkar mitos yang telah terbentuk seputar karangan bunga.
Lembaga peradilan dapat melakukan kampanye kesadaran internal yang mengeksplisitkan makna konotatif dari karangan bunga, sehingga pejabat pengadilan lebih sadar akan dinamika semiotik yang beroperasi di balik praktik ini. Hal ini sejalan dengan konsep "pembacaan kritis" (critical reading) yang diadvokasi oleh Barthes untuk melawan naturalisasi ideologi melalui tanda (Roland Barthes, 1972).
Selain demitologisasi, konsep rekonfigurasi sistem tanda dari Umberto Eco juga dapat digunakan sebagaimana Eco menyatakan, makna tanda dapat diubah melalui rekonfigurasi sistem semiotik (Umberto Eco, 1984) melalui pendekatan konsep rekonfigurasi sistem tanda dalam simbolisme seremonial di lembaga peradilan dapat dikembangkan sistem tanda alternatif untuk menggantikan fungsi sosial karangan bunga. Misalnya, penggantian karangan bunga dengan sertifikat digital atau sumbangan atas nama pejabat yang dilantik kepada program bantuan hukum masyarakat tidak mampu.
Rekonfigurasi ini, memungkinkan transformasi signified dari ekspresi relasi kuasa menjadi komitmen terhadap keadilan sosial. Pembatasan semiotik (semiotic limitation) pun pada dasarnya dapat dilakukan dimana Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan yang membatasi ukuran, jumlah, dan visibilitas karangan bunga, atau bahkan melarang sama sekali praktik ini dalam konteks pelantikan pejabat pengadilan. Pembatasan ini akan mengurangi potensi karangan bunga sebagai penanda status dan relasi kuasa.
Konsep terakhir untuk mengatasi konotasi yang berkembang dalam simbolisme seremonial pelantikan pejabat pengadilan dari sudut pandang semiotika adalah melalui counter-signification (penandaan tandingan).
Mengadopsi konsep "guerrilla semiotics" dari Umberto Eco, lembaga peradilan dapat mengembangkan sistem tanda tandingan yang secara aktif menantang konotasi yang problematik dari karangan bunga. Misalnya, setiap pejabat pengadilan yang dilantik dapat mempublikasikan pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak mengaitkan nilai personal atau profesional mereka dengan karangan bunga yang diterima. Tindakan ini menciptakan "noise" dalam proses signifikasi yang telah mapan, memutus rantai signifier-signified yang problematik (Umberto Eco, 1984).
Sebagai contoh praktiknya, beberapa negara telah mengembangkan praktik yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Di Singapura, ucapan selamat untuk pejabat publik sering diwujudkan dalam bentuk donasi untuk kegiatan sosial atas nama pejabat tersebut (Lee, H. L, 2017).
Sistem ini tidak hanya menghindari kesan transaksional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Praktik serupa telah mulai diterapkan di Korea Selatan dan Jepang, di mana institusi peradilan mendorong pengalihan dana karangan bunga menjadi donasi untuk program bantuan hukum.
Implementasi konkret lain dari pendekatan ini dapat berupa:
a) Program "Keadilan untuk Semua": Pengganti karangan bunga berupa donasi untuk dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Program ini dapat dikelola transparansi oleh lembaga independen yang melibatkan unsur pengadilan, masyarakat sipil, dan akademisi.
b) Dana Beasiswa Hukum: Alokasi dana yang sebelumnya digunakan untuk karangan bunga dialihkan menjadi beasiswa bagi mahasiswa hukum berprestasi dari keluarga prasejahtera, menciptakan generasi baru praktisi hukum yang berkualitas dan berintegritas
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan imbauan untuk membatasi penerimaan karangan bunga oleh pejabat pengadilan melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Pemberian Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan.
Namun, implementasi kebijakan ini masih terkendala oleh kuatnya tradisi dan ekspektasi sosial. Diperlukan upaya sistematis untuk mengubah budaya ini, termasuk melalui penguatan aturan etika, sosialisasi nilai-nilai integritas peradilan, dan penciptaan alternatif yang lebih bermakna.
Memang mengubah budaya institusional memerlukan pendekatan jangka panjang yang komprehensif, beberapa program pada dasarnya dapat mulai dirancang untuk membangun konstruksi makna dalam simbolisme seremonial pelantikan pejabat pengadilan seperti program sosialisasi "Peradilan Bermartabat", di mana dilakukan kampanye edukasi publik tentang pentingnya menjaga independensi dan martabat peradilan, termasuk pemahaman tentang implikasi negatif dari budaya pemberian karangan bunga. Program ini dapat melibatkan media massa, institusi pendidikan hukum, dan organisasi masyarakat sipil.
Era digital juga telah membuka peluang untuk alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti
a) Platform Digital "e-Congratulations": Pengembangan platform digital resmi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat pengadilan yang baru dilantik. Platform ini dapat menjadi sarana transparansi sekaligus menciptakan budaya baru yang lebih sesuai dengan era digital
b) Visualisasi Data Donasi Pengganti: Pengembangan dashboard publik yang menampilkan jumlah donasi pengganti karangan bunga dan dampak sosialnya, menciptakan insentif sosial bagi institusi dan individu untuk beralih dari karangan bunga ke donasi bermakna.
c) Augmented Reality (AR) Floral Tributes: Sebagai alternatif futuristik, pengembangan aplikasi AR yang memungkinkan pengiriman karangan bunga virtual yang dapat dilihat oleh semua peserta acara melalui perangkat mobile atau display khusus, menghilangkan pemborosan material sekaligus mempertahankan aspek simbolik
Sebagai alternatif budaya simbolik yang memang selalu dianggap tetap penting dalam masyarakat Indonesia, beberapa alternatif yang tetap memenuhi aspek simbolik namun lebih bermakna dapat dilakukan misalnya dengan membuat program Pohon Kenangan sebagai penggantian karangan bunga dengan penanaman pohon simbolis di area pengadilan atau taman kota, menciptakan "Hutan Keadilan" yang menjadi simbol pertumbuhan dan keberlanjutan sistem peradilan. Membuat Perpustakaan Mini dengan menambah sumbangan buku-buku hukum berkualitas untuk perpustakaan pengadilan sebagai pengganti karangan bunga, juga bisa menjadi alternatif dengan meningkatkan akses terhadap pengetahuan hukum bagi para praktisi dan masyarakat umum.
Penutup
Karangan bunga dalam pelantikan pejabat pengadilan bukan sekadar ornamen seremonial. Ia adalah bagian dari praktik simbolik yang menyampaikan makna sosial tertentu dan berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap independensi peradilan. Reformasi simbolik, yakni penataan ulang budaya seremonial yang tidak sejalan dengan nilai imparsialitas, perlu menjadi bagian dari agenda pembaruan lembaga peradilan.
Analisis semiotika terhadap budaya karangan bunga dalam pelantikan pejabat pengadilan menunjukkan bagaimana praktik ini telah berevolusi dari ekspresi selamat sederhana menjadi sistem tanda kompleks yang merepresentasikan jaringan sosial dan relasi kuasa. Transformasi makna ini menciptakan mitos tentang status dan pengaruh yang dapat berimplikasi pada independensi peradilan.
Beberapa solusi yang dapat ditawarkan dari perspektif semiotika meliputi dekonstruksi mitos, rekonfigurasi sistem tanda, pembatasan semiotik, counter-signification, dan edukasi semiotik. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya menawarkan jalan keluar praktis, tetapi juga mendorong transformasi budaya yang lebih dalam terkait dengan bagaimana kita memahami dan mempraktikkan simbol-simbol dalam konteks institusi hukum.
Adapun untuk menjaga integritas dan independensi pengadilan berkaitan dengan simbolisme dalam konteks seremonial pelantikan pejabat pengadilan, diperlukan refleksi kritis terhadap praktik budaya yang telah dinormalisasi ini. Implementasi solusi semiotik merupakan langkah penting dalam reformasi peradilan yang lebih luas, dengan tujuan akhir menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, independen, dan berorientasi pada keadilan substantif.