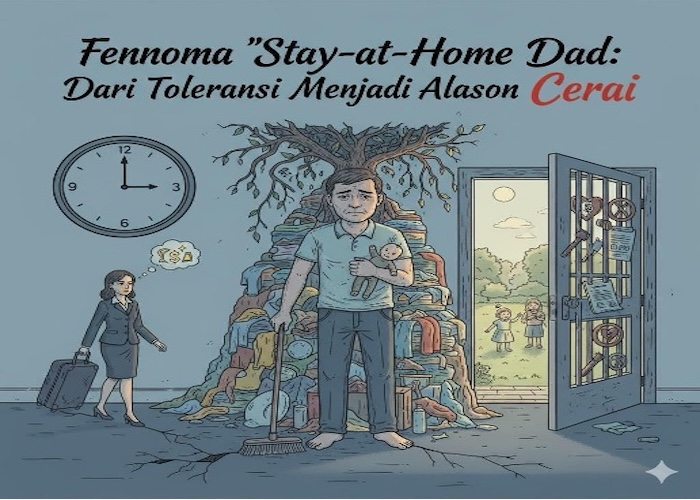Daluwarsa merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur hapusnya hak untuk menuntut atau mengajukan gugatan atas suatu hak keperdataan karena telah lewat jangka waktu tertentu.
Dengan kata lain, daluwarsa menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak menuntut maupun diperolehnya hak milik setelah waktu tertentu berlalu.
Namun demikian, timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang daluwarsa ini berlaku secara umum terhadap seluruh jenis sengketa keperdataan, termasuk dalam ranah hukum keluarga?
Tulisan ini mencoba membahas secara ringan dan reflektif mengenai masalah daluwarsa dengan pendekatan konseptual dan diskursif.
Dasar Hukum
Ketentuan mengenai daluwarsa diatur dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), dengan judul “Tentang Pembuktian dan Daluwarsa”.
Secara umum, terdapat dua macam daluwarsa yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia, yaitu:
1. Daluwarsa sebagai sarana hukum untuk memperoleh sesuatu (acquisitive prescription)
Yang dimaksud dengan daluwarsa jenis ini adalah keadaan di mana seseorang, dengan itikad baik, menguasai suatu benda tertentu selama jangka waktu tertentu, sehingga setelah lewat masa tersebut, ia memperoleh hak milik atas benda tersebut.
Berdasarkan Pasal 1963 KUH Perdata, seseorang yang menguasai suatu benda tidak bergerak, bunga, atau piutang dengan dasar penguasaan yang sah (bezit) selama 20 (dua puluh) tahun, akan memperoleh hak milik atas benda tersebut.
Sedangkan apabila penguasaan tersebut dilakukan tanpa dasar atau titel yang sah, maka hak milik baru diperoleh setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun.
2. Daluwarsa sebagai alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban (extinctive prescription)
Dalam pengertian ini, daluwarsa berfungsi sebagai pembebas dari kewajiban hukum. Artinya, apabila seseorang tidak menagih atau menuntut pelaksanaan suatu kewajiban dalam jangka waktu tertentu yaitu 30 (tiga puluh) tahun, maka pihak yang seharusnya berkewajiban tidak lagi dapat dituntut untuk melaksanakannya.
Dengan demikian, lewatnya waktu menjadi alasan hukum untuk menghapuskan hak menuntut maupun tanggung jawab perdata yang bersangkutan.
Sengketa Keperdataan
Ketika membicarakan ketentuan dalam Buku IV KUH Perdata, pembahasan akan terasa kurang lengkap tanpa menyinggung konteks sengketa keperdataan, sebab norma-norma dalam buku ini erat kaitannya dengan hukum acara perdata, yaitu perangkat hukum yang berfungsi menegakkan ketentuan hukum perdata materiil.
Secara umum, terdapat dua jenis sengketa keperdataan yang paling dikenal, yaitu:
1. Cidera Janji (Wanprestasi)
Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1246 KUH Perdata.
Akibat dari wanprestasi dapat berupa kewajiban untuk mengganti kerugian, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perikatan secara paksa.
2.Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad atau PMH)
PMH merujuk pada setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Pada awalnya, konsep “melawan hukum” dalam pasal tersebut hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis.
Namun, perkembangan doktrin dan praktik peradilan kemudian memperluas maknanya menjadi pelanggaran terhadap hukum dalam arti materiil, yaitu termasuk norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.
Di samping itu, konsep tanggung jawab dalam PMH juga tidak terbatas pada pertanggungjawaban langsung (strict liability), tetapi dapat meliputi pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), yakni tanggung jawab seseorang atas perbuatan orang lain di bawah pengawasannya.
Tentang Hukum Keluarga
Sebelum memasuki pembahasan utama, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai pengertian hukum keluarga itu sendiri.
Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga (keluarga).
Ruang lingkupnya meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, hibah, serta kewarisan.
Di Indonesia, hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua sistem utama, yaitu hukum keluarga Islam dan hukum keluarga nasional. Perbedaan pokok keduanya terletak pada sumber rujukan hukumnya, khususnya dalam hal landasan normatif di luar undang-undang.
Hukum keluarga Islam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya (Undang-Undang Perkawinan), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku I tentang Perkawinan dan Buku II tentang Waris, Wasiat, dan Hibah.
Hukum keluarga nasional, di sisi lain, mendasarkan pengaturannya pada Undang-Undang Perkawinan dan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang orang (van personenrecht).
Karena tulisan ini membahas masalah daluwarsa dalam hukum keluarga, maka pembahasannya bersifat umum dan komparatif, mencakup baik hukum keluarga Islam maupun hukum keluarga nasional.
Dengan pendekatan demikian, pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penerapan prinsip daluwarsa dalam berbagai konteks hukum keluarga di Indonesia.
Selain itu, pemaparan perbandingan antara dua sistem hukum tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap ide dan alur berpikir penulis, sekaligus menunjukkan dinamika penerapan konsep daluwarsa di dalam sistem hukum yang pluralistik.
Daluwarsa Dalam Hukum Keluarga
Alur pembahasan mengenai daluwarsa dalam hukum keluarga dapat dimulai dari aspek daluwarsa yang berkaitan dengan perolehan suatu benda, atau dengan kata lain, lewatnya waktu yang memungkinkan seseorang memperoleh hak milik atas benda tertentu.
Dalam konteks hukum keluarga, objek yang paling relevan dengan jenis daluwarsa ini adalah warisan.
1. Daluwarsa dalam Hukum Waris
Membahas soal waris memiliki nuansa tersendiri karena hukum waris tidak semata-mata berkaitan dengan kebendaan, melainkan juga dengan status dan hubungan keperdataan antarorang. Beberapa tulisan mencoba membedakan antara hak waris dan hak kepemilikan atas benda waris.
Menurut pembedaan tersebut, hak waris dianggap tidak mengenal daluwarsa, sementara hak kepemilikan atas benda waris tunduk pada ketentuan daluwarsa sebagaimana Pasal 1963 KUH Perdata.
Namun, menurut penulis, pembedaan tersebut mengandung kekeliruan konseptual. Sebab, hukum kewarisan bukan hanya mengatur tentang siapa yang berhak mewaris (siapa ahli warisnya), tetapi juga mencakup pembagian hak atas harta peninggalan (tirkah).
Dalam hukum waris Islam, tirkah justru merupakan salah satu rukun waris, di samping pewaris, ahli waris, dan harta warisan itu sendiri.
Dengan demikian, harta peninggalan tidak dapat dipisahkan dari hak mewaris, karena hak tersebut baru bermakna apabila terdapat objek warisan yang dapat dibagi.
Hal yang sama secara prinsip juga berlaku dalam hukum waris Barat (KUH Perdata), di mana hak mewaris dan hak atas benda waris saling terkait secara erat. Oleh karena itu, apabila kedua hal ini dipisahkan secara teoretis, akan muncul pertanyaan:
“Bagaimana mungkin menghitung bagian seorang ahli waris atas harta peninggalan yang secara hukum dianggap tidak dapat dibagi karena daluwarsa?”
Maka dari itu, penerapan konsep daluwarsa untuk menghapus hak atas benda waris harus dipahami secara hati-hati, sebab ia berpotensi meniadakan hak mewaris yang secara substansial melekat sejak pewaris meninggal dunia.
2. Daluwarsa dalam Kewajiban Perkawinan
Selanjutnya, bentuk daluwarsa yang kedua berkaitan dengan hapusnya hak menuntut pelaksanaan kewajiban karena lewat waktu, yang dalam hukum keluarga erat kaitannya dengan kewajiban dalam perkawinan.
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.” Ayat (3) dari pasal tersebut juga menegaskan bahwa “apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.”
Ketentuan ini oleh penulis ditafsirkan terutama berkaitan dengan kewajiban nafkah.
Dalam praktik hukum Islam di Indonesia, seorang istri yang menggugat cerai ke Pengadilan Agama dapat menuntut nafkah iddah (nafkah selama masa iddah, sekitar tiga bulan), nafkah madliyah (nafkah lampau), mut‘ah (pemberian sebagai penghormatan setelah perceraian), serta nafkah anak.
Hal serupa juga berlaku dalam perkara cerai talak (permohonan cerai oleh suami), di mana istri berhak mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) untuk menuntut nafkah-nafkah tersebut.
Namun demikian, dalam praktik peradilan agama tidak dikenal adanya ketentuan daluwarsa terhadap tuntutan nafkah, khususnya nafkah lampau.
Mahkamah Agung, melalui pedoman dalam lingkungan Kamar Agama, memberikan batasan bahwa tuntutan nafkah hanya dapat dikabulkan apabila:
- Istri tidak terbukti nusyuz (tidak durhaka atau menolak kewajiban terhadap suami); dan
- Dalam hal nafkah anak, tuntutan dapat dikabulkan selama anak secara nyata diasuh oleh ibunya.
Ketiadaan daluwarsa dalam hal tuntutan nafkah ini berpijak pada asas keadilan dan tanggung jawab moral suami terhadap keluarga.
Selama istri telah menjalankan kewajibannya (taat dan terjadi tamkin sempurna), maka menjadi adil bila suami diwajibkan memenuhi kewajiban nafkahnya, tanpa dibatasi oleh lewatnya waktu tertentu.
Selain itu, dasar normatifnya dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241, yang menegaskan: “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (diberikan) mut‘ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”
Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban pemberian nafkah dan mut‘ah tidak gugur karena waktu, melainkan merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang suami terhadap istrinya yang diceraikan.
Dengan demikian, konsep daluwarsa dalam hukum keluarga tidak dapat diberlakukan secara mutlak sebagaimana dalam hukum perdata umum, sebab hubungan hukum dalam keluarga tidak hanya berdimensi keperdataan, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan keagamaan yang bersifat terus-menerus.
Kesimpulan: Daluwarsa dalam Benturan Konsepsi
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam penerapan ketentuan daluwarsa sering terjadi benturan konsepsi antara hukum perdata umum (yang berfokus pada aspek kebendaan dan perikatan) dengan hukum keluarga (yang bersifat personal dan moral).
Kesalahan konseptual ini muncul ketika hukum keluarga diperlakukan sebagai sistem yang bekerja secara mekanis, mengikuti logika hukum perdata umum, tanpa mempertimbangkan bahwa hakikat hukum keluarga adalah hukum yang paling privat dari seluruh cabang hukum privat (hukum perdata).
Konsepsi daluwarsa dalam ranah keperdataan; seperti tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH), memang dapat digunakan sebagai kerangka berpikir analogis untuk memahami jenis sengketa dalam hukum keluarga.
Namun, penerapannya tidak dapat dilakukan secara utuh dan tekstual, sebab hubungan hukum keluarga mengandung dimensi moral, sosial, dan keagamaan yang melampaui batas-batas logika perikatan dan kebendaan.
Dengan demikian, daluwarsa dalam hukum keluarga harus dipahami bukan sekadar sebagai alat untuk menghapus hak menuntut, melainkan sebagai batas konseptual yang menegaskan perbedaan karakter antara hubungan hukum yang bersifat ekonomis dengan hubungan hukum yang bersifat personal dan kekeluargaan.
Penutup
Pada akhirnya, pembahasan mengenai daluwarsa dalam hukum keluarga bukan semata-mata persoalan teknis tentang lewatnya waktu, melainkan juga tentang bagaimana hukum memahami dinamika hubungan manusia yang penuh nilai dan rasa.
Dalam hukum keluarga, waktu tidak selalu dapat menjadi ukuran keadilan; sebab relasi keluarga dibangun atas dasar kasih, tanggung jawab, dan amanah yang bersifat berkelanjutan.
Oleh karena itu, hukum keluarga seharusnya tidak tunduk sepenuhnya pada logika kebendaan, melainkan harus memancarkan keadilan yang hidup (living justice) sebagaimana cita hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Dengan cara pandang demikian, daluwarsa tidak lagi dipahami sebagai alat pembatas, melainkan sebagai pengingat bahwa hukum harus bekerja selaras dengan hati nurani, menimbang setiap perkara keluarga bukan hanya dari hitungan tahun yang berlalu, tetapi dari keutuhan nilai yang hendak dijaga: kemaslahatan keluarga dan keadilan bagi manusia itu sendiri.