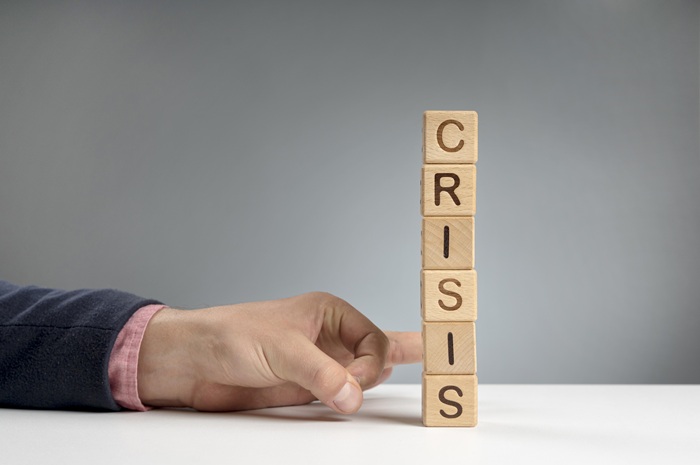Beberapa waktu lalu, ramai di media massa berita mengenai langkah TNI, yang berkonsultasi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan salah satu kreator konten, terkait pencemaran nama baik institusi.
Mengutip berita kompas.com dengan judul "Penjelasan TNI soal Rencana Laporkan Ferry Irwandi Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik", Kapuspen TNI Brigadir Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, kedatangan dia dan tiga jenderal lainnya ke Polda Metro Jaya masih dalam tahap konsultasi hukum terkait pernyataan maupun tindakan Ferry Irwandi.
"Intinya, ada dugaan pernyataannya di ruang publik, baik melalui media sosial maupun wawancara, yang berisi upaya-upaya provokatif, fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan framing untuk menciptakan persepsi dan citra negatif," ucap Freddy.
Namun, sepertinya langkah TNI yang akan melaporkan Ferry Irwandi, akan menghadapi hambatan karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXIII/2024, yang melarang instansi negara melaporkan individu, dalam kasus pencemaran nama baik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana langkah yang seharusnya ditempuh instansi negara dalam menghadapi isu serupa?
Dalam situasi seperti ini, humas pemerintahan mempunyai peran sebagai ujung tombak komunikasi organisasi, dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Humas tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi aktor utama dalam manajemen krisis.
Sejumlah pakar mendefinisikan krisis dari sudut pandang berbeda, namun semuanya menekankan dampak serius terhadap organisasi dan pentingnya penanganan strategis.
Menurut Fink (1986), manajemen krisis merupakan proses yang meliputi antisipasi, pencegahan, dan penanganan krisis, serta pemulihan setelah krisis terjadi.
Sementara itu Fearn-Banks (1996) mendefinisikan krisis sebagai “Suatu peristiwa besar dengan potensi dampak negatif yang memengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri, serta publiknya, produk, layanan, maupun reputasinya.”
Salah satu aspek terpenting dalam manajemen krisis adalah mengomunikasikan krisis. Coombs (2007) dalam Crisis Communication Theory menjelaskan bahwa manajemen krisis yang efektif memerlukan komunikasi yang strategis, transparan, dan berbasis pada informasi yang akurat,.
Hal ini diperkuat oleh Fearn-Banks (2017) yang menekankan bahwa komunikasi krisis adalah percakapan yang dilakukan organisasi dengan publik sebelum, selama, dan setelah krisis.
Dalam menangani krisis perlu memperhatikan tiga fokus utama manajemen krisis tercakup pada:
- Persiapan yang matang berarti organisasi/instansi memiliki rencana tanggap terhadap kondisi krisis informasi yang terstruktur dan dijalankan oleh tim humas yang terlatih sehingga bisa memberikan respon secara efektif serta mengurangi resiko dampak negatif terhadap kepercayaan publik.
- Respon cepat dan tanggap, organisasi/instansi segera merespon terhadap krisis informasi sehingga memungkinkan organisasi/instansi dapat memegang kendali atas narasi yang berkembang. Keterlambatan akan membuka ruang bagi penyebaran disinformasi dan memperburuk reputasi. Kemajuan teknologi informasi dan tersedianya media sosial saat ini mewajibkan organisasi merespon krisis dengan cepat untuk meminimalkan kerugian reputasi dan menjaga kepercayaan publik. karena opini publik terbentuk dalam hitungan menit.
- Evaluasi pasca krisis yaitu proses menganalisis kinerja dan efektivitas respon manajemen krisis setelah krisis mereda. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dan memperkuat rencana manajemen krisis di masa depan sehingga kepercayaan publik kembali pulih, serta terjaganya reputasi organisasi
Selain strategi komunikasi, keberadaan tim khusus menjadi faktor penentu keberhasilan manajemen krisis. Tim khusus ini sebagai pelaksana, yang akan bertindak secara langsung dalam menanggulangi krisis.
Mengutip tulisan yang berjudul “5 Peran yang Harus ada dalam Tim Krisis” (https://humasindonesia.id/berita/5-peran-yang-harus-ada-dalam-tim-krisis-2255), tim ini bertanggung jawab untuk mengelola situasi krisis secara efektif, meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan, dan mengarahkan organisasi menuju pemulihan dengan cepat.
Coombs, W. T dalam buku Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding (2019), membagi peran-peran pada tim dalam lima bagian yaitu:
1. Kepala atau Manajer Krisis
Peran ini memiliki tanggung jawab atas seluruh koordinasi dan pelaksanaan respons krisis, termasuk pengelolaan isu-isu sensitif.
2. Komunikasi Krisis
Pengisi peran ini harus spesialis komunikasi dengan pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam merancang pesan maupun strategi komunikasi yang tepat.
3. Ahli Hukum
Peran ini sangat diperlukan dalam tim krisis untuk memastikan respons organisasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, ahli hukum dapat memberikan saran terkait tanggung jawab organisasi, risiko hukum yang mungkin timbul, hingga membantu menyiapkan pernyataan resmi serta dokumen keperluan komunikasi eksternal.
4. Pimpinan Perusahaan
Pimpinan organisasi setara CEO atau direktur utama perlu dihadirkan, karena mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis dalam manajemen krisis.
5. Ahli Teknis
Dalam beberapa kasus, khususnya krisis yang diakibatkan kesalahan teknis, peran ahli teknis sangat penting untuk menjelaskan permasalahan utama, panduan, hingga penanganannya.
Kementerian Komunikasi dan Informasi, mengeluarkan buku Petunjuk Teknis Monitoring Isu dan Manajemen Krisis (2020), yang membagi anatomi krisis (tingkatan krisis) dalam empat tahap yaitu:
- Tahap Prodormal, yaitu tahap ketika krisis baru muncul dan belum mempunyai dampak yang luas pada citra institusi.
- Tahap Akut, yaitu tahap ketika persoalan muncul ke permukaan.
- Tahap Kronik, yaitu tahap ketika krisis berlalu dan menyisakan masalah akibat krisis,
- Tahap Revolusi, yaitu tahap ketika institusi harus memulihkan kekuatan agar kembali seperti semula dan dapat melanjutkan dengan normal dan lancar.
Ketika komunikasi krisis terjadi pada sebuah instansi pemerintah, pimpinan instansi tersebut harus segera melaksanakan sekurang-kurangnya lima hal utama, yaitu dengan mengaktifkan tim Manajemen Krisis dan tim Komunikasi Krisis, mengaktifkan pusat krisis, membuat laporan serta melaporkan ke pihak-pihak yang dianggap perlu mengetahui perkembangan krisis, dan mempersiapkan konten informasi yang dibutuhkan.
Selain itu perlu ditunjuk seseorang yang berkompeten, sebagai juru bicara utama dan bertanggung jawab terhadap seluruh informasi, tanggapan serta respon instansi terhadap krisis yang terjadi.
Dalam kondisi tertentu dengan kategori luar biasa yang memerlukan juru bicara dengan keahlian tertentu, pimpinan instansi dapat menunjuk juru bicara yang memiliki keahlian sesuai dengan konteks situasi krisis.
Terakhir, setelah sebuah instansi pemerintah sudah berhasil melewati krisis perlu dilakukan evaluasi pascakrisis,
Menurut Marlinda Irwanti (2023) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Krisis Komunikasi, Tinjauan Teoritis dan Praktis, evaluasi dalam manajemen komunikasi krisis berperan membantu organisasi, untuk memahami sejauh mana respons mereka dalam menghadapi krisis.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa evaluasi manajemen komunikasi krisis juga berguna untuk mengukur dampak terhadap reputasi, mengevaluasi rencana krisis, dan memberikan pelajaran berharga di kemudian hari.
Dengan demikian, manajemen krisis yang baik bukan hanya soal meredam masalah saat krisis, tetapi juga membangun ketahanan organisasi untuk menghadapi krisis di masa mendatang.