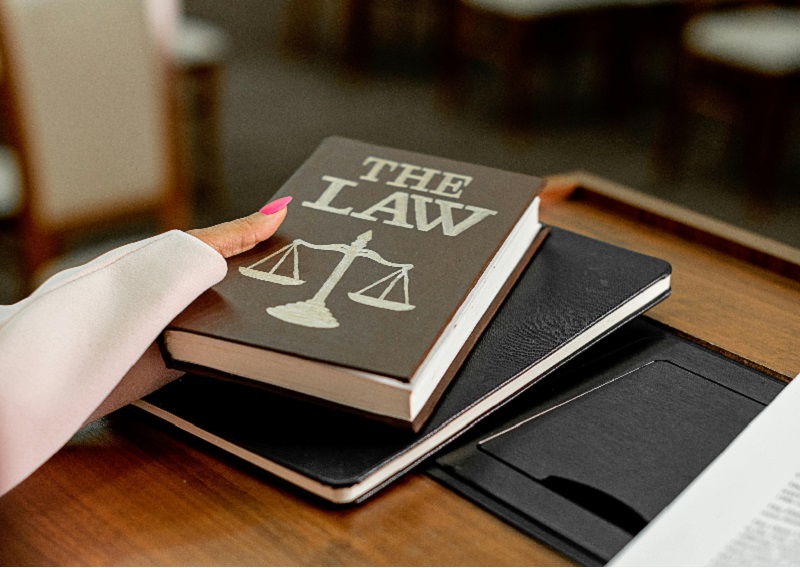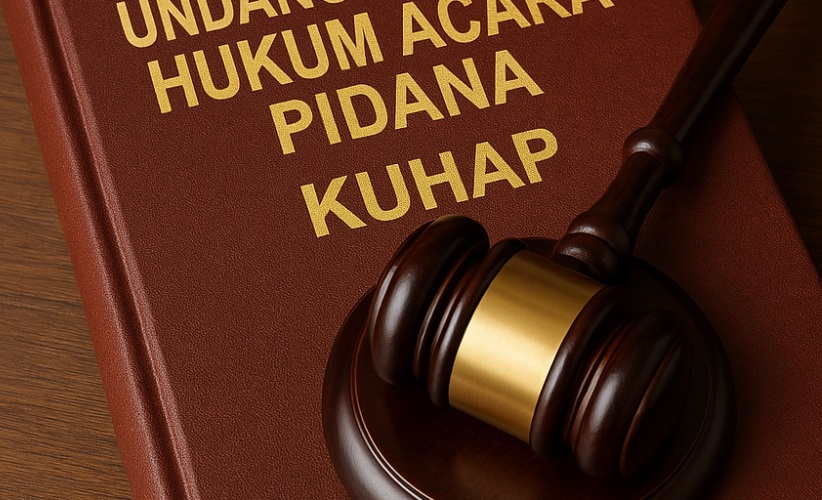Asas legalitas mensyaratkan suatu peraturan pidana sudah harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan sebelum suatu perbuatan dilakukan. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara, serta mencegah adanya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa.
Asas ini pun menyiratkan peraturan pidana itu harus tertulis, tegas dan jelas. sehingga menutup peluang dilakukan penafsiran analogi dalam penerapannya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional.
Namun Pasal 1 ayat (1) sepintas terlihat disimpangi oleh Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan kaidah terkait asas legalitas tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), yaitu hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini, berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.
Pendekatan tentang teori hukum yang hidup tidak dapat lepas dari sosiolog hukum Eugen Ehrlich, yang melihat hukum bukan sebagai suatu aturan yang berada di luar masyarakat, melainkan diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan masyarakat itu sendiri. Hukum diyakini telah ada sejak masyarakat itu ada, serta lahir dari kesadaran masyarakat akan kebutuhannya (opinion necessitates).
Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif legalistik dengan hukum yang hidup (living law). Seolah hukum yang hidup itu ada di sisi kutub yang berseberangan dengan hukum yang bercorak positivisme.
Kembali ke masa lampau sebelum Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië 1918 diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di berbagai wilayah nusantara telah lestari penerapan hukum yang bentuknya tidak terkodifikasi seperti layaknya undang-undang. keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di berbagai kerajaan nusantara menandakan bahwa telah ada hukum berlaku di masyarakat nusantara meskipun bentuk, pembuktian, dan sanksinya masih sederhana.
Sebelum KUHP Nasional disahkan, banyak pakar dari berbagai latar belakang yang mendorong agar hukum pidana Indonesia kembali ke asalnya, yakni dengan menerapkan hukum asli Indonesia yaitu hukum adat.
Gayung bersambut, secara tidak langsung pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Kemudian dengan berlakunya KUHP Nasional, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) nampak ada upaya dari pembentuk undang-undang untuk melegalisasi dan mewadahi pemberlakuan hukum adat yang tidak tertulis tetapi masih hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Jika mencermati Pasal 2 Ayat (2) KUHP Nasional, pemberlakuan hukum adat tersebut memiliki pembatasan, pertama; kaidah tentang larangan perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP Nasional, kedua; nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa beradab. Selain itu penjelasan dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, kaidah ini hanya berlaku untuk perkara-perkara ringan.
Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional mensyaratkan bahwa kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Yang mana pedoman dari peraturan pemerintah tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat di daerahnya untuk dituangkan ke dalam peraturan daerah.
Jika mencermati uraian Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional beserta penjelasannya, tampak bahwa pengaruh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional tersebut sangat mempengaruhi keberlakuan hukum adat. Pemberlakuan hukum adat di daerah harus tetap dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni peraturan daerah, yang syaratnya pun harus tertulis.
Pemberlakuan tersebut memberikan dampak positif, yakni keberlakuan hukum adat di suatu daerah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, memperjelas penegakan sanksinya, serta menjamin keberlakuan hukum adat agar tetap lestari tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
Namun, di sisi lain juga memberikan dampak negatif, yakni karakteristik hukum adat sebagai living law akan semakin dikesampingkan, yang mana hukum adat sebagai hukum hidup yang tidak terkodifikasi dan sifatnya luwes menjadi hukum yang kaku dan sulit untuk mengikuti perkembangan masyarakatnya, serta keberlakuannya tidak lagi pada tataran kesadaran masyarakat, karena akan dipaksakan penegakannya oleh aparatur penegak perda, yakni satuan Polisi Pamong Praja.
Oleh karenanya, setelah mencermati hubungan antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional, tampak hukum adat yang dulunya sebagai living law akan dijadikan sebagai hukum bercorak legalistik, yang saling menopang pemberlakuannya, karena hukum adat yang telah tumbuh dan berlaku dalam suatu masyarakat juga akan diakui keberlakuannya oleh pemerintah, dengan syarat adalah ketentuan hukum pidana adat tersebut harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang juga merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, sebagai wujud asas legalitas itu sendiri.
Dalam penerapannya hukum pidana adat tidak hanya akan menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya, namun juga dapat menjadi alasan untuk melepaskan seorang dari pertanggungjawaban pidana.