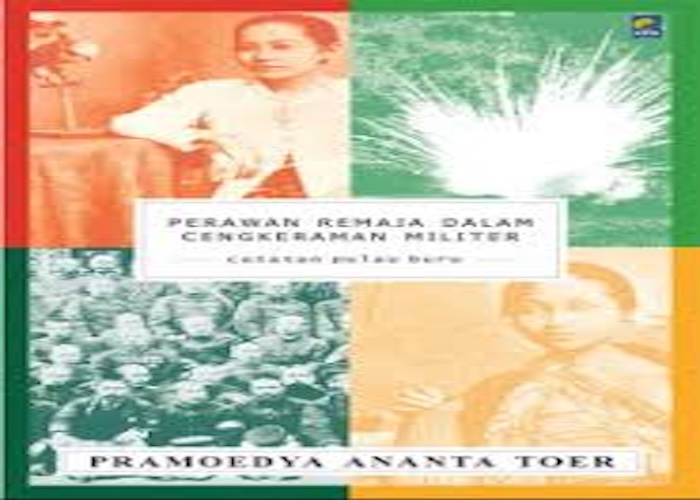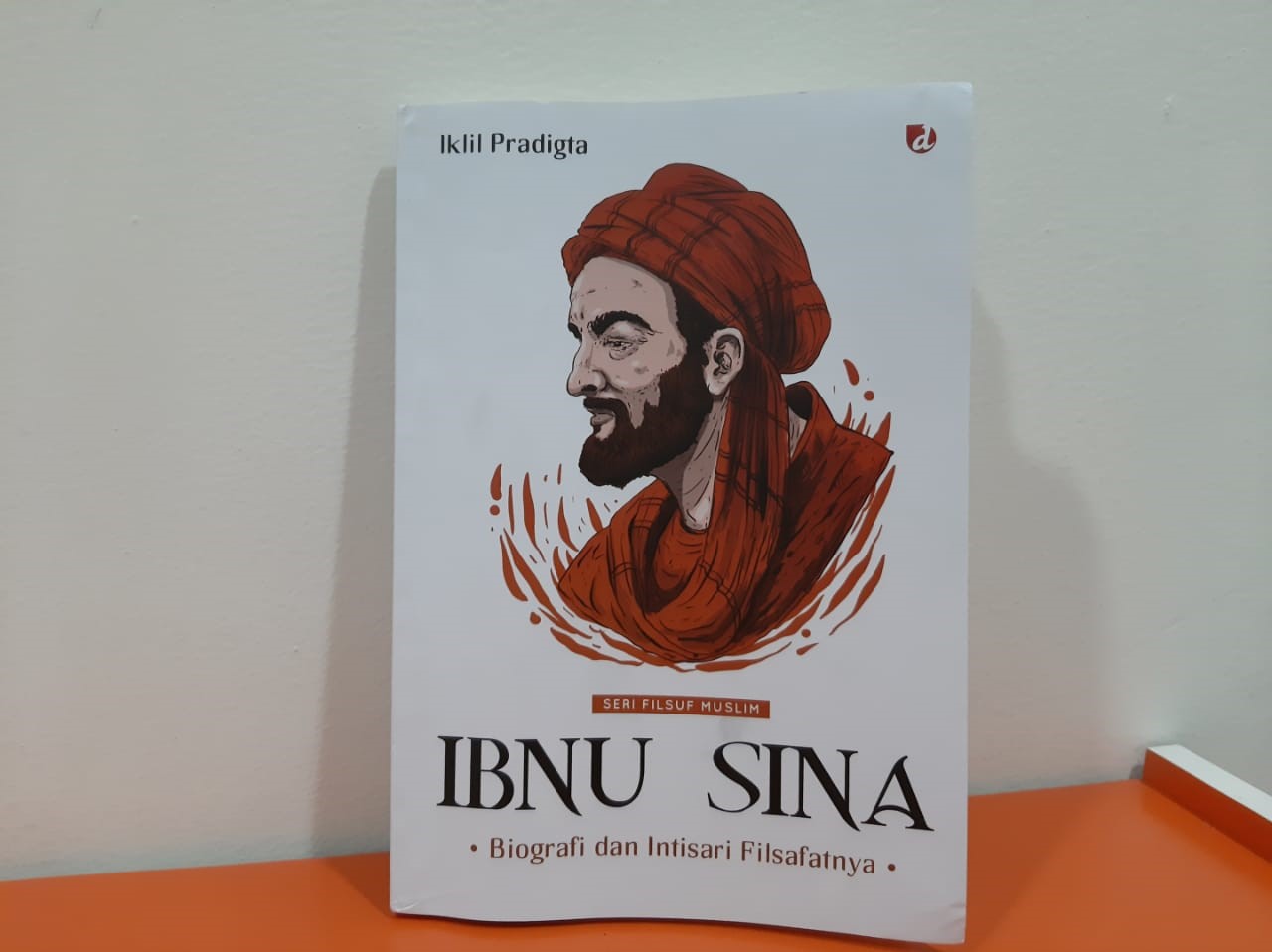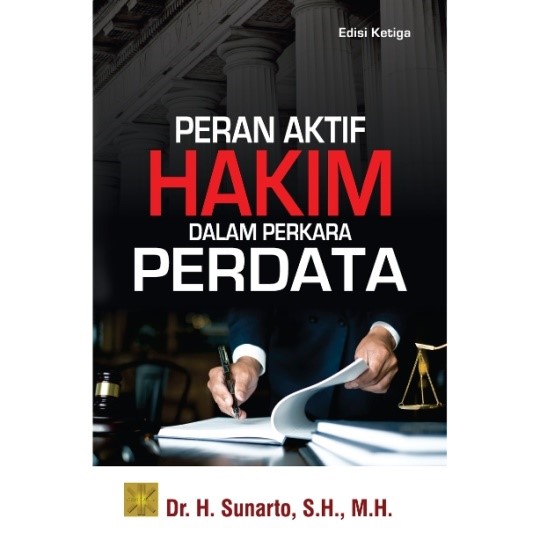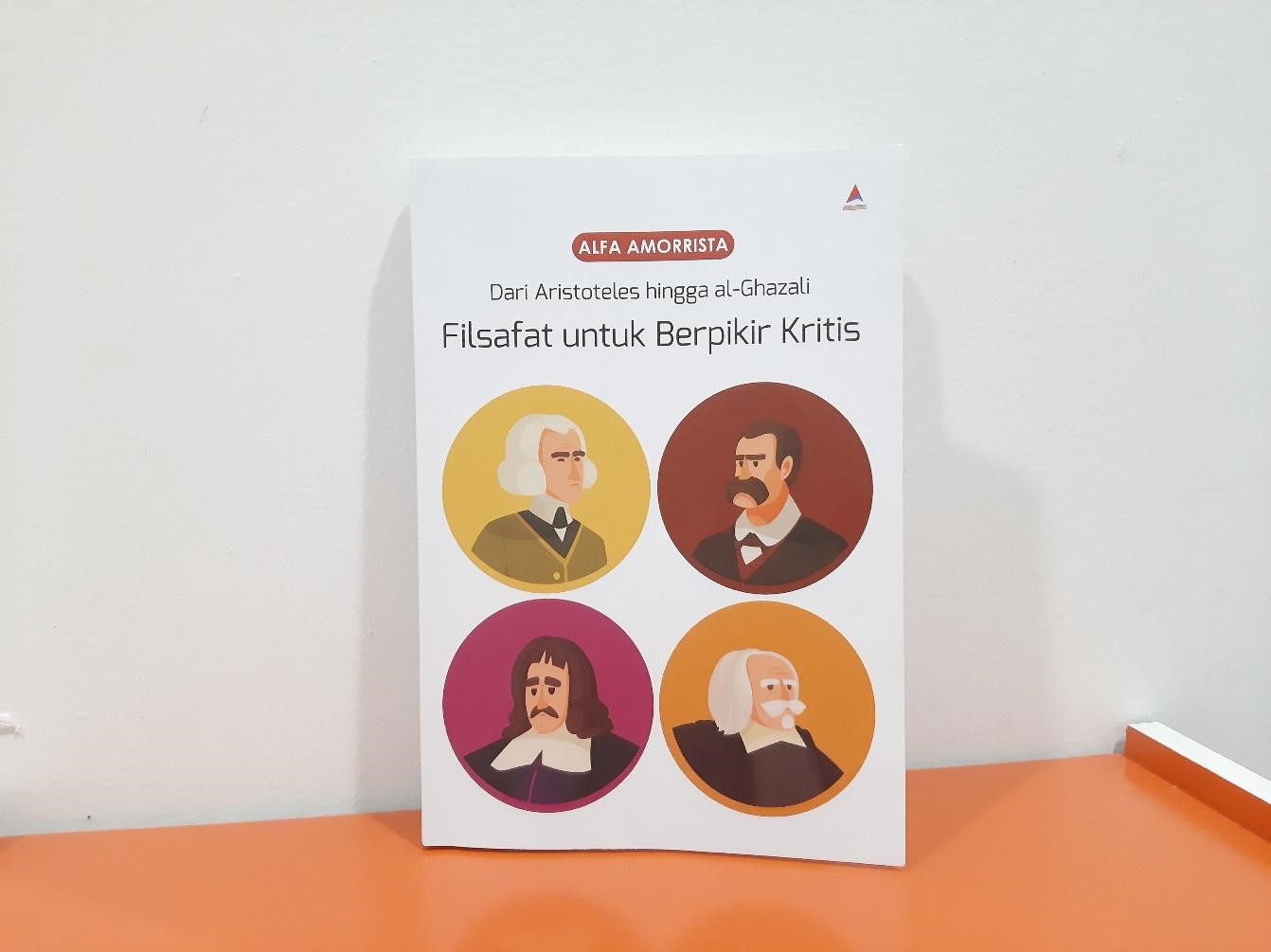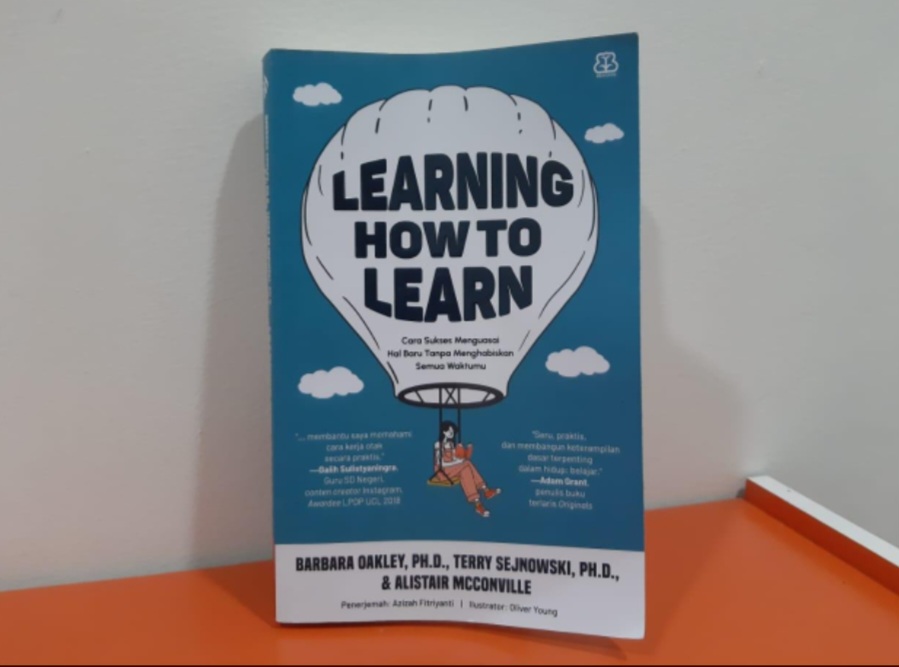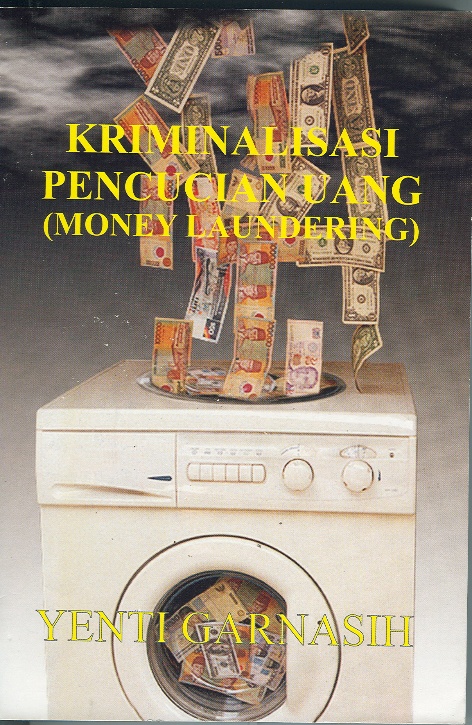Di rumah, kala malam, setiap kali semua kebutuhan anak-anak selesai kutunaikan, aku selalu mencari sedikit ruang untuk diriku sendiri.
Dalam sunyi yang tersisa, aku duduk sambil seringnya scroll media sosial, namun tidak jarang juga aku membaca.
Di rumah ini buku banyak sekali, suamiku rajin sekali belanja buku, Ia sedang membangun perpustakaan kecil, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya, atau siapa pun di sekitar rumah yang kelak ingin berteduh dalam dunia kata-kata.
Di antara tumpukan yang tak pernah habis itu, mataku terpaku pada satu nama, Pramoedya Ananta Toer. Rasa yang muncul itu seperti bertemu kekasih lama: akrab, hangat, dan sedikit menegangkan.
Judulnya Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer. Aku menghela napas, bukan karena ragu, tetapi karena aku khawatir, ini bukan buku ringan. Meski begitu, aku mengambilnya juga. Mungkin karena aku merasa punya memori baik pada belasan tahun lalu, saat aku membaca Tetralogi Pulau Buru dengan penuh gairah dan rasa kagum yang sulit dijelaskan.
Aku masih ingat betul bagaimana dulu aku jatuh cinta pada gaya berceritanya. Pilihan katanya sederhana, tetapi Pram menyusunnya dengan magis, aku khawatir niatnya dia menulis adalah untuk menyihir, sehingga membuatku tidak bisa berhenti membaca.
Alurnya mengalir seperti sungai, tenang namun menghantam. Ada bagian diriku yang selalu luluh tiap kali membaca karyanya.
Dan di antara semua hal tentang Pram, yang paling membuatku tersentuh adalah kelembutan hatinya yang jarang ditonjolkan orang. Aku masih ingat kisah yang diceritakan Buya Hamka.
Saat Pram meminta putrinya menemui Buya Hamka, ulama yang ia tuduh sebagai plagiator. Tuduhan tersebut dibantah Hamka namun tak pernah mereka bicarakan langsung. Entah itu sebuah permintaan maaf yang tak terucap atau sekadar bentuk penghormatan, Pram meminta anak perempuannya memohon kesediaan Hamka mengajarkan Islam kepada calon suaminya.
Aku melihat, ada kerendahan hati di situ, yang mungkin tak banyak orang tahu. Sejak saat itu, cintaku pada karya-karyanya Pram bukan hanya soal kata, tetapi soal kemanusiaan.
Maka tak heran jika ketika menemukan namanya lagi, di antara ribuan deret buku yang mulai memenuhi rumah, aku mengambil buku itu tanpa pikir panjang.
Seperti biasa, aku mulai dengan membuka halaman pertama. Judul babnya Ancang-Ancang. Sebuah pembuka yang ditujukan untuk para perempuan muda di masa setelahnya.
Dari kalimat pertama saja, Pram sudah menusuk: ia menceritakan bahwa pada tahun 1942–1944, ribuan gadis perawan kehilangan kehormatan mereka dengan cara yang tak pernah bisa kita bayangkan dengan tenang.
Mereka adalah perempuan baik-baik, anak-anak dengan cita-cita yang sederhana dan suci. Dibohongi dengan janji akan disekolahkan ke Tokyo atau Singapura.
Dijanjikan kesempatan mengubah nasib, memperbaiki hidup yang serba sulit saat perang menggerogoti negeri. Namun kenyataan yang menanti mereka bukanlah pendidikan—melainkan neraka. Mereka dijadikan pemuas nafsu para prajurit Jepang. Direnggut dari keluarga, dari mimpi, dari tubuh mereka sendiri.
Pram menuliskan bagaimana ia mendapat cerita itu saat menjadi tahanan politik di Pulau Buru pada tahun 1960-an. Ia bertemu para perempuan itu setelah mereka menua, setelah bertahun-tahun memikul beban yang tidak pernah mereka pilih.
Mereka sudah tampak renta ketika Pram tiba, namun kesedihan mereka tidak pernah tua. Cerita yang mereka simpan pun, seperti luka, tidak pernah sembuh.
Aku membaca kalimat demi kalimat, tapi semakin jauh aku masuk, semakin aku merasa napasku tertahan. Kekhawatiranku mewujud. Ada bagian dari diriku yang menolak melanjutkan, meski aku tahu kisah ini sejarah, dan sejarah harus dihadapi.
Namun kali ini… kali ini aku kalah. Aku cinta pada Pram, aku cinta pada keberaniannya, pada kepeduliannya terhadap perempuan. Tapi untuk pertama kalinya, aku mengubur cinta itu sementara. Bukan karena kecewa, tetapi karena aku tak sanggup menatap lebih lama penderitaan kaumku sendiri.
Aku tak kuasa membayangkan perempuan-perempuan itu. Aku tak kuasa melihat bagaimana cita-cita mereka dikubur hidup-hidup oleh kebiadaban perang. Dan aku tak kuasa membayangkan bahwa mereka pernah percaya bahwa dunia akan berubah menjadi lebih baik melalui pendidikan, tetapi justru dijebak oleh tangan-tangan yang merusakkan martabat manusia.
Air mataku meleleh. Bulu kudukku berdiri. Hatiku terasa diremas dari dalam. Ada duka yang muncul bukan hanya dari kisah mereka, tetapi dari kenyataan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan terus berulang, dalam bentuk yang mungkin berbeda, namun dengan luka yang serupa.
Astaghfirullah
Aku menutup buku itu pelan-pelan. Tidak untuk meninggalkannya, tetapi karena aku butuh jeda untuk menghormati cerita mereka dan tentu saja untuk menenangkan diriku sendiri.