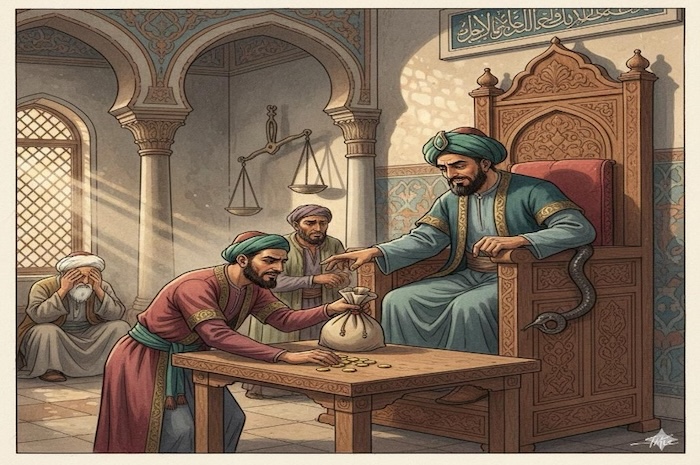GoodStats dan Indonesia Corruption Watch (ICW), merilis data adanya 791 kasus korupsi di Indonesia, pada 2023, dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang.
Sementara itu, data Kejaksaan Agung menunjukkan periode 2011 hingga 2015, tingkat pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme uang pengganti hanya berada di bawah 28 persen.
Kondisi ini, menggambarkan mekanisme penyelesaian perkara korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara, masih dinilai belum efektif dan efisien.
Atas dasar itu, diperlukan alternatif kebijakan yang lebih tepat, salah satunya dengan mempertimbangkan penerapan prinsip Deferred Prosecution Agreement, sebagaimana telah diimplementasikan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris.
Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan merupakan suatu kesepakatan antara jaksa dengan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, khususnya korporasi, untuk menangguhkan proses penuntutan resmi selama syarat-syarat tertentu dipenuhi.
Persyaratan tersebut, dapat berupa kerja sama dalam proses investigasi, pembayaran denda, maupun pelaksanaan perbaikan internal perusahaan.
Mekanisme ini, bertujuan mempercepat dan mengefisienkan penyelesaian perkara, sekaligus mengurangi risiko kerugian lain, seperti kebangkrutan korporasi, dengan tetap mengedepankan pemulihan kerugian negara.
Walaupun demikian, perlu dipahami pelaksanaan DPA tidaklah seragam dan bervariasi antarnegara.
Di Amerika Serikat, DPA dapat diterapkan apabila korporasi mengakui adanya tindak pidana, menyatakan kesediaan untuk bekerja sama, serta menyepakati jangka waktu tertentu disertai kewajiban pembayaran sejumlah dana atau pelaksanaan kewajiban non-finansial.
Jenis sanksi yang lazim dikenakan mencakup restitusi, denda, hukuman bersyarat, penunjukan pihak pengawas, hingga pembebasan tanggung jawab individu tertentu.
Namun, dalam hal pengawasan yudisial, ruang lingkupnya terbatas. Hakim hanya berperan menerima DPA yang diajukan, tanpa kewenangan untuk memeriksa secara substantif atau melakukan sidang yudisial penuh (hearing judicial).
Sementara di Inggris, DPA dipandang sebagai bentuk pidana bersyarat bagi korporasi, yang harus melalui beberapa tahapan.
Tahap awal berupa negosiasi, di mana perusahaan mengakui adanya tindak pidana, serta menyepakati kewajiban tertentu dan berlaku hingga jangka waktu yang ditentukan.
Kemudian, tahap persetujuan dilakukan melalui penilaian pengadilan atau crown court untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, rasionalitas, dan proporsionalitas.
Pada tahap akhir, yaitu pelaksanaan, jaksa berwenang meminta pengadilan melakukan penilaian kembali, serta melanjutkan penuntutan apabila perusahaan gagal memenuhi komitmen yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
Dari uraian tersebut, tampak keterlibatan Hakim dalam mekanisme DPA di Inggris, yang lebih dominan dibandingkan di Amerika Serikat, sehingga menimbulkan perbedaan cukup signifikan dalam praktik penerapannya di kedua negara.
Kendati demikian, penting dicatat DPA lahir dan berkembang di negara-negara dengan tradisi common law, sementara Indonesia menganut sistem civil law.
Hal ini, menimbulkan pertanyaan apakah penerapan DPA, benar-benar mendesak dan relevan untuk diadopsi dalam konteks hukum Indonesia.
Mekanisme DPA tidak lepas dari sorotan kritis. David M. Uhlmann menilai penerapan DPA berpotensi menimbulkan erosion of corporate criminal liability atau pengikisan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Menurutnya, DPA dapat melemahkan supremasi hukum, karena membatasi fungsi hukuman yang bersifat represif, sekaligus mengurangi efek jera dari penegakan hukum.
Pandangan ini, didasarkan kasus di Amerika Serikat, yang melibatkan jaksa dengan perusahaan tambang Massey Energy.
Melalui DPA, perusahaan tersebut berhasil menghindari tuntutan pidana atas lebih dari 300 pelanggaran hukum, termasuk sembilan pelanggaran serius yang memicu ledakan besar, pada 25 April 2010 dan menewaskan 29 pekerja.
Walaupun konsep DPA berakar dari Amerika Serikat dan Inggris, yang menganut sistem common law, penerapannya tidak tertutup kemungkinan di Indonesia.
Hal ini, disebabkan sistem hukum Indonesia meskipun berbasis civil law, dalam praktiknya telah mengadopsi sejumlah prinsip dari tradisi common law.
Fenomena ini menunjukkan adanya konvergensi hukum, di mana berbagai negara saling meminjam dan mengadaptasi konsep dari sistem hukum lain.
Contohnya, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memasukkan prinsip fidusia dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang keduanya berasal dari praktik common law.
Maka, secara implisit Indonesia menunjukkan keterbukaan terhadap konsep tersebut, sehingga membuka peluang bagi penerapan DPA dalam penanganan perkara korupsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemulihan kerugian negara.
Dalam rangka penerapan DPA di Indonesia, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya penetapan batasan kewenangan DPA, yang wajib disertai mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban yang jelas.
Selain itu, dibutuhkan landasan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang komprehensif, termasuk pengaturan mengenai standar etika yang wajib dipatuhi aparat penegak hukum, beserta sanksi atas setiap pelanggaran dalam proses pelaksanaannya.
Hal ini menjadi penting mengingat sistem yang ada saat ini dinilai belum cukup kompleks untuk mengakomodasi mekanisme tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dari semua pihak terkait, termasuk dimensi etisnya, agar implementasi DPA dapat dikelola secara efektif.
Selain itu, aspek krusial yang harus diputuskan adalah mengenai subjek penerapan (DPA), apakah mekanisme ini berlaku bagi korporasi sekaligus individu, atau hanya terbatas pada korporasi.
Perdebatan ini, muncul karena adanya perbedaan praktik antara Amerika Serikat dan Inggris.
Maka, kajian yang mendalam dan menyeluruh sangat dibutuhkan, dengan mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing opsi.
Dengan demikian, Indonesia dapat merancang mekanisme DPA yang lebih berkualitas, terstruktur, detail, serta mampu berjalan secara efektif dan efisien.
Di sisi lain, dalam konteks penyelesaian perkara secara non-litigasi, karakteristik sistem peradilan Inggris dinilai lebih relevan untuk dijadikan acuan bagi Indonesia.
Hal itu mengingat di dalamnya terkandung berbagai instrumen, antara lain sanksi finansial, pemberian kompensasi kepada korban yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud restorative justice, donasi, pengembalian keuntungan hasil tindak pidana, program kepatuhan, kerja sama dalam proses investigasi melalui peran justice collaborator, pembayaran biaya, dan bentuk kewajiban lainnya.
Diharapkan, apabila mekanisme ini diterapkan, wujudnya mampu menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan manfaat nyata bagi pemulihan kerugian negara.
Bahwa DPA berpotensi jadi salah satu instrumen hukum dalam mempercepat, mengefisienkan, serta meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.
Meskipun, penerapannya tidak luput dari kritik maupun keterbatasan. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif, sehingga dapat terbentuk mekanisme DPA yang ideal di Indonesia.
Dengan desain yang tepat, diharapkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat berlangsung lebih optimal, adil, dan efisien.