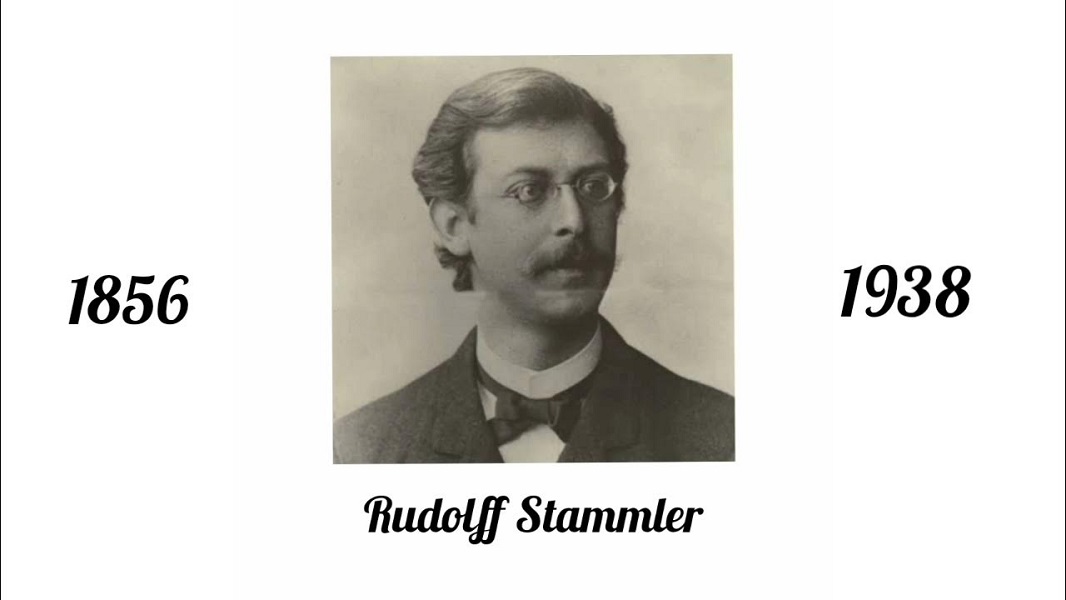filsafat hukum menjadi lentera bagi hakim yang menyinari ruang kosong ketika teks tidak memberi jawaban. Tanpa lentera itu, putusan akan kering seperti batu, dengan lentera itu, putusan lahir sebagai karya sadar antara akal, empati, dan integritas.
Kata "filsafat" berasal dari Bahasa Yunani, philosophia artinya ("cinta pada kebijaksanaan").
Para ahli filsafat seperti Radbruch, Stammler, Kant, sampai Roscoe Pound, mereka semua sepakat bahwa Hukum itu harus mempunyai hati.
Filsafat Hukum itu bukan teori yang sulit, tapi perjalanan pribadi kita yang membuat faham mengapa kita harus patuh?
Karena interaksi hukum dengan denyut nadi kehidupan nyata harus sederhana, namun mendalam, ia harus menjadi "jantung yang berdetak untuk keadilan," yang berarti hukum berfungsi sebagai pelayan untuk merangkul dan membela martabat setiap manusia, bukan menjadi "rantai yang membelenggu" melalui formalitas dan kerumitan yang kaku.
Inti dari Filsafat Hukum, yang diserukan dalam pelatihan hakim oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) MA, melampaui sekadar 'mengetok palu' atau kepastian teks (positivisme).
Ia menuntut keadilan substantif yang dipikirkan dengan penuh kebijaksanaan (epikeia), direnungi dengan empati, dan dipahami dengan kejernihan untuk melihat jiwa di balik aturan.
Hukum yang ideal harus menyeimbangkan tiga pilar (Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan) demi memastikan, setiap pasal dan keputusan lahir dari niat untuk memanusiakan keadilan bagi semua orang tanpa kecuali.
Karena begitu pentingnya Filsafat Hukum, maka Pustrajak Kumdil, sebagai lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan filsafat hukum yang diikuti 436 hakim.
Di sana, para hakim diberi pemahaman yang tajam, keadilan tidak cukup diputus, ia harus dipikirkan, direnungi, dan dipahami dengan jernih.
Setiap ketukan palu yang tampak sederhana ternyata lahir dari perjalanan batin yang panjang, dari pertemuan antara teks hukum, realitas manusia, dan kebatinan seorang hakim.
Karena itu, pelatihan filsafat hukum bagi hakim di Pustrajak Kumdil MA, bukan sebagai teori yang melambung cukup tinggi, tetapi sebagai kompas yang menuntun mereka agar tidak hanya mahir membaca teks undang undang, tetapi juga peka membaca perasaan, konteks, dan martabat para pencari keadilan.
Itulah mengapa filsafat hukum menjadi lentera yang menyinari ruang kosong ketika teks tidak memberi jawaban. Tanpa lentera itu, putusan akan kering seperti batu, dengan lentera itu, putusan lahir sebagai karya sadar antara akal, empati, dan integritas.
Filsafat Hukum sebagai Kompas Moral dalam Memutus Perkara
Filsafat hukum bekerja seperti Kompas dalam membantu hakim memutus perkara dengan lebih bijak, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan yang lebih dalam dari sekadar teks hukum.
Ia tidak memaksa hakim memilih arah, tetapi memastikan arah itu tidak salah, membantu hakim memutus perkara dengan lebih bijak, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan yang lebih dalam dari sekadar teks hukum.
Di tengah tumpukan berkas, tekanan waktu, dan ekspektasi para pihak, hakim mudah tergelincir pada rutinitas: memeriksa, menimbang, memutus. Namun, kompas filsafat mengingatkan, setiap perkara adalah manusia, bukan nomor register.
Ia menuntun hakim untuk tidak terburu-buru merasa paham, tetapi berani bertanya: apa nilai yang ingin dilindungi? Siapa yang akan paling terdampak? Apakah putusan ini membawa keadilan atau sekadar kepastian?
Dengan cara itu, filsafat hukum bukan hanya ilmu; ia adalah penjaga langkah agar hakim tetap setia pada nurani, meski jalur hukum sering kali berliku dan menantang.
Dari Pasal ke Makna: Menyelami Hakikat Keadilan di Balik Teks
Pasal-pasal itu tampak tegas di atas kertas, tetapi hidup jauh lebih cair dari yang tertulis.
Di hadapan hakim, sering muncul perkara yang tidak sepenuhnya cocok dengan batas rumusan undang-undang.
Ada orang tua yang datang dengan mata sembab, ada anak yang hanya menunduk, ada suami-istri yang kelelahan oleh konflik bertahun-tahun.
Situasi seperti itu tidak bisa dibaca hanya lewat frasa “menimbang” dalam teks putusan. Di titik itulah filsafat hukum memberi ruang bernapas.
Ia membantu hakim melihat, tujuan hukum tidak berhenti pada kata-kata, tetapi pada nilai yang ingin dijaga keselamatan, kehormatan, dan kemaslahatan manusia.
Terkadang tafsir pasal harus menemukan jalannya melalui empati dan akal sehat. Bukan untuk meninggalkan aturan, tetapi untuk memastikan aturan itu tidak kehilangan jiwanya.
Ketika Pengalaman Bertemu Nalar: Ruang Hening yang Dibutuhkan Hakim
Filsafat hukum memasuki ruang-ruang hening itulah bukan untuk mengganti undang-undang, tetapi untuk membantu hakim membaca nilai yang tersembunyi di balik ketentuan yang belum lengkap.
Ini adalah wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh nalar yang terlatih untuk bertanya lebih dalam daripada sekadar apa aturannya, melainkan untuk apa aturan itu dibuat.
Kadang, sebelum hakim memutus perkara, ada detik-detik ganjil yang tidak pernah muncul dalam berita atau putusan.
Detik ketika berkas sudah dibaca, para pihak sudah didengar, tetapi hati masih belum bulat juga.
Di momen seperti itu, pengalaman lama sering muncul tanpa diundang kasus yang pernah ditangani, ucapan seorang saksi yang dahulu membuat dada terasa sesak, bahkan nasihat guru yang entah kenapa masih melekat.
Filsafat hukum masuk dari celah-celah kecil semacam itu. Bukan sebagai teori yang harus dihapal, tapi sebagai pengingat, keputusan tidak selalu selesai dengan logika.
Ada nilai yang harus dipijak, ada martabat manusia yang harus dijaga. Hakim mungkin tidak menyadari kapan persisnya ia berpikir secara filosofis, bisa saja saat perjalanan pulang, atau waktu melihat wajah anak di rumah, atau ketika tiba-tiba teringat, putusannya akan menentukan masa depan seseorang.
Yang jelas, filsafat membantu hakim menata ulang batin, jangan tergesa-gesa menganggap paham, jangan merasa paling benar, dan jangan biarkan teks menjadi tembok yang menutupi jeritan para pihak.
Ia menuntun diam-diam, seperti suara kecil yang berkata, “Coba lihatlah sekali lagi. Mungkin ada yang terlewat.”
Urgensi Filsafat Hukum bagi Hakim, Mengapa Ia Muncul dan Menjadi Kebutuhan Mendesak?
Filsafat hukum muncul sebagai kebutuhan mendesak bagi hakim, bukan karena ia sekadar wacana akademik yang indah, tetapi karena realitas hukum hari ini terlalu cepat berubah, terlalu kompleks, dan terlalu sarat nilai untuk hanya diselesaikan dengan teks dan prosedur.
Ketika perkara datang ke meja hijau, hakim tidak hanya diminta membaca aturan, tetapi membaca jiwa dari aturan itu.
Di titik inilah filsafat hukum menjadi lentera menerangi ruang yang tidak tersentuh oleh pasal, tetapi menentukan arah keadilan. Tanpa filsafat, hukum bisa kering, kaku, dan berjarak dari kemanusiaan.
Namun dengan filsafat, hakim memiliki kompas batin untuk menyeimbangkan tiga hal yang selalu bertarung di ruang sidang kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
Di tengah derasnya arus teknologi, krisis moral, tekanan publik, dan viralitas media sosial, filsafat hukum memberi hakim kemampuan paling esensial untuk berpikir jernih, mendalam, dan bijaksana.
Ibn Rushd (Averroes) menegaskan, penafsiran terhadap teks hukum tidak boleh berhenti pada literalitas.
Ia menulis, “ketika teks tampak sempit, akal yang sehat wajib bekerja untuk menangkap makna yang lebih luas.”
Prinsip ta’wil dalam pemikiran Ibn Rushd justru menjadi kekuatan hakim tidak sekadar membaca kata, tetapi membaca realitas.
Urgensi Filsafat Hukum: Kompas Navigasi Bagi Hakim Indonesia
Peran hakim dalam peradilan Indonesia adalah sebagai penjaga marwah hukum.
Ini lebih dari sekadar tandatangan untuk penutupan. Setiap putusan meninggalkan warisan.
Inilah alasan mengapa Filsafat Hukum tidak sekadar menjadi mata pelajaran di meja belajar.
Ini telah menjadi kompas moral yang sangat penting di meja hakim. Mengapa demikian?
Karena kenyataannya, seorang hakim tidak pernah dihadapkan pada pasal hukum yang tertulis rapi saja. Mereka dihadapkan pada kehidupan yang kacau.
Hukum adalah peta dasar, tetapi makna terdalam dari keadilan sering kali terletak di luar teks tertulis. Di dalam celah-celah inilah filsafat hukum memainkan peranannya, memberikan arahan kepada hakim untuk melihat alternatif ketika sebuah kasus tidak menawarkan jawaban yang siap pakai dan instan.
Hakim bukan sekadar legistik. Mereka adalah arsitek keadilan yang menyeimbangkan fakta, moralitas, dan tujuan mulia hukum.
Tanpa dasar yang reflektif, sebuah putusan pasti akan menjadi tindakan dingin, tanpa jiwa, mekanis, prosedural, dan repetitif dari keputusan birokrasi yang tidak pribadi.
Tapi, dengan filsafat di tangan, seorang hakim menantang hukum alam, menghidupkan hukum dan menjamin, keadilan bukanlah keadilan 'legal', tetapi keadilan kemanusiaan yang holistik, memberikan keadilan bagi para litigasi yang mencari perlindungan hukum di ruang kosong ketika sebuah ketentuan diam, Nilai Berbicara Hukum positif tidak akan pernah sempurna.
Pasti ada keadaan unik, apa yang penulis sebut sebagai 'ruang kosong', di mana teks tertulis dari aturan gagal memberikan jawaban.
Penutup
Sebagai pelatihan dalam tulisan ini, ingin menegaskan Kembali, filsafat hukum pada intinya adalah waktu yang diberikan kepada para hakim untuk mengambil nafas, menenangkan pikiran, dan mengingat kembali hal paling fundamental, setiap putusan yang mereka buat, jauh dari sekadar merangkai pasal-pasal, adalah perjumpaan mendalam antara logika hukum yang formal dengan realita hidup manusia yang penuh warna.
Di tengah tumpukan perkara yang menekan, tatapan penuh harap para pencari keadilan, dan kompleksitas dunia yang terus bergerak, filsafat hukum hadir sebagai pemandu yang menuntut hakim untuk selalu berpijak pada kejernihan pikiran, ia mengajarkan untuk melihat melampaui teks saat undang-undang diam, mendengar dengan kepekaan saat prosedur terasa kaku, dan memutus dengan kebijaksanaan sejati.
Sehingga, hakim tidak hanya menegakkan aturan, melainkan menjaga dan memuliakan martabat manusia yang dipertaruhkan, dan di situlah keadilan menemukan maknanya yang paling murni.
Sumber bacaan
Gustav Radbruch, Legal Philosophy. Oxford University Press, 1950.
Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. Dar al-Fikr, t.t.
Rudolf Stammler, The Theory of Justice. New York: The Lawbook Exchange, 2002.
Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
MariNews (29/11)