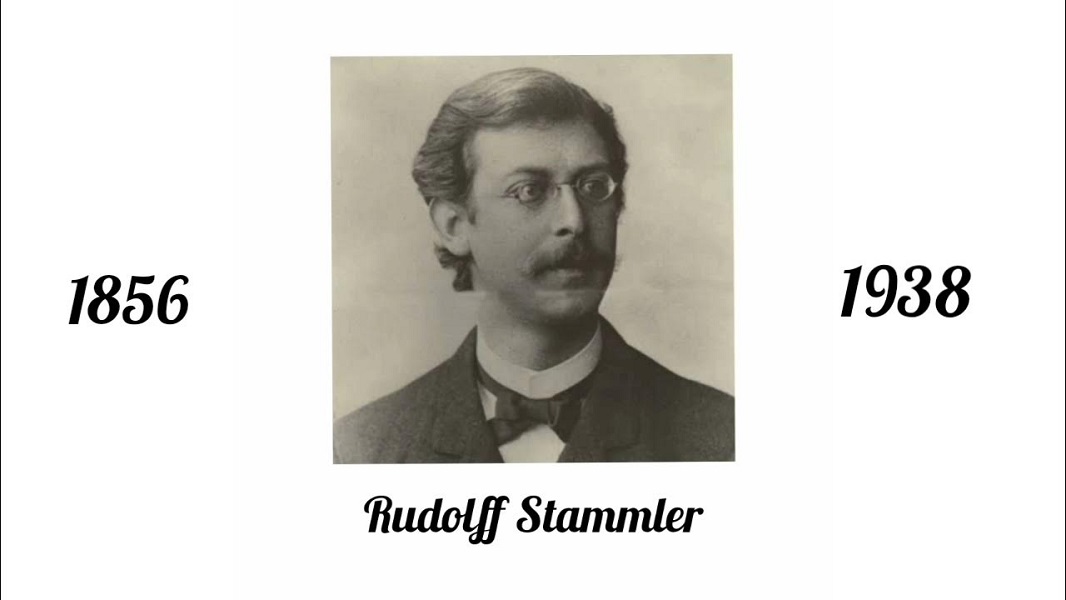“In the world of knowledge, the idea of the Good appears last of all, and is seen only with an effort; but when seen, it is inferred to be the cause of all that is right and beautiful.” – Plato (The Republic).
Pemikir dan peletak dasar filsafat dan pengetahuan Barat, Aristokles, atau yang lebih dikenal dengan nama “Plato”, meletakkan satu syarat sebelum dapat bergabung ke Akademia, sekolah yang didirikannya (Britannica, 2025).
Siapapun, menurut Plato, “ageometretos mēdeis eisitō” (tidak akan sampai ke filsafat bila tidak melewati geometri) (Proclus, 1992). Plato sendiri masih merupakan kerabat Solon, begawan ilmu hukum di Athena pada masa Yunani Klasik.
Tumbuh dalam keluarga bangsawan yang mengedepankan rasionalitas, Plato percaya bahwa sikap mental yang tepat adalah yang dapat mengabstraksikan yang riil. “Geometry is knowledge of the eternally existent, not of something that comes to be and passes away” (Geometri adalah pengetahuan tentang yang tidak akan pernah usang, bukan tentang sesuatu yang hanya datang dan pergi), ujarnya dalam karya seminalnya, Politeia (Plato, 527b). Tuntutan Plato ini sebenarnya dapat dipahami karena memang filsafatnya menekankan tentang eidos, kesunyataan.
Eidē (bentuk jamaknya) adalah realitas yang paling nyata (ta ontōs onta), dan kehadirannya hanya bisa dikenali dengan akal budi (noēsis). Geometri adalah tahapan ketiga (dianoia) dari empat tahapan mengetahui dalam pemikiran Plato, dari yang paling rendah ke paling tinggi: eikasia, pistis, dianoia, dan noēsis.
Plato tidak sedang memutlakkan matematika sebagai inti segala pengetahuan. Plato hanya ingin memastikan bahwa berfilsafat mulai dengan akal budi, dan bukan dengan impuls-impuls seperti kesan atau perasaan, sebagaimana reaksi spontan atas gambar di media sosial (eikasia) membangkitkan nuansa emosional (pistis) atas sebuah tayangan umpan, klik semu yang sebenarnya tidak pernah ada. Bagi Plato, siapapun yang bersikap eikastik dan pistik tidak akan mampu dan siap untuk berfilsafat.
Gerbang dan Pagar Dianoetik Berfilsafat Hukum
“Undangan” bagi setiap orang untuk berfilsafat mulai disebarluaskan setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Berfilsafat dianggap bukan lagi monopoli wilayah elitis yang hanya dibahas di menara gading oleh sekelompok akademisi.
Seiring dengan tumbangnya “rezim kebenaran”, lokus dari filsafat dicoba untuk dikembalikan ke rumah-rumah, tidak jauh berbeda dengan “citizen journalism”, saat berita tidak lagi dimonopoli oleh otoritas professional seperti wartawan.
Filsuf Perancis Gilles Deleuze dan Felix Guattari mengatakan bahwa “Philosophy is the art of forming, inventing, and fabricating concepts” (Filsafat adalah seni membuat, mengembangkan, dan memfabrikasi konsep-konsep) (Deuleze & Guattari, 1994:2).
Bila dibaca sekilas “kartu undangan” yang diberikan oleh Deleuze dan Guattari ini seolah memperkuat anggapan bahwa filsafat adalah permainan silat kata yang dibuat-buat untuk keperluan pribadi. Siapapun dapat dengan leluasa mengembangkan kosa kata, tanpa ada pagar atau rambu dan batasan. Filsafat menjadi sangat keotik: sebuah permainan ilusoris yang nir-fungsional.
Untuk tidak terjebak ke dalam labirin peyoratif dari ekses pembacaan filsafat yang terlalu superfisial semacam itu, kita dapat meminjam pagar-pagar yang diberikan filsuf Inggris Thomas Nagel. Pertama, “Is it a meaningful possibility that the inside of your mind is the only thing that exists-or that even if there is a world outside your mind, it is totally unlike what you believe it to be?” (Apakah merupakan kemungkinan yang bermakna bahwa isi pikiran manusia adalah satu-satunya hal yang benar-benar ada, atau bahwa sekalipun ada dunia di luar pikiran, dunia itu sama sekali tidak seperti yang diyakini oleh manusia?).
Selanjutnya, “If these things are possible, do you have any way of proving to yourself that they are not actually true?” (Jika hal-hal ini mungkin benar, adakah cara bagi manusia untuk membuktikan kepada dirinya bahwa semua itu tidak benar-benar terjadi?”).
Terakhir, “If you can't prove that anything exists outside your own mind, is it all right to go on believing in the external world anyway?” (Jika kamu tidak dapat membuktikan bahwa ada sesuatu di luar pikiranmu sendiri, bolehkah kamu tetap percaya pada keberadaan dunia luar?) (Nagel, 1987:18).
Ketiga pagar yang diberikan Nagel dapat disederhanakan sebagai berikut: (1) apakah pernyataan filosofis kita solipsistik (hanya untuk kita sendiri), (2) apakah kita sanggup membuktikan kebenarannya, dan terakhir, (3) jika kita sulit membuktikannya, sejauh mana kita masih mungkin meyakininya.
Dalam tulisannya yang lain, The View from Nowhere, Thomas Nagel mencoba untuk memberi catatan bahwa salah satu hambatan terbesar bagi manusia dalam upayanya untuk menemukan kebenaran sejati (Nagel menyebutnya “objective reality”) adalah dirinya: “the very idea of objective reality guarantees that such a picture will not comprehend everything; we ourselves are the first obstacles to such an ambition” (Gagasan tentang realitas objektif itu sendiri menjamin bahwa gambaran semacam itu tidak akan mampu mencakup segalanya; manusia sendirilah rintangan pertama bagi ambisi semacam itu) (Nagel, 1986:13).
Dengan kata lain, persoalan terbesar bagi manusia untuk bisa berfilsafat adalah ketidaktertibannya dalam berpikir, atau dalam istilah Plato, berpikir eikastik dan pistik.
Filsuf Inggris Bertrand Russell mencoba mempertegas Kembali gagasan Plato tentang dianoia sebagai prasyarat berfilsafat dengan mencoba membangun teori matematika yang sepenuhnya dibangun lewat logika, bukan dengan sekadar opini (doxa) (Russell, 1963).
Tidak Ada Hukum tanpa Filsafat dan Upaya Berfilsafat
Filsuf hukum Ronald Dworkin menegaskannya pentingnya untuk berpikir jernih dalam memahami dan menafsirkan hukum (Dworkin, 1986:52-55).
Selain Dworkin, bertolak dari pemikiran Gustav Radbruch, hukum sangat kompleks dan multidimensional, dan tantangan terberatnya adalah untuk menyesuaikannya dengan persoalan jaman yang terus berubah. Saat ilmu hukum (legal science) membentur dinding, tugasnya diambil alih oleh filsafat hukum (philosophy of law) agar hukum dapat terus relevan dan berfungsi bagi masyarakat.
Dengan kata lain, hukum positif dimulai dari ilmu hukum, dan ilmu hukum dibangun di atas fondasi filsafat hukum (Adachi, 2023:2920-2924). Lon Fuller juga mencatat peran sentral pemikiran filosofis dalam hukum: “law is a purposeful enterprise that it displays structural constancies which the legal theorist can discover and treat as uniformities in the factually given” (hukum merupakan suatu usaha yang berorientasi tujuan, sehingga hukum menampilkan ketetapan-ketetapan struktural yang dapat ditemukan oleh pakar hukum dan diperlakukan sebagai konsistensi dalam kenyataan yang muncul secara faktual) (Fuller, 1964:151).
Para iuris dengan demikian diasumsikan untuk telah dan terus berfilsafat. Belajar filsafat secara formal dan berfilsafat adalah dua sisi dari mata uang yang sama.
Bila filsafat diambil sebagai disiplin, yang dipelajari adalah keseluruhan jangkauan dan lapisan-lapisannya sebagai sebuah disiplin. Berfilsafat sebagai dalam peran yudisial berarti memeriksa dan mengolah berbagai konsep dengan pisau bedah yang salah satunya diberikan oleh Nagel.
Seorang hakim dapat berperan dalam berfilsafat hukum dengan bertanya, apakah pemahamannya solipsistik, apakah ia dapat menunjukkan secara logis dan faktual pemahamannya tentang duduk perkara, dan apakah jika ia menemui situasi sulit seperti yang dicatat Radbruch. Mampukah ia, seperti yang dipaparkan Fuller, menemukan benang merah konsistensi teoretik dari perkara yang sedang ia hadapi.
Tindakan Hukum pada Hakikatnya Berfilsafat
Dalam kasus S v Rabie 1975 (4) SA 855 (A) di Afrika Selatan pada 1975, Maurice Rabie, seorang aparat kepolisian diputuskan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara oleh pengadilan Afrika Selatan yang setara Pengadilan Negeri karena pencurian dan penggelapan.
Rabie mengajukan banding ke Appellate Division (setingkat Pengadilan Tinggi), dengan asumsi bahwa hukuman yang diterimanya terlalu berat. Hakim di Tingkat banding menolak banding yang diajukan Rabie, dan ia harus tetap menjalani masa hukuman seperti yang telah ditetapkan sebelumnya (Supreme Court of South Africa, 1975).
Dari kasus ini, dapat dikaji penerapan instrumen filosofis yang diberikan Nagel. Hakim pengadilan di tingkat banding mesti meyakinkan bahwa putusan tersebut bukan solipsisme. Hakim juga perlu memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk mendukung vonis yang dijatuhkan pada Rabie. Hakim juga perlu untuk mencari justifikasi untuk mengikis keragu-raguan putusan tersebut.
Dengan demikian, berfilsafat hukum menuntut lebih dari sekadar kemampuan teknis membaca peraturan atau menafsirkan pasal. Ia menuntut disposisi batin untuk berpikir dianoetik seperti yang digariskan Plato, tertib, dan mampu menahan diri dari godaan impulsif yang mereduksi persoalan menjadi sekadar kesan atau preferensi pribadi.
Setiap upaya memahami hukum, baik sebagai norma maupun sebagai praktik sosial, selalu melibatkan kerja intelektual yang menuntut konsistensi, objektivitas, dan keberanian untuk menelusuri alasan-alasan terdalam yang menopang sebuah keputusan.
Karena itu, berfilsafat bukanlah pelengkap, tetapi syarat yang membuat hukum dapat dikenali sebagai hukum: suatu upaya rasional untuk menata tindakan manusia melalui alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa fondasi ini, hukum kehilangan arah dan melebur menjadi serangkaian keputusan tanpa pijakan.