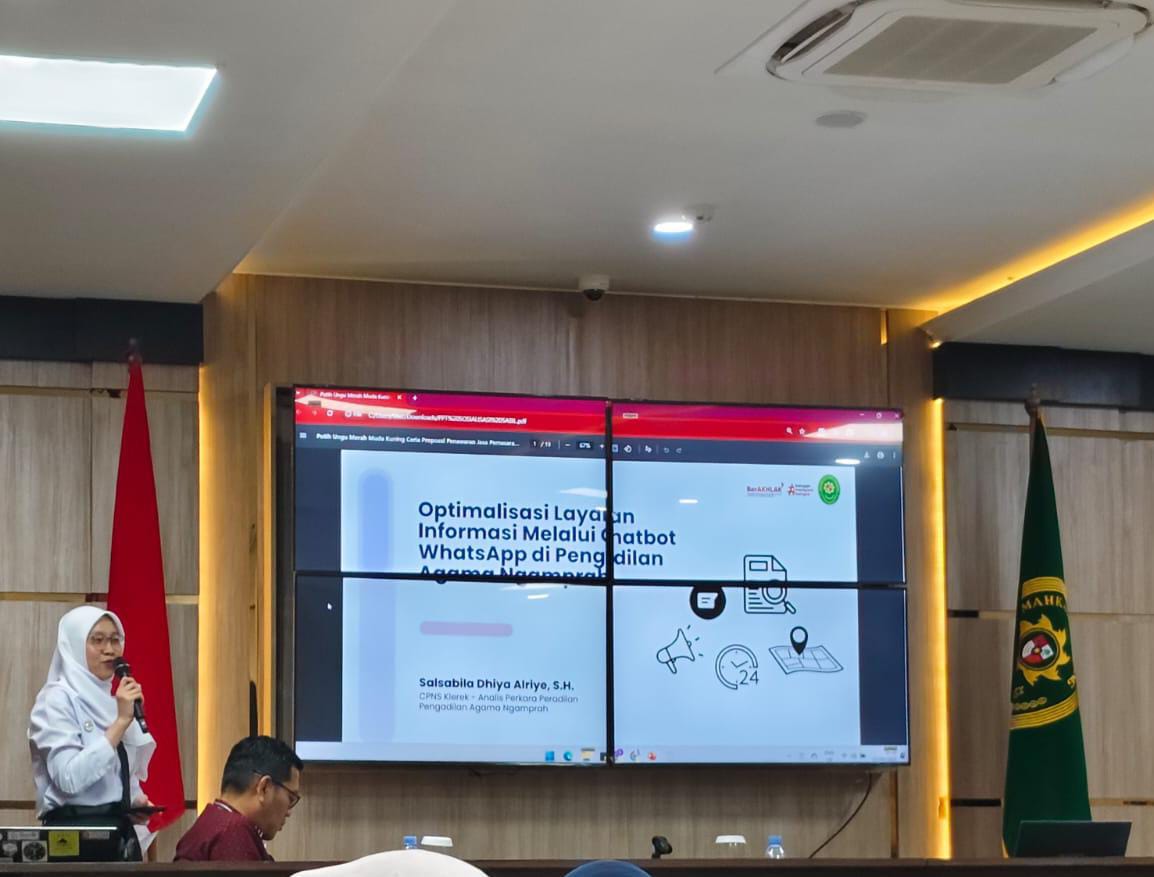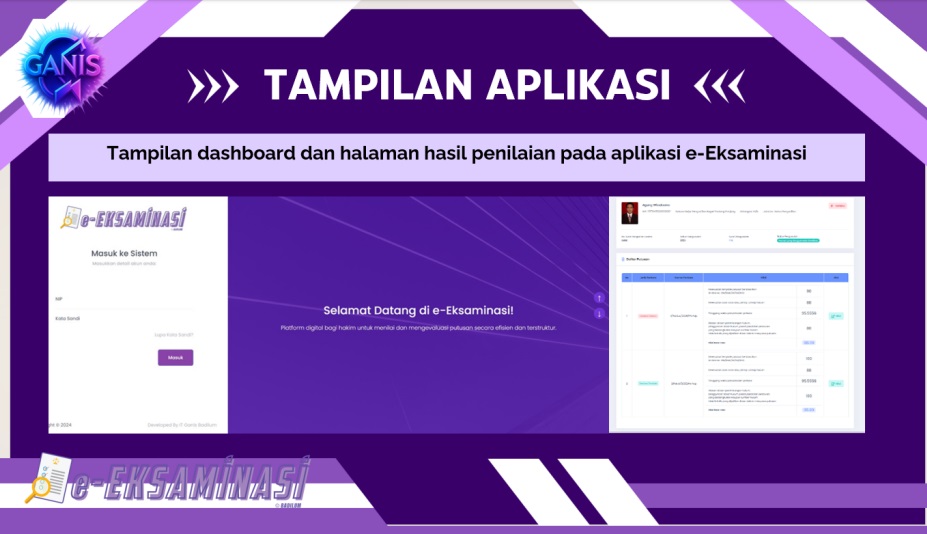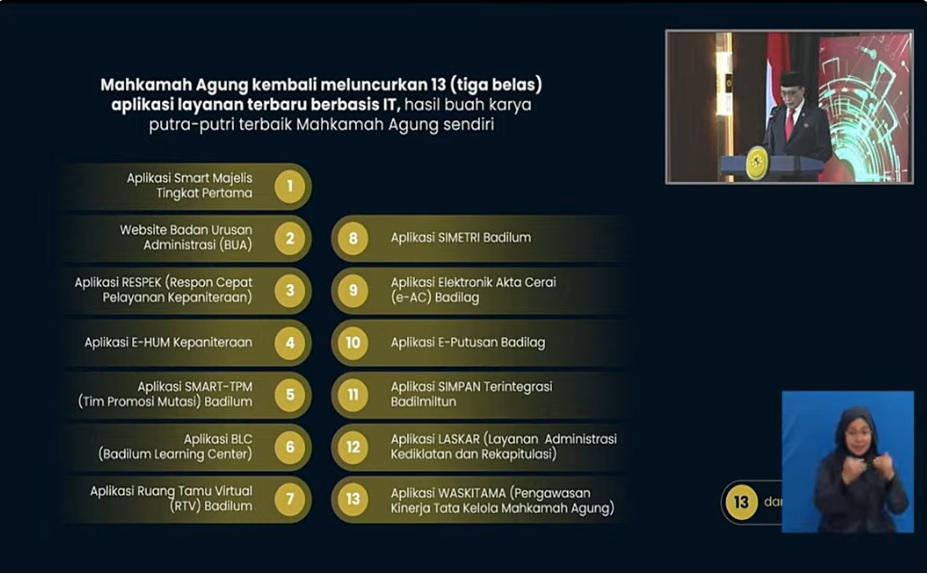“A judge must decide not just who shall have what, but who has behaved well, who has met the responsibilities of citizenship, and who by design or greed or insensitivity has ignored his own responsibilities to others or exaggerated theirs to him.”
Ronald Dworkin (Law’s Empire).
Benturan konstruktif terbesar yang membentuk hukum, menurut Ronald Dworkin (1997), adalah “hard cases”: kasus-kasus sulit yang menjadi catatan sangat penting dan membentuk alur jurisprudensi. Kasus landmark (Riggs v. Palmer) di Amerika Serikat yang diangkat Dworkin adalah saat seorang cucu (Elmer Palmer) membunuh kakeknya (Francis B. Palmer) demi warisan yang memang secara resmi mencantumnya namanya sebagai ahli waris.
Hukum pada waktu itu, debat Dworkin, tidak memberikan ruang untuk menganulir hak sang cucu untuk mendapatkan warisannya. Hakim, bagi Dworkin, harus berhadapan dengan situasi ini dan menjadi pilar dari konstruksi hukum yang lebih solid dan matang.
Di sisi lain, bagi Gustav Radbruch (1950), hukum yang tidak mengayomi hakikat keadilan adalah hukum yang tidak adil (unjust laws). Keberadaan hukum ini sah secara juridis, namun secara moralitas adalah cacat dalam alur pemberadaban manusia. Hukum yang “buruk” tetap memiliki finalitas yang absolut (res judicata).
Oleh karena itu peran hakim menurut Radbruch menjadi sangat sentral. Bila ketidakadilan menjadi produk dari sebuah mekanisme hukum dan mencapai titik ekstrim, konstruksi juridis di sebuah negara akan kolaps. Bila argumen Radbruch ini kita terapkan dalam konteks lembaga peradilan, dapat dibayangkan bahwa risiko yang ada dalam sebuah putusan menjadi sangat serius.
Menimbang Skala dan Urgensi Perkara
Di Amerika Serikat (AS) tidak semua kasus bisa naik ke Supreme Court of the United States (SCOTUS). Saringan “writ-of-certiorari” memilah kasus-kasus mana yang akan dibahas. Setidaknya perlu empat Hakim Agung yang memberikan suaranya agar sebuah usulan bisa diloloskan. Dalam masa bakti 2024-2025, sudah ada sekitar 65 kasus yang lolos (Encyclopedia of American Politics, 2025).
Masih di negara yang menganut common law, Inggris memiliki mekanisme “permission to appeal” (izin untuk banding), dengan syarat pengajuan harus memiliki poin-poin hukum yang menyangkut kepentingan publik yang paling genting (points of law of the greatest public importance). Dari sekitar 200 yang diajukan pada dari 2024-2025, hanya 43 yang diteruskan (Supreme Court UK, 2025). Di Kanada, hanya 7%, atau 35 kasus dari 526 pengajuan yang diterima (Paul-Erik Veel, 10 Januari 2025).
Dari ketiga negara tersebut, kita dapat melihat bahwa arah yang dituju adalah perbaikan kualitas putusan terhadap kasus-kasus, bila kita dapat membahasakannya dalam istilah Dworkin, yang sifatnya hard cases.
Berbeda dengan beberapa negara lainnya, Mahkamah Agung di sejumlah negara masih menangani perkara dengan skala beragam. Di India, Supreme Court masih memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa rumah tangga (Supreme Court Observer, 7 Agustus 2024). Sementara di Brasil, Supremo Tribunal Federal bahkan dapat mengadili kasus pelanggaran lalu lintas seperti denda tilang (Migalhas, 19 Desember 2024).
Di Prancis, Cour de Cassation secara rutin menangani perkara ketenagakerjaan, termasuk kasus perceraian (Cour de cassation, 2023). Sedangkan di Italia, Corte di Cassazione tetap membuka ruang untuk perkara perdata seperti gugatan kontrak berskala kecil (Corte di Cassazione, 24 Januari 2025). Adapun di Filipina, perkara perpajakan secara rutin dapat diajukan hingga ke Supreme Court of the Philippines (2025).
Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan tertinggi di negara-negara tersebut, tetap menjadi penentu dalam berbagai persoalan hukum, terlepas dari besar atau kecilnya perkara. Mekanisme ini dimungkinkan karena fungsi mereka sebagai instrumen korektif terhadap kemungkinan kesalahan dalam proses hukum di tingkat sebelumnya.
Di Pusat Simpul Hukum: Kompleksitas Tugas dan Fungsi Yudisial
Di Amerika Serikat (AS), ada tujuh poin yang dicatat oleh Alexander Bickel (1986). Pertama, SCOTUS memiliki tegangan internal yang membuatnya sulit melepaskan diri dari kepentingan politik, terutama karena di AS Hakim Agung dipilih oleh lembaga eksekutif, dan bukan dari pemilihan umum. Kedua, dalam kasus-kasus yang pelik, SCOTUS sepatutnya memiliki kewenangan untuk menunda putusan hingga ada klarifikasi lebih jelas. Ketiga, dalam kasus rumit yang berkaitan dengan situasi politik, SCOTUS mesti memainkan peran penyeimbang.
Keempat, hakim-hakim di SCOTUS mesti sedapat mungkin menarik jarak dengan ketidaksukaan mereka (personal dislikes), termasuk yang berkaitan dengan preferensi pribadi. Kelima, SCOTUS adalah instrumen kenegaraan yang bekerja dengan lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan gerak intitusional secara keseluruhan. Keenam, SCOTUS perlu memiliki visi ke depan, dan bukan menjadi lembaga yang berpatokan pada situasi dan kondisi lampau. Ketujuh, dan yang paling berkaitan dengan tulisan ini, menyelesaikan seluruh perkara yang ada di masyarakat akan menyulitkan SCOTUS untuk mengoptimalkan kinerjanya.
Dalam kaitannya dengan poin ketujuh di atas, Bickel mengatakan: “The tendency of a common and easy resort to this great function, now lamentably too common, is to dwarf the political capacity of the people, and to deaden its sense of moral responsibility” (kecenderungan untuk terlalu mudah dan terlalu sering menggunakan fungsi ini, yang sayangnya telah menjadi kebiasaan, berakibat pada mengecilnya kapasitas politik rakyat serta melemahnya kesadaran lembaga tersebut akan tanggung jawab moral) (Bickel, 1986:22).
Kembali ke “hard cases”, Dworkin mengatakan, “even when no settled rule disposes of the case, one party may nevertheless have a right to win. It remains the judge’s duty, even in hard cases, to discover what the rights of the parties are, not to invent new rights retrospectively” (bahkan ketika tidak ada aturan yang mapan untuk menyelesaikan suatu perkara, salah satu pihak tetap memiliki hak untuk menang. Dalam kasus-kasus yang sulit sekalipun, adalah tugas hakim untuk menemukan apa yang menjadi hak para pihak, bukan menciptakan hak-hak baru secara retrospektif) (Dworkin, 1997:105).
Etika dan Empati dalam Pengambilan Keputusan Hukum
John Rawls dalam A Theory of Justice (1971) mengangkat poin bahkan keadilan mesti berangkat dari mereka yang secara sosial dan ekonomi paling tidak diuntungkan (the least advantaged). Bila kita berangkat dari gagasan Rawls ini, maka mungkin kita sampai pada kesimpulan bahwa lembaga peradilan tertinggi mesti mengayomi masyarakat dalam skala apapun.
Namun demikian, pemikiran Rawls tersebut dapat dibaca dengan cara lain: kasus-kasus yang sampai ke tahapan tersebut semestinya menjadi preseden konstruktif terhadap implementasi prinsip-prinsip keadilan. Prinsip yang diberikan Immanuel Kant (1785), imperatif kategoris, dapat menjadi argumen penting untuk memilah dan menyeleksi kasus yang perlu diselesaikan di tingkat ini. Kant mengatakan bahwa tindakan yang paling rasional memiliki aspek universal dan eksemplaris. Dengan kata lain, lembaga yudikatif dapat memilih kasus-kasus yang berfungsi sebagai panduan bagi putusan-putusan berikutnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Kasus United States v. Holmes, 26 F. Cas. 360 (C.C.E.D. Pa. 1842) dapat menjadi catatan penting tentang seberapa kritis muatan sebuah kasus kemanusiaan, seperti yang ditegaskan Rawls dan Kant, sebagai materi jurisprudensi. Dalam sebuah kecelakaan kapal William Brown di 1841, pelaut yang bertugas di kapal, Alexander Holmes, dengan mempertimbangkan bahwa jumlah sekoci tidak sepadan dengan penumpang kapal, membiarkan 31 orang yang tidak tertampung tenggelam di laut lepas.
Korban yang jatuh umumnya adalah imigran yang hendak menuju Philadelphia, AS. Holmes dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana pembantaian (manslaughter). Hakim Henry Baldwin menegaskan dalam pembacaan putusan bahwa dalam kondisi kritis, Holmes tidak berhak untuk memilih mana yang perlu diselamatkan dan mana yang dibiarkan tenggelam (Federal Judicial Center, 2025). Imigran yang tewas tenggelam dapat dikategorikan sebagai the least advantaged, dan tindakan Holmes bukanlah sebuah keputusan yang dapat dijadikan patokan universal.
“Hard cases” akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia, terutama dalam perkembangan hukum dan jurisprudensi. Dalam seluruh kerumitannya, kasus-kasus sulit merefleksikan pertentangan antara hukum positif dan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal, sebagaimana dikemukakan oleh Dworkin dan Radbruch.
Pertimbangan mengenai skala kasus dan urgensinya memperlihatkan pentingnya mekanisme seleksi yang jelas, agar lembaga peradilan tertinggi di sebuah negara dapat menjalankan fungsi strategisnya sebagai penjaga keadilan substantif, sekaligus pencipta preseden hukum yang matang dan konsisten.
Perspektif Rawls menegaskan pentingnya pertimbangan sosial-ekonomi dalam memilih perkara yang sampai pada tahapan ini, guna melindungi mereka yang paling rentan.
Sementara itu, Kant menawarkan landasan moral rasionalitas universal yang mengharuskan kasus yang diloloskan secara esensial membangun standar moral dan keadilan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, seleksi perkara yang cermat bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab moral dan sosial hukum terhadap peradaban manusia secara menyeluruh.