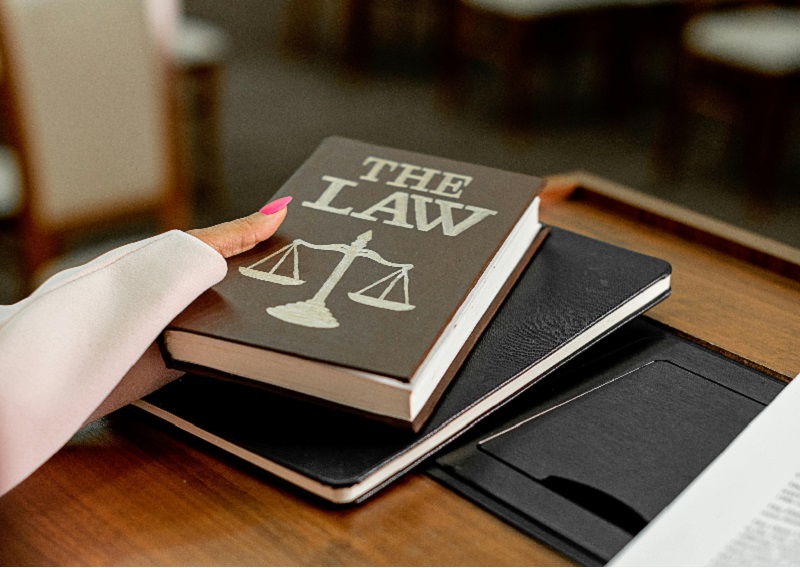Kolonialisme membawa pengaruh yang begitu kuat dalam berbagai struktur sosial bagi masyarakat yang terjajah.
Proses dominasi pengetahuan, budaya, cara berpikir bahkan sampai dengan cara berhukum diambil alih oleh penjajah dan diotorisasikan dalam berbagai aspek dan tindakan.
Berpuluh-puluh tahun Republik Indonesia berdiri, baru dewasa ini bisa menciptakan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku penuh pada Januari 2026.
UU itu menjadi suatu kodifikasi yang ‘dirasa’ paling mendekati ciri jati diri bangsa Indonesia. Sebab, selama ini anak bangsa dirasa belum pantas, belum layak, atau bahkan inferior untuk merumuskan apa dan bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan dirinya sendiri.
Hal tersebutlah yang dinamakan kolonialisme epistemik, penjajahan cara berpikir, mengakar begitu kuat sekalipun penjajahan secara fisik sudah tidak ada puluhan tahun yang lalu.
Dominasi perspektif Barat (dalam hal ini negara penjajah) yang selalu dianggap paling bagus dan paling benar, pengkerdilan hukum dan budaya lokal karena dianggap terbelakang dan tidak relevan, sampai dengan rasa inferioritas yang menjelma menjadi ketakutan untuk berhukum sesuai dengan cara dan cita rasa nasional. Beberapa hal tersebut mendasari Wetboek van Straftrecht (WvS) voor Nederlandsch Indië melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku dan tetap dipakai selama puluhan tahun.
Walaupun harus disadari, beberapa kebuntuan tersebut sudah mulai dijawab dengan kewenangan Hakim untuk menggali dan mengangkat hukum yang hidup (living law) di Masyarakat (UU Kekuasaaan Kehakiman), kritik dan berkembangnya aliran hukum progresif akibat penegakan hukum yang hanya mengedepankan legalitas formal dan minim substansi, sampai dengan mulai berkembangnya judicial activism sebagai cara untuk menghadapi kebuntuan hukum yang berlaku.
Mengangkat Kembali Martabat Hukum Adat dan Pengetahuan Lokal
Salah satu ciri kolonialisme epistemik adalah menghancurkan, merendahkan, dan menggantikan sistem pengetahuan lokal dengan kerangka berpikir asing yang dianggap lebih “unggul”, “rasional”, atau “modern”.
Padahal Republik Indonesia sendiri memiliki 715 bahasa daerah, 2.161 komunitas adat (Setkab RI: 2023), serta berbagai hukum adat yang tidak terkodifikasi, melainkan hidup dan berlaku dalam masyarakat di daerah tertentu.
KUHP Nasional telah memberikan hukum adat ruang untuk hidup, sebagaimana termuat dalam asas bahwa hukum tertulis tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP Nasional.
Hal ini juga tentunya menjadi tantangan, sejauh mana masyarakat adat, ahli atau para pemerhati adat dapat membuktikan bahwa hukum adat tersebut ada dan berlaku secara eksis dalam komunitas masyarakat adat.
Tetapi semangat yang patut diapresiasi adalah diangkat kembali martabat hukum adat yang selama ini diasingkan atau bahkan terpinggirkan dan dijadikan another choice (pilihan lain) dalam kerangka KUHP yang lama.
Sehingga, penegakan hukum nantinya akan menjadi lebih dinamis dengan memperhatikan substansi-subtansi hukum adat yang berlaku di masyarakat.
Upaya Dekolonisasi Mentalitas Dalam Berhukum: Sebuah Pencarian Jati Diri
Diskursus dan pematangan konsep KUHP Nasional telah dilangsungkan di berbagai ruang diskusi baik langsung ataupun virtual, sarana seminar ataupun lokakarya, sampai dengan berbagai Focus Group Discussion (FGD) yang dilangsungkan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Tetapi yang barangkali harus disiapkan dan diskusikan adalah, sejauh mana mentalitas para praktisi dan akademisi serta masyarakat akan diuji dengan berbagai hal-hal baru seperti sistem "double track" (pidana dan tindakan), pengakuan penyelesaian perkara di luar pengadilan (restorative justice), pidana alternatif (tutupan, pengawasan, kerja sosial, denda), dan tujuan pemidanaan yang lebih jelas (pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, efek jera).
Selain itu, ada penyesuaian terkait tindak pidana korporasi, perubahan aturan pidana mati, dan ketentuan baru mengenai tindak pidana agama serta pemeliharaan hewan.
Tentunya, sama seperti semua konsep dan tatanan sistem yang baru, akan terjadi adaptasi (atau bahkan pergolakan) yang terjadi, baik yang sifatnya vertikal (antar instansi) ataupun horizontal (dengan masyarakat).
Dalam hal ini, mentalitas yang dibutuhkan adalah sejauh mana kita dapat terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya kritik ataupun korektif terhadap penerapan dalam tataran praktek.
Pencarian sebuah jati diri, terutama jati diri dalam ber-Hukum, pasti memerlukan waktu yang tidak instan dan perlu perbaikan di berbagai aspek.