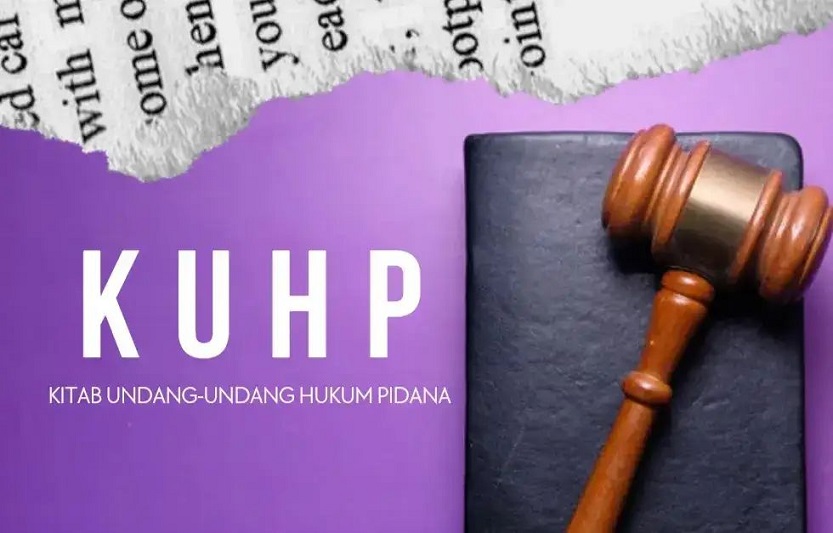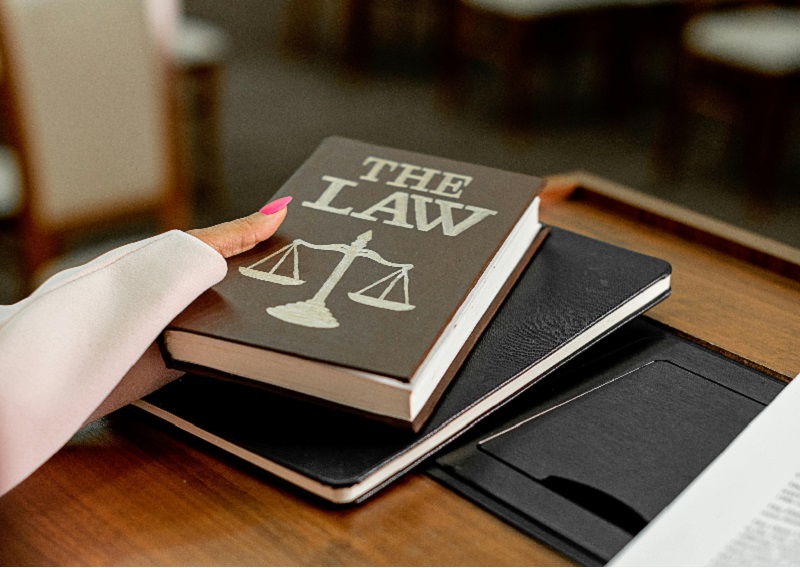Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai fajar yang memecah malam panjang dominasi hukum pidana kolonial di Indonesia. Ini bukanlah sekadar suksesi kodifikasi, melainkan sebuah proklamasi intelektual dan filosofis yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Selama lebih dari tujuh dekade, sistem peradilan pidana Indonesia bergerak dalam kerangka Wetboek van Strafrecht (WvS), sebuah artefak hukum yang dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik Abad ke-18.
Filsafat ini secara inheren bersifat positivistik legalistik, memusatkan perhatiannya secara dingin pada perbuatan (delict) dan cenderung mengebiri konteks kemanusiaan pelakunya (dader). Ia adalah produk zaman yang memandang hukum sebagai instrumen kekuasaan dan ketertiban (imperium), yang secara filosofis terasa asing bagi bangsa yang merdeka di atas fondasi Pancasila.
Artikel ini akan membedah sebuah tema sentral yang menjadi benang merah sekaligus jiwa dari kodifikasi baru ini: pergulatan kemanusiaan dalam kerangka hukum pidana.
Tema ini merefleksikan sebuah upaya monumental untuk mendekonstruksi warisan kolonial dan merekonstruksi jiwa hukum pidana Indonesia.
Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasannya, kodifikasi ini mengemban berbagai misi luhur: "dekolonialisasi", "demokratisasi", "konsolidasi", serta "adaptasi dan harmonisasi".
Fundamen dari semua misi ini adalah ikhtiar untuk menyuntikkan kembali nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, ke dalam setiap pasal dan ayatnya. Ia secara sadar dirancang untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang acap kali berbenturan: antara kepentingan umum dan individu, antara perlindungan pelaku dan korban, antara kepastian hukum dan keadilan, serta antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Analisis ini berargumen bahwa KUHP Nasional adalah arena pergulatan ideologis yang paling fundamental dalam sejarah hukum Indonesia. Ia menandai pergeseran paradigma dari keadilan yang semata-mata retributif (pembalasan) menuju sebuah konsepsi keadilan hibrida yang merangkul aspek-aspek korektif (perbaikan), restoratif (pemulihan), dan rehabilitatif (pembinaan).
Analisis ini akan menelusuri bagaimana KUHP Nasional menjadi cermin pergulatan bangsa dalam menyeimbangkan antara tuntutan ketertiban negara dan imperatif untuk senantiasa menjunjung tinggi martabat manusia, bahkan bagi mereka yang telah dinyatakan bersalah.
Permasalahan
Untuk membedah kompleksitas tema pergulatan kemanusiaan ini dengan kedalaman yang memadai, dirumuskan dua pertanyaan fundamental sebagai berikut:
- Bagaimana KUHP Nasional secara fundamental mendekonstruksi filsafat positivisme legalistik warisan kolonial dan merekonstruksinya dengan paradigma keadilan Pancasila yang berorientasi pada kemanusiaan, yang menyeimbangkan antara faktor perbuatan objektif dan sikap batin subjektif pelaku?
- Di titik-titik krusial manakah dialektika antara keadilan retributif dan keadilan restoratif korektif termanifestasi secara paling tajam, yang merefleksikan pergulatan Indonesia dalam mendefinisikan ulang makna penghukuman, pengampunan, dan kemanusiaan dalam konteks hukum pidana modern?
Pembahasan
A. Anima Iustitiae: Jiwa Baru dalam Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
Jika WvS beroperasi dengan logika mekanis yang dingin, maka KUHP Nasional mencoba menanamkan anima iustitiae, jiwa keadilan, yang baru dan berdenyut dengan napas kemanusiaan.
Hal ini paling eksplisit tertuang dalam Bab III. Pasal 51 merumuskan tujuan pemidanaan yang jauh melampaui sekadar pembalasan, melainkan mencakup: (a) pencegahan tindak pidana demi pengayoman masyarakat; (b) pemasyarakatan terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna; (c) penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai; dan (d) penumbuhan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Puncaknya adalah kredo humanistik dalam Pasal 52, yang menjadi leitmotif seluruh kodifikasi ini: "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia".
Ini adalah sebuah penegasan yang secara diametral membedakannya dari semangat hukum pidana warisan kolonial yang lebih berorientasi pada penjeraan melalui penderitaan.
Jiwa baru ini kemudian diberi kerangka operasional dalam Pasal 54, yang dapat disebut sebagai fondasi bagi "yurisprudensi empatik". Hakim tidak lagi diposisikan sebagai "corong undang-undang" (la bouche de la loi) yang kaku, melainkan sebagai seorang arif yang wajib mempertimbangkan spektrum kemanusiaan yang luas.
Secara eksplisit, hakim wajib menimbang "sikap batin pelaku", "riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku", "pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku", hingga adanya "pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban".
Lebih jauh, Pasal 54 ayat (2) memperkenalkan konsep pemaafan hakim (judicial pardon), di mana hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan "segi keadilan dan kemanusiaan".
Kewajiban-kewajiban ini secara efektif mengubah optik peradilan dari yang semula delict centric menjadi lebih dader centric, sebuah pergeseran yang merefleksikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
B. Harmonisasi Hukum Formil dan Keadilan Substantif: Pengakuan Hukum Adat
Pergulatan kemanusiaan juga tercermin dalam upaya KUHP Nasional menjembatani jurang antara hukum negara yang formil dan rasa keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.
Pengakuan terhadap "hukum yang hidup dalam masyarakat" (hukum adat) dalam Pasal 2 adalah sebuah langkah dekolonialisasi yuridis yang revolusioner. Ia merupakan sebuah bentuk pengakuan epistemologi hukum bahwa sumber keadilan tidak dimonopoli oleh negara, melainkan juga bersemayam dalam kearifan kolektif komunitas.
Namun, pengakuan ini tidak absolut. KUHP Nasional melakukan pergulatan dengan menetapkan syarat-syarat yang ketat: hukum tersebut berlaku sepanjang tidak diatur dalam KUHP Nasional dan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
Dengan mengakomodasi sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat yang dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II, KUHP Nasional membuka ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih restoratif, yang bertujuan memulihkan harmoni sosial alih-alih sekadar menjatuhkan derita. Ini adalah manifestasi pergulatan untuk menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang tidak tercerabut dari akar sosio kulturalnya.
C. Pertanggungjawaban Pidana: Dialektika Antara Kesalahan dan Keadaan
KUHP Nasional menegaskan kembali asas fundamental tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban hanya dapat diminta atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
Ini adalah benteng utama melawan penghukuman yang sewenang-wenang. Namun, KUHP Nasional juga mengakui kompleksitas modern dengan membuka ruang terbatas bagi pengecualian, seperti pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), namun hanya jika ditentukan secara tegas oleh undang-undang.
Pergulatan kemanusiaan dalam ranah ini tampak paling jelas pada pengakuan terhadap alasan pembenar (justifikasi) dan alasan pemaaf (ekskus).
Konsep seperti pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Pasal 34, keadaan darurat (noodtoestand) dalam Pasal 33, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena "keguncangan jiwa yang hebat" (noodweer exces) dalam Pasal 43, adalah bentuk pengakuan hukum bahwa manusia tidak selalu bertindak dalam kondisi ideal.
Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa hukum tidak menutup mata terhadap tekanan psikologis dan situasi ekstrem yang dapat memaksa seseorang melakukan perbuatan terlarang. Ini adalah dialog antara norma hukum yang rigid dengan realitas kemanusiaan yang rapuh dan kompleks.
D.Paradoks Hukuman Mati: Titik Tegang Antara Kedaulatan dan Belas Kasih
Tidak ada arena yang merefleksikan pergulatan kemanusiaan lebih dramatis daripada pengaturan pidana mati. Di satu sisi, KUHP Nasional masih menegaskan kedaulatan negara untuk menjatuhkan sanksi tertinggi ini, yang diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Ini adalah wajah retributif negara dalam merespons kejahatan-kejahatan paling brutal.
Namun, di sisi lain, Pasal 100 memperkenalkan sebuah inovasi yang sarat dengan nilai kemanusiaan: pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Mekanisme ini menciptakan sebuah "limbo yudisial", di mana nasib terpidana tidak ditentukan secara final pada saat putusan dibacakan.
Terpidana diberi kesempatan untuk membuktikan adanya "rasa penyesalan... dan ada harapan untuk memperbaiki diri", yang dapat berujung pada perubahan hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Ditambah lagi dengan Pasal 101, yang memungkinkan perubahan pidana mati menjadi seumur hidup jika eksekusi tidak dilaksanakan dalam 10 tahun setelah grasi ditolak, menunjukkan adanya pengakuan bahwa waktu dan perubahan dalam diri seorang manusia memiliki nilai yuridis.
Pengaturan ini adalah sebuah paradoks yang indah: negara memegang pedang, namun menahan ayunannya untuk memberi ruang bagi secercah harapan, bagi kemungkinan penebusan.
E. Humanisasi Sanksi: Melampaui Tembok Penjara
Menyadari bahwa penjara, terutama untuk pidana jangka pendek, seringkali menjadi "pabrik residivisme" yang justru mendehumanisasi, KUHP Nasional menawarkan jalan keluar. Diperkenalkannya pidana kerja sosial (Pasal 85) dan pidana pengawasan (Pasal 75) sebagai alternatif pidana penjara merupakan langkah progresif.
Pidana kerja sosial, misalnya, hanya dapat dijatuhkan dengan mempertimbangkan "persetujuan terdakwa" dan "kemampuan kerja terdakwa", menunjukkan sebuah pendekatan yang partisipatif dan tidak semata-mata menghukum. Sanksi-sanksi ini tidak bertujuan mengisolasi, melainkan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam jejaring sosial secara konstruktif.
Kemanusiaan sebuah sistem hukum pada akhirnya diukur dari caranya memperlakukan kelompok paling rentan. KUHP Nasional menunjukkan sensitivitas ini dengan tegas. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak ditetapkan pada 12 tahun, dengan kewajiban diversi untuk tindak pidana tertentu dan penerapan tindakan non-pemenjaraan sebagai prioritas.
Terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, KUHP Nasional membuka kemungkinan pengurangan pidana (Pasal 38) atau pengenaan tindakan non pemenjaraan (Pasal 39).
Ini adalah bukti konkret bahwa KUHP Nasional berupaya menerapkan keadilan yang diskriminatif secara positif, yang memahami bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak berarti perlakuan yang sama rata, melainkan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi dan kapasitas setiap individu.
Kesimpulan
KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) adalah sebuah manifesto filosofis. Ia bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan cermin dari pergulatan panjang sebuah bangsa untuk mendefinisikan kembali hubungannya dengan keadilan, kekuasaan, dan kemanusiaan.
Melalui dekonstruksi paradigma kolonial yang kaku, KUHP Nasional telah merekonstruksi jiwa hukum pidana Indonesia menjadi lebih humanis, restoratif, dan berlandaskan Pancasila, dengan menjaga keseimbangan antara perbuatan dan pelaku (daad dader strafrecht).
Pergulatan antara idealisme retributif dan restoratif termanifestasi dalam setiap aspek krusialnya: dari tujuan pemidanaan yang memanusiakan, pengakuan hukum adat yang menghargai kearifan lokal, dialektika dalam pertanggungjawaban pidana yang mengakui kerapuhan manusia, pengaturan pidana mati yang memberi ruang harapan, hingga diversifikasi sanksi yang melampaui logika pemenjaraan.
Tentu, kodifikasi ini tidaklah sempurna dan tantangan terbesarnya terletak pada napas penegakan hukumnya. Namun, teks hukum ini telah meletakkan fondasi yang kokoh.
Fajar keadilan Pancasila telah terbit, dan kini menjadi tugas para penegak hukum, akademisi, dan seluruh masyarakat untuk memastikan cahayanya benar-benar menerangi setiap sudut ruang peradilan, mewujudkan sebuah sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memanusiakan.