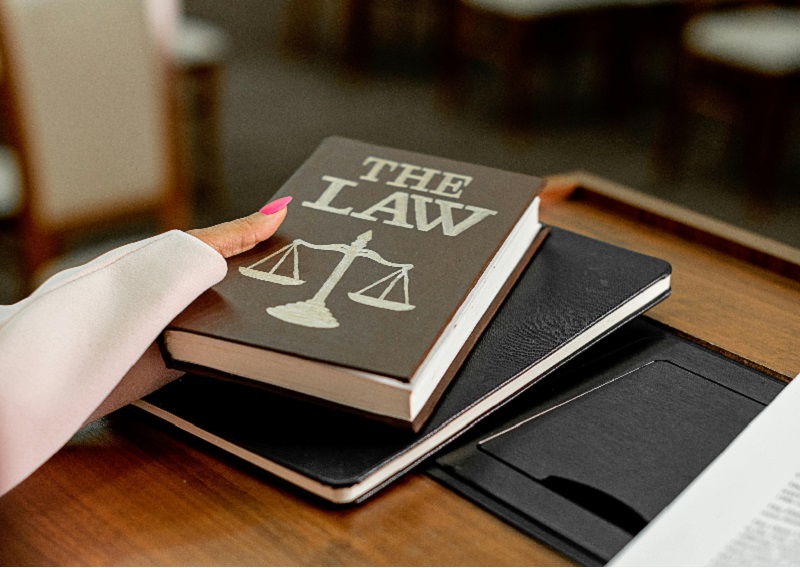Kedalaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional patut diapresiasi oleh karena banyak filosofi pidana yang diimplementasikan dalam penyusunannya.
Perubahan paradigmanya dari retributif menjadi restoratif dan bermartabat juga patut dipandang lebih humanis. Salah satu semangat progresif yang terkandung dalam KUHP Nasional adalah penerapan konsep therapeutic jurisprudence, sebuah pendekatan yang mengutamakan aspek terapeutik dalam proses peradilan.
Therapeutic jurisprudence, sebagaimana dikembangkan oleh Michael Perlin (1981), merupakan pendekatan interdisipliner antara hukum dan psikologi yang mengkaji bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai sarana terapi.
Perlin menekankan bahwa sistem peradilan tidak hanya berfokus pada aspek retributif, melainkan juga mempertimbangkan dampak psikologis dan kesehatan mental dari proses hukum terhadap individu yang terlibat.
Yamada (2025) memperkuat konsep ini dengan menegaskan therapeutic jurisprudence mengutamakan kesehatan mental terdakwa sebagai elemen fundamental dalam proses peradilan.
Pendekatan ini mengakui bahwa kondisi mental seseorang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memahami akibat hukum dan efektif berperan aktif dalam proses peradilan.
Esensi therapeutic jurisprudence terletak pada penggunaan hukum sebagai sarana pengubah perilaku terdakwa. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung bersifat punitif, therapeutic jurisprudence melihat sistem hukum sebagai instrumen rehabilitatif yang dapat memfasilitasi perubahan positif dalam diri pelaku tindak pidana.
Pendekatan ini memandang bahwa banyak tindak pidana berakar dari masalah kesehatan mental, trauma, atau gangguan perilaku yang memerlukan intervensi terapeutik atau psikologis daripada hukuman semata.
Dengan demikian, sistem peradilan tidak hanya menangani konsekuensi dari tindak pidana, tetapi juga berusaha mengatasi akar penyebabnya.
Semangat therapeutic jurisprudence telah diadopsi secara konkret dalam KUHP Nasional, khususnya melalui Pasal 38 dan Pasal 110. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi mental terdakwa dalam penjatuhan putusan.
Pasal 38 KUHP Nasional memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tindakan kepada pelaku yang menderita disabilitas mental. Ketentuan Pasal 38 KUHP Nasional harus dirujuk pada Pasal 110 KUHP Nasional.
Pasal 110 KUHP Nasional mengatur mekanisme pidana tindakan berupa perawatan di rumah sakit, yang secara eksplisit mengakui kebutuhan intervensi medis dan terapeutik bagi pelaku dengan kondisi disabilitas jiwa.
Adopsi therapeutic jurisprudence dalam KUHP Nasional memberikan harapan bagi terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Hakim kini memiliki instrumen hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana tindakan perawatan di rumah sakit bagi pelaku tindak pidana yang menderita disabilitas mental, alih-alih hanya menjatuhkan pidana penjara konvensional.
Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis, tetapi juga berpotensi lebih efektif dalam mencegah residivis karena menangani akar masalah yang mendasari perilaku kriminal.
KUHP Nasional dengan semangat therapeutic jurisprudence-nya menjadi langkah maju dalam evolusi sistem hukum pidana Indonesia menuju keadilan yang lebih komprehensif dan terapeutik.