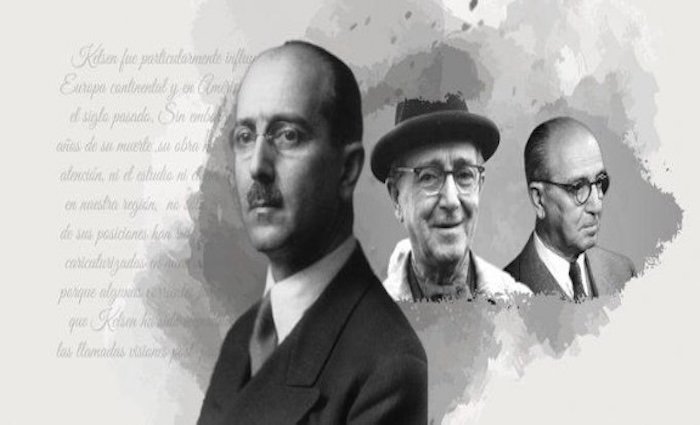Krisis Paradigma dalam Ilmu Hukum Positivistik
Ilmu hukum Indonesia masih banyak mewarisi tradisi positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri, terlepas dari konteks sosial yang melingkupinya.
Cara pandang ini membentuk generasi sarjana hukum yang lebih fasih membaca pasal daripada memahami kenyataan sosial dibaliknya. Padahal, hukum bukan sekadar kumpulan peraturan, tetapi realitas yang hidup di tengah masyarakat.
Sulistyowati Irianto (2009) menegaskan, krisis paradigma ini menjadi akar dari stagnasi penelitian hukum di Indonesia: hukum hanya diuraikan secara tekstual, tanpa memahami bagaimana ia benar-benar bekerja dalam praktik sosial.
Positivisme hukum memang memberikan kepastian dan logika sistematis. Namun, ketika diterapkan secara mutlak, ia mengabaikan dimensi moral, nilai, dan kemanusiaan yang justru menjadi substansi hukum itu sendiri.
Paul Scholten (2005) mengingatkan, hukum yang hanya dibaca dari teks adalah bloodless phantom—kerangka tanpa daging—karena kehilangan ruh kemanusiaannya.
Sementara itu, Wignjosoebroto (2002) menyebutkan, keberlakuan hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks sosial yang melahirkannya.
Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, hukum formal sering kali gagal bekerja efektif karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan pluralitas nilai dan norma sosial.
Di titik inilah pendekatan sosio-legal menawarkan jalan keluar. Ia tidak menolak sistem hukum positif, tetapi melengkapinya dengan analisis empiris terhadap bagaimana hukum dijalankan, diabaikan, atau dinegosiasikan dalam kenyataan sosial.
Dengan demikian, hukum dapat dipahami bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan berubah seiring dinamika masyarakat (Irianto, 2009).
Dari Normativisme ke Interdisiplinaritas Hukum
Kajian sosio-legal lahir dari kesadaran bahwa hukum tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan pendekatan monodisipliner.
Hukum tidak pernah netral; ia selalu berinteraksi dengan ekonomi, politik, budaya, dan relasi kekuasaan. Karena itu, memahami hukum membutuhkan integrasi antara analisis normatif dan metode ilmu sosial (Banakar & Travers, 2005).
Dalam pendekatan ini, teks hukum menjadi titik awal, bukan titik akhir. Peneliti harus membaca undang-undang, kebijakan, dan putusan pengadilan, tetapi menelusuri bagaimana norma-norma itu bekerja dalam kenyataan.
Misalnya, pasal tentang nafkah pasca cerai dalam Kompilasi Hukum Islam hanya bermakna normatif bila tidak dikaitkan dengan data sosial tentang pelaksanaannya di pengadilan agama.
Di sinilah penelitian empiris menjadi penting untuk menjelaskan kesenjangan antara law in the books dan law in action.
Pendekatan interdisipliner ini, tidak bermaksud mengaburkan batas antara hukum dan ilmu sosial, tetapi memperkaya keduanya.
Hukum menyediakan kerangka normatif, sementara ilmu sosial menyediakan pemahaman tentang konteks, nilai, dan perilaku yang membuat hukum itu bekerja atau gagal bekerja.
Dengan cara ini, ilmu hukum tidak lagi terkurung dalam dogma, tetapi menjadi ilmu yang hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Irianto, 2009).
Metodologi Sosio-Legal sebagai Paradigma Baru Ilmu Hukum
Salah satu kekuatan utama kajian sosio-legal, adalah pendekatan metodologinya yang menggabungkan penelitian tekstual dan penelitian lapangan.
Studi tekstual menelaah pasal-pasal hukum, peraturan, dan putusan pengadilan secara kritis untuk mengungkap makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.
Sementara itu, studi empiris menelusuri bagaimana norma-norma itu diimplementasikan oleh hakim, jaksa, advokat, dan masyarakat pencari keadilan (Merry, 2005).
Metode sosio-legal tidak hanya mengandalkan data statistik atau survei, tetapi juga pendekatan kualitatif seperti observasi persidangan, wawancara mendalam, dan studi etnografi hukum.
Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap “cerita di balik hukum”—bagaimana putusan lahir, bagaimana aktor hukum bernegosiasi dengan nilai, dan bagaimana masyarakat memahami keadilan.
Sulistyowati Irianto (2009) menyebut, metode ini membuka ruang bagi keterlibatan moral peneliti. Peneliti hukum bukan sekadar pengamat netral, tetapi bagian dari proses sosial yang ditelitinya.
Dengan kesadaran reflektif ini, penelitian hukum menjadi lebih jujur, transparan, dan peka terhadap dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik praktik hukum.
Membongkar Makna dan Kuasa di Balik Hukum
Kajian sosio-legal berakar kuat pada dua paradigma besar ilmu sosial, yaitu interpretivisme dan kritikal.
Paradigma interpretif menempatkan hukum sebagai teks sosial yang sarat makna. Ia mendorong peneliti untuk membaca hukum bukan hanya dari bunyi pasalnya, tetapi dari konteks sosial, politik, dan budaya yang membentuknya (Neuman, 1997).
Hukum tidak lagi dipandang sebagai cerminan objektif dari keadilan, tetapi sebagai hasil dari proses interpretasi manusia yang selalu terikat oleh nilai dan kepentingan tertentu.
Sementara itu, paradigma kritikal, sebagaimana dijelaskan oleh Sarantakos (1997), menyoroti relasi kekuasaan di balik hukum. Bahasa hukum yang tampak netral sering kali menyembunyikan struktur ketimpangan sosial, gender, dan ekonomi.
Dalam pandangan ini, penelitian hukum tidak cukup berhenti pada deskripsi, tetapi harus sampai pada dekonstruksi, membongkar bias kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai alat legitimasi ketidakadilan.
Dengan demikian, pendekatan sosio-legal tidak hanya memperluas metode, tetapi juga mengubah orientasi moral penelitian hukum.
Ia mengajak peneliti, hakim, dan akademisi untuk menimbang kembali siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh suatu kebijakan hukum.
Implikasi Paradigma Sosio-Legal terhadap Sistem Hukum Nasional
Paradigma sosio-legal memiliki implikasi langsung terhadap reformasi sistem hukum dan peradilan.
Ia menegaskan, keadilan tidak dapat ditegakkan hanya melalui kepastian hukum, tetapi juga melalui kepekaan sosial dan etika kemanusiaan.
Dalam konteks peradilan Indonesia, pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa banyak putusan yang “benar secara hukum”, namun gagal dirasakan adil oleh masyarakat.
Misalnya, penelitian Irianto & Nurchayo (2006) menunjukkan, pelaksanaan putusan pengadilan sering terhambat oleh faktor sosial dan administratif.
Di peradilan umum, eksekusi perdata kerap menghadapi resistensi masyarakat; di peradilan pidana, vonis penjara sering tidak menyelesaikan akar masalah sosial; sedangkan di peradilan agama, kewajiban nafkah pasca cerai sulit dijalankan tanpa dukungan kelembagaan lintas sektor.
Fakta-fakta ini menegaskan, efektivitas hukum bergantung pada pemahaman terhadap jaringan sosial di mana hukum bekerja (Irianto & Nurchayo, 2006).
Dalam konteks reformasi peradilan, pendekatan sosio-legal dapat membantu merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial.
Program seperti e-Court, restorative justice, dan mediasi penal merupakan bentuk nyata penerapan semangat sosio-legal, yaitu hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga memulihkan relasi sosial.
Dengan cara ini, peradilan tidak lagi hanya menjadi menara formalitas, melainkan wadah moral yang menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan.
Etika Sosio-Legal dan Humanisasi Ilmu Hukum
Selain menawarkan metode, sosio-legal juga membawa visi etik: hukum harus berpihak pada manusia.
Ia menolak cara berpikir yang menjadikan hukum sekadar alat kekuasaan, dan mengembalikannya sebagai sarana keadilan sosial.
Dalam hal ini, studi sosio-legal bukan hanya proyek akademik, melainkan juga gerakan moral yang menghidupkan kembali idealisme hukum sebagai pelindung martabat manusia (Irianto, 2009).
Dengan memahami hukum secara sosial, para penegak hukum dituntut untuk lebih empatik dan reflektif. Hakim tidak hanya dituntut memahami teks undang-undang, tetapi juga konteks sosial para pihak yang berperkara.
Jaksa dan polisi tidak hanya mengejar pembuktian, tetapi juga pemulihan. Advokat tidak hanya memperjuangkan kliennya, tetapi juga etika keadilan yang lebih luas.
Di tengah arus birokratisasi hukum, pendekatan sosio-legal menjadi pengingat bahwa hukum pada akhirnya adalah tentang manusia.
Keadilan sejati tidak lahir dari kepastian formal, tetapi dari keberanian moral untuk menafsirkan hukum secara hidup, sebagaimana diungkapkan oleh Scholten: hukum akan selalu membutuhkan manusia yang menegakkannya dengan nurani (Scholten, 2005).
Menuju Hukum yang Humanis dan Adaptif
Kajian sosio-legal membawa pesan penting bagi pembaruan hukum Indonesia, yakni hukum tidak dapat dipahami tanpa masyarakat, dan masyarakat tidak dapat dipahami tanpa hukum.
Hubungan keduanya bersifat dialektis, saling memengaruhi dan membentuk. Dalam konteks negara hukum yang plural dan dinamis seperti Indonesia, paradigma sosio-legal memberikan landasan konseptual dan metodologis untuk membangun hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan humanis.
Hukum yang hidup bukanlah hukum yang keras, melainkan hukum yang mampu berdialog dengan realitas sosial. Hukum yang efektif bukan hanya yang memiliki sanksi, tetapi yang dihayati sebagai bagian dari nilai keadilan bersama.
Dengan cara pandang ini, sistem peradilan Indonesia dapat berkembang menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat moralitas sosial.
Paradigma sosio-legal, dengan semangat interdisipliner dan orientasi kemanusiaannya, menjadi fondasi bagi rekonstruksi ilmu hukum di abad ke-21.
Ia mengingatkan bahwa hukum, betapapun modern dan rasional sistemnya, pada akhirnya hanya bermakna sejauh ia mampu melayani manusia.