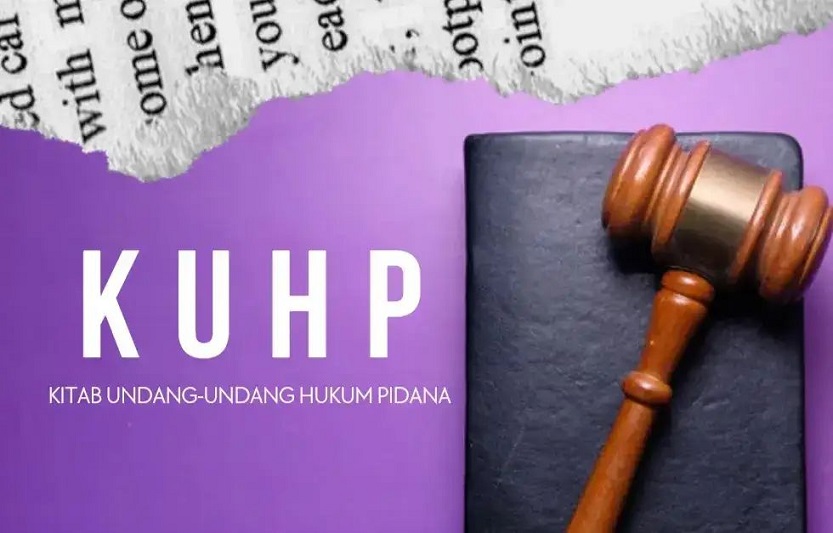Dinamika perkembangan hukum pidana Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dalam tiga babakan periodisasi.
Pertama, hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan (retributif) dengan paradigma daad-strafrecht (fokus pada perbuatan/tindak pidana) artinya sanksi pidana hanya ditujukan dan dikonsepsikan sebagai alat pembalasan semata dengan menekankan pada aspek penjeraan terhadap pelaku dan rasa takut kepada masyarakat.
Pada fase ini, hak-hak hukum pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) belum mendapatkan pelindungan yang berarti sehingga praktik-praktik penyiksaan dan kekerasan kerap terjadi.
Pada periodesasi hukum pidana yang pertama, konsep pemasyarakatan belum dikenal dalam tata hukum Indonesia dan hukum acara pidana masih menggunakan HIR. Istilah pemasyarakatan sendiri dikenal pertama kali pada 1963 yang dicetuskan oleh Dr. Saharjo (Menteri Hukum dan Kehakiman saat itu) dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia. Secara formal konsep pemasyarakatan mulai memiliki landasan yuridis formal sejak diundangkannya UU Pemasyarakatan pada 1995.
Kedua, hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan-tujuan tertentu (relatif) dengan paradigma daad-dader-strafrecht (fokus pada perbuatan dan pelaku tindak pidana). Periodesasi ini dimulai sejak UU Pemasyarakatan mulai diterapkan. Pada periodesasi ini, sanksi pidana tidak sekadar dijadikan alat pembalasan melainkan sebagai sarana reformasi untuk memperbaiki narapidana (resosialisasi).
Pemasyarakatan layaknya obat bagi orang 'sakit' yakni narapidana agar sembuh dan dapat melebur kembali ke dalam masyarakat sebagai pribadi yang baik untuk mendukung pembangunan bangsa.
Dalam periodisasi kedua ini, pusat perhatian dalam penegakan hukum pidana tidak hanya pada perbuatan pidana tetapi juga kepada pelaku sehingga kemudian pada tahap ini dikenal konsep mengenai individualisasi pidana.
Ketiga, hukum pidana yang berorientasi pada kepentingan korban. Jika pada periodesasi pertama dan kedua, sanksi pidana hanya berfokus pada perbuatan dan pelaku tindak pidana, pada periodesasi ketiga ini, sanksi pidana mulai memberikan perhatian terhadap korban sebagai pihak yang paling terdampak dari terjadinya tindak pidana.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana 2006 menjadi milestones eksistensi hukum pidana yang berorientasi pada kepentingan korban. Dari sinilah melembaga konsep restitusi dan kompensasi yang berfokus pada pemulihan hak-hak dan kepentingan hukum korban yang sebelumnya terampas akibat suatu tindak pidana.
Saat ini, lembaga-lembaga penegak hukum juga memiliki aturan internal sendiri terkait penegakan hukum berbasis keadilan restoratif.
Hal ini menandakan bahwa paradigma hukum pidana kita telah bergeser ke arah daad-dader-victim-strafrecht, fokus perhatian hukum pidana tertuju pada tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan korban tindak pidana secara integral. Maka kemudian dikenal varian-varian pendekatan dalam hukum pidana seperti diversi, restorative justice, strict liability, vicarious liability, dan individualisasi pidana.
Individualisasi pidana merupakan pendekatan hukum pidana yang meletakkan fokus dan atensi terhadap pelaku tindak pidana. Prof Sudarto dalam buku berjudul Hukum Pidana 1 Edisi Revisi (2018) menyatakan, individualisasi pidana artinya adalah dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku. Lebih lanjut, beberapa prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief terbagi dalam tiga komponen.
Komponen kesatu, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas personal). Komponen kedua, pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Komponen ketiga, penjatuhan sanksi pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Setiap pelaku memiliki latar belakang, kondisi, dan keadaan yang unik, sehingga hukuman yang diberikan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut.
Prinsip individualisasi pidana bertolak pada pentingnya pelindungan individu (pelaku tindak pidana) dalam sistem hukum pidana. Prinsip individualisasi pidana ini merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern hukum pidana sebagai kontradiksi terhadap aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan dan penjeraan (daadstrafrecht).
Individualisasi Pidana KUHP Baru
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang akan diterapkan mulai 2 Januari 2026 membawa spirit dekolonialisasi atau spirit perubahan dengan penguatan sistem hukum nasional, artinya substansi KUHP disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia dan kebutuhan dinamika zaman. KUHP baru membawa tiga spirit keadilan secara integral dalam teknis operasionalisasinya yakni keadilan korektif (bagi pelaku), keadilan rehabilitatif (bagi korban dan pelaku), dan keadilan restoratif (bagi korban).
Dalam KUHP baru prinsip individualisasi pidana diperkuat dan secara teknis dikonstruksikan dalam bentuk pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan representasi dari konsep individualisasi pidana karena dalam pedoman pemidanaan esensinya adalah dalam memberikan sanksi pidana harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku yang eksesnya kemudian hakim diberikan fleksibilitas atau keleluasaan untuk menentukan pidana yang paling tepat terhadap pelaku demi tegaknya hukum dan keadilan.
Oleh sebab itu, dalam KUHP baru ditentukan poin-poin personal dalam diri pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi bahan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan vonis pemidanaan maupun peniadaan vonis pidana meski terpenuhi aspek perbuatan melawan hukumnya.
Konsep pedoman pemidanaan pada KUHP Baru diatur dalam Pasal 54 ayat (1), bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a.bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pelaku tindak pidana; d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dari 11 aspek pedoman pemidanaan tersebut, delapan aspek (poin a hingga poin h) merupakan pengejawantahan dari konsep pendekatan individualisasi pidana. Artinya, karakteristik dan keadaan si pelaku menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Individualisasi pidana juga dapat menjadi dasar dari peniadaan vonis pidana meskipun perbuatan melawan hukumnya terpenuhi.
Hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (2), bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Dalam konteks ini, maka individualisasi pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai standardisasi bagi hakim untuk menggali nilai keadilan substantif.