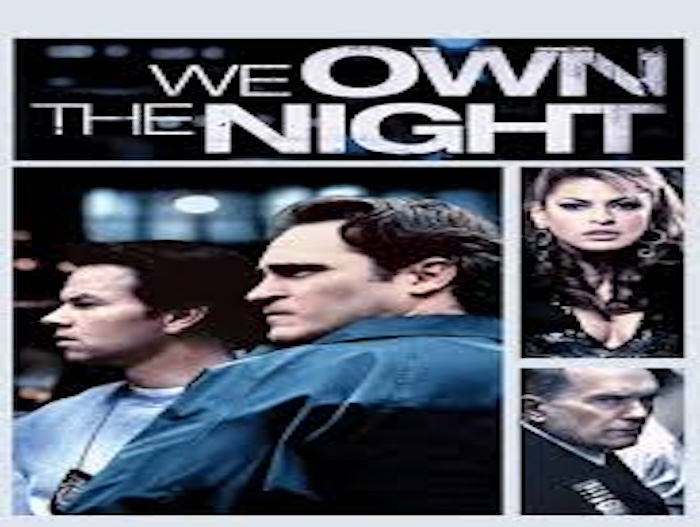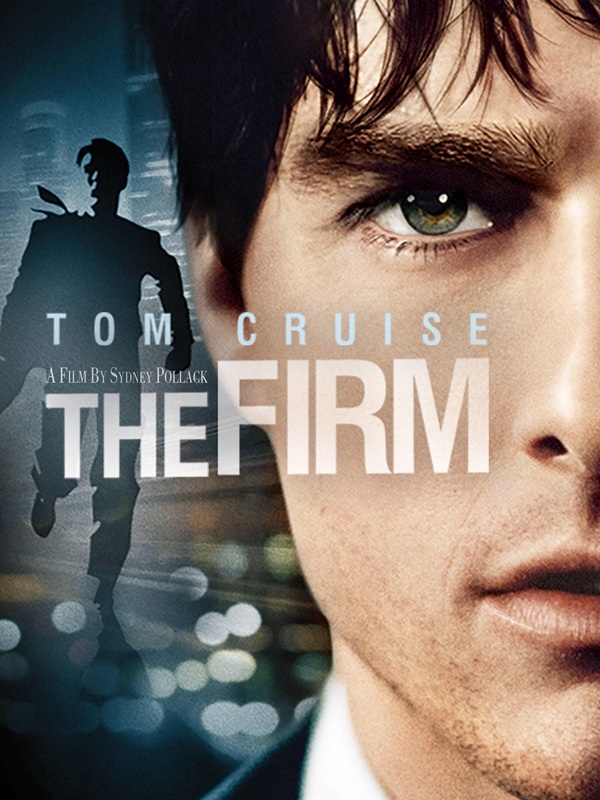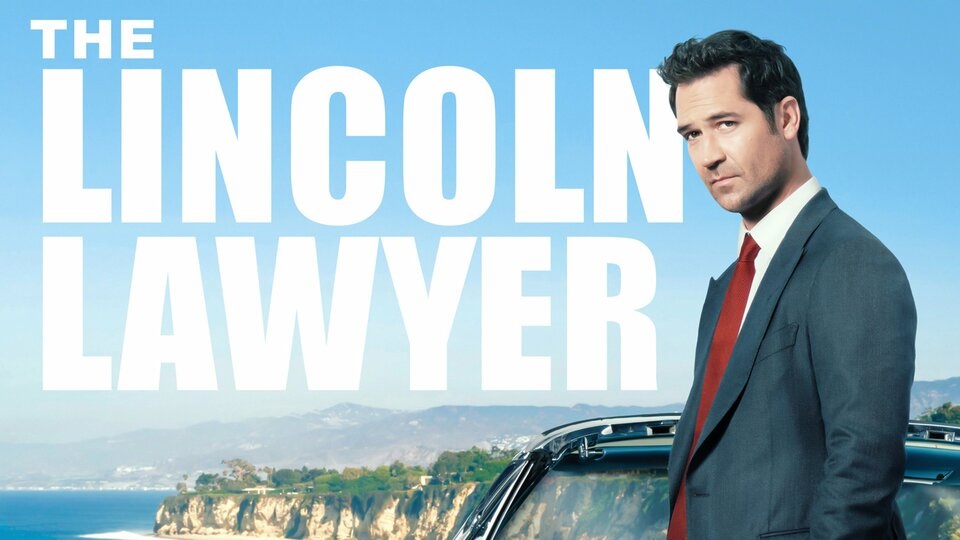Karya agung Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, melampaui batas-batas cerita cinta biasa. Di dalamnya terukir sebuah narasi yang menghujam, memperlihatkan bagaimana suatu “penghakiman” atas pelanggaran cinta yang tercabik oleh desakan adat, ekonomi, dan yang paling menyakitkan, oleh "keadilan" yang dipersepsikan secara personal.
Pusat dari drama ini adalah Zainuddin dan Hayati, dua jiwa yang terikat oleh takdir namun terpisah oleh pakem sosial Minangkabau awal abad ke-20.
Prahara Adat dan "Pelanggaran" Hayati
Kisah bermula dengan pertemuan Zainuddin, pemuda yatim berdarah campuran Minang-Bugis, dengan Hayati, kembang desa Batipuh yang berdarah murni Minang.
Cinta mereka bersemi, tulus dan mendalam, namun terganjal oleh status Zainuddin sebagai "orang asing" yang tak memiliki harta dan garis keturunan jelas, sebuah "cacat" fundamental dalam sistem matrilineal Minangkabau. “Hukum adat” yang kala itu berkuasa mutlak, dengan tegas menghakiminya sebagai suatu ketidakpantasan terhadap norma.
Zainuddin “terusir” dan Hayati “terkekang” oleh tekanan keluarga dan masyarakat. Di hadapkan pada pilihan sulit—mempertahankan cinta atau mematuhi adat—Hayati memilih yang kedua, menikahi Azis, seorang pria kaya dan terpandang.
Dari perspektif Zainuddin, keputusan Hayati adalah sebuah "pelanggaran kontrak" moral dan janji suci. Ia tidak hanya mengkhianati cinta, tetapi juga menghancurkan masa depannya. Di sinilah benih-benih "penghukuman" mulai ditanam.
"Pengadilan" dan "Putusan" Zainuddin: Sebuah Studi Kasus Retributif
Tahun demi tahun berlalu, Zainuddin bangkit dari keterpurukan. Ia merantau ke Batavia, menjadi sastrawan sukses di Soerabaja dengan nama pena "Tuan Zabir," bergelimang harta dan kehormatan.
Takdir mempertemukannya kembali dengan Hayati, yang kini menjadi janda terlantar setelah Azis bunuh diri akibat kebangkrutan dan gaya hidup hedonis.
Momen puncak, yang menjadi inti dari "penghukuman" ini, terjadi ketika Hayati memohon ampun dan kesempatan kedua kepada Zainuddin.
Dialog berikut bukan sekadar luapan emosi, melainkan sebuah "persidangan" personal yang sarat filosofi keadilan dan teori hukum:
Hayati: "Zainuddin, saya sudi menanggung segenap cobaan yang menimpa diriku, asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku."
Hayati tampil sebagai “terdakwa” yang memohon keringanan hukuman, mengakui kesalahannya, dan menawarkan dirinya untuk menerima konsekuensi apa pun asalkan mendapatkan pengampunan. Ini adalah panggilan terhadap prinsip kasih sayang dan pengampunan, yang seringkali bertentangan dengan “keadilan retributif.”
Zainuddin: "Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf."
Respon Zainuddin adalah pukulan telak. Ia tidak lagi melihat Hayati sebagai kekasih, melainkan sebagai pelanggar janji. Kata "maaf" di sini menjadi dangkal di hadapan kerusakan yang telah terjadi. Ini mencerminkan pandangan bahwa beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf, menyinggung konsep kerugian yang tidak dapat diperbaiki (irreparable harm).
Hayati: "Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini."
Hayati berargumen dari posisi kelemahan dan penderitaan, mencoba mengaktifkan sisi kemanusiaan Zainuddin. Ia memohon agar "hukuman" tidak dijatuhkan, mengacu pada nasib buruk yang bertubi-tubi menimpanya. Ini adalah permohonan untuk keadilan restoratif atau setidaknya pengurangan hukuman berdasarkan faktor-faktor mitigasi.
Zainuddin: "Demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan ia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah diantara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh ninik mamak mu, karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dina, tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke persimpangan jalan, kau berjanji akan menunggu kedatanganku? Berapapun lamanya? tapi kemudian kau berpaling pada yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. Dua bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur, kau jenguk saya dalam sakit ku menunjukkan bahwa tangan kau telah berinai. Menunjukkan bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah diantara kita yang kejam Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itik, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, beranang di dalam emas, bersayap uang kertas. Siapakah diantara kita yang kejam Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini. Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komedi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Tidak Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu hilangkan dan dilupakan saja? diganti dengan persahabatan yang kekal. Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulu memegang cintaku. Itulah sebabnya dengan segenap ridho hati ini, kau ku bawa tinggal dirumahku untuk menunggu suami mu, tapi kemudian bukan dirinya yang kembali pulang, tapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu sebagai seorang sahabat pula kau akan ku lepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu. Tanah minangkabau yang kaya raya yang beradat, berlembaga, yang tak lapuk dihujan, yang tak lekang di panas."
Monolog panjang Zainuddin adalah puncak dari "penghakiman" ini. Ia mengambil peran sebagai jaksa dan hakim sekaligus, dengan cermat membeberkan "bukti-bukti" pelanggaran Hayati:
- Pelanggaran Janji (Breach of Contract): Ia mengingatkan Hayati tentang janji untuk menunggu, yang kemudian dilanggar. Dalam teori hukum, ini adalah elemen fundamental dari pelanggaran kontrak, meskipun disini kontraknya bersifat personal dan emosional.
- Motif Materialistis: Zainuddin menyoroti pilihan Hayati pada Azis yang "lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat," serta surat Hayati yang menyebutkan kemiskinan sebagai alasan. Ini adalah tuduhan bahwa Hayati mengutamakan keuntungan materiil dan status sosial di atas cinta sejati.
- Kekejaman Balasan: Ia mengutip balasan surat Hayati yang "tersudu di itik, tak termakan di ayam," sebuah ungkapan pedih yang menggambarkan betapa kejamnya penolakan Hayati. Zainuddin berargumen bahwa tindakannya sekarang adalah cerminan dari kekejaman Hayati di masa lalu.
- Keadilan Retributif Personal: Pernyataan "Tidak Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu" adalah inti dari keadilan retributif yang ia jalankan. Zainuddin merasa bahwa ia hanya memberikan apa yang Hayati tanam. Jika Hayati meminta cinta mereka dilupakan, maka Zainuddin akan mewujudkannya dalam bentuk penolakan dan pengembalian Hayati ke habitat asalnya.
"Keputusan" Zainuddin adalah melepaskan Hayati pulang ke Minangkabau sebagai seorang "sahabat" atau "saudara," bukan kekasih. Ini adalah hukuman pengasingan emosional, sebuah penolakan total terhadap kembalinya status mereka sebagai pasangan.
Hayati: "Zainuddin, itukah keputusan yang kau berikan kepadaku? Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan dan biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang, berapapun banyaknya, saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin."
Hayati mencoba menolak "vonis" Zainuddin. Ia menawarkan untuk menerima hukuman serendah apa pun (menjadi babu), asalkan tetap berada di sisi Zainuddin.
Zainuddin: "Tidak. Pantang pisang berbuah dua kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang kembali ke Padang. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asalnya. Negeri Minangkabau beradat."
Ungkapan Zainuddin menegaskan kembali prinsip adat dan menutup pintu bagi rekonsiliasi.
Konsekuensi Tragis dan Keadilan yang Terluka
Dalam keputusasaan mendalam, Hayati menuruti "putusan" Zainuddin untuk kembali ke kampung halamannya dengan menumpang kapal Van der Wijck. Ironisnya, kapal itu tenggelam, dan Hayati menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Zainuddin, dengan penyesalan di matanya dan nama Zainuddin di bibirnya.
Tragedi ini menguak lapisan-lapisan kompleks tentang keadilan. Zainuddin yang telah "menghukum" Hayati dengan menolaknya, kini harus menyaksikan konsekuensi ekstrem dari keputusannya. Buya Hamka menutup kisah ini dengan refleksi bahwa putusan Zainuddin justru merugikan semuanya, karena kebahagiaan sejati hanya ada pada Hayati, namun telah pupus akibat penghukuman yang tidak berkeadilan.
Dari perspektif filosofi keadilan, kisah ini mengajarkan bahwa keadilan yang murni retributif, yang hanya berfokus pada pembalasan setimpal tanpa mempertimbangkan konteks, motif, atau potensi rekonsiliasi, seringkali gagal mencapai tujuan sejati.
Keadilan sejati mungkin memerlukan dimensi kasih sayang, pengampunan, dan pemahaman akan kompleksitas situasi manusia. Zainuddin, dalam usahanya menyeimbangkan "timbangan keadilan" atas penderitaannya, justru menciptakan ketidakadilan yang lebih besar bagi dirinya sendiri.
Kisah Zainuddin dan Hayati adalah peringatan abadi bahwa dalam labirin hati manusia, di mana cinta dan luka berjalin, pencarian akan "keadilan" seringkali menjadi pedang bermata dua yang justru melukai sang “penegak hukum” itu sendiri. Sebuah "hukuman" yang, pada akhirnya, tidak berkeadilan bagi siapa pun.