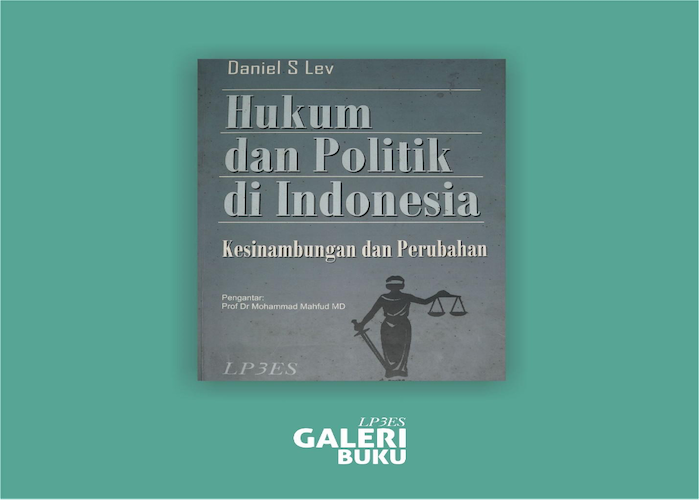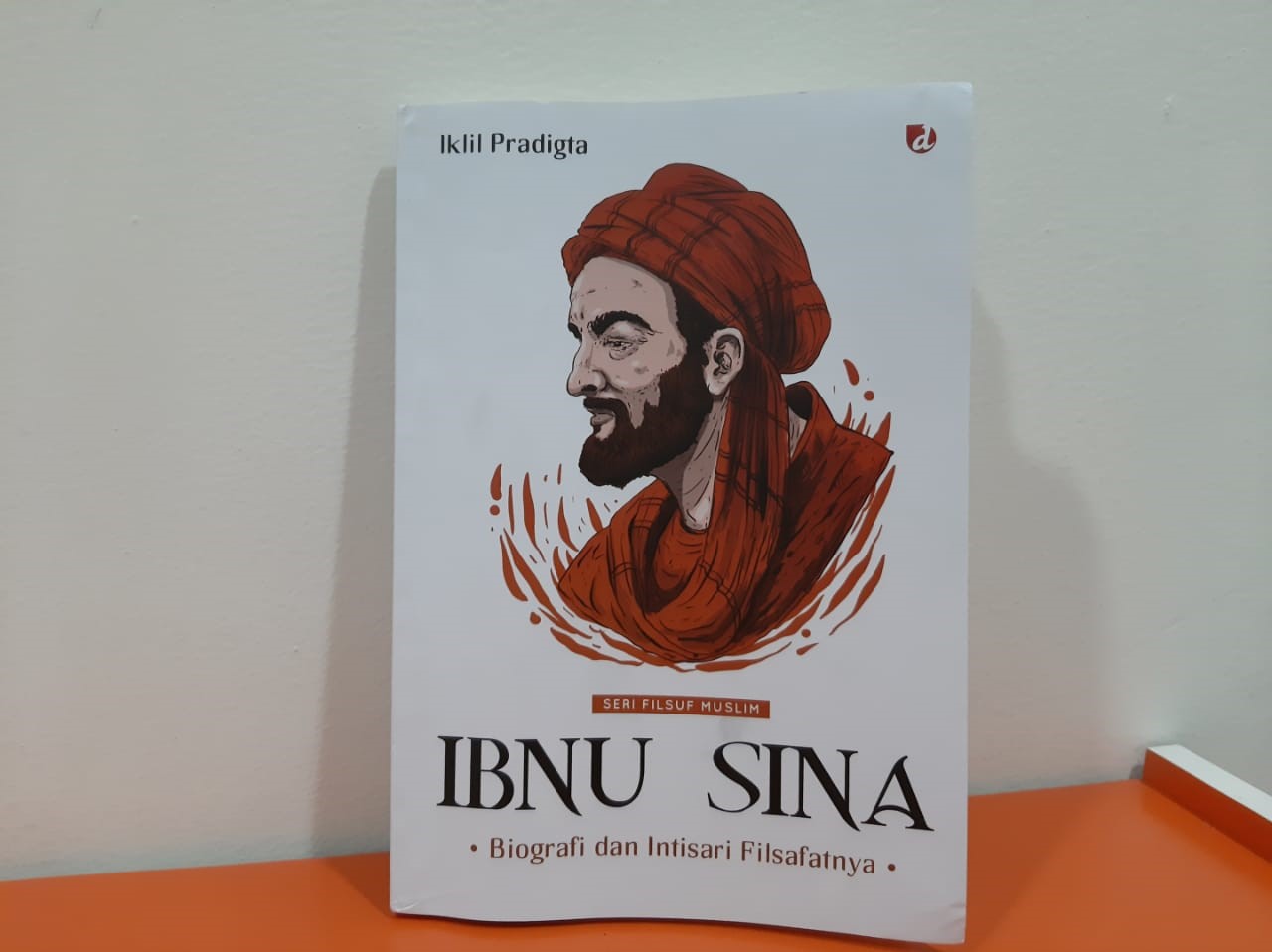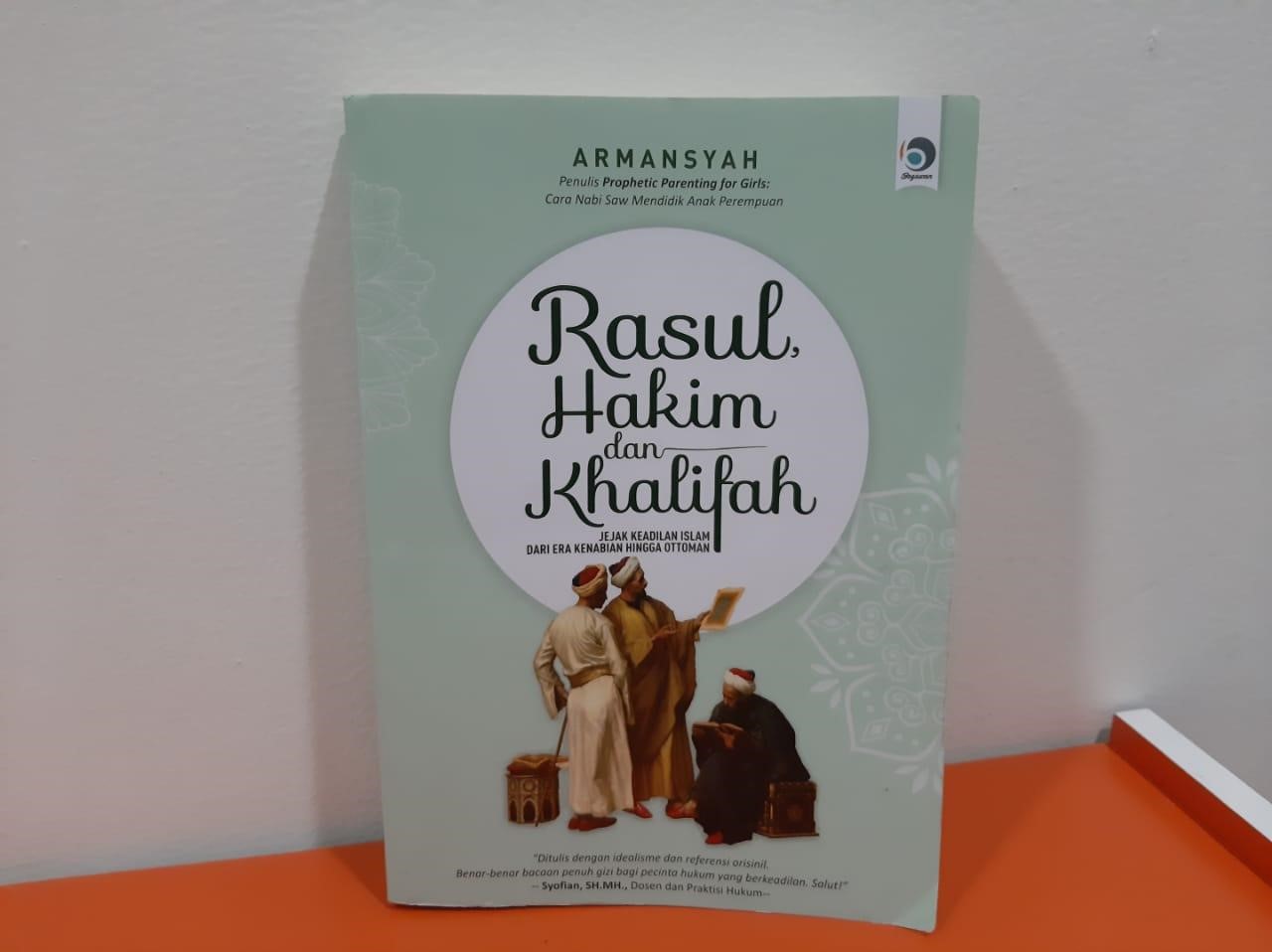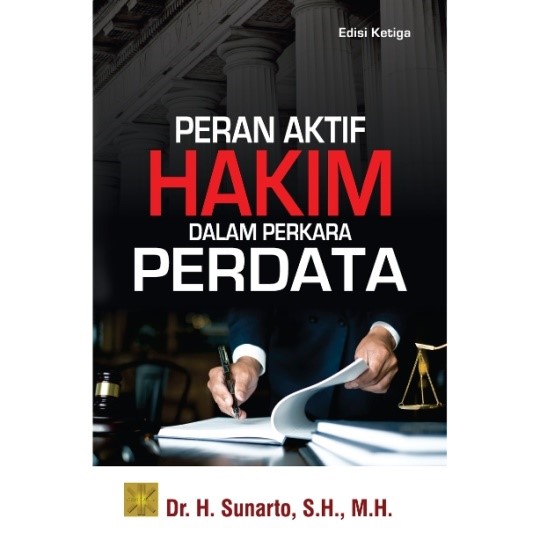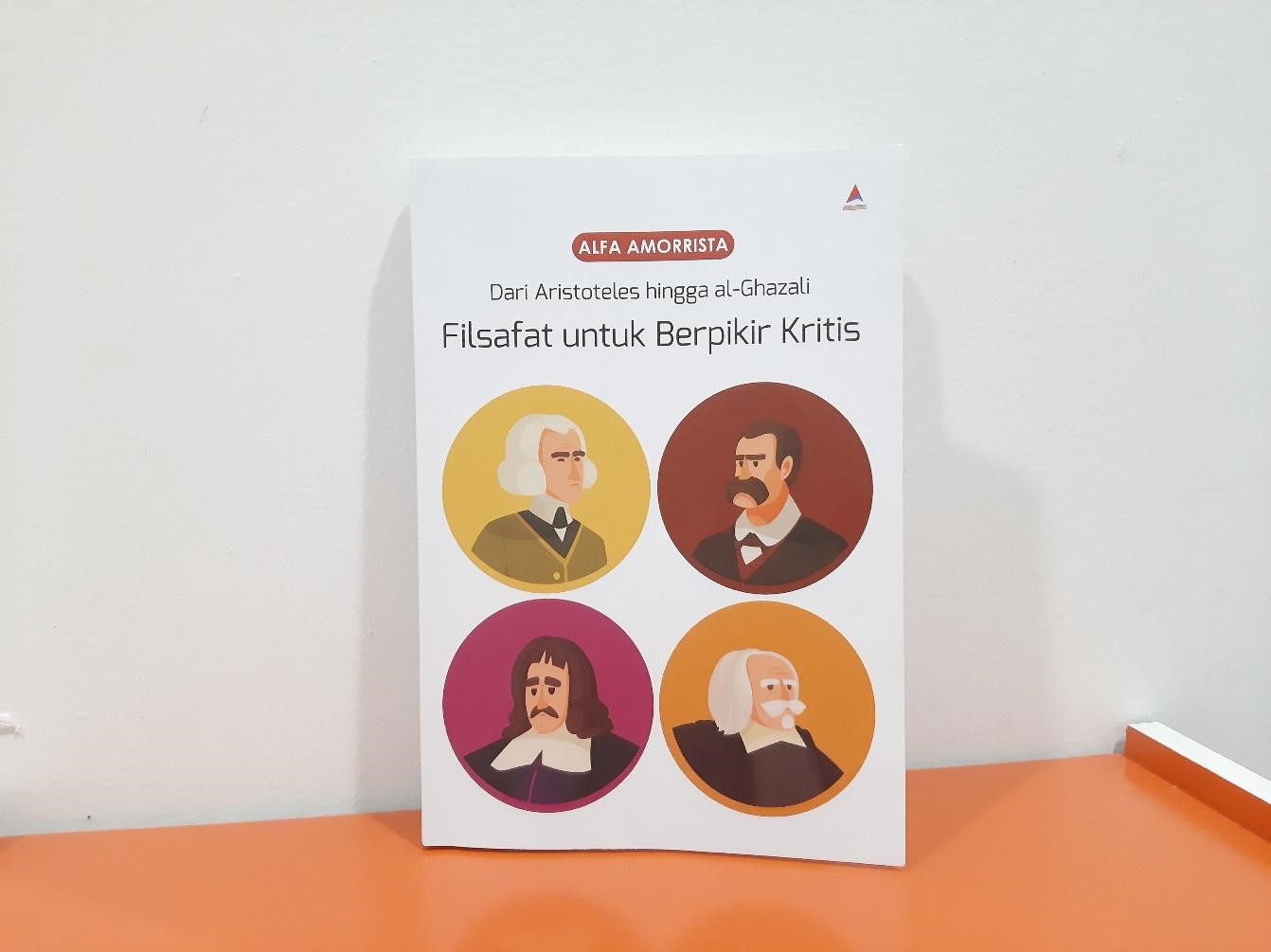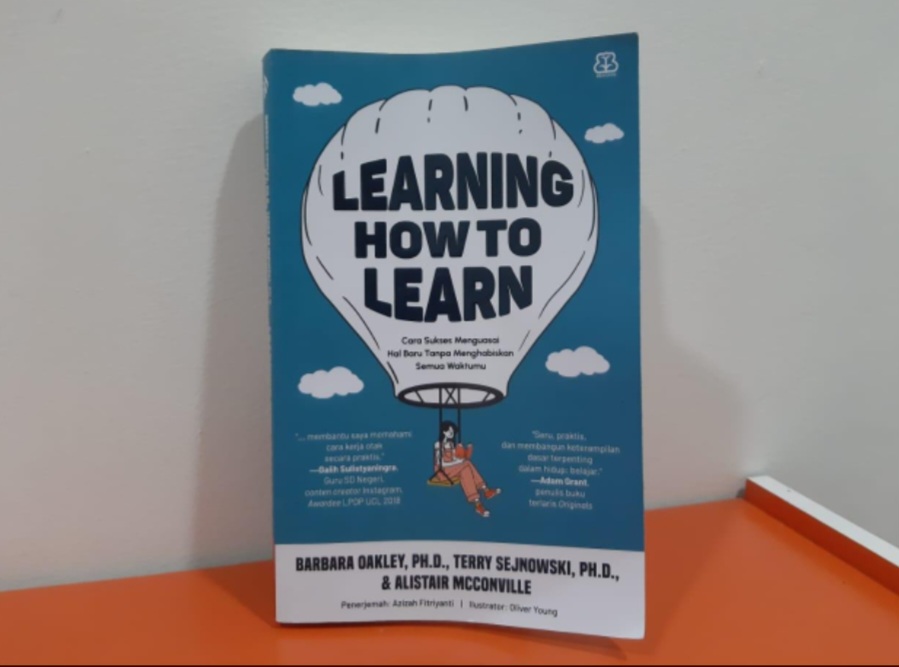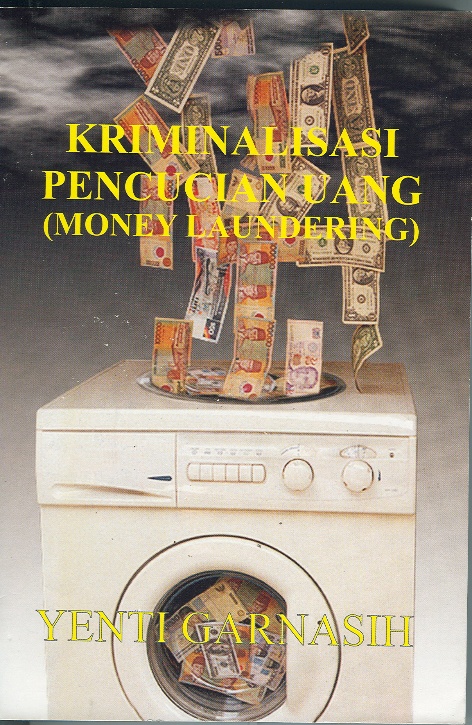Daniel S. Lev menuliskan dalam pengantar buku ini, bahwa hal yang menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik.
Daniel S. Lev berkeyakinan bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik. Hukum dapat mempengaruhi politik, atau sebaliknya hukum yang banyak dipengaruhi politik.
Daniel S. Lev tidak hanya menulis mengenai pengaruh politik dalam hukum formal, dalam artian hukum tertulis saja. Ia juga menulis lebih jauh mengenai bagaimana politik mempengaruhi hukum dalam praktik, hukum yang dijalankan setiap hari oleh hakim, jaksa, polisi, dan pegawai pemerintah pada umumnya.
Ia juga melihat lebih dalam yaitu dengan menganalisa proses hukum yang dialami oleh mereka yang harus berurusan dengan hukum.
Oleh karenanya, dalam melakukan penelitian, Daniel S. Lev tidak hanya membaca buku atau media massa saja, namun Ia juga melakukan wawancara dan observasi dengan segala macam orang, baik itu pimpinan Lembaga, pegawai atau masyarakat yang cenderung awam hukum.
Tulisan-tulisan sebagai hasil dari penelitian Daniel S. Lev itulah yang dikumpulkan dalam buku ini. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengumpulkan dan menerjemahkan 12 tulisan karya Daniel S. Lev pada September 1990 dan menerbitkannya dalam sebuah buku yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan.
Bila dilihat dari konteks peradilan, tulisan-tulisan dalam buku ini mencoba memotret beberapa momen penting. Dalam tulisan pertama yang berjudul “Mahkamah Agung dan Politik Hukum Waris Adat”, Daniel S. Lev memotret faktor-faktor yang mengubah konsepsi para hakim, termasuk Hakim Agung dalam perubahan hukum adat, serta penyusunan yurisprudensi mengenai hukum kekeluargaan adat.
Lebih jauh dalam tulisan ini, Ia mencoba menguraikan persoalan waris yang menurutnya paling sulit, yakni mengenai kedudukan istri (janda) dalam waris.
Ia menggambarkan diskursus para hakim agung sebagai penjaga kesatuan hukum mengenai kedudukan istri (janda) dalam waris, dikaitkan dengan bagaimana Pengadilan di bawahnya melakukan respons atas hal tersebut dan struktur masyarakat saat itu.
Dalam tulisan “Politik Pengembangan Kekuasaan Kehakiman”, Ia mengkaji mengenai tegangan antara para penegak hukum yaitu hakim, jaksa, dan polisi mengenai perkembangan Lembaga-lembaga peradilan pasca revolusi.
Tulisan ini memotret bagaimana prestise atau status aparat penegak hukum mempengaruhi prosedur pidana dan proses perubahan hukum, termasuk di dalamnya problem pembagian kekuasaan, yang akhirnya pada gambaran besarnya mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia sesudah kemerdekaan.
Dalam tulisan ini, Daniel S. Lev juga mencatat pada 1956 hakim melakukan mogok kerja, meskipun para hakim saat itu tidak menggunakan istilah “mogok.” Saat itu Hakim menolak memeriksa perkara karena tidak diposisikan dalam posisi yang terhormat baik dari sisi status ataupun kesejahteraan.
Selanjutnya dalam tulisan “Lembaga-Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia”, Ia mengkaji pola perubahan sistem hukum Indonesia pada masa Revolusi.
Termasuk di dalamnya, bagaimana proses politik dan ekonomi, serta nilai budaya, berkait dengan perubahan Lembaga peradilan secara umum.
Salah satu hal yang diulas dalam esai ini adalah mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan dilakukan secara kekeluargaan (konsiliasi), dan kaitannya dengan peradilan perdata saat itu.
Daniel S. Lev dalam tulisan “Unifikasi Pengadilan pada Masa Pasca Kolonial” menuliskan bahwa Ia memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan bahan mengenai perkembangan pengadilan nasional pada masa pendudukan Jepang, masa revolusi dan masa awal kemerdekaan.
Dalam tulisan ini Daniel S. Lev mengulas mengenai tegangan-tegangan yang terjadi dalam proses unifikasi hukum nasional dikaitkan dengan adanya pengadilan lokal atau pengadilan adat.
Kemudian pada 1977, dalam tulisan “Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Negara Hukum: Sebuah Sketsa Politik” Daniel S. Lev menitikberatkan pada persoalan yang timbul dalam pembaruan peraturan perundang-undangan terkait organisasi dan kekuasaan kehakiman.
Daniel S. Lev merekam dalam tulisan tersebut bahwa saat itu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Kementerian Kehakiman berdebat dengan sengit mengenai isi pemisahan kekuasaan negara. Para pemimpin IKAHI berpegang teguh pada prinsip trias politica.
Refleksi atas kebutuhan peradilan yang otonom ditulis oleh Daniel S. Lev dalam esai “Gerakan Sosial, Konstitusionalisme dan Hak Asasi.”
Lev menuliskan bahwa tuntutan akan adanya badan peradilan yang bebas merupakan respons atas kenyataan bahwa peradilan Indonesia dibatasi secara politik.
Menurut Lev, adanya kenyataan bahwa hakim-hakim merupakan pegawai negeri sehingga sebagaimana pegawai negeri lainnya seolah dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak pemerintah. Peradilan yang otonom akan lebih tanggap pada persoalan masyarakat karena cenderung tidak akan korup karena tidak tergantung pada perlindungan politik kekuasaan lain.
Signifikansi dari otonomnya kekuasaan peradilan ini, juga terletak pada gagasan bahwa hukum merupakan alat untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan perlu adanya pengawasan kelembagaan.
Sebastiaan Pompe menuliskan dalam obituari bahwa Daniel S. Lev adalah salah satu pelopor dalam bidang analisis sosial-politik hukum. Ia termasuk generasi pertama akademisi yang menjembatani kesenjangan tradisional antara ilmu hukum dan ilmu politik.
Ia menerapkan ilmu politik ke dalam bidang hukum, menggunakan relasi kuasa sebagai instrumen untuk menganalisis lembaga hukum dan hukum. Namun pada saat yang sama, Ia mengakui lembaga hukum dan praktisi hukum sebagai aktor yang memiliki otonominya sendiri.
Pendekatan ini khususnya relevan bagi Indonesia dimana setelah tahun 1957, ketika lembaga dan profesi hukum kehilangan otonominya dan hanya menjadi sekedar perpanjangan tangan elit politik.
Daniel S. Lev merupakan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Washington, Amerika Serikat.
Ia menyelesaikan Ph.D. di Universitas Cornell dengan disertasi berjudul “the Transition to Guided Democracy” pada 1966. Ia banyak melakukan studi Sejarah tentang masalah hukum dan politik di Indonesia.