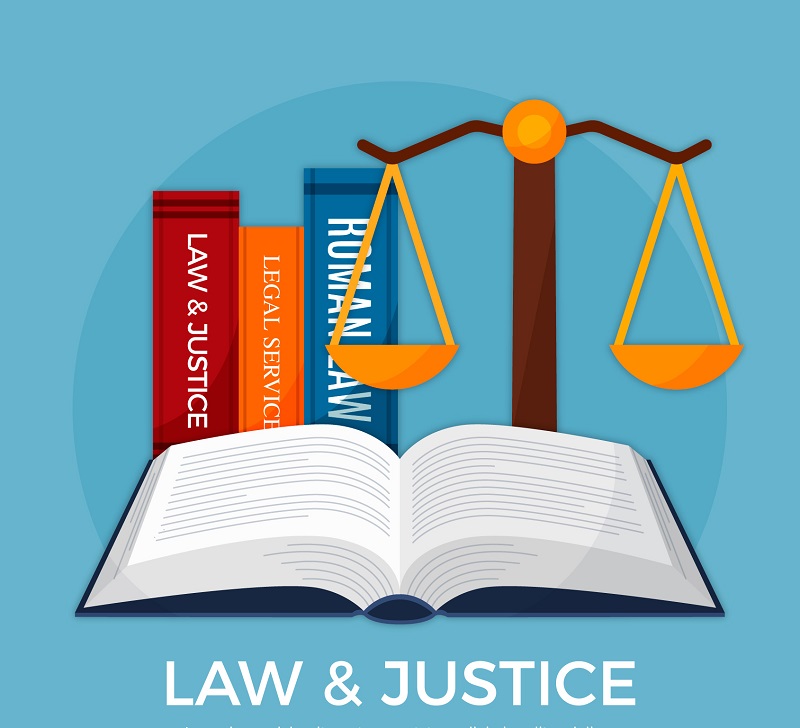“Consciousness is a fascinating but elusive phenomenon: it is impossible to specify what it is, what it does, or why it evolved.”
David Chalmers (The Conscious Mind, 1995).
Hukum menghadapi tantangan terberatnya dalam neurosains. Bagi Stephen J. Morse dalam The Philosophical Foundations of Law and Neuroscience mencatat: “Rational agency is thus fundamental to criminal responsibility and thus mental states are the royal road to ascriptions of responsibility” (Agensi rasional dengan demikian merupakan dasar yang fundamental bagi pertanggungjawaban pidana, dan oleh karena itu kondisi mental adalah elemen utama dalam meletakkan pertanggungjawaban) (Morse, 2016:35). Ini erat kaitannya dengan kehendak bebas.
Pengkaji lainnya dari Brookln Law School, Adam J. Kolber mengatakan, setidaknya kalau kita berbicara tentang seberapa bebas manusia dalam berkehendak (free will), ada dua posisi utama. Pertama, ada kendali lain di luar manusia yang membuatnya tidak pernah mungkin bertanggung jawab atas apapun. Kedua, sekalipun manusia dikendalikan oleh elemen eksternal apapun, ia tetap bisa dimintai pertanggungjawaban moral (Kolber, 2016:9).
Dari sisi neurosains, realitas sensorik adalah konstruksi atau “karangan” otak manusia: diciptakan oleh otak. Semua elemen panca indera bergerak mencari data, untuk selanjutnya dirangkai sebagai narasi pikiran. Organ mata manusia, misalnya, bergerak secara acak (saccades) ke berbagai sudut. Sederhananya, mata manusia dalam hitungan 20-200 mikrodetik (satu per seribu detik) mengumpulkan informasi seperti permainan petak-petak puzzle (NewScientist, 2018:35-36).
Singkatnya dari neurosains tidak ada hal riil yang dialami oleh manusia. Realitas pada dasarnya adalah “fiksi” serebral dan tidak pernah berkorelasi dengan kenyataan. Dalam istilah pakar neurosains Anil Seth (2017), manusia selalu berhalusinasi kapanpun dan di manapun. Yang membedakan realitas dengan kenyataan sesungguhnya (kasunyataan) adalah terkendali tidaknya halusinasi tersebut. Dunia manusia bagi Seth adalah “controlled hallucination” (halusinasi terkendali).
Kesadaran Bertindak dalam Hukum
Mungkin “realitas fiktif” semacam inilah yang menjadi tantangan bagi dunia hukum. Pakar hukum dari Universitas Duke, Nita A. Farahany, mencatat bahwa “Scholars claim that the law holds individuals responsible for their actions not because they are free, but because it is expedient to treat them as if they are free” (Para sarjana berpendapat bahwa hukum menempatkan individu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakannya bukan karena mereka sungguh-sungguh bebas, melainkan karena dianggap lebih bermanfaat untuk memperlakukan mereka seolah-olah bebas) (Farahany, 2016:53).
Pemikiran semacam itu, sejalan dengan catatan Kolber tentang jalur kedua, pada dasarnya dalam hukum seseorang bertanggung jawab penuh atas tindakannya, sekalipun misalnya secara neurosains ia tidak bisa sepenuhnya mengontrol tubuh dan pikirannya.
Sebuah landmark case dari Amerika Serikat, Hoskins v. State, 702 So.2d 202, 203–04 (Fla. 1997) (Hoskins I) (per curiam), dapat menjadi contoh bagaimana sekalipun neurosains telah memberikan catatan penting dan sangat ilmiah tentang intensi seseorang, hukum tetap berpatokan pada prinsip bahwa jalur yang kedua, manusia diniscayakan sebagai seolah-olah bebas.
Pada 1992, seorang anak perempuan berusia delapan tahun Dorothy Berger tewas dibunuh setelah sebelumnya dirudapaksa. Pelakunya adalah Johnny Hoskins, tetangga korban. Berbagai proses banding dilakukan oleh terdakwa dengan alasan hasil pindaian PET (Positron Emission Tomography-Tomografi Emisi Positron) menunjukkan bahwa bagian otak Hoskins yang berhubungan dengan rasionalitas tindakan mengalami gangguan (impairment).
Dengan kata lain, Hoskins tidak bisa mengendalikan dirinya karena memang otaknya secara fisik terganggu. Pengadilan akhirnya tetap memutus hukuman mati dan mengesampingkan keberatan dari sisi neurosains (Denno, 2016:69-70).
Dua pakar hukum, Michael S. Pardo dan Dennis Patterson, mengangkat artikel seminal dari Oliver Goodenough yang mengatakan bahwa “neuroscience will dispel our Cartesian presuppositions about the nature of law and turn our attention to the role of the brain in legal reasoning” (Neurosains akan menggugurkan prapemahaman Kartesian kita tentang hakikat hukum dan mengarahkan perhatian kita pada peran otak dalam penalaran hukum) (Pardo & Patterson, 232).
Bagi Pardo dan Patterson, selalu ada kemungkinan bahwa di masa depan hukum akan mengalami perubahan secara signifikan dan bahkan radikal karena neurosains. Meskipun demikian, untuk saat ini dilema untuk mengasumsikan manusia sebagai makhluk rasional dan sadar sepenuhnya (atau biasa disebut sebagai manusia Kartesian), atau menerima klaim yang diberikan oleh neurosains sebagai sebuah disiplin empirik masih sangat terbuka untuk diperdebatkan.
Manusia sebagai Subjek Hukum Berkesadaran
Mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar bukan persoalan sederhana (Seager, 2007:9-11). Sejak filsuf René Descartes dengan semboyan terkenalnya “aku berpikir maka aku ada” (cogito ergo sum), manusia selalu diasumsikan berkesadaran. Namun kesadaran manusia dalam pewacaan hukum saat ini cenderung datang dari sistem pemikiran Barat. Dari tradisi pemikiran India, “aku sadar” memiliki dua elemen utama: mengenali sesuatu (jñã) dan menyadari kehadiran sesuatu (buddh).
Secara umum, kesadaran adalah fenomena yang tidak mungkin dimaterialkan. Kesadaran bersifat eksternal, dan tidak diasumsikan sebagai sosok personal, seperti dalam pemikiran Barat. Prinsip ini dapat kita lihat dalam animisme dan dinamisme. Kehadiran kesadaran dalam entitas nonmanusia bukan sebuah persoalan pelik seperti di Barat (Dreyfus & Thompson, 2007:90). Singkatnya, menerima bahwa manusia berkesadaran dalam pemikiran Timur seperti di India tidak berarti mengatakan manusia sebagai satu-satunya pemilik kesadaran.
Pendekatan ini lebih mudah untuk menjadi pintu masuk tentang mengapa manusia menjadi subjek hukum berkesadaran, dan sekaligus melihat absurditas dari polemik neurosaintifik di Barat, dan akhirnya terpolarisasi menjadi dua kutub: manusia yang tidak mungkin sadar dan dipaksakan sadar. Pemikiran Timur ini juga gagasan untuk melihat kesadaran sebagai niat untuk melakukan suatu tindakan, pelaksanaan niat tindakan, atau persepsi atas akibat dari tindakan yang telah dilakukan (Umiltà, 2007:327).
Maksudnya, bila di Timur kesadaran dilihat sebagai kognisi, maka pendekatan ini melihatnya sebagai intensi dan kemampuan mengendalikan intensi. Membaca berkesadaran hukum dari dua perspektif ini bisa berarti: pertama, memiliki kesadaran karena mampu mengenali realitas (kognisi), dan kedua, berkesadaran karena mampu mengendalikan niat.
Secara kendali intensi, dalam kasus Hoskins v. State, ketidakmampuan Hoskins untuk mengendalikan intensinya dapat menjadi alasan vonis bersalah, lepas dari ada atau tidaknya kesadaran dalam tubuh manusia dari perdebatan Barat.
Menjadi Manusia Sadar Hukum
Pendekatan kognisi dan intensi dari kesadaran, dan bukan seberapa relevan otak sebagai satu-satunya instrumen kesadaran seperti yang diklaim neurosains, adalah dapat menjadi landasan pemikiran untuk menerima bahwa hukum harus disadari dan bukan reaksi spontan.
Meskipun berbeda dengan kelainan otak, menerima hukum atas dasar ketakutan sama irasionalnya dengan anomali kesadaran seperti klaim neurosains. Mengenali sebuah negara dan keberadaan masyarakat adalah ciri berkesadaran, yang akhirnya akan berlanjut pada kesadaran, bukan ketakutan, akan hukum. Bila niat manusia tidak bisa dikekang, maka upaya untuk mengendalikan niat jahat (mens rea), dapat menjadi tolak ukur dari seberapa sadar manusia akan tatanan yudisial.
Sebuah lembaga pemeringkatan, World Justice Project, melaporkan bahwa negara yang paling sadar hukum di dunia adalah Denmark, dengan nilai 0,90. Negara berperingkat terendah peringkatnya adalah Venezuela, dengan angka 0,26. Di Denmark, kekuasaan pemerintah dibatasi (indeks 0,94), sementara di Venezuela kekuasaan pemerintah hampir tanpa batas (indeks 0,18).
Ini berarti masyarakat di Denmark adalah masyarakat yang sadar hukum, karena meskipun pemerintah tidak memiliki otoritas mutlak, namun rakyatnya mampu menjamin pelaksanaan hukum. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) di Denmark juga sangat tinggi, dengan skor 0,962 pada tahun 2023. Dengan kata lain, kualitas manusia sejalan dengan kesadaran hukumnya (Our World in Data, 2025).
Kesimpulannya, perdebatan antara hukum dan neurosains menunjukkan bahwa kesadaran manusia tetap menjadi inti persoalan dalam filsafat hukum. Hukum pada akhirnya tidak hanya berurusan dengan otak sebagai organ biologis, melainkan dengan manusia sebagai subjek berkesadaran, mampu mengenali realitas dan mengendalikan intensinya.
Dengan demikian, persoalan tanggung jawab hukum tidak semata-mata ditentukan oleh klaim neurosains mengenai determinisme atau gangguan saraf, melainkan oleh pengakuan filosofis bahwa hukum hanya bermakna ketika dijalankan oleh manusia yang sadar akan tindakannya.
Kesadaran hukum, dalam hal ini, bukanlah hasil dari paksaan ataupun sekadar reaksi, melainkan pilihan reflektif yang meneguhkan manusia sebagai pelaku rasional sekaligus entitas moral dalam tatanan yuridis.