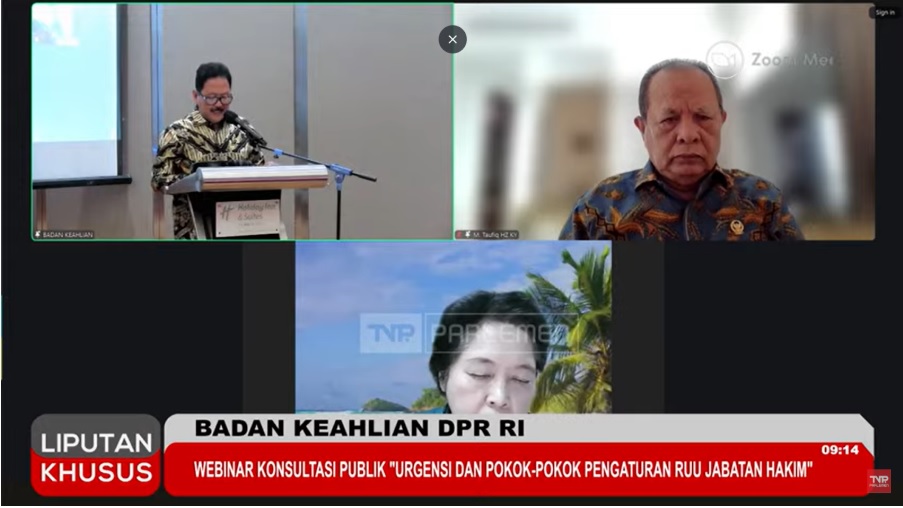Perdebatan mengenai status dan kedudukan hakim kembali mencuat pascadiskusi daring Mahkamah Agung (MA) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim pada Selasa (15/7) dan Webinar Konsultasi Publik Badan Keahlian DPR RI pada Rabu (16/7).
Fokus utama diskusi adalah status ganda hakim sebagai pejabat negara sekaligus Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta urgensi pengaturan khusus melalui RUU Jabatan Hakim. Tulisan ini bertujuan menganalisis implikasi penetapan hakim sebagai pejabat negara murni dan konsekuensinya dalam system kepegawaian.
Secara normatif, tidak terdapat definisi baku mengenai "Pejabat Negara" dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya (UU No. 8/1974 dan UU No. 43/1999) maupun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang berlaku saat ini (UU No. 5/2014 dan UU No. 20/2023) hanya menyebut istilah "Pejabat Negara" dalam konteks mengatur konsekuensi kepegawaian bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara. Ketiadaan definisi ini menyebabkan ketidakjelasan kriteria suatu jabatan dapat dikategorikan sebagai pejabat negara.
Draf RUU Jabatan Hakim (14 Juli 2025) menawarkan definisi konseptual: "Pejabat negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
Definisi itu menegaskan, pejabat negara memiliki peran inti dalam penyelenggaraan negara. Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48/2009 secara tegas menyatakan, hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.
Ketentuan ini menegaskan, bahwa fungsi peradilan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan negara di ranah yudikatif, sehingga legitimasi status hakim sebagai pejabat negara tidak diragukan.
Namun, Pasal 57 UU ASN No. 20/2023 hanya menyebutkan jabatan-jabatan hakim (ketua, wakil ketua, ketua muda, Hakim Agung MA, serta Ketua, wakil ketua, dan hakim di semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc) tanpa mengatur mekanisme pengangkatan PNS menjadi pejabat negara serta pemberhentiannya.
Ini berbeda dengan ketentuan Pasal 59 UU ASN yang jelas mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sementara bagi PNS yang menjadi pejabat negara selain hakim.
Ketiadaan pengaturan khusus dalam UU ASN mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim sebagai pejabat negara inilah yang menimbulkan ambiguitas dan menjadi akar persoalan status ganda. Kekosongan hukum ini, menyebabkan status PNS secara de facto dianggap masih melekat pada hakim, meskipun secara de jure mereka adalah pejabat negara berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman. Berbeda dengan ketentuan UU No. 43/1999 (UU Kepegawaian) sebelum disahkannya UU ASN yang menyebutkan Hakim sebagai pejabat negara tertentu yang mana terhadap pejabat negara tertentu ini status PNS masih melekat ketika diangkat sebagai Hakim.
Meskipun mekanisme pengangkatan hakim selama ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang terakhir kalinya rekrutmen pengangkatan hakim diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Hakim yang ditentukan, bahwa hakim berasal dari jabatan Analis Perkara Peradilan (PNS) Tahun Anggaran 2021. Pengaturan pada level peraturan di bawah undang-undang ini dianggap tidak cukup kuat, dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar mengenai status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Persoalan fundamental seperti ini memerlukan penyelesaian dan kepastian hukum pada tingkat undang-undang.
Menetapkan hakim sebagai pejabat negara murni (tanpa status PNS) memiliki konsekuensi signifikan dalam sistem kepegawaian:
1. Pola Rekrutmen dan Karir: Hakim merupakan satu-satunya pejabat negara yang saat ini memiliki pola karir melalui proses rekrutmen PNS dan jenjang kenaikan pangkat/golongan.
Pejabat negara lain umumnya bersifat periodik dan diangkat berdasarkan proses pemilihan atau pertimbangan elektabilitas atau politik. Penghapusan status PNS berarti menghapus sistem karir berbasis pangkat atau golongan PNS ini dan memerlukan penggantinya (hal ini telah diterapkan dalam jabatan TNI dan/atau POLRI yang memiliki sistem karir tersendiri).
2. Mekanisme Pengangkatan & Pemberhentian: Perlu dirumuskan secara jelas dalam undang-undang mekanisme pengangkatan hakim sebagai pejabat negara dan pemberhentiannya dari jabatan tersebut, termasuk konsekuensi setelah pemberhentian (kembali sebagai PNS atau tidak).
Hak dan Kewajiban Kepegawaian: Segala hak dan kewajiban yang melekat pada status PNS (seperti tunjangan, pensiun, disiplin PNS) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tidak lagi berlaku. Perlu dibangun sistem hak dan kewajiban kepegawaian tersendiri bagi hakim sebagai pejabat negara di bidang yudikatif.
3. Independensi dan Akuntabilitas: Argumen utama pendukung status pejabat negara murni adalah memperkuat independensi hakim dari struktur birokrasi pemerintahan (eksekutif). Namun, ini juga harus diimbangi dengan sistem akuntabilitas yang kuat dan khusus bagi hakim.
Penutup
Ambivalensi status hakim sebagai pejabat negara sekaligus PNS yang bersumber dari kekosongan pengaturan dalam UU ASN menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerancuan konseptual. RUU Jabatan Hakim muncul sebagai respons untuk memberikan kepastian dan kejelasan menyeluruh mengenai status, kedudukan, hak, kewajiban, pengangkatan, pemberhentian, dan pola karir hakim.
Memutuskan apakah hakim akan menjadi pejabat negara murni atau mempertahankan status ganda dengan mekanisme yang jelas, serta merancang konsekuensi kepegawaiannya secara komprehensif, merupakan hal mendesak yang perlu diatur dalam payung hukum setingkat undang-undang.
Pengaturan melalui PERMA, dinilai tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini. Keberadaan RUU Jabatan Hakim menjadi krusial untuk memperkuat posisi, independensi, dan akuntabilitas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.