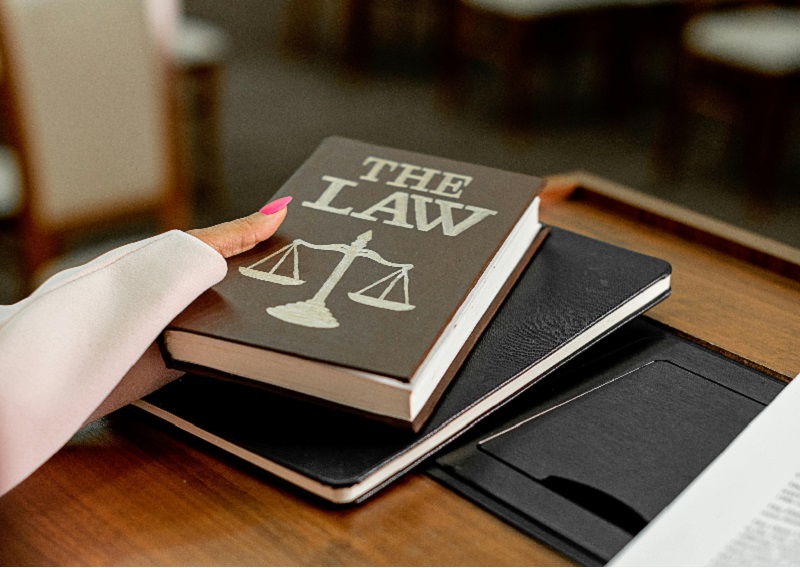Setidaknya ada dua ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam teori hukum pidana, yakni ajaran monistis dan ajaran dualistis.
Ajaran monistis yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bagian dari unsur delik. Sedangkan ajaran dualistis yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan bagian dari rumusan unsur delik. Kedua ajaran ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Kelebihan dari ajaran monistis adalah pertanggungjawaban pidana menjadi jelas, sebab ia merupakan bagian dari unsur. Sehingga hakim dan jaksa harus membuktiannya sebagai bagian dari delik.
Kekurangan dari ajaran monistis adalah bahwa ia menyatukan antara perbuatan material (materiele daad) dengan sikap batin/niat jahat (mens rea). Misalnya dalam kasus pencurian, Pasal 362 KUHP Lama (UU No. 1/1946) mengatur adanya unsur sikap batin berupa “dengan maksud untuk dimiliki” (bahasa lain dari dengan sengaja), dan unsur tersebut disatukan dengan unsur perbuatan materiil delik pencurian yakni “mengambil barang milik orang lain”.
Padahal sikap batin bukanlah bagian dari perbuatan materiil. Sehingga kekurangannya lebih bersifat kekurangan teoritis bukan kekurangan praktis.
Di sisi lain, kelebihan dari ajaran dualistis adalah ia benar secara teori, sebab unsur pertanggungjawaban pidana adalah sikap batin, bukan perbuatan materiil. Sehingga memang sebenarnya ia bukan bagian dari delik yang berisi tentang perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana kemudian diatur tersendiri, bukan sebagai rumusan unsur delik.
Namun, di sisi lain, kemudian menjadi sulit membedakan antara delik yang mengandung kesalahan berupa kesengajaan (dolus) dan yang mengandung kesalahan berupa kealpaan/kelalaian (culpa). Sehingga dalam delik-delik yang mengandung kesalahan berupa kelalaian (culpa) unsur kelalaian dimasukkan sebagai unsur delik.
Pada akhirnya ajaran dualistis ini menjadi tidak konsisten karena tetap memasukkan unsur kelalaian sebagai unsur delik dalam delik-delik kelalaian. Padahal kelalaian adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana yang merupakan sikap batin, bukan bagian dari perbuatan materiil.
KUHP Lama menganut ajaran monistis, artinya kesengajaan merupakan unsur dari delik meski pun ia merupakan sikap batin.
Sedangkan KUHP Baru menganut ajaran dualistis, yakni sebagian besar deliknya yang merupakan delik kesengajaan justru tidak mengandung unsur kesengajaan tetapi unsur kesengajaan itu diatur dalam Pasal 36 yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana. Namun ternyata terdapat beberapa inkonsistensi dalam penerapan ajaran dualistis pada KUHP Baru.
Inkonsistensi Penggunaaan Ajaran Dualistis dalam Beberapa Delik di KUHP Baru
Inkonsistensi tidak hanya ada pada ajaran dualistis dalam pertanggungjawaban pidana terkait unsur kesalahan. Mengenai unsur melawan hukum pun demikian. Pasal 12 KUHP Baru mengatur bahwa Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
Namun tetap saja ada delik-delik tertentu mengandung unsur melawan hukum misalnya Pasal 257 ayat (1) KUHP Baru yakni Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam rumah orang lain (trespassing).
Lagi pula rumusan Pasal 12 ini keliru sebab setiap tindak pidana pasti mengandung unsur melawan hukum. Jika tidak melawan hukum maka ia bukan tindak pidana. Contoh, adanya dasar pembenar maka menghapus unsur melawan hukum, sedangkan adanya dasar pemaaf menghapus kesalahan.
Justru kesengajaanlah yang tidak pasti merupakan unsur pidana, sebab ada delik kealpaan. Namun topik tulisan ini bukan mengenai unsur melawan hukum tetapi mengenai unsur kesalahan (geen straf zonder schuld) dalam ajaran dualistis pada KUHP Baru.
Dalam konteks Inkonsistensi yang terjadi terkait dengan unsur kesengajaan, walau pun unsur kesengajaan sudah dianggap ada (inherent) atau terinkorporasi dalam delik menurut ajaran dualistis dalam Pasal 36 KUHP Baru, tetap saja ada delik-delik tertentu yang mengandung unsur “dengan sengaja”. Misalnya Pasal 332 ayat (1) KUHP Baru yakni Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun (Hacking).
Artinya penerapan ajaran dualistis dalam KUHP Baru ini tidak konsisten. Sebab ada beberapa delik yang meskipun sudah dianggap ada unsur kesengajaan dalam Pasal 36 KUHP Baru, tetap saja diberikan unsur sengaja dalam rumusan deliknya.
Kenapa dengan adanya ajaran dualistis dalam Pasal 36 KUHP Baru masih ada delik-delik yang mengandung unsur kesengajaan? Dengan adanya inkonsistensi penerapan ajaran dualistis ini maka patut dipertanyakan, apakah memang unsur sengaja ini wajib menjadi unsur delik atau tidak? Sebab hal ini akan berakibat pada pembuktian terkait pertanggungjawaban pidana.
Inkonsistensi Konsep dan Pengaturan Pembuktian Unsur Kesengajaan Ajaran Dualistis KUHP Baru
Inkonsistensi penerapan ajaran dualistis ini juga terbukti dengan adanya kewajiban pembuktian unsur kesengajaan. Menurut Rudi Pradisetia Sudirdja, “Elementen atau unsur yang tidak tertulis tidak dibuktikan dan dianggap ada, kecuali dibuktikan sebaliknya yang diajukan oleh pihak terdakwa.”
Dengan demikian harusnya hakim dan penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan dari terdakwa. Bahkan Terdakwa harus membuktikan ketiadaan unsur kesengajaan agar ia terbebas dari jerat pidana.
Ini mengindikasikan adanya pembuktian terbalik dalam setiap delik kesengajaan. Namun menurut Rudi Pradisetia Sudirdja, Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP Baru justru mewajibkan setiap tahapan (termasuk hakim dan penuntut umum) membuktikan kesengajaan. Ini jelas tidak konsisten dengan ajaran dualistis.
Pasal 36 ayat (2) KUHP Baru (UU No. 1/2023) mengatur bahwa pada pokoknya Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pertanyaannya, kenapa kealpaan harus diatur tegas sebagai unsur delik sedangkan kesengajaan tidak?
Di dalam Penjelasan Pasal lain yakni misalnya Pasal 458 ayat (1) KUHP Baru, tujuan dari tidak dicantumkannya unsur Kesengajaan dalam delik non-kealpaan adalah:
“Dalam ketentuan ini tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.”
Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 458 ayat (1) tersebut apakah hakim tidak perlu membuktikan adanya kesengajaan dalam pembunuhan?
Jika ajaran dualistis dalam KUHP Baru memisahkan pertanggungjawaban pidana, khususnya unsur kesengajaan dalam bab tersendiri bukan sebagai unsur delik dengan alasan bahwa kesengajaan adalah sikap batin bukan perbuatan materiil, harusnya unsur kesengajaan dalam Pasal 458 ayat (1) KUHP Baru tetap tidak perlu dibuktikan.
Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 458 ayat (1) KUHP Baru, maka seolah hakim tidak perlu membuktikannya dan dapat lebih mengutamakan mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat. Sehingga antara Pasal 36 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 458 ayat (1) KUHP Baru bertentangan satu sama lain.
Penjelasan Pasal 458 ayat (1) KUHP Baru tersebutlah yang sebenarnya menggambarkan ajaran dualistis yakni hakim tidak perlu mempertimbangkan kesengajaan. Terdakwalah yang harusnya membuktikan secara terbalik bahwa ia tidak memiliki kesengajaan.
Tidak Tercapainya Efektivitas dan Efisiensi Praktik Penerapan Ajaran Dualistis KUHP Baru
Dengan adanya inkonsistensi mengenai penggunaan/penerapan ajaran dualistis dalam delik-delik KUHP Baru dan inkonsistensi pengaturan mengenai kewajiban pembuktian unsur kesengajaan dalam delik-delik dalam KUHP Baru, maka timbul pertanyaan. Apakah dengan demikian ajaran dualistis ini efektif dan efisien diterapkan secara praktik?
Dengan adanya inkonsistensi penggunaan unsur kesengajaan dalam delik-delik tertentu seperti dalam delik trespassing pada Pasal 257 ayat (1) KUHP Baru maka ajaran dualistis ini menjadi tidak efektif. Sebab masih ada beberapa pasal yang memasukkan kesengajaan sebagai rumusan delik di dalamnya.
Selain itu unsur kesengajaan ini tidak hanya digambarkan dengan kata “Sengaja” tetapi juga dengan frasa/kata lain (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP Baru) yakni di antaranya:
- “dengan Maksud” (misal Pasal 188 ayat (2) KUHP Baru);
- "mengetahui” (misal Pasal 195 ayat (1) huruf c KUHP Baru);
- "yang diketahuinya" (misal Pasal 206 KUHP Baru);
- "padahal diketahuinya" (misal Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru); atau
- "sedangkan ia mengetahui" (tidak ada contohnya di KUHP Baru).
Contoh-contoh di atas menggambarkan bahwa pada dasarnya penerapan ajaran dualistis di KUHP Baru tidak efektif sebab tidak konsisten.
Jadi apa tujuannya menghapuskan unsur kesengajaan dalam beberapa delik dan memasukkannya ke dalam ketentuan umum (Pasal 36 KUHP Baru) jika kemudian unsur kesengajaan muncul lagi di Pasal-Pasal delik lain?
Selain tidak efektif, ia juga tidak efisien. Menurut Rudi Pradisetia Sudirdja, “Rumus pemidanaan dalam ajaran dualistis adalah tindak pidana + pertanggungjawaban pidana = pidana dan pemidanaan”. Sehingga selain membuktikan unsur-unsur delik, harus juga dibuktikan unsur pertanggungjawaban pidananya agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan pidana dan dapat dipidana.
Pertanyaannya, berdasarkan rumusan tersebut, jika kesengajaan telah menjadi unsur dalam delik, apakah tetap harus dibuktikan lagi pertanggungjawabannya sebagai unsur terpisah? Misal dalam delik trespassing pada Pasal 257 ayat (1) KUHP Baru yang di dalamnya mengandung unsur dengan sengaja. Di mana letak unsur kesengajaan dalam rumusan tersebut? Apakah ia terletak di bagian tindak pidana, atau di bagian pertanggungjawaban pidana?
Dalam putusan hakim, pertimbangan mengenai kesalahan (schuld terutama berupa kesengajaan/dolus) akan menjadi rancu, apakah ia harus dipertimbangkan sebagai rumusan delik, atau terpisah sebagai rumusan pertanggungjawaban pidana? Sebab jika digabung sebagai rumusan delik maka tidak sesuai dengan ajaran dualistis yang memisahkan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana. Sedangkan jika dipisah dan tidak dipertimbangkan sebagai unsur delik maka hakim tidak sempurna dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik, sehingga putusannya bisa batal.
Di sisi lain jika pertimbangan kesengajaan dilakukan dua kali, dalam pertimbangan unsur delik dan juga dalam pertanggungjawaban pidana, maka hal ini tentu tidak efisien. Namun mengingat ia merupakan bagian yang terpisah menurut ajaran dualistis maka harusnya ia wajib dipertimbangkan terpisah.