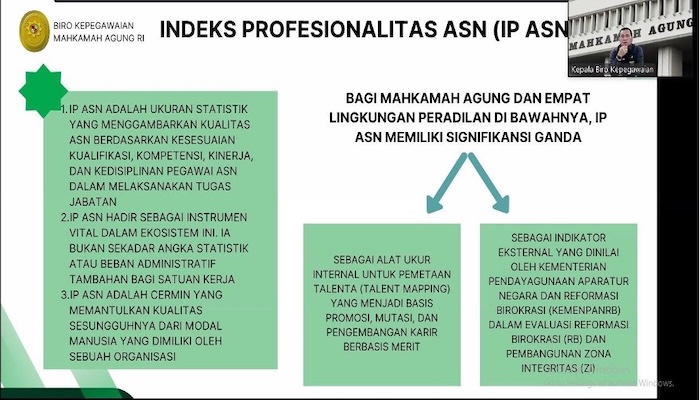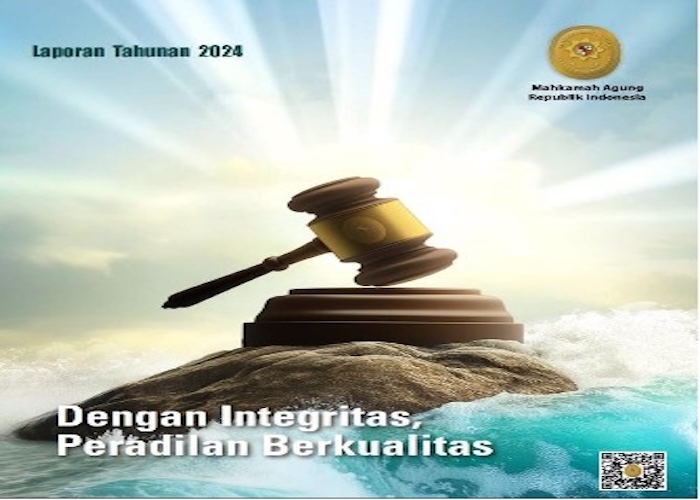Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kedudukannya diatur secara tegas dalam Pasal 24 dan 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menerangkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kedudukan MA sebagai lembaga negara memiliki makna strategis, karena berperan sebagai the highest judicial body atau pengadilan tertinggi yang menjalankan fungsi pengawasan, pemutus akhir, sekaligus penjaga konsistensi hukum di Indonesia.
Secara konstitusional MA merupakan puncak dari seluruh struktur peradilan di Indonesia (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara), kedudukan ini mencerminkan prinsip kesatuan peradilan di Indonesia, serta memperlihatkan MA tidak hanya menjadi Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, tetapi juga simbol supremasi hukum dan keadilan yang bersifat final dan mengikat.
Adapun salah satu fungsi MA yakni mengatur. Fungsi pengaturan dimaknai sebagai kewenangan MA untuk menetapkan ketentuan hukum dalam rangka mengisi kekosongan norma atau aturan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu aspek yang membedakan MA, dari lembaga peradilan lain adalah kewenangannya dalam melaksanakan fungsi mengatur (regelende functie).
Fungsi ini memberikan legitimasi bagi MA untuk mengeluarkan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan peradilan dan hukum acara, yang dikenal sebagai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
Berdasarkan perspektif ketatanegaraan, fungsi ini mengandung signifikansi strategis, sebab wujud menunjukkan MA tidak semata-mata menjadi lembaga adjudikatif, tetapi juga berperan sebagai pembentuk norma hukum dalam lingkup tertentu, baik yang bersifat mengatur (regeling), keputusan (beschikking) dan surat edaran.
Adapun substansi surat edaran, adalah arahan pimpinan untuk penyelenggaraan tertib peradilan agar ada sebuah kelancaraan dan mengatur sebuah hal tertentu yang sifatnya penting dan mendesak atau beleidsregel (Sugiarto, 2024).
Secara spesifik, Pasal 79 UU MA memberikan kewenangan bagi MA untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, fungsi mengatur bukanlah hasil ekstrapolasi, melainkan otoritas yang dilekatkan secara eksplisit oleh hukum positif.
Kedudukan dan landasan filosofis fungsi mengatur MA berakar pada kebutuhan institusional untuk memastikan kelancaran, efisiensi, dan keseragaman proses peradilan di seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
Sedangkan landasan filosofisnya adalah prinsip keadilan substansial dan kepastian hukum.
Fungsi ini menjadi instrumen kebijakan yudisial (judicial policy), yang krusial dalam menjembatani kebutuhan hukum masyarakat dengan keterbatasan legislasi formal.
Dengan demikian, kebijakan fungsi mengatur tidak sekadar dimaknai sebagai langkah administratif, melainkan sebagai proses normatif yang memengaruhi arah pembangunan hukum nasional.
Adapun kontribusi MA dalam perkembangan hukum nasional melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Komisi Pidana Presiden (president’s crime commissionis) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.
Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960, ditandai berdirinya peradilan anak (children’s court) sebelum abad ke-19, yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning) (Mulyadi, 2023, hal. 110).
Di Indonesia pedoman pelaksanaan diversi pertama kali diatur dalam Perma 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Selain hadir lebih awal dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Perma 4 tahun 2014 dinilai lebih progresif dan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (the best interest of the child),
Hal dimaksud, terlihat dalam ketentuan Pasal 3 yang berbunyi “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”
Ketentuan tersebut, tidak terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan PP Nomor 65 tahun 2015.
UU SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015, secara limitaif menentukan syarat diversi hanyalah “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”
Pertanyaannya adalah bagaimana jika anak didakwa dengan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana berlapis, baik di bawah tujuh tahun maupun lebih dari tujuh tahun penjara?
Hal demikian belum cukup diatur, sehingga dalam hal ini terdapat kekosongan hukum, selanjutnya MA menetapkan Perma Nomor 4 tahun 2014 untuk melengkapi kekosongan hukum tersebut dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan aspek keadilan substantif.
Perma Pedoman Mediasi di Pengadilan
Dalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi adalah “Mediaton is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement.” (Hidayat, 2016, hal. 51)
Mediasi diposisikan bukan sekadar prosedur formalitas, melainkan sebuah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip konsensus, win-win solution, dan efisiensi.
Kewajiban mediasi memiliki justifikasi akademis sekaligus praktis. Dari sudut pandang teori hukum progresif, mediasi menegaskan penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada menang atau kalah, melainkan pada tercapainya keadilan substantif yang lebih memuaskan para pihak.
Secara normatif, kewajiban mediasi diatur Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, yang mengatur kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara.
Berdasarkan ketentuan tersebut, serta adanya kekosongan hukum terkait pedoman pelaksanaan mediasi, MA kemudian menetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Regulasi ini, memuat ketentuan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan mediasi, klasifikasi perkara yang wajib maupun yang dikecualikan dari proses mediasi, batas waktu serta sifat mediasi, dan juga pengaturan mengenai kategori para pihak yang dianggap tidak beritikad baik dalam menjalankan proses mediasi beserta implikasi hukumnya.
Misalnya apabila Penggugat dinilai tidak beritikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan bagi Tergugat yang beritikad tidak baik, dapat dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi.
Dalam pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini tentunya proses persidangan di pengadilan negeri berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan (Hadrian, E & Hakim, L, 2020, hal. 91).
Seiring perkembangan zaman, MA menyempurnakan pedoman mediasi melalui Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik, Secara prinsip, ketentuan mengenai mediasi elektronik memiliki substansi yang serupa dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Namun perbedaannya terletak pada aspek sarana yang digunakan, yakni melalui pemanfaatan media atau fasilitas elektronik sebagai instrumen pelaksanaannya.
Kebijakan SEMA dalam menyikapi perbedaan usia Anak
Kedudukan anak sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan nasional menjadikan anak perlu mendapat perhatian secara khusus supaya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan bagi anak (Sulatri, 2023, hal. 3).
Namun batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan konseptual.
Dalam UU Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA), batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Pada UU SPPA, batas minimal anak telah berumur 12 (dua belas) tahun. Hakikatnya mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PUU-VII/2010 tanggal 24 februari 2012 yang merevisi batas usia minimal anak 8 (delapan) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 (Mulyadi, 2023, hal. 34).
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seseorang dianggap dewasa dan memiliki hak pilih pada usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah, ketentuan serupa juga diatur UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan usia 17 (tujuh belas) tahun, sebagai syarat minimal untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi.
Dalam ranah hukum perdata, sebagaimana diatur Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa hingga mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.
Adapun UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan 19 (sembilan belas) tahun.
Sementara itu, menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut telah mencapai usia dewasa lebih awal.
Dari berbagai pengertian dalam peraturan perundang-undangan tersebut, disimpulkan masih terdapat pluralisme dalam penentuan usia anak. (Sulatri, 2023, hal. 2-3).
Dalam rangka mewujudkan keseragaman dalam penerapan hukum, MA menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
SEMA tersebut, memuat ketentuan yang menegaskan penentuan batas usia kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak bersifat universal, melainkan harus disesuaikan dengan undang-undang atau norma hukum yang mengaturnya secara spesifik dalam konteks perkara tertentu (bersifat kasuistis).
Dengan demikian, SEMA tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yudisial, tetapi juga berperan dalam memberikan solusi terhadap adanya antinomi atau pertentangan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang telah terkodifikasi.
Dengan demikian, Mahkamah Agung melalui fungsi regulatifnya tidak hanya berperan dalam menjaga keseragaman hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak pembaruan hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.
Peran ini menegaskan eksistensi Mahkamah Agung sebagai the guardian of law and justice, yang berfungsi tidak semata menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga menghidupkan semangat hukum yang berkeadilan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Referensi
Hakim, L & Hadrian, E (2020). Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. Sleman: Deepublish.
Hidayat, M. (2016). Strategi & Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: KENCANA.
Mulyadi, L. (2023). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung: P.T. Alumni.
Sugiarto, D. (2024, April 29). Kebijakan Mahkamah Agung RI tentang Tindak Pidana Narkotika. (B. Haryantho, Interviewer) Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Sulatri, K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.