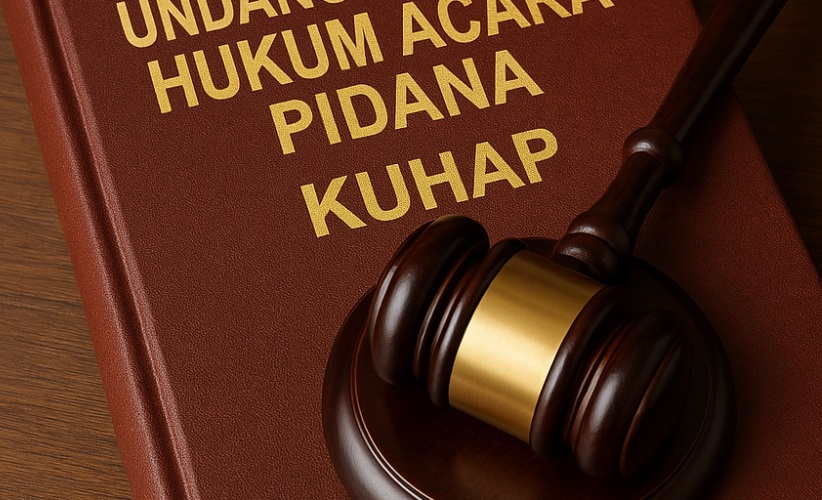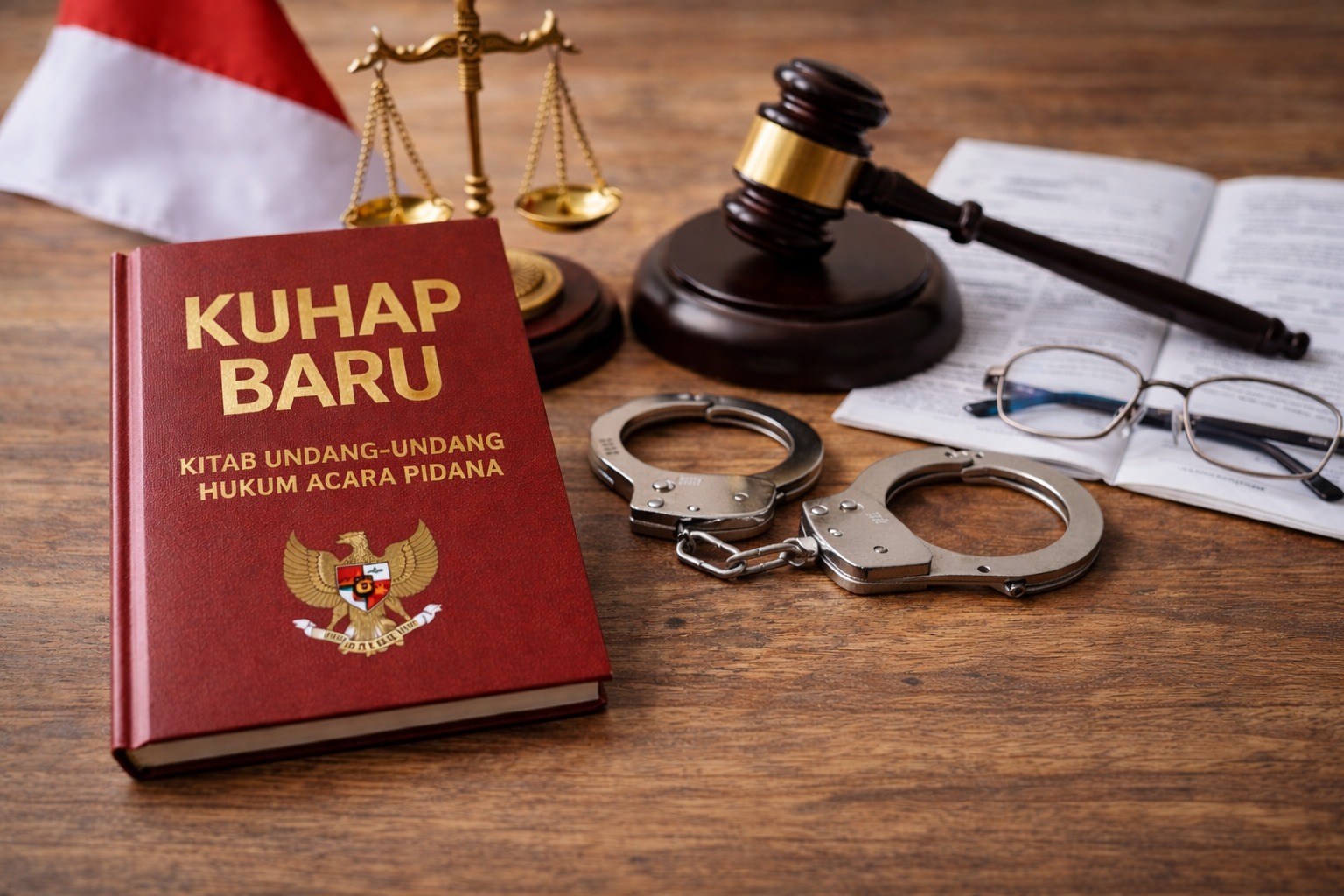Revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan sekadar agenda legislasi, tetapi merupakan titik kritis dalam menentukan arah dan watak sistem peradilan pidana di Indonesia ke depan.
KUHAP yang berlaku saat ini produk hukum warisan Orde Baru pada 1981, dianggap tidak sepenuhnya relevan menghadapi dinamika hukum modern, terutama menjawab kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas penegak hukum, serta efisiensi peradilan.
Kebutuhan akan pembaruan KUHAP, menjadi semakin mendesak di tengah berkembangnya wacana negara hukum yang demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi due process of law.
Namun, revisi yang seharusnya jadi sarana memperkuat perlindungan hak-hak warga negara, justru berpotensi menimbulkan regresi. Draf RUU KUHAP, yang saat ini sedang disusun dan dibahas secara terbatas oleh pemerintah serta DPR, menunjukkan sejumlah ketentuan yang berpotensi melemahkan prinsip fair trial dan memperkuat dominasi negara.
Misalnya, perluasan kewenangan penahanan, penguatan diskresi penuntutan oleh kejaksaan, serta tidak adanya penguatan signifikan terhadap mekanisme praperadilan, menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara individu dan negara dalam proses hukum.
Hal itu juga disoroti oleh Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, dengan menyebut, proses buruk penyusunan dan pembahasan RUU KUHAP yang tertutup dan terburu-buru. (mediaindonesia.com, 2025)
Salah satu isu krusial, dalam revisi KUHAP, adalah posisi poin praperadilan. Dalam praktiknya, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa, yang dilakukan aparat penegak hukum.
Akan tetapi, dalam draf revisi yang berkembang, tidak terdapat penguatan signifikan terhadap fungsi lembaga ini. Bahkan, muncul kekhawatiran dibatasinya ruang gerak hakim praperadilan, dalam memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Padahal fungsi kontrol tersebut, elemen penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional tersangka/terdakwa.
Selain itu, pengaturan mengenai penyadapan, perpanjangan masa penahanan, dan penghilangan kewajiban notifikasi terhadap keluarga tersangka dalam tahap awal penahanan, menjadi sorotan serius. Ketentuan semacam itu, apabila diberlakukan, membuka ruang sangat besar, bagi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dan mereduksi prinsip presumption of innocence, yang menjadi ruh utama dalam sistem peradilan pidana modern.
Dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, arah revisi KUHAP semestinya tidak hanya bertumpu pada kepentingan efisiensi penegakan hukum semata. Melainkan juga harus berimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, yang berhadapan dengan hukum. Hal ini, sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak, dalam berbagai konvensi internasional seperti ICCPR, yang mengatur secara ketat standar minimal perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses hukum.
Maka, revisi KUHAP, harus menjadi momentum memperbaiki desain sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan prosedural. Partisipasi publik, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, harus dilibatkan secara substansial. Agar, proses revisi tidak terjebak pada logika kekuasaan semata.
Jika tidak diarahkan benar, revisi KUHAP justru menjadi alat legalisasi terhadap praktik-praktik koersif negara. Maka, pertanyaan penting yang menjadi permasalahan, Quo Vadis KUHAP? Ke mana arah dan tujuan sistem hukum acara pidana Indonesia, di bawa menuju kemajuan hukum yang berkeadilan, atau justru kemunduran menindas?
Pertanyaan Quo Vadis KUHAP, bukan hanya soal arah teknis pembaruan hukum acara pidana, tetapi soal nilai dan ideologi hukum, seperti apa yang hendak dibangun bangsa ini. Apakah hukum, dijadikan alat melindungi hak warga negara, menjamin proses yang adil, dan membatasi kekuasaan? Atau justru direduksi menjadi instrumen kekuasaan represif, dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan?
Revisi KUHAP seharusnya jadi momentum memulihkan kembali kepercayaan publik, terhadap sistem peradilan pidana. KUHAP, harus menjawab tantangan-tantangan krusial, seperti akuntabilitas penegak hukum, perlindungan kelompok rentan, serta kepastian hukum berkeadilan. Jika arah revisi hanya memperkuat kewenangan negara, tanpa memperhatikan prinsip fair trial, presumption of innocence, dan due process of law, maka revisi tidak akan membawa kemajuan hukum, melainkan kemunduran yang menindas.
Dengan demikian, revisi KUHAP tidak boleh berhenti pada kalkulasi formal dan efisiensi prosedural, tetapi harus dibimbing komitmen moral dan konstitusional, guna menciptakan sistem hukum acara pidana yang humanis, adil, dan berpihak, pada prinsip negara hukum demokratis. Jika tidak, maka sejarah mencatat pembaruan hukum semestinya, jadi jalan menuju keadilan, justru sebagai alat legitimasi penyimpangan kekuasaan.
Terhadap konteks ini, penulis mengutip, Prof. Dr. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (2009), yang menyebut, hukum bukan semata-mata teks, melainkan juga nilai. Bila hukum hanya menjadi teks yang tidak mencerminkan keadilan, maka rakyat akan mencari keadilan di luar hukum, dan negara bisa kehilangan wibawa.
Pernyataan tersebut, menegaskan hukum acara pidana, tidak cukup hanya dinilai dari kepatuhan prosedural atau formalitas norma semata, tetapi harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan substantif. Dalam konteks revisi KUHAP, jika pembaruan hukum berorientasi penguatan kekuasaan negara, tanpa memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, maka hasil legislasi yang lahir, justru dapat menciptakan jurang antara hukum dan keadilan itu sendiri.
Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana
Salah satu sorotan, paling serius terhadap draf revisi KUHAP, adalah potensinya untuk mengancam prinsip fair trial dan asas presumption of innocence, dua pilar fundamental dalam sistem hukum acara pidana demokratis. Kedua prinsip ini, tidak hanya dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam bukunya Satjipto Rahardjo yang berjudul Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (2008), Satjipto Rahardjo mengembangkan teori hukum progresif, yang berpandangan hukum harus digunakan untuk membela rakyat kecil dan mencapai keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan aturan formalistik. Dalam konteks KUHAP, hukum acara pidana, seharusnya melindungi warga negara dari kekerasan negara, bukan malah melanggengkan dominasi aparat penegak hukum.
Revisi KUHAP, yang tidak berpihak pada prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu, dapat berdampak serius terhadap masa depan sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara normatif, perubahan KUHAP, semestinya diarahkan untuk memperkuat prinsip due process of law, memperjelas batas-batas kewenangan aparat penegak hukum, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara.
Namun, bilamana revisi memperluas kewenangan penyidik dan penuntut, tanpa kontrol yudisial memadai, maka akan terbuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Penulis berpandangan, ada beberapa implikasi, yang jadi permasalahan terhadap RUU KUHAP. Pertama, yang paling nyata pelemahan kontrol yudisial, terhadap aparat penegak hukum, khususnya melalui institusi praperadilan.
Jika kewenangan hakim praperadilan dibatasi atau tidak diperkuat, maka mekanisme pengawasan terhadap tindakan sewenang-wenang, seperti penahanan tanpa dasar, penyadapan ilegal, atau penyiksaan dalam proses penyidikan akan menjadi lemah. Ketiadaan penguatan lembaga praperadilan, dalam draf revisi KUHAP mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap tindakan sewenang- wenang aparat penegak hukum.
Dalam praktik, praperadilan adalah benteng utama bagi tersangka, untuk menggugat kesewenang-wenangan penyidik. Melemahkan fungsi ini, sama saja dengan mereduksi prinsip fair trial. Sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, praperadilan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam menjamin hak-hak tersangka sejak awal proses pidana.
Kedua, ketimpangan relasi antara aparat dan warga negara, akan semakin lebar. KUHAP yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan, justru bisa berubah jadi alat legitimasi dominasi negara atas individu. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menurunkan kepercayaan publik, terhadap lembaga peradilan dan memperburuk krisis legitimasi institusi hukum, yang telah lama terjadi di Indonesia.
Ketiga, dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu, revisi KUHAP yang mengabaikan prinsip keadilan prosedural, akan menciptakan ketidaksinkronan dengan semangat pembaruan hukum pidana materiil (revisi KUHP) dan hukum kelembagaan. Hal ini dapat memicu disorientasi dalam penegakan hukum yang adil terutama dalam perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, atau korban kriminalisasi.
Dengan demikian, arah revisi KUHAP, akan sangat menentukan wajah dan kualitas sistem peradilan pidana Indonesia ke depan, apakah menjadi sistem yang berkeadaban dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, atau justru sistem represif, yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan semata. Dan juga, revisi KUHAP harus diuji tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari prinsip keadilan, moralitas hukum, konsistensi sistem, dan keberpihakan terhadap hak asasi manusia.
Jika revisi hanya berorientasi memperkuat kekuasaan negara dan melemahkan mekanisme kontrol, maka secara teoritis dan normatif, revisi tersebut gagal memenuhi syarat sebagai hukum yang adil dan sah.