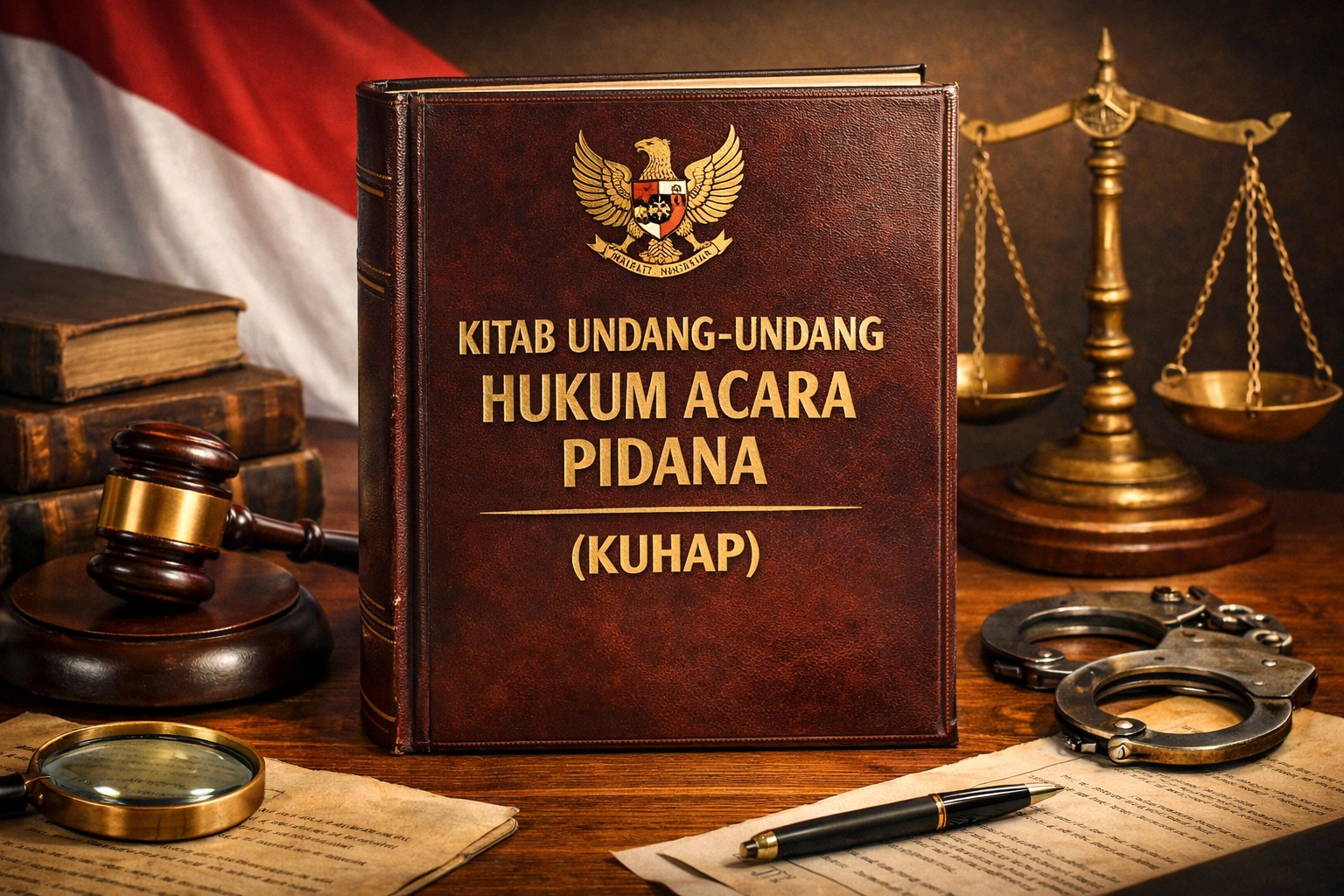Reformasi hukum acara pidana di Indonesia memasuki tahap penting melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah upaya komprehensif yang menandai perubahan paradigma dari model prosedural yang dibangun pada 1981 menuju sistem yang lebih responsif terhadap teknologi, hak asasi manusia, dan perkembangan global.
KUHAP 1981 pada masanya merupakan pencapaian fundamental, terutama karena memberikan batasan terhadap tindakan sewenang-wenang dan memuat prinsip minimal due process pasca-Orde Baru (Pompe, 2005).
Namun, dinamika kejahatan modern seperti kejahatan digital, kejahatan korporasi, serta tuntutan transparansi mengungkapkan berbagai kelemahan struktural KUHAP 1981, termasuk keterbatasan dalam pengawasan hakim, ketimpangan posisi antara aparat penegak hukum dan tersangka, serta ketiadaan kerangka pembuktian elektronik.
Rancangan KUHAP (RKUHAP) menggeser orientasi kodifikasi tradisional menjadi pendekatan harmonisasi yang lebih adaptif.
Pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan global di mana banyak negara bergerak dari model inquisitorial murni menuju sistem hibrida yang memadukan unsur adversarial sebagai jaminan keseimbangan posisi para pihak (Jackson & Summers, 2012).
Pembaruan ini tampak dari perluasan kewenangan praperadilan, penguatan kontrol yudisial atas upaya paksa, serta pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik, sebuah elemen yang tidak mungkin dihindari dalam era digital sebagaimana dibahas Wall (2008).
Peningkatan judicial scrutiny terhadap tindakan penyidik juga mencerminkan kesadaran tentang perlunya mekanisme akuntabilitas untuk mencegah penyiksaan dan penyalahgunaan kewenangan, isu yang telah lama menjadi sorotan lembaga internasional (UNODC, 2011).
Salah satu aspek paling progresif dalam rancangan baru adalah pengaturan mekanisme penyelesaian alternatif, termasuk restorative justice dan kesepakatan penyelesaian perkara.
Mekanisme ini sejalan dengan literatur internasional yang menilai pendekatan restoratif sebagai strategi yang mumpuni untuk mengurangi beban peradilan, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif (Zehr, 2002).
Selain itu, rancangan baru mengatur tata acara pidana terhadap korporasi, sebuah perkembangan yang sangat penting mengingat meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi dan lingkungan.
Pengaturan ini selaras dengan penelitian Coffee (2006) yang menekankan perlunya model prosedural khusus bagi entitas korporasi karena karakteristiknya yang berbeda dari individu.
RKUHAP juga memperkuat perlindungan tersangka dalam proses pemeriksaan melalui kewajiban perekaman audio visual, pelarangan penyiksaan, serta pembatasan penggunaan tindakan koersif.
Hal ini merupakan langkah yang konsisten dengan best practices internasional, termasuk rekomendasi Komite Menentang Penyiksaan PBB yang mendorong dokumentasi visual untuk mencegah praktik penyiksaan dan meminimalkan false confession (Nowak, 2006).
Selain itu, pengenalan judicial pardon sebagai bentuk putusan baru menunjukkan komitmen terhadap prinsip individualisasi pemidanaan, sebuah prinsip yang banyak dianalisis dalam studi pemidanaan modern (Ashworth, 2010), yang menekankan pentingnya mempertimbangkan proporsionalitas, penyesalan pelaku, dan rehabilitasi pascakejahatan.
Dengan demikian, RKUHAP tidak hanya memperbarui aspek teknis hukum acara pidana, tetapi menggeser fondasi filosofis penyelenggaraan peradilan pidana Indonesia.
RKUHAP mengintegrasikan kehendak untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan kemanusiaan.
Tantangannya, tentu saja, terletak pada implementasinya yaitu profesionalisme penyidik, integritas hakim, dan kesiapan kelembagaan akan menentukan apakah reformasi ini benar-benar membawa transformasi substansial atau hanya mempertebal tumpukan teks hukum tanpa perubahan di tingkat praktik.
Sumber:
Ashworth, A. (2010). Sentencing and Criminal Justice. Cambridge University Press.
Coffee, J. C. (2006). Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance. Oxford University Press.
Jackson, J., & Summers, S. (2012). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press.
Nowak, M. (2006). UN Convention Against Torture: A Commentary. Oxford University Press.
Pompe, S. (2005). The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. Cornell Southeast Asia Program.
UNODC. (2011). Handbook on Criminal Justice Responses to Terrorism. United Nations Office on Drugs and Crime.
Wall, D. (2008). Cybercrime and the Culture of Fear. Information, Communication & Society, 11(6), 861–884.
Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.