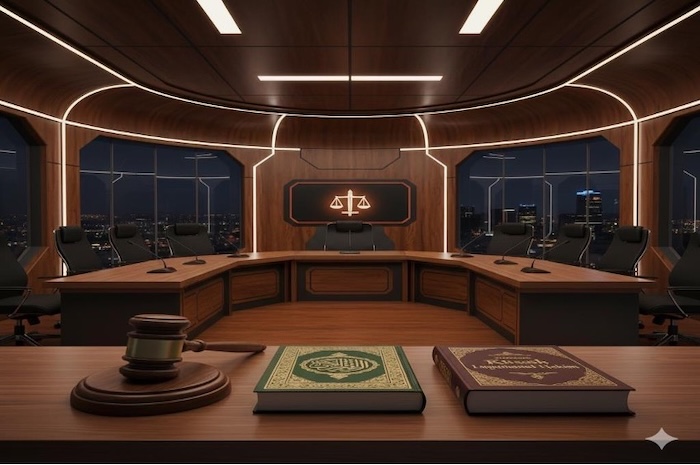“The equitable is just, but not legally just. It is a correction of legal justice.”-Aristoteles (Nicomachean Ethics).
Dua organisasi kriminal besar, yakni Cosa Nostra di Italia pada dekade 1980-an dan Triad di Hong Kong pada 1970-an, sempat memicu gelombang protes besar dari masyarakat. Aksi Triad kala itu, bahkan merambah hingga ke tubuh kepolisian Hong Kong. Tekanan publik yang semakin kuat mendorong pemerintah setempat membentuk ICAC (The Independent Commission Against Corruption), lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi.
Sementara itu, Cosa Nostra menunjukkan perlawanan yang jauh lebih agresif. Mereka bahkan sempat mendeklarasikan perang terbuka terhadap pemerintah Italia. Jika di Hong Kong keterlibatan kejahatan terorganisasi terbatas pada aparat penegak hukum, di Italia situasinya lebih mengkhawatirkan-politisi, bahkan hingga perdana menteri, disebut-sebut menjadi pendukung kelompok mafia tersebut.
Baru di dekade 1990-an Italia dapat melepaskan diri dari peliknya jeratan kolusi dengan organisasi kriminal dalam skala nasional. Salah satu gembong mafia terbesar dari faksi Cosa Nostra Salvatore Riina, ditangkap pada 1992, dan menjadi cerita penutup dari sekitar tiga dekade kekerasan di negara itu.
Hong Kong (saat masih menjadi protektorat Inggris) dan Italia di dekade 1970-an dan 1980-an mengalami kondisi yang dideskripsikan sosiolog Emile Durkheim (1952) sebagai bunuh diri anomik (anomic suicide). Anomia adalah situasi tanpa kehadiran hukum (“lawless”). Dalam kondisi ini, negara kehilangan otoritasnya.
Durkheim menengarai, dalam sebuah kondisi yang semakin mekanis lewat pembagian kerja (division of labour), kesepakatan sosial yang mewujud dalam hukum modern menjadi semakin genting dan penting (Durkheim, 2019).
Dalam masyarakat awal (first societies) ketika setiap orang mengenali anggota masyarakat yang lain, konstruksi hukum bersifat tacit (kontekstual)-dan tidak perlu dikodifikasi. Negara bahkan perlu menjamin status hukum warganya di luar wilayah juridiksinya, dengan memberikan paspor sebagai perlindungan dari diskrepansi aturan dan perundang-undangan di berbagai belahan dunia atau “the stateness” of state – seberapa negara sebuah negara (Torpey, 2018:3).
Korupsi dan Teror: Belajar dari Kasus Hong Kong dan Italia
Menurut situs resmi ICAC, pada era 1970-an Kepolisian Hong Kong menjalin hubungan simbiosis dengan organisasi kriminal Triad, yang diwujudkan dalam bentuk gratifikasi dan suap kepada para pejabat kepolisian. Situasi ini menciptakan sistem pemerintahan kleptokratik, di mana hampir seluruh elemen birokrasi terlibat dalam praktik korupsi secara sistematis—sebuah struktur yang disebut pyramid of graft.
Puncak skandal ini terjadi ketika Kepala Kepolisian Hong Kong (Chief Superintendent) Peter Godber diketahui memiliki kekayaan tak wajar sebesar 55 juta dolar Hong Kong (sekitar 4,5 juta dolar AS pada 1973). Saat itu, tingkat inflasi tahunan tercatat sekitar 5%, menjadikan angka tersebut sangat mencolok dan mencurigakan.
Akibat kuatnya praktik suap dan gratifikasi, penegakan hukum di Hong Kong kala itu berjalan tidak merata dan cenderung diskriminatif-bergantung pada besarnya uang pelicin yang diterima. Disfungsi hukum ini menggambarkan kegagalan prinsip dasar congruence dalam filsafat hukum Lon L. Fuller.
Dalam bukunya (1964:81), Fuller menyatakan: “A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration can be as destructive to a system of law as the failure of any of the other desiderata.” (Kegagalan kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan pelaksanaannya secara nyata bisa sama merusaknya terhadap sistem hukum seperti kegagalan dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar lainnya).
Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya ICAC (Independent Commission Against Corruption), sebagai upaya membenahi sistem hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan pemerintahan Hong Kong.
Bila kondisi di Hong Kong dapat diibaratkan seperti penyakit kanker dari dalam, yang terjadi di Italia, tepatnya di Sisilia, adalah teror. Dalam pemikiran filsafat hukum Carl Schmitt (2006), kondisi hukum di Italia pada waktu itu adalah “exception” (pengecualian): ada berbagai aspek yang tidak diatur oleh aturan atau undang-undang, tetapi para iuris berada dalam posisi untuk menarik garis tegas untuk dijadikan fondasi legal selanjutnya.
Pada awal 1980-an, saat gelombang aksi Cosa Nostra mengguncang Italia, kelompok mafia tersebut, belum secara resmi dikategorikan sebagai organisasi kriminal. Ironisnya, meskipun aparat kepolisian bekerja keras menindak kejahatan, banyak pejabat pemerintah justru berada di belakang Cosa Nostra, dan memberikan dukungan secara terselubung.
Situasi di Sisilia saat itu, kembali terjerumus dalam kondisi yang kacau dan penuh ketakutan-mirip dengan gambaran klasik dari filsuf Thomas Hobbes (1651) tentang kehidupan yang “solitary, poor, nasty, brutish, and short” (terasing, miskin, kejam, brutal, dan singkat).
Jika di Hong Kong otoritas negara-yang dalam teori Hobbes dikenal sebagai Leviathan-terkooptasi oleh korupsi dalam tubuh penegak hukum, maka di Italia Leviathan seolah-olah tidak hadir. Teror yang dilakukan oleh Cosa Nostra secara efektif menegasikan kehadiran negara. Aparat penegak hukum bagaikan macan tanpa cakar dan taring-kehilangan daya paksa dan kewibawaannya dalam menegakkan hukum secara efektif.
Kondisi tersebut, menunjukkan betapa berbahayanya ketika sistem hukum dan otoritas negara dilemahkan oleh kekuatan kriminal terorganisir yang memiliki jaringan hingga ke elite politik. Dalam konteks tersebut, supremasi hukum tidak hanya terancam, tetapi benar-benar lumpuh.
Dari Korupsi ke Integritas: Transformasi Lembaga Penegak Hukum
Sejarah manusia memberi catatan penting tentang betapa kebesaran hati untuk memercayai, dibutuhkan dalam mengembalikan kepercayaan itu sendiri. Aristoteles mengangkat gagasan epieikeia atau pertimbangan atas kesetaraan harkat manusia sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi, restrukturisasi, dan rekonstruksi.
Korupsi dan kolusi di kepolisian Hong Kong di era 1970-an dapat dilihat sebagai fenomena sosial. Saat polisi dan Triad berangkat dan tumbuh besar di lingkungan yang sama dan mengalami masalah tekanan ekonomi yang sama pula. Untuk membersihkan lembaga ini dari suap dan gratifikasi serta memulihkan kepercayaan publik, ICAC mengambil langkah yang sejalan dengan epieikeia: memberikan amnesti untuk tindak kejahatan yang dilakukan aparat penegak hukum, menerapkan sistem pengawasan ketat, memutus hubungan dengan Triad, dan mengadili pihak-pihak yang terlibat langsung dengan organisasi kejahatan tersebut, terutama Godber yang melarikan diri ke luar negeri.
Langkah amnesti ini sejalan dengan pemikiran filsuf John Rawls tentang keadilan dalam restrukturisasi sebuah lembaga. Rawls mengatakan, “The persons in the original position are not moved by benevolence, or a sense of solidarity; their conception of justice must be acceptable to persons with the various ends and attachments that such principles are to govern. In the absence of a firm assurance that the principles will be honored, the strains of commitment may become too great” (Individu-individu dalam posisi asali tidak didorong oleh kebajikan hati ataupun rasa solidaritas; konsepsi keadilan yang mereka pilih haruslah dapat diterima oleh individu dengan berbagai tujuan dan keterikatan yang akan diatur oleh prinsip-prinsip tersebut. Tanpa adanya jaminan kuat bahwa prinsip-prinsip ini akan dihormati, maka beban komitmen yang harus dipikul mungkin akan menjadi terlampau berat) (Rawls, 1999:153).
Tindakan untuk memberikan pengampunan bersyarat bagi mereka yang terimbas praktik koruptif dan kolusif di jajaran kepolisian Hong Kong ini, memperkuat komitmen mereka untuk menjadi polisi yang bersih dan akuntabel. Dalam istilah Rawls, mereka dibekali dengan modal yang cukup untuk mengikatkan diri dalam strains of commitment (beban komitmen) dalam institusi yang dibenahi.
Untuk situasi di Italia, langkah terpenting yang menjadi tonggak pembenahan situasi dan kondisi stabilitas publik adalah dengan meloloskan undang-undang yang melabeli organisasi Cosa Nostra dan mafia lainnya sebagai kejahatan terorganisasi. Secara patologis, mafia Italia sudah ada pada tahapan subversif yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan seperti di Hong Kong.
Organisasi kriminal ini melakukan teror dengan aksi pembantaian hakim, polisi, dan wartawan yang dianggap merugikan mereka. Beberapa tokoh perlawanan terhadap mafia yang menjadi korban misalnya Boris Giuliano, Hakim Cesare Teranova, Gubernur Piersanti Mattarella, dan Jendral Militer Carlo Alberto Dalla Chiesa-masing-masing terbunuh pada 1979, 1980, dan 1982.
Desakan publik semakin menguat terutama setelah dua hakim yang berperan sentral dalam penuntasan perkara anggota Cosa Nostra, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino tewas dibunuh pada 1988 dan 1992 (The Sicilian Documentation Center, 2 Maret 2015; Reuters dan berbagai sumber lainnya).
Putusan Yuridis dan Tanda Kebangkitan Komitmen Hukum
Putusan Kasasi Nomor 80 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Italia pada 30 Januari 1992 (Corte di Cassazione, Sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992) secara eksplisit menetapkan Cosa Nostra sebagai organisasi kriminal terorganisasi. Keputusan ini merupakan tonggak penting yang secara tegas meneguhkan legitimasi negara dalam menghadapi ancaman kejahatan terorganisasi, yang sebelumnya sulit ditangani oleh perangkat hukum yang ada.
Lebih dari sekadar vonis juridis, putusan tersebut menyampaikan pesan simbolis yang kuat tentang tekad negara untuk mengembalikan otoritasnya yang telah terkompromikan oleh kolusi politik dan ancaman teror. Sebagai dampak langsung dari putusan ini, Italia memasuki babak baru dalam penegakan hukum dengan memperjelas prinsip legalitas, keadilan, dan supremasi hukum yang tidak lagi tunduk pada intimidasi kelompok kriminal.
Hal serupa juga terjadi di Hong Kong, di mana reformasi yang diinisiasi oleh ICAC secara bertahap mengembalikan marwah, integritas, dan kredibilitas kepolisian sebagai institusi yang dipercaya menjaga keamanan dan ketertiban publik.
Kedua contoh di atas menegaskan, rekonsiliasi institusional melalui pendekatan hukum yang kuat dan komitmen negara yang kokoh, menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik serta mewujudkan stabilitas sosial secara berkelanjutan.