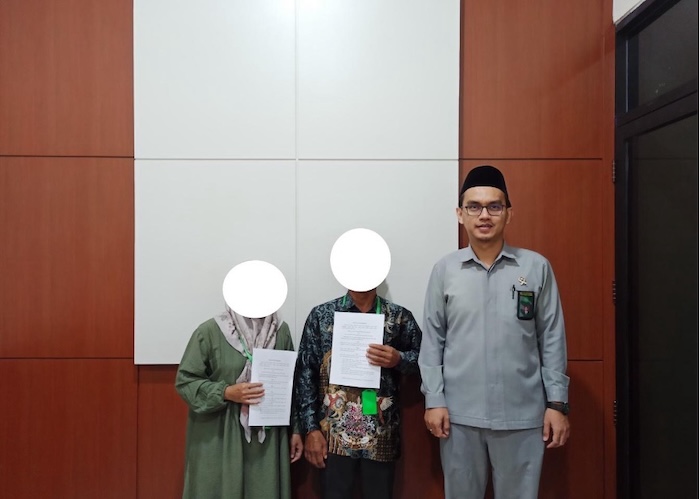Perkawinan merupakan institusi sakral yang tidak hanya mengandung dimensi sosial, tetapi didalamnya juga terkandung dimensi spiritual.
Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan bentuk ibadah panjang yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tataran praktiknya, banyak pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga menghadapi konflik berkepanjangan yang tidak sedikit pula berakhir pada perceraian.
Perceraian tidak hanya semata-mata dipandang sebagai peristiwa hukum, tetapi lebih dari itu, perceraian memiliki dampak sosial dan psikologis yang tidak bisa diabaikan dan yang sering kali menimbulkan dampak besar terutama bagi perempuan.
Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama (bagi mereka yang beragama Islam) setelah upaya perdamaian dilakukan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Ketentuan ini menegaskan bahwa peran pengadilan tidak hanya terbatas sebagai lembaga yang memutus perkara, namun juga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mendamaikan suami istri yang sedang beperkara.
Salah satu bentuk upaya perdamaian yang diwajibkan dalam proses peradilan adalah mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Mediasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asas penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Melalui mediasi, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan yang cukup untuk mencoba melakukan negosiasi, menyusun rencana solusi hingga mencapai kesepakatan yang adil dan manusiawi tanpa perlu melakukan proses persidangan yang panjang serta melelahkan.
Dalam perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami, isu mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian menjadi sangat penting.
Sering kali perempuan berada pada posisi yang lemah secara sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga diperlukan perlindungan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi.
Artikel ini membahas bagaimana lembaga mediasi dapat berperan sebagai sarana pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, dilihat dari perspektif maslahah Izzuddin bin Abdussalam yang menekankan pentingnya menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
Hak Perempuan Pascaperceraian dalam Sistem Hukum Indonesia
Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam konteks perkawinan, hak-hak perempuan setelah perceraian diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Pasal 41 poin c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri.
Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 149 menegaskan kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut’ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah bagi anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut sering hanya berlaku dalam perkara cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami. Adapun dalam perkara cerai gugat, istri yang mengajukan gugatan perceraian sering kali tidak memperoleh hak-hak yang sama.
Padahal, alasan perceraian yang diajukan istri umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi rumah tangga yang tidak sehat, seperti kekerasan, penelantaran, atau perselingkuhan suami. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan reformasi hukum yang berpihak pada keadilan substantif.
Transformasi Perlindungan Hukum bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa regulasi penting yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkara perceraian.
Pertama, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Regulasi ini menegaskan prinsip kesetaraan gender dan perlakuan yang adil bagi perempuan dalam seluruh proses peradilan. Hakim diwajibkan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis perempuan yang berperkara.
Kedua, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. SEMA ini menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Aturan ini merupakan terobosan penting karena sebelumnya hak tersebut hanya diberikan dalam perkara cerai talak.
Ketiga, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, yang memberikan pedoman agar pengadilan dapat menahan akta cerai hingga suami memenuhi kewajibannya terhadap istri pasca perceraian sepanjang tuntutan tersebut telah diuraikan dalam posita dan petitum gugatan. Kebijakan ini memastikan kembali bahwa hak-hak perempuan terlindungi secara konkret, bukan hanya normatif.
Keempat, Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang memuat petunjuk untuk menyediakan blanko/template surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri.
Dengan adanya transformasi hukum tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai lembaga kasasi, tetapi juga sebagai policy maker dalam menegakkan keadilan substantif.
Dengan demikian, perempuan yang mengajukan cerai gugat kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut hak-haknya.
Mediasi sebagai Instrumen Keadilan dan Kemaslahatan
Mediasi berfungsi untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari jalan damai dengan bantuan mediator.
Dalam konteks perkara perceraian, mediasi memiliki nilai yang sangat strategis karena tidak hanya menekankan pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan pemenuhan hak-hak pasca perceraian.
Mediator memiliki peran ganda, yaitu sebagai fasilitator komunikasi dan sebagai penjaga nilai kemaslahatan. Ia harus netral, empati, serta mampu memahami dinamika emosional dan sosial dari pihak-pihak yang berperkara.
Dalam perkara cerai gugat, mediator dapat membantu pihak istri dan suami untuk berdialog tentang konsekuensi perceraian, seperti penentuan nafkah iddah dan mut’ah.
Mediasi juga menjadi wadah untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), di mana penyelesaian konflik diarahkan pada pemulihan hak, bukan sekadar penjatuhan hukuman.
Dengan demikian, keberhasilan mediasi bukan hanya diukur dari apakah perceraian dapat dihindari, tetapi juga sejauh mana para pihak memperoleh kepastian dan keadilan pasca perceraian.
Mediasi dalam Perspektif Maslahah Izzuddin bin Abdussalam
Pemikiran Izzuddin bin Abdussalam tentang maslahah menempati posisi penting dalam etika hukum Islam. Ia mendefinisikan maslahah sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan (jalb al-mashalih) dan menolak kerusakan (dar’u al-mafasid). Prinsip ini menjadi dasar bagi penetapan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan manusia.
Dalam konteks mediasi dalam perkara perceraian, penerapan maslahah dapat dilihat pada dua tingkatan. Pertama, maslahah haqiqiyyah, yaitu manfaat nyata berupa kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian.
Kedua, maslahah majaziyyah, yakni upaya mediator sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar melalui perundingan damai.
Mediator, dalam pandangan ini, bukan hanya pelaksana prosedur formal, melainkan juga agen moral yang berperan menghadirkan kebaikan bagi kedua belah pihak.
Upayanya dalam mengarahkan suami untuk memenuhi kewajiban kepada istri, atau membantu istri memahami hak-haknya, merupakan bagian dari realisasi nilai maslahah. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga spiritual dan kemanusiaan.
Tantangan dan Upaya Optimalisasi
Meskipun telah diatur secara komprehensif, implementasi mediasi di Pengadilan Agama masih menghadapi sejumlah kendala.
Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakhadiran para pihak, keteguhan untuk bercerai, atau keterbatasan kemampuan mediator dalam membangun komunikasi efektif.
Selain itu, sebagian besar mediator berasal dari hakim yang sudah dibebani banyak perkara, sehingga waktu dan perhatian untuk proses mediasi menjadi terbatas.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan khusus mengenai psikologi keluarga, teknik negosiasi, dan pendekatan berbasis gender menjadi sangat penting.
Kesimpulan
Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan.
Melalui mediasi, para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dan lebih sederhana serta tanpa mengabaikan sisi kemaslahatan bagi suami dan istri, serta memastikan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah dan mut’ah tetap terpenuhi.
Regulasi Mahkamah Agung seperti PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan SEMA No. 2 Tahun 2019 serta Surat Ditjen Badilag nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, menjadi landasan kuat bagi penguatan posisi hukum perempuan berhadapan dengan hukum.
Dalam perspektif maslahah Izzuddin bin Abdussalam, peran mediasi mencerminkan upaya menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
Mediator berfungsi tidak hanya sebagai penengah formal, tetapi juga sebagai pembawa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari perdamaian, tetapi dari sejauh mana proses tersebut mampu melindungi martabat dan hak perempuan pasca perceraian.
Daftar Pustaka
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.
Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021.
Izzuddin bin Abdussalam. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam.
Aziz Sholeh, dkk. (2019). Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Jurnal CIC.
Nia Maulina, dkk. (2022). Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Intizar Raden Fatah.
Robi Awaludin. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi. Jurnal Hukum Islam Nusantara