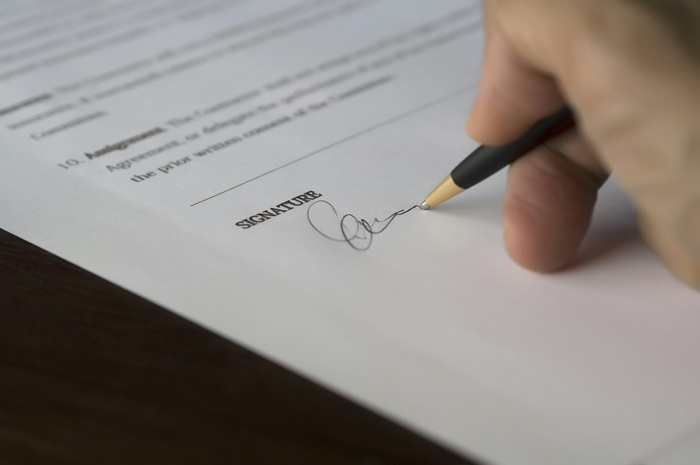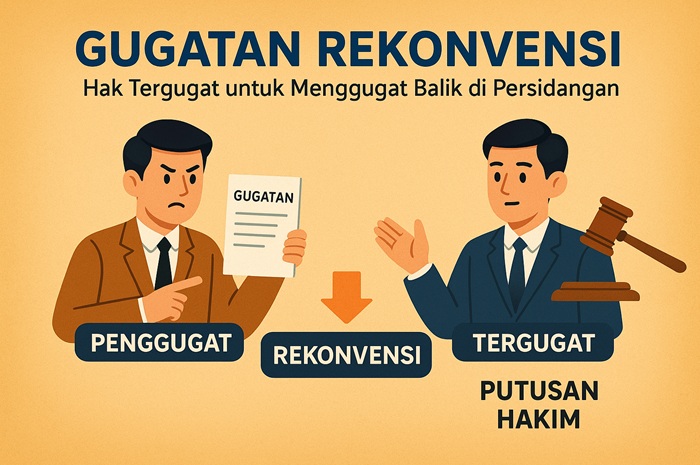Persangkaan hakim, merupakan salah satu instrumen pembuktian, yang memiliki peran penting dalam hukum acara perdata di Indonesia.
Ketika alat bukti langsung seperti saksi yang melihat dan mendengar sendiri suatu peristiwa sulit dihadirkan, hakim masih dapat membangun keyakinannya melalui persangkaan.
Dasar hukumnya memang sudah diatur dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG, namun kedua ketentuan tersebut sangat ringkas sehingga tidak cukup memadai untuk menjelaskan seluruh aspek penting, baik mengenai definisi, syarat, maupun kekuatan pembuktiannya.
Karena itu, rujukan yang lebih tepat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1915–1922, yang memberikan pengaturan lebih detail (Mertokusumo, 1988, h. 122).
Pasal 1915 KUH Perdata, menyatakan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.
Dari rumusan ini, tampak jelas bahwa persangkaan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berangkat dari fakta yang telah terbukti untuk kemudian diarahkan pada fakta yang belum diketahui.
Subekti menegaskan, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari fakta yang terbukti menuju fakta lain yang belum terbukti (Subekti, 1977, h. 86). Dengan demikian, persangkaan pada hakikatnya merupakan proses inferensi hukum yang berangkat dari sesuatu yang nyata menuju sesuatu yang tersembunyi.
KUH Perdata membagi persangkaan menjadi dua, yakni persangkaan undang-undang (rechtsvermoeden) dan persangkaan hakim (rechtelijke vermoeden).
Persangkaan undang-undang adalah dugaan yang ditetapkan oleh hukum, baik yang bersifat tidak dapat dibantah (irrebuttable) maupun yang dapat dibantah (rebuttable).
Misalnya, anak yang lahir dalam perkawinan dianggap sah sebagai anak suami ibunya, kecuali dibantah melalui mekanisme li‘ān.
Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang dibangun berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dan dibiarkan kepada kebebasan hakim untuk menarik kesimpulannya (Harahap, 2019, h. 29).
Dalam praktik peradilan, persangkaan hakim banyak digunakan dalam perkara-perkara perdata yang sifatnya privat dan tertutup, misalnya perceraian.
Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus, sering kali tidak ada saksi yang menyaksikan langsung pertengkaran di rumah tangga.
Namun, jika terungkap fakta bahwa para pihak sudah pisah rumah selama enam bulan, suami tidak lagi memberi nafkah, dan istri kembali tinggal di rumah orang tuanya, maka dari fakta-fakta itu hakim dapat menarik persangkaan bahwa rumah tangga sudah pecah secara permanen.
Artinya, meskipun tidak ada bukti langsung tentang pertengkaran, persangkaan yang dibangun dari fakta relevan dapat meneguhkan keyakinan hakim mengenai kebenaran dalil perceraian (Sutantio & Iskandar, 2019, h. 110).
Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Persangkaan Hakim
Secara teoretis, persangkaan sering diperdebatkan apakah ia dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti tersendiri atau sekadar metode penalaran.
Beberapa sarjana menyebutnya sebagai oneigenbewijs (alat bukti tidak sebenarnya) karena ia hanya hidup melalui keberadaan bukti langsung. Persangkaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang alat bukti lain, sebab sifatnya hanya pelengkap.
Namun dalam praktik, persangkaan tetap dianggap sah sebagai bagian dari mekanisme pembuktian. KUH Perdata bahkan memberikan bobotnya bersifat bebas (vrij bewijskracht), sehingga nilainya ditakar sepenuhnya oleh hakim (Pitlo, 1986, h. 77).
Persangkaan berfungsi sebagai perantara dalam pembuktian. Ia menjembatani bukti langsung yang tersedia dengan fakta yang hendak dibuktikan, sehingga celah bukti dapat ditutup.
Dalam perkara perceraian karena kekerasan rumah tangga misalnya, hakim dapat menarik persangkaan dari visum et repertum, laporan kepolisian, dan kesaksian tetangga yang konsisten.
Dari rangkaian bukti itu, hakim dapat menyimpulkan bahwa kekerasan memang berulang terjadi, meskipun tidak ada rekaman video atau pengakuan dari pelaku.
Dengan begitu, persangkaan berperan memastikan bahwa keadilan tidak terhenti hanya karena bukti langsung sulit dihadirkan (Sari & Yudowibowo, 2016, h. 67).
Ada dua unsur penting, yang membentuk persangkaan hakim. Pertama adalah fakta yang terbukti di persidangan. Tanpa fakta yang jelas, persangkaan tidak sah secara formil. Kedua adalah akal atau intelektualitas hakim, sebab hanya melalui nalar yang sehat fakta yang terbukti dapat diarahkan pada fakta tersembunyi.
Oleh karena itu, kualitas persangkaan sangat ditentukan oleh kombinasi fakta yang kuat dan kapasitas intelektual hakim. Persangkaan yang dibangun dari fakta kokoh akan mendekati kepastian, sedangkan persangkaan dari fakta rapuh hanya akan menghasilkan dugaan lemah (Harahap, 2019, h. 31).
Kualitas persangkaan hakim, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. Pertama, persangkaan yang benar-benar mendekati kepastian, misalnya ketika fakta-fakta konsisten dan saling menguatkan, sehingga hampir pasti menggambarkan realitas yang sesungguhnya.
Kedua, persangkaan yang kurang mendekati kepastian, biasanya lahir dari bukti lemah atau saksi tidak kredibel, seperti dalam perkara hadhanah yang hanya bertumpu pada kesaksian tetangga tanpa rekam medis.
Ketiga, persangkaan yang tidak mendekati kepastian sama sekali, yakni ketika hanya bersumber dari satu saksi yang tidak dapat dipercaya. Persangkaan kategori terakhir tidak sah dipakai untuk memperkuat dalil dalam pembuktian (Mertokusumo, 1988, h. 127).
Selain itu, terdapat prinsip penting dalam memperhitungkan nilai kekuatan persangkaan hakim. Pertama, satu persangkaan tidaklah cukup; harus ada dua persangkaan atau lebih yang saling berhubungan, sesuai asas bahwa “satu persangkaan bukanlah persangkaan.”
Hakim dilarang memperhitungkan persangkaan yang saling bertentangan, karena hal itu menegasikan nilai pembuktiannya. Ketiga, fakta yang dijadikan dasar persangkaan harus bersumber dari bukti yang sah, baik berupa tulisan, keterangan saksi, atau pengakuan. Dengan demikian, kehati-hatian hakim menjadi kunci agar persangkaan benar-benar sahih sebagai sarana probatoris (Subekti, 1977, h. 93).
Qarīnah dalam Fikih Islam
Hukum Islam sejak lama telah mengenal instrumen pembuktian yang mirip dengan persangkaan, yakni qarīnah. Secara etimologis, qarīnah berarti tanda atau indikasi yang menunjukkan sesuatu melalui keterikatan (muqāranah) atau keter-iringan (muṣāḥabah).
Secara terminologis, fuqaha mendefinisikannya sebagai amārah, yaitu sesuatu yang apabila diketahui melazimkan dugaan kuat terhadap adanya suatu hal (Az-Zarqa, 2004, h. 211). Contoh sederhana adalah awan gelap yang menjadi qarīnah akan turunnya hujan.
Legitimasi penggunaan qarīnah sangat kuat dalam tradisi fikih. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dari mazhab Hanbali menegaskan pentingnya qarīnah dalam penegakan hukum. Dari mazhab Hanafi, pandangan serupa disampaikan oleh Ibnu ‘Ābidīn dan al-Ṭarābulusī. Mazhab Maliki juga mengakui peran qarīnah, sebagaimana ditegaskan Ibnu Farḥūn dan Ibnu Juzayy.
Bahkan, ulama Ibadi seperti Muhammad Aṭfīsh juga menyatakan hal yang sama. Konsensus ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama mendukung penggunaan qarīnah sebagai dasar pertimbangan yudisial (Al-Jauziyah, 1989, h. 44).
Agar sah sebagai dasar pembuktian, qarīnah harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, adanya fakta yang jelas dan tetap, sehingga inferensi hukum memiliki pijakan nyata.
Kedua, hubungan logis yang kuat antara fakta lahiriah dengan kesimpulan yang ditarik. Qarīnah yang hanya bersandar pada asumsi lemah tidak sah dijadikan dasar putusan (Az-Zuhaili, 1987, h. 65).
Jenis-jenis qarīnah terbagi dalam tiga kategori. Pertama, qarīnah qāṭi‘ah, yakni indikasi yang bersifat final dan dapat berdiri sendiri sebagai bukti. Contohnya adalah asas firāsy dalam penetapan nasab, di mana anak yang lahir dalam perkawinan sah otomatis dinasabkan kepada suami.
Kedua, qarīnah tarjīḥiyyah, yaitu qarīnah yang memperkuat bukti lain, misalnya dalam sengketa hadhanah, kedekatan anak dengan pihak yang selama ini merawatnya.
Ketiga, qarīnah da‘īfah, yakni indikasi lemah yang tidak dapat dijadikan dasar hukum, contohnya hanya sekadar dugaan bahwa seseorang belum membayar utang karena tidak terlihat menyerahkan uang (Az-Zuhaili, 1987, h. 72).
Selain itu, dikenal pula qarīnah qaḍā’iyyah, yakni indikasi yang ditarik hakim dari fakta dan perilaku para pihak di persidangan. Contoh klasik adalah kisah Nabi Sulaiman yang memutuskan hak asuh anak berdasarkan reaksi emosional ibu kandung saat diuji.
Dalam praktik peradilan agama modern, qarīnah qaḍā’iyyah tampak dalam perkara harta bersama, ketika hakim tidak hanya terpaku pada bukti formal kepemilikan, tetapi juga mempertimbangkan perilaku dan kontribusi pihak istri dalam perawatan objek yang disengketakan (Az-Zarqa, 2004, h. 225).
Dengan demikian, qarīnah dipandang sebagai instrumen iḥtiyāṭī, yakni alternatif pembuktian dalam kondisi darurat ketika bukti primer tidak tersedia. Walaupun tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan jika ada bukti langsung yang lebih kuat, qarīnah tetap sah digunakan untuk melengkapi, menguatkan, atau menguji alat bukti lain (Al-Jauziyah, 1989, h. 55).
Analisis Komparatif Persangkaan Hakim dan Qarīnah Qaḍā’iyyah
Analisis komparatif menunjukkan bahwa persangkaan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia dan qarīnah qaḍā’iyyah dalam fikih Islam memiliki kesamaan filosofis, yakni berfungsi menutup kekosongan bukti langsung.
Keduanya lahir dari kebutuhan praktis peradilan untuk mencegah denial of justice, khususnya dalam perkara privat yang sulit diakses pihak ketiga. Persangkaan maupun qarīnah sama-sama berangkat dari fakta yang terbukti, lalu melalui penalaran logis diarahkan pada fakta tersembunyi (Harahap, 2019, h. 36).
Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam bobot dan klasifikasi. KUH Perdata menekankan bahwa persangkaan hakim bersifat aksesori dan nilainya bebas, sehingga harus didukung oleh bukti lain atau lebih dari satu persangkaan.
Sebaliknya, dalam fikih Islam, qarīnah qāṭi‘ah dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti final, bahkan mampu mengalihkan beban pembuktian kepada pihak lawan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fikih Islam memberikan gradasi yang lebih rinci dalam menakar kualitas indikasi (Az-Zuhaili, 1987, h. 83).
Integrasi kedua konsep ini penting terutama di peradilan agama. Dengan memadukan fleksibilitas persangkaan dalam KUH Perdata dan klasifikasi qarīnah ala fikih, hakim dapat memiliki pedoman yang lebih objektif dalam menilai kekuatan indikasi.
Prinsip kehati-hatian fiqih, misalnya larangan menggunakan qarīnah da‘īfah, dapat menjadi rambu etis agar hakim tidak gegabah dalam menarik persangkaan lemah. Sebaliknya, prinsip vrij bewijskracht dalam KUHPerdata memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk membangun inferensi sesuai konteks perkara.
Dengan demikian, persangkaan hakim dan qarīnah qaḍā’iyyah dapat dipandang sebagai instrumen probatoris transformatif yang melampaui perdebatan teoretis tentang kategorisasi alat bukti.
Hakikat keduanya adalah memberikan jalan bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif melalui inferensi yang sah, logis, dan proporsional.