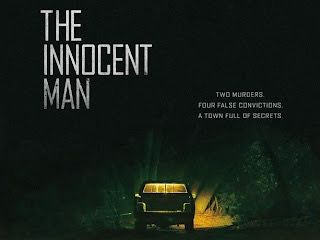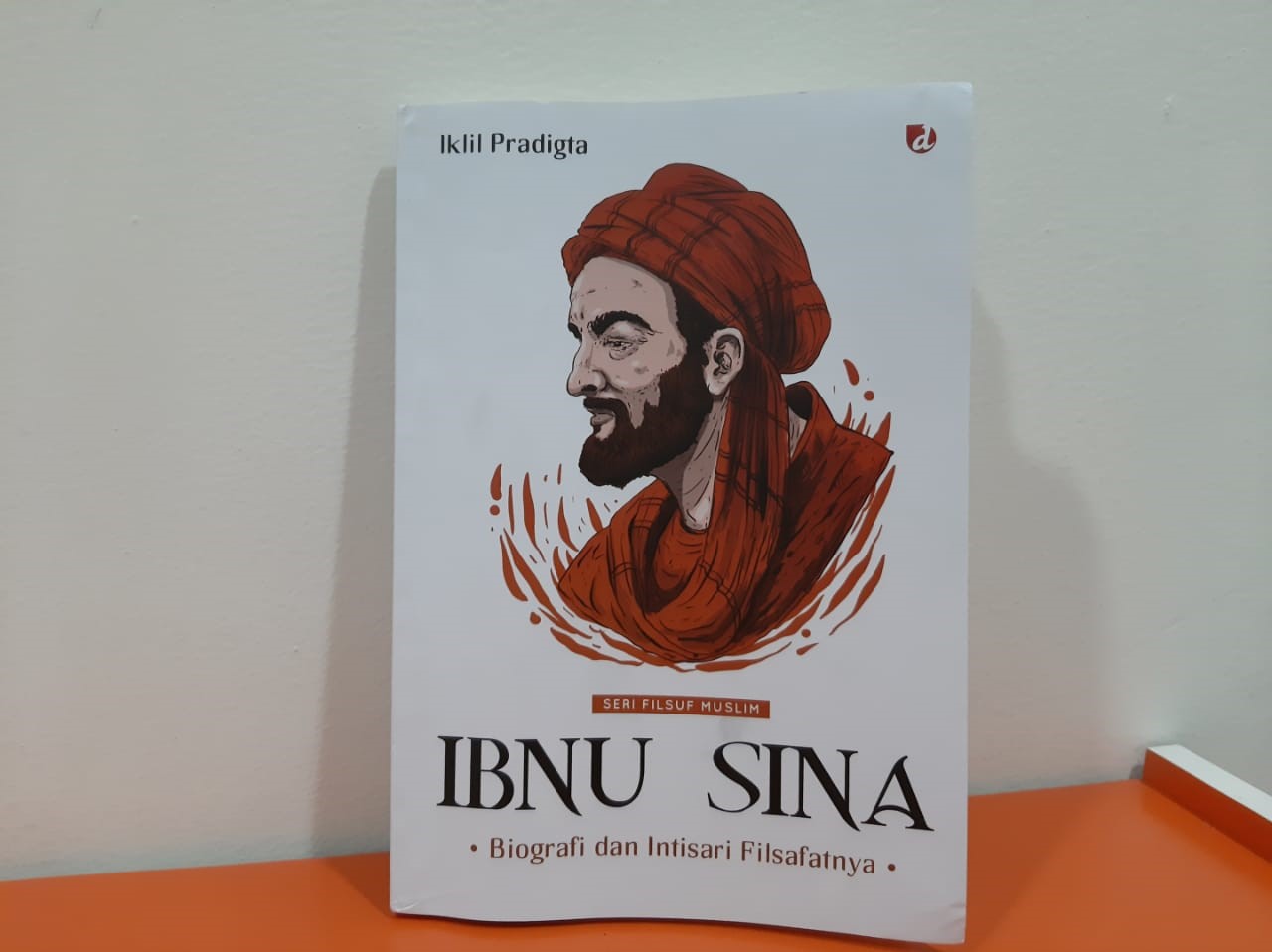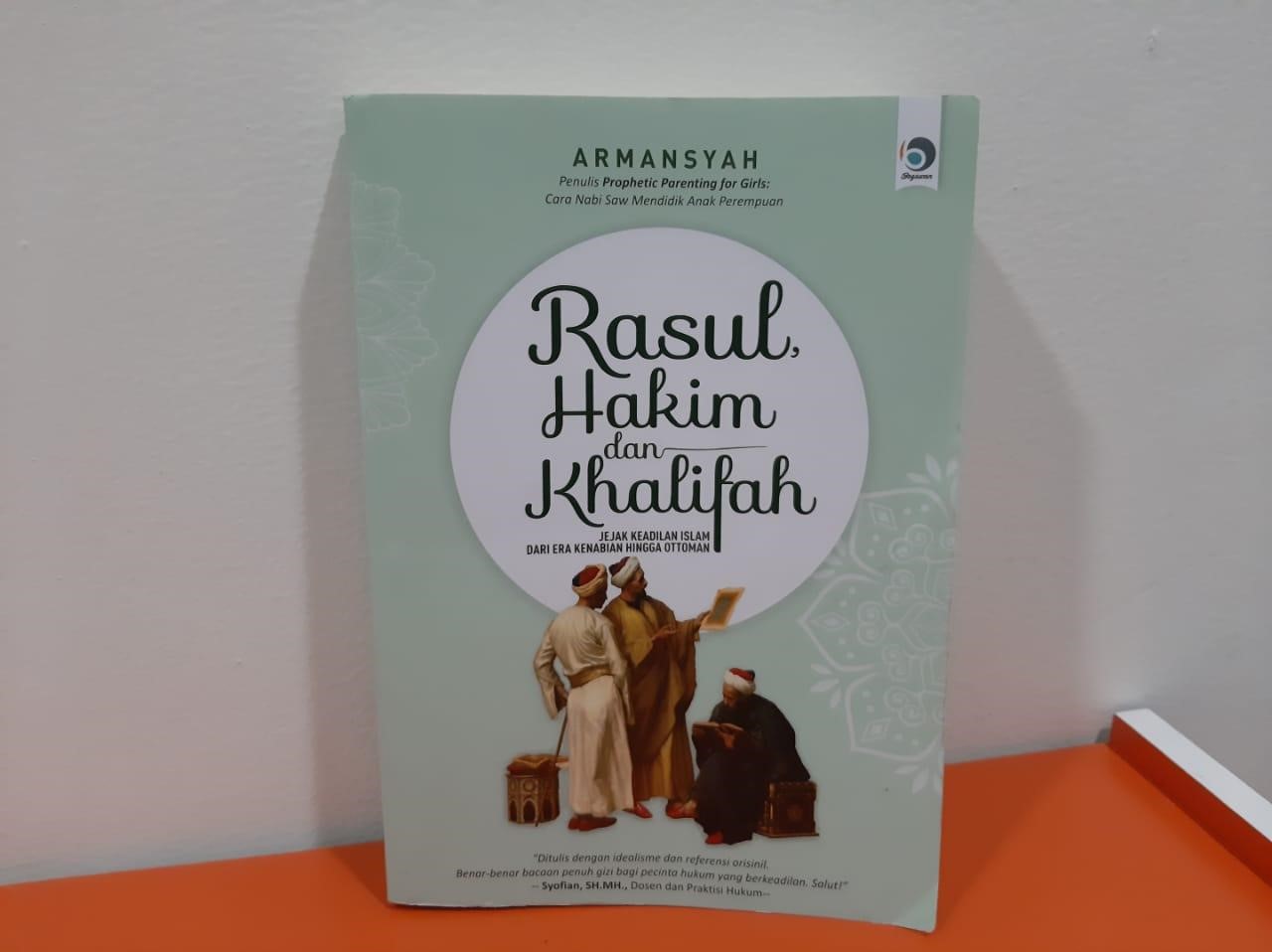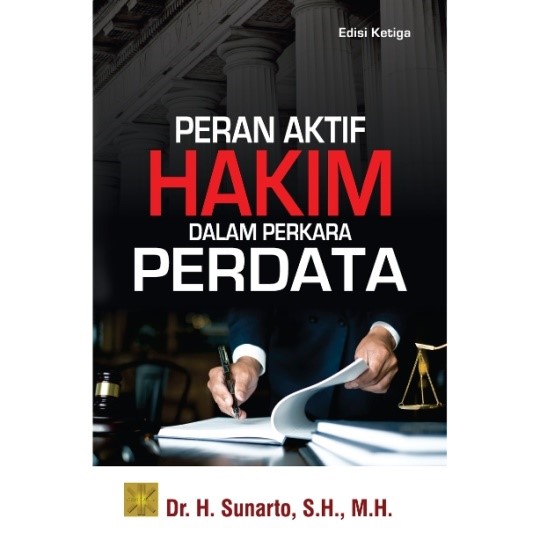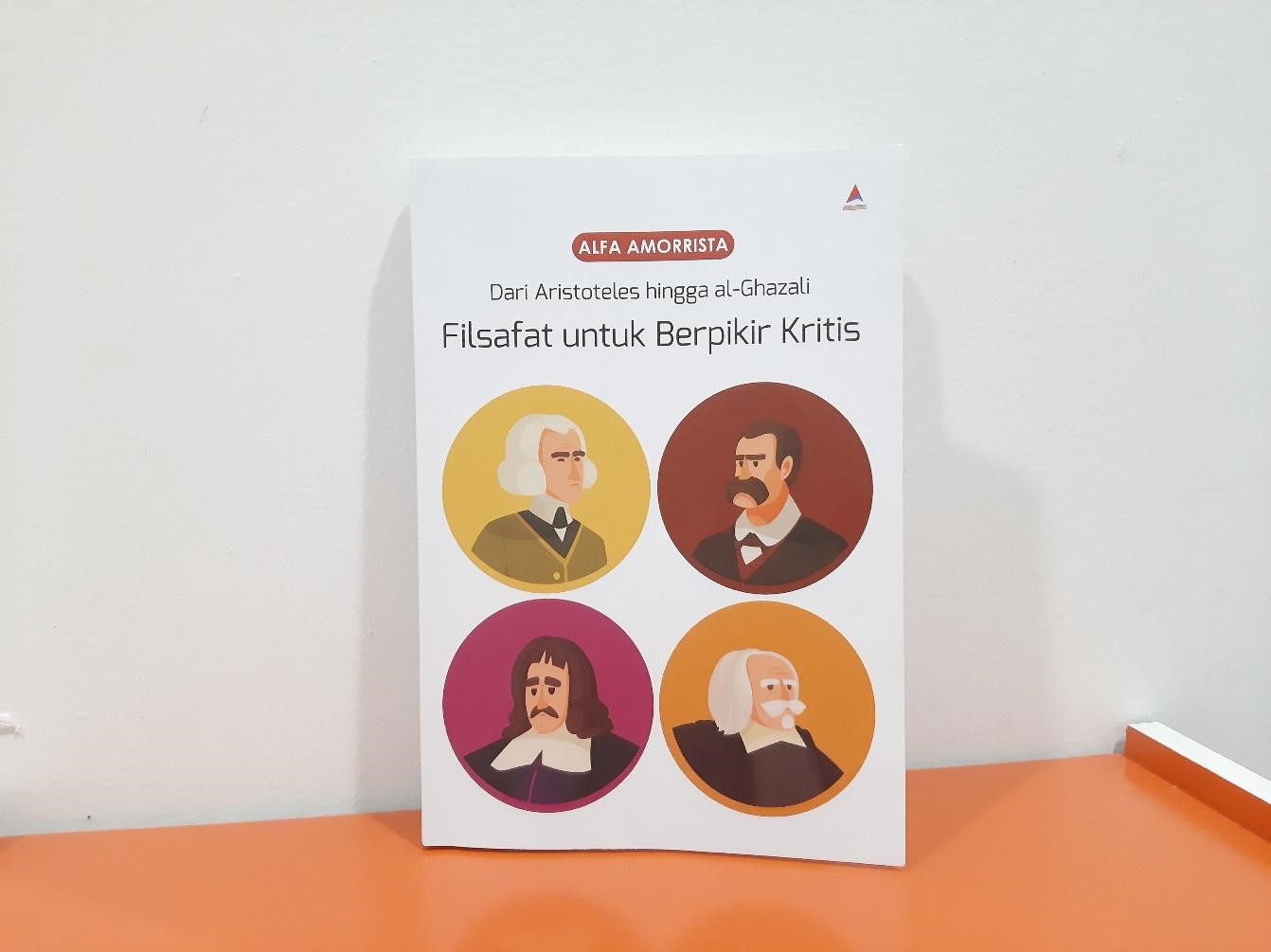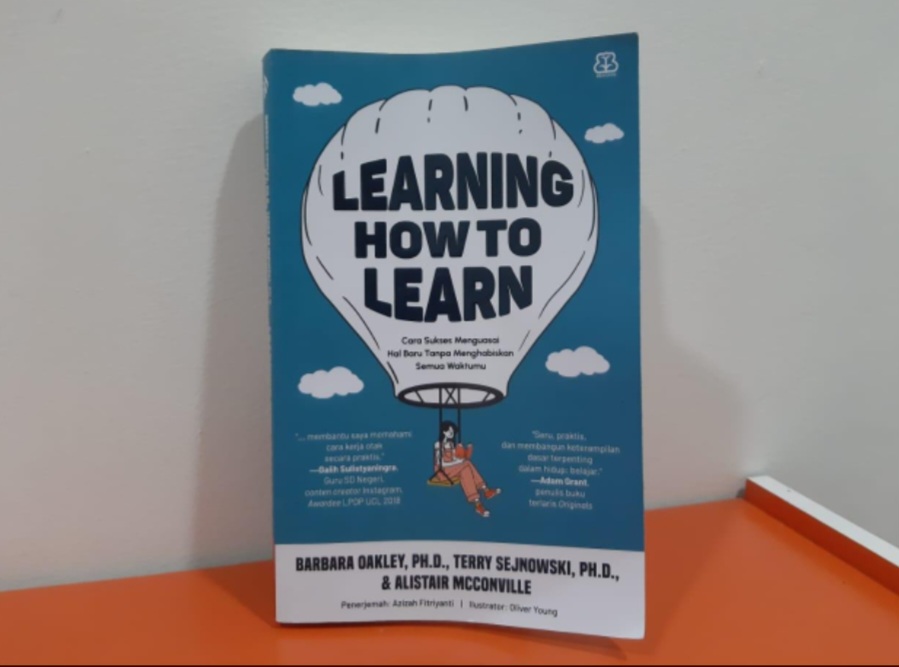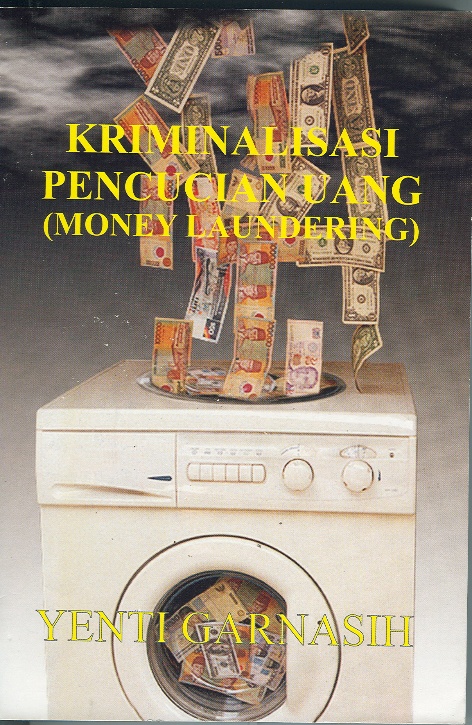John Grisham selama ini dikenal sebagai novelis thriller hukum yang piawai merangkai fiksi. Namun dalam The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town (2006), ia menulis sebuah kisah nyata, sebuah dokumen hukum sekaligus tragedi kemanusiaan.
Buku ini menceritakan perjalanan Ron Williamson, seorang pria yang nyaris dieksekusi mati di Oklahoma, Amerika Serikat, untuk kejahatan yang tidak pernah ia lakukan.
Kisah ini layak disebut sebagai bacaan wajib bagi para hakim, termasuk di Indonesia. Sebab, di balik alur investigasi yang salah arah, terdapat pelajaran mendalam tentang bagaimana sistem peradilan pidana bisa meruntuhkan hidup seseorang ketika asas praduga tak bersalah diabaikan.
Inti Cerita The Innocent Man
The Innocent Man adalah buku non-fiksi karya John Grisham yang dirilis pada 2006. Buku ini menceritakan kisah nyata tentang Ronald Keith "Ron" Williamson, seorang mantan pemain bisbol yang hidupnya berubah drastis setelah dituduh dan dihukum atas kasus pembunuhan.
Pada 1982, Debbie Carter, seorang pelayan bar di kota kecil Ada, Oklahoma, ditemukan tewas dibunuh di apartemennya. Kasus ini mengguncang komunitas kecil tersebut, dan pihak kepolisian berada di bawah tekanan besar untuk segera menemukan pelakunya.
Setelah bertahun-tahun penyelidikan yang tidak membuahkan hasil, polisi mengalihkan fokus mereka kepada dua pria lokal yakni Ron Williamson dan temannya, Dennis Fritz.
Ron, yang saat itu sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental dan penggunaan narkoba, adalah figur yang rentan. Ron memiliki perilaku aneh dan kadang membuat pengakuan-pengakuan yang membingungkan.
Berbekal bukti-bukti yang lemah, kesaksian dari orang-orang yang tidak kredibel, dan pengakuan Ron yang didapat pada saat ia sedang tidak stabil, jaksa penuntut berhasil meyakinkan juri dan atas itu Ron Williamson diputus hukuman mati atas pembunuhan Debbie Carter, sementara Dennis Fritz dijatuhi hukuman seumur hidup.
Selama bertahun-tahun, Ron dan Dennis berjuang dari balik jeruji besi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Kisah perjuangan mereka memuncak ketika sebuah kelompok aktivis hukum, Innocence Project, datang untuk membantu.
Dengan menggunakan teknologi tes DNA yang saat itu sudah lebih canggih, mereka berhasil membuktikan bahwa sidik jari dan DNA yang ditemukan di lokasi pembunuhan tidak cocok dengan Ron maupun Dennis. Akhirnya, setelah 12 tahun mendekam di penjara dan menunggu eksekusi mati, Ron Williamson dan Dennis Fritz dinyatakan bebas.
Sinopsis ini menyoroti bagaimana kelemahan dalam sistem peradilan, mulai dari proses investigasi yang cacat, penggunaan bukti yang tidak kuat, hingga tekanan publik untuk menutup kasus, dapat menghancurkan kehidupan orang yang tidak bersalah.
Cermin bagi Indonesia: Kasus Sangkon dan Karta
Kasus Sangkon (Kupang, 1980-an): Frans Sangkon divonis seumur hidup atas tuduhan pembunuhan siswi SMA. Putusan didasarkan pada pengakuan yang diperoleh lewat penyiksaan, tanpa bukti meyakinkan. Setelah 13 tahun, pelaku sebenarnya baru ditemukan dan Sangkon dibebaskan.
Kasus Karta (Banyuwangi, 1984): Seorang buruh tani dituduh memperkosa dan membunuh anak kecil. Ia dihukum seumur hidup dengan bukti tipis. Setelah 8 tahun, pelaku sebenarnya tertangkap, Karta bebas, tapi sudah kehilangan harga diri, keluarga, dan hidupnya tak pernah sama.
Baik The Innocent Man maupun kasus Sangkon & Karta menyingkap benang merah yang sama, yakni kerugian permanen yang harus dijalankan oleh korban salah tangkap.
Ironi Antara Putusan Hakim dan Opini Publik
Hakim dituntut menegakkan asas praduga tak bersalah, tetapi ketika hasil putusannya berbeda dengan keyakinan publik, disinilah terbentuknya ironi, kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa menurun.
Publik sering beranggapan bahwa jika ada orang ditangkap, pasti ia bersalah. Maka ketika hakim membebaskan karena bukti tidak cukup, masyarakat menilai “hakim melindungi penjahat.” Padahal justru sebaliknya, hakim sedang menegakkan hukum secara murni.
Masalahnya bukan pada putusan hakim, melainkan pada literasi hukum masyarakat.
Prinsip in dubio pro reo, prinsip hukum yang menyatakan bahwa ketika ada keraguan dalam pembuktian suatu perkara, maka keraguan tersebut harus diartikan untuk keuntungan terdakwa, masih jarang dipahami luas. Akibatnya, putusan yang benar secara hukum bisa terlihat keliru di mata publik.
Ketika Palu Hakim berhadapan dengan Suara Mayoritas
Pesan dari buku The Innocent Man dan tragedi peradilan sesat lainnya begitu gamblang: hakim tidak boleh populis.
Dalam ruang sidang, di mana nasib seseorang digantungkan, keputusan hakim harus sepenuhnya berdiri di atas pilar bukti yang sah dan keyakinan nurani yang jernih.
Tugas hakim bukanlah untuk memuaskan publik, melainkan untuk mencari dan menegakkan kebenaran hukum, bahkan ketika kebenaran itu tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh banyak orang.
Seberapapun kuatnya desakan publik yang menuntut seorang terdakwa dihukum, bila bukti di persidangan tidak memenuhi syarat, maka hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membebaskannya.
Prinsip klasik “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” bukan sekadar slogan, melainkan fondasi etika yang membedakan peradilan yang beradab dengan peradilan massa. Menghukum seseorang yang tidak bersalah adalah tragedi yang tidak termaafkan, sebuah noda yang tidak bisa dihapus dari sejarah peradilan.
Vonis yang mengikuti opini massa mungkin terasa menenangkan masyarakat dalam jangka pendek. Ia memberikan ilusi "keadilan yang cepat" dan memadamkan amarah publik. Namun, dalam jangka panjang, praktik seperti ini hanya akan meruntuhkan legitimasi hukum itu sendiri.
Hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua, termasuk minoritas dan mereka yang tidak populer, akan berubah menjadi alat untuk melayani selera mayoritas.
Apabila hakim mulai tunduk pada tekanan populisme, maka ia telah mengkhianati sumpahnya. Ia tidak lagi melayani keadilan, melainkan sedang tampil di panggung politik.
Dalam skenario ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman yang stabil dan objektif, melainkan sekadar refleksi dari emosi kolektif yang mudah berubah. Ini adalah resep pasti menuju sistem hukum yang tidak dapat dipercaya, di mana keadilan menjadi barang langka dan hak-hak asasi manusia bisa dikorbankan demi tepuk tangan publik.
Penutup
Buku The Innocent Man bukan sekadar kisah tragis dari Amerika, melainkan peringatan universal. Buku tersebut mengajarkan bahwa sistem hukum bisa salah arah, dan ketika itu terjadi, hakim adalah benteng terakhir.
Kasus Ron Williamson, Frans Sangkon, dan Karta menjadi bukti nyata bahwa putusan keliru bisa menghancurkan kehidupan seseorang lebih kejam daripada kejahatan itu sendiri.
Karena itu, hakim harus berani tidak populer, berani menentang arus opini, dan berdiri tegak di atas bukti serta nurani. Sebab, pada akhirnya, keadilan yang sejati tidak ditentukan oleh seberapa besar tepuk tangan publik, melainkan seberapa teguh hakim menjaga hak asasi manusia di ruang sidang.