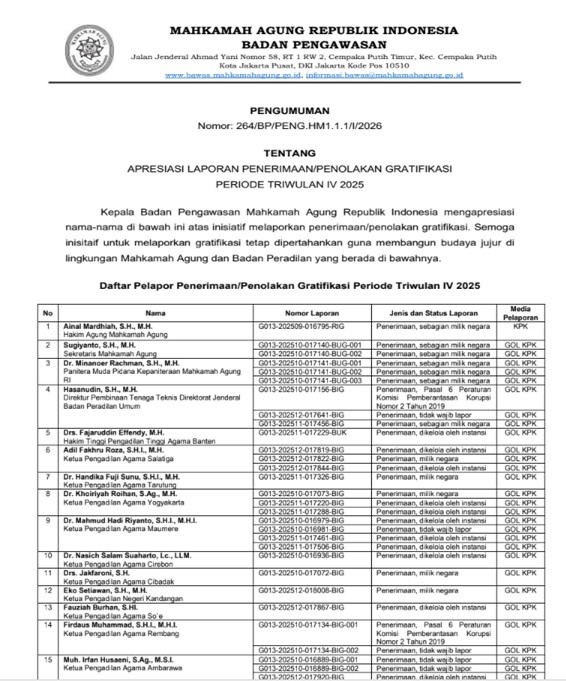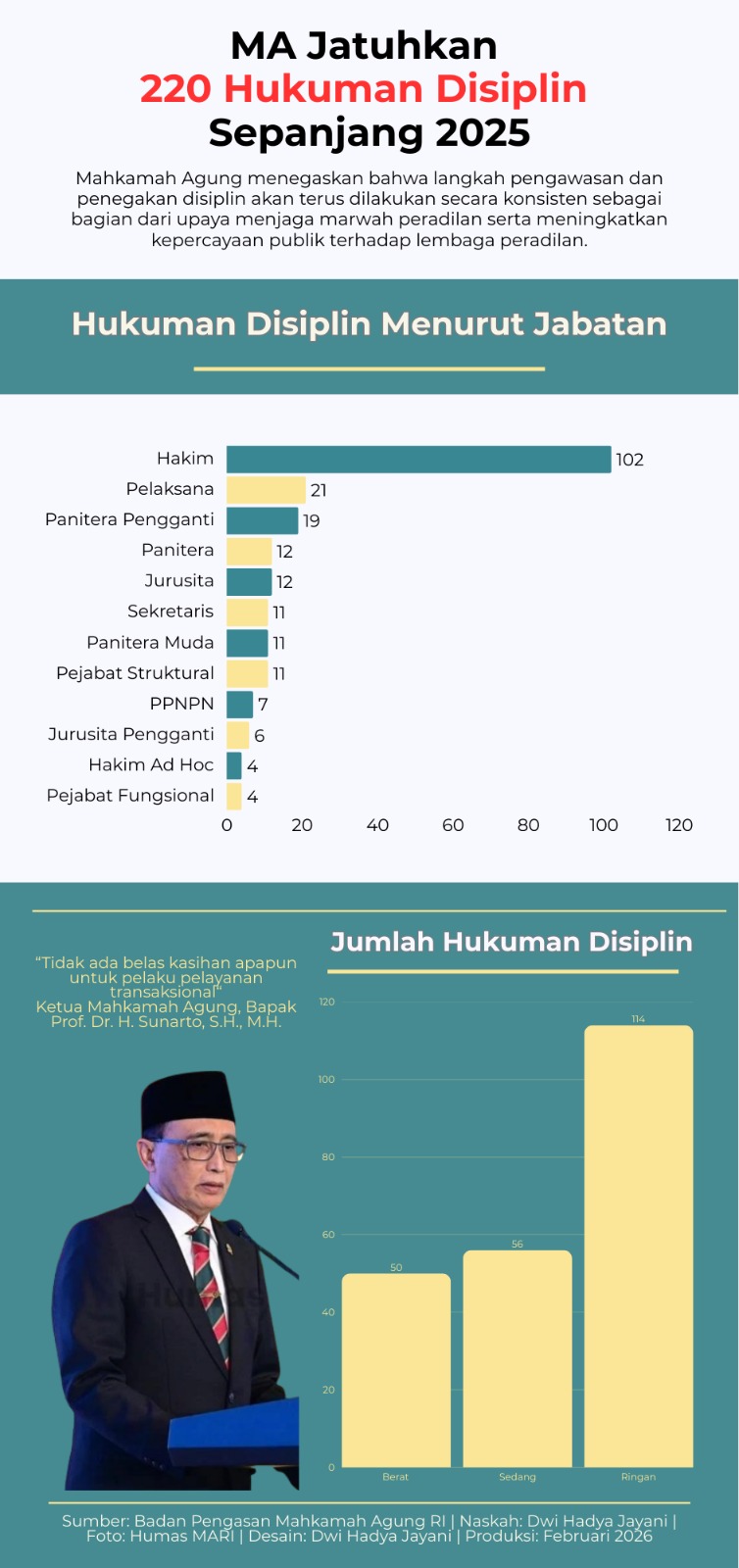Media massa kembali gaduh, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok terjaring OTT, pada Kamis (5/2/2026).
Kemudian Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, ditetapkan sebagai tersangka. Publik terperanjat dan rekan sejawat mengelus dada.
Pilu, ini tragedi integritas di jantung benteng keadilan. Mengapa ini berulang? Seperti drama yang naskahnya sudah kita hafal, tapi aktornya selalu ganti baru.
Publik sudah hafal alurnya. Asas praduga tak bersalah. Proses hukum berjalan dan penyidikan lanjut penuntutan. Kemudian, sidang dibuka untuk umum. Penuntut Umum membuktikan dan pihak terdakwa ajukan pembelaan.
Ujungnya putusan dijatuhkan dan menyusul putusan etiknya. Tapi ada sisi lain yang layak dicermati. Sebagai bahan refleksi.
OTT tidak terjadi tanpa indikasi. Ada petunjuk awal. Pada era kini, transaksi kegiatan peradilan hampir pasti meninggalkan jejak digital.
Percakapan terekam dan pergerakan terpantau. Hampir tidak ada kegiatan menyimpang, pun yang bersifat transaksasional, yang bisa disembunyikan.
Teknologi ibarat "malaikat pencatat" yang tidak bisa dirayu dengan suap. Hal ini, menilai kejahatan bisa tertutup rapat adalah kenaifan. Semua akan terbuka pada waktunya.
Pertanyaan besarnya bergeser yakni bukan apa yang terjadi, tapi, mengapa itu bisa terjadi. Maka, beragam frasa “mengapa” berebut keluar mempertanyakannya.
Sumpah hakim itu berat. Kalimatnya sakral. Nama Tuhan disebut dan diperdengarkan kepada khalayak. Ada konsekuensi dunia dan akhirat. Tapi, mengapa sumpah sering berakhir menjadi sekadar deretan kata tanpa makna? Hanya diucapkan di bawah kitab suci, lalu dilupakan saat diberitahukan sudah disiapkan “bungkusan” dalam tas ransel warna hitam.
Sumpah pimpinan pengadilan lebih berat lagi. Pasca sumpah, mereka wajib berperan sebagai role model. Membumikan nilai-nilai kode etik, yang karenanya mesti nampak dalam tutur kata, sikap dan perilaku nyata. Menjadi kode etik berjalan. Meski tak ada mata yang mengawasinya.
Sejarah mengingatkan, Kode etik hakim yang kita pedomani hari ini tidaklah lahir dari ruang hampa.
Para founding fathers kita, menyusunnya dengan cucuran keringat pemikiran. Mereka melakukan studi banding terhadap prinsip-prinsip universal The Bangalore Principles of Judicial Conduct.
Para pimpinan MA telah berpikir panjang, bagaimana agar nilai-nilai etik ini tidak hanya gagah di atas kertas, tapi juga applicable dan executable.
Katanya, kode etik hakim sejatinya tak berbeda dengan kaidah agama. Idem dito sebagai tuntunan luhur. Perintahnya adalah kebaikan, larangannya adalah keburukan.
Mengkhianati kode etik sama saja dengan mengkhianati nilai religiusitas yang kita agungkan. Namun, mengapa etika hakim sering kali berhenti di kulit kognitif?
Ada hakim fasih bicara integritas di forum. Suaranya lantang, mengajak bawahan taat. Namun kemudian ditemukan kenyataan, di mana ucapannya tidak segaris lurus dengan perilakunya?
Integritas dinilai hanya kosmetik, yakni dihafal ketika fit and proper test, dinampakkan saat dilihat. Padahal etika adalah otot integritas ketika dirayu godaan dan ditekan intervensi, serta teruji ketika sunyi.
Negara sudah berupaya menjaga integritas. Tunjangan jabatan dinaikkan dan fasilitas dipenuhi.
Kebutuhan dasar seharusnya sudah selesai. Tinggal fokus pada tugas yudisialnya.
Namun ternyata ada yang berani melompati koridor kebutuhan dan berenang di lautan keinginan yang tidak bertepi.
Fakta membuktikan, mengabdi pada keinginan adalah perbudakan tanpa akhir. Seberapa pun besar gaji, tidak akan pernah cukup untuk memberi makan naga keserakahan, yang terus lapar di dalam dada.
Apakah martabat dan kehormatan lembaga tidak cukup kuat menjadi rem? Profesi hakim adalah profesi mulia, officium nobile.
Mestinya, itu menjadi baju zirah. Namun. “baju perang” itu kerap ditanggalkan ketika berhadapan dengan pedang bermata uang.
Lupa pakem, uang haram memang diam, tapi baunya amis. Bau amisnya mampu membangunkan fungsi deteksi. Lalu dicoba dilawan dengan mitigasi, dibuat sedemikian sehingga tidak gampang diendus.
Bisa jadi seminggu, dua bulan aman. Namun, alam nyata memberi fakta, yakni kebatilan tidak ada yang abadi. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk menemukan jalan keluar.
Bau amis itu pasti akan terdeteksi, tidak peduli seberapa tebal tembok ruang kerja anda menutupi transaksi haram itu.
Para penggadai integritas, apakah saat melakukan transaksi, pernahkah terbayang wajah anak-anaknya? Dimasukkankah dalam bagian kalkulasi?
Kasihan, anak-anaknya yang tidak bersalah dipaksa memikul beban stigma negatif, bahwa ayah, atau ibunya koruptor. Jejak digital ini, tidak pernah hilang. Ia abadi di mesin pencari.
Arah angin penegakan hukum sudah bertiup jelas. Aparatur daerah disikat dan pejabat pajak dibersihkan. Aparat penegak hukum lain diproses.
Mengapa masih menganggap hakim dan aparatur pengadilan tidak bisa disentuh? Ketika ada yang tidak nyaman melihat kemungkaran, maka itu adalah titik awal kebocoran informasi. Lalu radar intersepsi sigap bergerak. Tinggal tunggu momen.
Refleksi ini, bukan untuk menggurui. Ini adalah cermin pengingat. Bahwa godaan itu nyata, dalam berbagai rupa.
Bahwa integritas itu kebutuhan diri pribadi, keluarga dan lembaga. Maka, marilah kita tetap kukuh di jalan mulia. Menjadi hakim yang memegang timbangan dengan tangan gemetar karena takut pada Tuhan.
Pakta integritas yang ditandatangani di setiap awal tahun menegaskan komitmen, yakni bertekad menjadi pelayan hukum yang berkeadilan.
Memberikan layanan ikhlas, tidak berpamrih kepada justiciabelen. Dicamkan di setiap helaan nafas. Diniati sebagai ibadah.
Mari kita saling menjaga, saling mengingatkan dalam dan demi kebaikan. Agar masyarakat pencari keadilan tetap percaya sepenuhnya pada lembaga kita tercinta. Smoga!