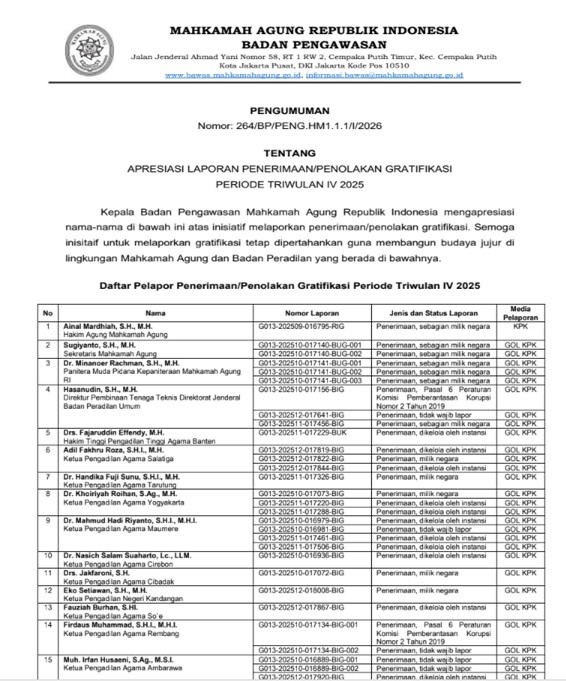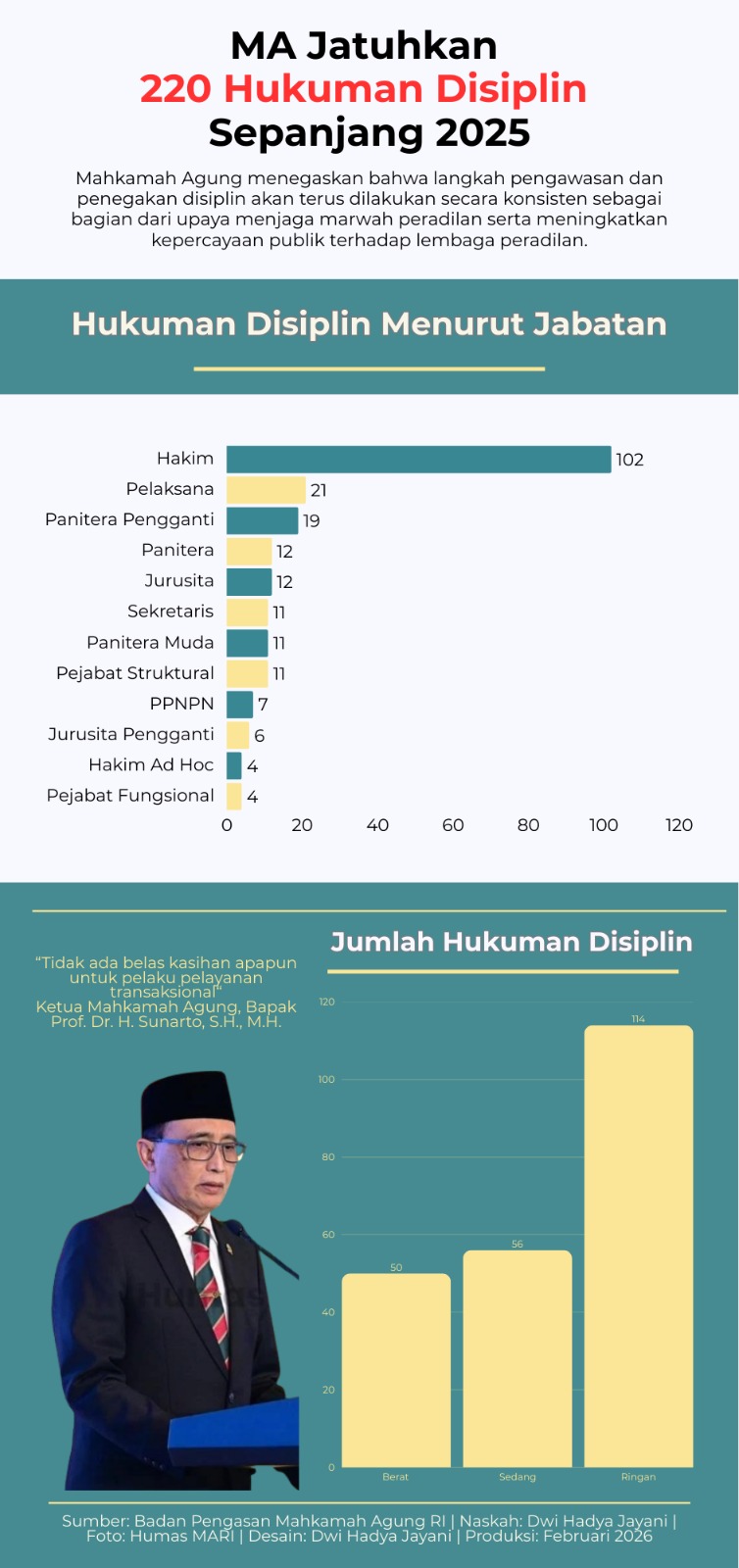Pendahuluan
Dalam setiap diskursus hukum di Indonesia, irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan sekadar residu formalitas yuridis. Kalimat tersebut merupakan sebuah manifestasi filosofis yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman beroperasi dalam ruang kesadaran transendental.
Hakim diposisikan sebagai pemangku mandat (amanah) untuk mengartikulasikan keadilan yang tidak hanya koheren secara legalitas-positivistik, tetapi juga resonan secara moral dan spiritual.
Namun, dalam praktiknya, metafora hakim sebagai wakil Tuhan kerap mengalami reduksi makna atau bahkan distorsi sosiologis. Tatkala simbol ketuhanan disalahpahami sebagai legitimasi absolut, muncul risiko sakralisasi figur hakim yang justru mengeliminasi ruang kritik dan akuntabilitas.
Padahal, esensi amanah ketuhanan adalah mekanisme pembatas (limitasi) kekuasaan, bukan instrumen pengukuh supremasi personal. Oleh karena itu, distingsi antara representasi simbolik amanah ilahi dan bahaya pengkultusan manusia dalam peradilan menjadi krusial untuk dikaji.
Hakim sebagai Wakil Tuhan dalam Paradigma Amanah
Dalam tradisi hukum Islam klasik, posisi hakim dipahami sebagai na’ib al-syar’ seorang wakil syariat yang bertugas membumikan nilai-nilai keadilan universal ke dalam partikularitas realitas sosial. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menekankan bahwa kewenangan qadi (hakim) bersifat delegatif dan terbatas. Ia bukanlah sumber kebenaran absolut, melainkan eksekutor hukum yang terikat secara ketat pada teks (nash), kaidah-kaidah hukum, dan kemaslahatan publik.
Sejalan dengan itu, Al-Ghazali memperingatkan bahwa otoritas yang dibalut simbol teologis merupakan ujian integritas yang paling berat. Baginya, rasa takut terhadap Tuhan (khauf) harus melampaui kebanggaan atas status sosial jabatan.
Tanpa kesadaran ini, kekuasaan kehakiman berisiko menjadi pintu masuk bagi kesombongan spiritual (kibr) yang memisahkan keadilan dari substansinya. Dalam perspektif hukum modern, pemikiran ini memiliki paralelitas dengan gagasan Ronald Dworkin mengenai hakim sebagai penafsir prinsip (judge as interpreter), yang wajib tunduk pada integritas hukum daripada kehendak subjektifnya.
Integritas dan Nilai Ketuhanan sebagai Konsekuensi Etis
Mengemban predikat wakil Tuhan dalam koridor amanah membawa implikasi etis yang eksistensial. Integritas hakim tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai kepatuhan pada kode etik formal, melainkan sebagai sinkronisasi antara rasio hukum dan suara hati. Imam al-Nawawi menggarisbawahi bahwa kualitas putusan tidak cukup hanya ditopang oleh kecerdasan intelektual, melainkan harus didukung dengan sifat waraʿ sebuah kehati-hatian moral yang mendalam dalam menggunakan otoritas.
Nilai ketuhanan menuntut hakim untuk mengakui keterbatasan kodratinya sebagai manusia. Al-Ghazali mengingatkan bahwa distorsi keadilan sering kali bukan disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum, melainkan oleh kerapuhan karakter saat berhadapan dengan godaan materialitas, popularitas, dan intervensi kekuasaan. Dengan demikian, integritas merupakan bentuk paling konkret dari internalisasi nilai transendental dalam ruang peradilan.
Integritas sebagai Pilar Legitimasi Publik
Legitimasi sosiologis lembaga peradilan berbanding lurus dengan integritas para hakimnya. Masyarakat tidak hanya mengukur keadilan dari diktum putusan, tetapi juga dari persepsi bahwa putusan tersebut lahir dari proses yang otonom, jujur, dan bermoral. Al-Khaṣṣaf dalam Adab al-Qaḍi menegaskan bahwa dekadensi peradilan selalu bermula dari degradasi akhlak hakim, bukan semata-mata karena kelemahan regulasi.
Al-Qarafi dalam Al-Furuq mempertajam argumen ini dengan memisahkan secara tegas antara wilayah al-ḥukm (otoritas yuridis) dan wilayah al-taqdis (sakralitas personal).
Hakim memegang otoritas untuk memutus perkara, namun ia tidak memiliki hak atas kesucian moral yang membuatnya kebal kritik. Ketika upaya koreksi dianggap sebagai serangan terhadap kewibawaan, saat itulah integritas peradilan sedang berada dalam titik nadir. Ibn al-Jawzi dalam Talbis Iblis memberikan peringatan pedas mengenai bagaimana jabatan tinggi sering kali menipu manusia hingga merasa maksum (tidak berdosa).
Melawan Sakralisasi demi Akuntabilitas
Sakralisasi figur hakim adalah ancaman laten bagi prinsip Rule of Law. Apabila hakim diposisikan sebagai entitas yang tidak mungkin keliru, maka mekanisme kontrol (check and balances) kehilangan relevansinya. Independensi hakim bukanlah cek kosong melainkan prasyarat yang harus dibarengi dengan akuntabilitas. Independensi tanpa integritas hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan yang dibungkus jubah hukum.
Dalam perspektif maqaṣid al-syari‘ah sebagaimana dikembangkan Al-Shaṭibi, tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan mustahil tercapai jika aktor hukumnya kehilangan kompas moral. Hukum yang presisi di tangan hakim yang tuna-integritas tetap akan menghasilkan ketidakadilan yang sistemik. Oleh karena itu, mendudukkan hakim kembali pada posisi kemanusiaannya yang terbatas adalah cara terbaik untuk menjaga kemurnian amanah Tuhan dalam peradilan.
Penutup: Mengembalikan Manusia, Menjaga Keadilan
Menafsirkan hakim sebagai wakil Tuhan haruslah dipahami sebagai upaya untuk membatasi ego manusia melalui tanggung jawab transendental. Amanah ini menuntut kerendahan hati, bukan arogansi. Hakim tidak dipanggil untuk menjadi figur mitologis yang tak tersentuh, melainkan menjadi abdi keadilan yang terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Pada akhirnya, peradilan yang bermartabat tidak dibangun di atas fondasi kultus individu, melainkan di atas konsistensi menjaga integritas di setiap ketukan palu. Dengan menjaga hakim tetap dalam watak kemanusiaannya yang rendah hati, keadilan tetap memiliki ruh ilahi hadir sebagai manifestasi pengabdian tulus bagi kebenaran, kemanusiaan, dan kemaslahatan semesta
Daftar Pustaka
Al-Ghazali, A. H. (2011). Ihya Ulum ad-Din (Vol. 2). Dar al-Minhaj. (Karya asli diterbitkan sekitar 1100).
Al-Khassaf, A. B. (1994). Adab al-Qadi. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Mawardi, A. H. (2006). Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara Islam. (F. Jauhar, Terj.). Darul Falah. (Karya asli diterbitkan sekitar 1058).
Al-Qarafi, S. D. (1998). Anwar al-Buruq fi Anwa al-Furuq (Vol. 4). Dar al-Salam.
Al-Shatibi, I. (2003). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Karya asli diterbitkan sekitar 1388).
Dworkin, R. (1986). Law’s empire. Harvard University Press.
Ibn al-Jawzi, A. F. (2005). Talbis Iblis. Dar al-Qalam.
Nawawi, Y. S. (2001). Al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab. Dar al-Fikr.