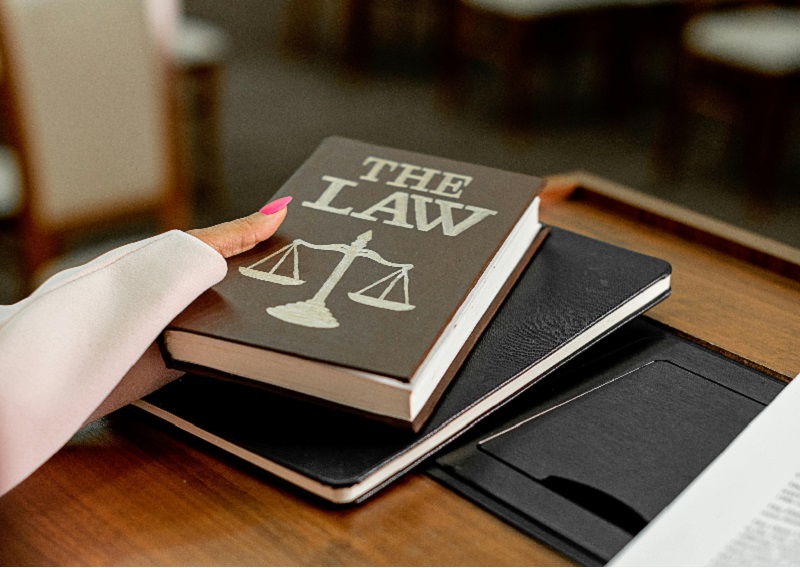Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) bukan sekadar pembaruan teks hukum, melainkan sebuah revolusi paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Salah satu pilar utama perubahan ini terletak pada Pasal 2, yang secara eksplisit mengakui keberadaan "hukum yang hidup dalam masyarakat" (the living law) sebagai dasar pemidanaan, berdampingan dengan hukum positif tertulis.
Pengakuan ini menandakan pergeseran fundamental dari asas legalitas formal yang kaku menuju keseimbangan dengan legalitas materiel, menegaskan bahwa keadilan tidak selalu tunggal wajahnya dalam teks undang-undang.
Secara mendasar, maksud dan tujuan utama dari Pasal 2 adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pembuat undang-undang menyadari bahwa hukum tertulis (positif) sering kali tertinggal dari dinamika masyarakat atau gagal menangkap nuansa keadilan lokal.
Dengan mengakui hukum yang hidup, Pasal 2 bertujuan mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam situasi di mana suatu perbuatan dianggap sangat tercela dan menuntut sanksi oleh masyarakat adat, namun luput dari jangkauan delik formal dalam KUHP.
Lebih jauh, tujuan filosofis dari pasal ini adalah untuk mengubah paradigma penegakan hukum dari yang bersifat legistik-kaku menjadi responsif-berkeadilan.
Dalam rezim hukum lama, hakim sering kali "terbelenggu" oleh teks undang-undang, dipaksa memutus perkara yang secara formal benar namun secara substansial melukai rasa keadilan masyarakat.
Melalui Pasal 2, negara bermaksud memberikan otoritas kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup guna mewujudkan keadilan substantif, menempatkan "rasa keadilan" di atas sekadar "bunyi pasal".
Secara historis, hukum pidana Indonesia telah lama terbelenggu dalam paradigma Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda yang sangat positivistis. Dalam tradisi kolonial tersebut, hukum adat sering kali diposisikan sebagai inferior, bahkan diabaikan demi unifikasi hukum.
Kehadiran KUHP Nasional mengusung misi dekolonialisasi, sebuah upaya sadar untuk melepaskan diri dari nilai-nilai kolonial dan menggali kembali nilai-nilai luhur bangsa. Pasal 2 hadir sebagai manifestasi pengembalian jati diri hukum nasional yang menghormati pluralisme hukum yang telah ada jauh sebelum negara terbentuk.
Dari perspektif filosofi perundang-undangan, Pasal 2 mencerminkan transisi dari aliran klasik yang berpusat pada perbuatan (daad-strafrecht) menuju aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan) dan subjektif (pelaku/masyarakat).
Pembaruan ini tidak lagi memandang hukum semata-mata sebagai apa yang tertulis (legisme), melainkan mengakui apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Penjelasan Pasal 2 menegaskan bahwa hukum yang hidup identik dengan hukum adat, yang keberlakuannya kini diperkuat namun tetap dalam koridor hukum nasional.
Inti dari Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa berlakunya asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana.
Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis bahwa perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat adat, meskipun tidak diatur dalam KUHP, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah bentuk pengakuan negara bahwa rasa keadilan yang tumbuh di akar rumput memiliki validitas sosiologis yang harus dihormati oleh sistem peradilan nasional.
Secara filosofis, keberadaan masyarakat adat dengan hukumnya adalah manifestasi dari Volksgeist (jiwa bangsa). Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, hukum bukan sekadar aturan larangan, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan kosmis dan harmoni sosial. Ketika keseimbangan itu terganggu oleh suatu perbuatan, masyarakat adat menuntut pemulihan yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh sanksi penjara semata.
Maksud dari pasal ini adalah memungkinkan hukum negara merangkul mekanisme penyelesaian lokal ini, memastikan bahwa hukum negara tidak menjadi asing (alienated) dari masyarakat yang diaturnya.
Namun, pengakuan terhadap hukum yang hidup ini dibingkai oleh prinsip teritorialitas yang ketat. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa hukum tersebut berlaku "dalam tempat hukum itu hidup". Frasa ini mengandung filosofi keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika), apa yang dianggap sebagai delik adat di satu wilayah tidak serta-merta berlaku di wilayah lain.
Hal ini bertujuan mencegah perbedaan nilai satu kelompok masyarakat terhadap nilai kelompok lain, sekaligus menghormati nilai lokal yang beragam di seluruh nusantara.
Lebih lanjut, pengakuan ini tidak bersifat tanpa batas. Pasal 2 ayat (2) memberikan serangkaian batasan. Hukum yang hidup tersebut hanya berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
Ini adalah mekanisme pengaman untuk memastikan bahwa hukum adat yang diadopsi selaras dengan pilar-pilar kebangsaan dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara.
Batasan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi titik temu krusial antara tradisi dan modernitas. KUHP Nasional berusaha memadukan paham yang terdapat pada suatu hukum adat dengan universalisme hak asasi. Artinya, praktik hukum adat yang diskriminatif, merendahkan martabat manusia, atau menerapkan sanksi fisik yang kejam tidak akan mendapatkan tempat dalam sistem hukum nasional, meskipun praktik tersebut "hidup" di masyarakat.
Dengan demikian, Pasal 2 berfungsi ganda yakni sebagai pintu masuk kearifan lokal sekaligus sebagai alat seleksi untuk memajukan peradaban hukum yang manusiawi.
Dalam tataran implementasi, tantangan terbesar adalah menjaga kepastian hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 2 ayat (3) memandatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Mandat ini menempatkan negara sebagai administrator yang bertugas menginventarisasi dan memformulasikan norma-norma tidak tertulis tersebut ke dalam aturan yang lebih terukur (misalnya melalui Peraturan Daerah), sehingga tercipta penyilangan hubungan antara fleksibilitas hukum adat dan kepastian hukum positif.
Dari sisi pemidanaan, Pasal 2 membawa semangat keadilan restoratif. Sanksi atas pelanggaran hukum yang hidup ini diselaraskan dengan Pasal 597, yang menyebutkan pidananya berupa pemenuhan kewajiban adat. Sanksi ini dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.
Filosofi ini menandai pergeseran dari orientasi retributif (pembalasan) menuju pemulihan keadaan, yang sejatinya adalah nafas utama dari hukum adat itu sendiri, memulihkan keseimbangan yang terganggu, bukan sekadar menghukum pelaku.
Sebagai penutup, Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) KUHP Nasional merupakan kristalisasi dari cita-cita hukum nasional yang demokratis, berkarakter, dan adaptif. Maksud dan tujuannya sangat jelas: menjembatani jurang antara hukum negara dan hukum rakyat, serta menghormati sejarah masa lalu dengan meninggalkan kacamata kuda kolonial.
Melalui pasal ini, Indonesia menegaskan bahwa hukum pidana nasional bukan hanya soal menghukum raga demi ketertiban, tetapi juga soal merawat jiwa bangsa dan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Referensi
[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.