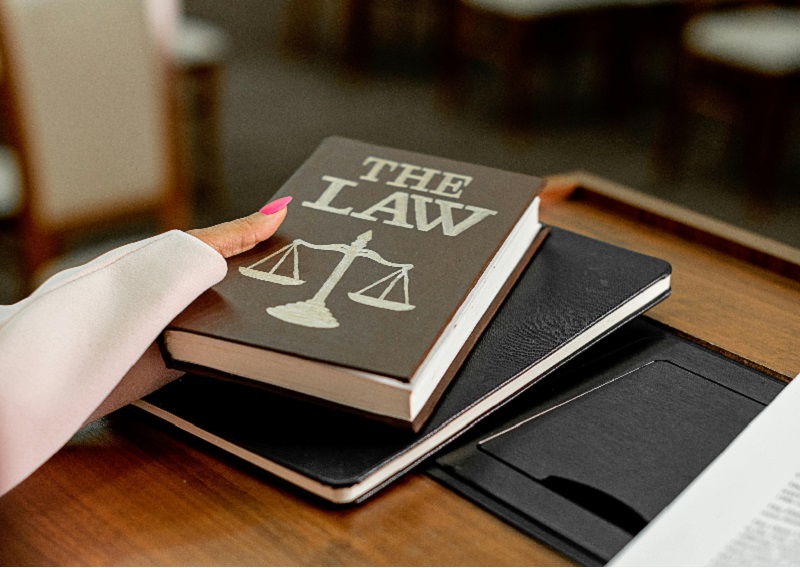Pendahuluan
Berbagai negara di dunia, memiliki konsensus berbeda dalam menentukan sistem pemerintahannya. Terdapat negara yang mengadopsi sistem pemerintahan presidensial, parlementer, monarki ataupun model campuran.
Secara historis, negara Indonesia pernah mengadopsi dua sistem pemerintahan baik parlemen maupun presidensial.
Sistem pemerintahan parlementer, diberlakukan pada awal Indonesia berdiri. Namun, pasca dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah meneguhkan sistem yang digunakan adalah Presidensial.
Negara yang adopsi sistem pemerintahan presidensial, di mana mendudukan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Menurut ahli hukum C.F. Strong, menerangkan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan merupakan bagian kekuasaan eksekutif.
Jabatan sebagai kepala negara disebut nominal executive. Sedangkan kepala pemerintahan dikenal dengan real executive.
Indonesia dan Sistem Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, sentral kekuasaan berada di tangan Presiden. Presiden memiliki hak penuh menentukan Menteri yang membantu tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam hal ini termasuk Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung.
Para Menteri yang diangkat Presiden, melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab kepada Presiden.
Demikian juga, presiden dalam sistem presidensial memiliki kewenangan penuh dalam urusan administrasi negara, diplomatik, dan militer.
Termasuk sebagian kewenangan yang berkaitan dengan tugas legislatif, yakni mengusulkan rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang, termasuk dalam kondisi tertentu membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undangan (perpu) dan peraturan pemerintah.
Konteks Indonesia, Presiden juga memiliki kewenangan memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung RI, sesuai Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945.
Selain itu, Presiden juga dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945.
Presiden dan KUHP Nasional
KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang diberlakukan mulai Januari 2026, dinilai oleh berbagai pihak sebagai terobosan progresif hukum pidana, yang mengubah tujuan pemidanaan, dari sebelumnya menggunakan pendekatan pembalasan (retributif) dalam KUHP lama, menjadi rehabilitatif dan juga berorientasi pada pemenuhan hak korban tindak pidana, sebagaimana tergambarkan dalam tujuan dan pedoman pemidanaan (vide Pasal 51 dan Pasal 53 KUHP Nasional.
Namun, hadirnya karya anak bangsa KUHP Nasional bukan tanpa tantangan. Terdapat beberapa ketentuan pidana, yang menjadi isu krusial dan perdebatan di ruang publik.
Salah satunya, muncul kembalinya tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden, sebagaimana ketentuan Pasal 218 ayat (1) KUHP Nasional.
Ancaman pidana untuk perbuatan tersebut, yakni pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (kategori IV).
Namun ketentuan Pasal 218 ayat (2) KUHP Nasional memberikan pengecualian, bilamana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, maka bukanlah termasuk tindak pidana.
Sedangkan, untuk penghinaan presiden dan/atau wakil presiden yang menggunakan sarana teknologi informasi diancam dengan pidana penjara lebih berat, yakni penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (kategori IV), sebagaimana ketentuan Pasal 219 KUHP Nasional.
Ketentuan ini menjadi kontroversial, seolah menghidupkan kembali Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP lama, yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandopotan Lubis selaku para pemohon.
Penting untuk dicermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dimaksud, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya.
Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. SedangkanPasal penghinaan terhadap kualitas pribadi (bukan jabatan) telah diatur dalam ketentuan Pasal 321 KUHP lama. Maka, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
Demikian juga Pasal Penghinaan Presiden di KUHP lama (vide Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137) bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selain itu, ketentuan pidana penghinaan Presiden menyulitkan untuk melakukan klarifikasi seandainya diduga melakukan pelanggaran hukum berat yang termasuk dalam syarat impeachment sebagaimana ketentuan Pasal 7A UUDNRI 1945
Bahkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 telah memberikan harapan dalam pertimbangan putusan dimaksud, bahwa seharusnya ketentuan pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi masuk dalam KUHP Nasional yang saat itu masih dalam tahap penyusunan, dikarenakan ketentuan Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak selaras dengan upaya pembaharuan hukum pidana dan bernuansa kolonial.
Kedua ketentuan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional (Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wapres) tersebut, juga menunjukan kuatnya sistem pemerintahan presidensial yang memberikan pengaturan khusus tentang ancaman pidana atas penghinaan Presiden.
Meskipun dalam KUHP lama, ketentuan pidana penghinaan Presiden telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, sebenarnya Pasal penghinaan terhadap individu tanpa membedakan status pekerjaan atau jabatan seseorang, telah diatur dalam KUHP Nasional (vide Pasal 433 s.d. Pasal 436).
Potensi Penerapan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Nasional
Mekanisme penerapan Pasal penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden didasarkan adanya aduan, sebagaimana ketentuan Pasal 220 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional.
Namun, praktiknya penerapan Pasal 218 ayat (1) dan/atau Pasal 219 KUHP Nasional, berpotensi menimbulkan tantangan tersendiri, seandainya terdapat seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan aduan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana dimaksud, karena secara hirarkis Kepolisian dan Kejaksaan bagian dari eksekutif dan ditunjuk oleh Presiden.
Walupun akhirnya, lembaga peradilan yang menentukan salah atau tidaknya individu yang dihadapkan atas dugaan penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ini jadi ujian independensi Hakim yang mengadili perkara dimaksud. Meskipun sering kita saksikan, Majelis Hakim dalam berbagai putusan yang berkaitan dengan penguasa (seperti perkara pidana melawan petugas dalam demonstrasi dsb), berbeda pandangan dengan penuntut umum. Termasuk dalam berbagai Putusan Perdata atau Tata Usaha Negara yang menjadikan negara sebagai pihak Tergugat.
Menurut penulis Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, seolah “berbeda jalan” dengan semangat pembaharuan hukum pidana melalui diberlakukannya KUHP Nasional, yang berikan alternatif pemidanaan seperti pidana pengawasan, denda dan kerja sosial, serta berparadigma rehabilitatif. Termasuk diaturnya, pemaafan oleh hakim terhadap tindak pidana yang memenuhi persyaratan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional.
Namun, penulis percaya lembaga peradilan akan menjadi benteng terakhir yang menilai dan memutuskan secara objektif, seandainya terdapat perkara dugaan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dihadapkan ke persidangan.
Lembaga peradilan akan hadir dalam bentuk paling mendasar dari independensi peradilan, yakni kemerdekaan putusan yang didasarkan pada kecakapan dan profesional hakim dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, serta tanpa intervensi pihak manapun.
Sebagai informasi, Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Nasional sempat diuji oleh berbagai akademisi pada tahun 2023 lalu, sebelum KUHP Nasional diberlakukan.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023 pada pokoknya menyatakan “ketentuan Pasal Penghinaan Presiden yang digugat tersebut, belum berlaku dan belum berdampak pada kerugian pemohon, karena akan belaku pada 2 Januari 2026”.
Saat ini KUHP Nasional telah berlaku efektif dan terdapat juga 12 warga negara yang mengajukan Judicial Review atas ketentuan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Nasional, sebagaimana penelusuran penulis di website Mahkamah Konstitusi.
Judicial Review Pasal Penghinaan Presiden telah masuk dalam pemeriksaan pendahuluan dan teregister dengan Nomor Perkara 275/PUU-XXIII/2025.
Selanjutnya eksistensi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Nasional, kita tunggu saja ujung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 275/PUU-XXIII/2025.
Sumber Referensi
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Kencana, 2018, Depok
- Arnita, Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol . 10, No. 2, 2020, hlm. 194-195- M. Ashanul Khuluqi dan Muwahid, Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia, Jurnal Al Qanun, Vol. 26, No. 2, Desember 2023, hlm. 174
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006