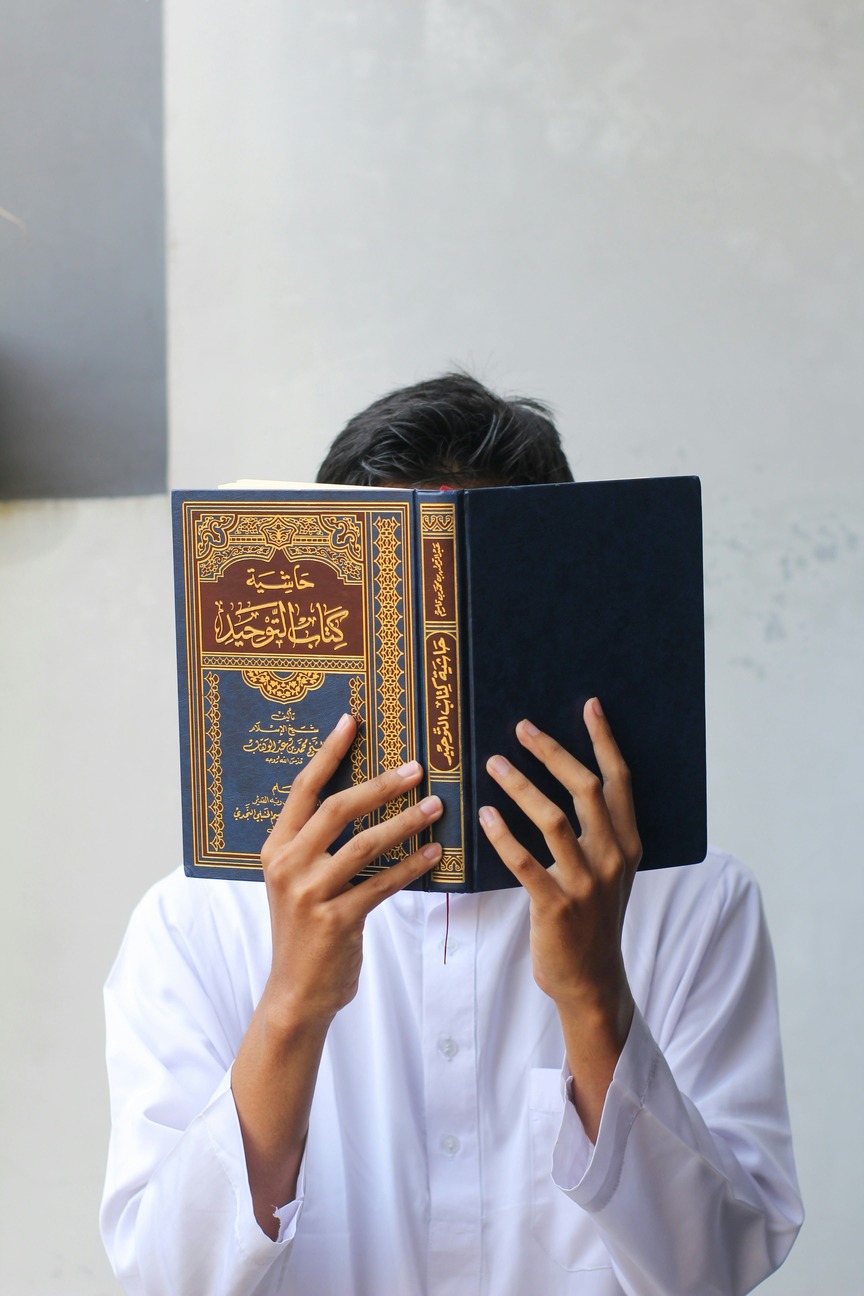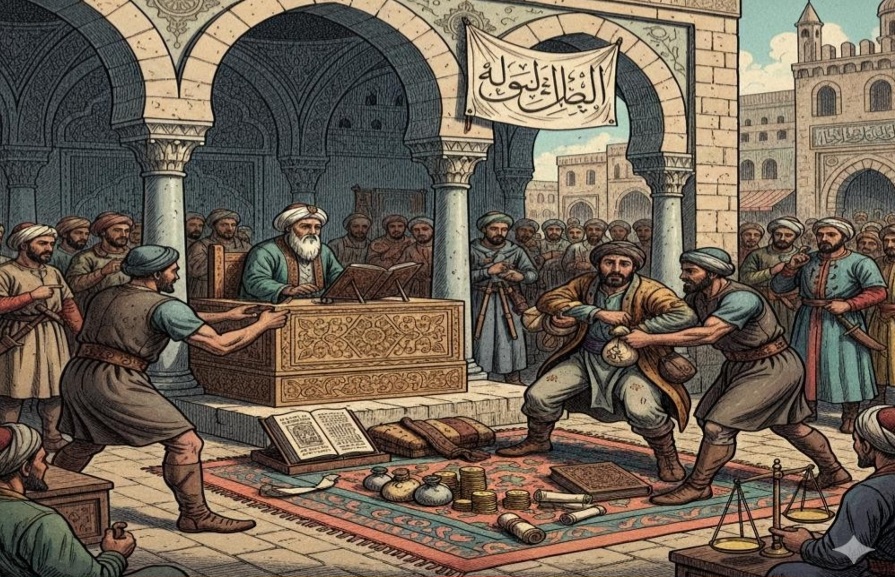Kesaksian dan Syahādah al-istifāḍah dalam Hukum Pembuktian Perdata
Dalam hukum acara perdata, saksi merupakan alat bukti primer yang bersifat esensial dalam pembuktian fakta hukum. Secara yuridis, kesaksian merupakan pernyataan lisan di persidangan tentang peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar secara langsung oleh saksi terkait objek sengketa. Sebagai subjek hukum, saksi harus memenuhi syarat formal dan material untuk memberikan keterangan yang menguatkan kebenaran peristiwa (Mertokusumo 2009:128).
Namun dalam praktik peradilan, tidak semua fakta dapat dijangkau oleh saksi mata. Dalam konteks inilah muncul konsep syahādah al-istifāḍah, yakni bentuk kesaksian yang tidak didasarkan pada pengalaman langsung, melainkan bersumber dari informasi yang telah tersebar luas di masyarakat.
Kesaksian ini, memperoleh dasar normatif dan pengakuan yang cukup kuat dalam literatur fikih, meskipun dalam sistem hukum positif Indonesia-khususnya hukum acara perdata-ia kerap disejajarkan dengan testimonium de auditu yang secara umum dianggap lemah atau tidak dapat diterima sebagai alat bukti.
Syahādah al-istifāḍah sebagai Kesaksian Kolektif
Secara etimologis, istifāḍah merujuk pada tersebarnya suatu informasi secara luas di tengah masyarakat, yang saling mendengar dan menyampaikan satu sama lain. Dalam konteks pembuktian, syahādah al-istifāḍah merupakan bentuk kesaksian tidak langsung dari pihak ketiga yang tidak mengalami atau mendengar sendiri suatu peristiwa hukum, melainkan berdasarkan berita yang telah menyebar luas di masyarakat (Asmuni 2014).
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mendefinisikannya sebagai reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan secara luas, bukan berdasarkan rekayasa narasi, melainkan berita yang benar-benar masyhur (khabar istifāḍah), yang posisinya berada antara yang posisinya berada antara khabar āḥād (berita yang diriwayatkan oleh individu atau kelompok kecil dan tidak mencapai tingkat keyakinan mutlak) dan khabar mutawātir (berita yang disampaikan oleh banyak perawi dalam setiap tingkat sanad secara mustahil untuk berdusta, sehingga menghasilkan keyakinan pasti). Berita semacam ini dapat dijadikan dasar kesaksian dan memiliki kekuatan pembuktian tersendiri (Ibnu Qayyim 1989).
Fuqaha sepakat bahwa khabar istifāḍah memiliki kekuatan probatif yang signifikan dalam hukum acara, bahkan dapat melebihi kekuatan dua orang saksi laki-laki dalam kasus tertentu. Perbedaan pendapat hanya terletak pada ruang lingkup penerapannya, seperti apakah dapat digunakan dalam perkara nasab, wakaf, kepemilikan, atau utang-piutang (Ibn Abi al-Dam 1984).
Menurut Zakariyya al-Anshari, syahādah al-istifāḍah merupakan bentuk kesaksian berdasarkan tasāmu‘ (mendengar informasi yang tersebar), yang dapat digunakan dalam perkara-perkara status keperdataan seperti nasab, perbudakan, wakaf, atau kepemilikan (Zakariyya al-Anshari n.d.: Jld. 4, h. 225). Dengan demikian, syahādah al-istifāḍah diakui sebagai bentuk kesaksian kolektif berbasis reputasi publik yang dapat diterima secara yuridis dalam keadaan tertentu.
Kedudukan Epistemologis dan Syarat Yuridis Syahādah al-istifāḍah
Dalam khazanah fikih, syahādah al-istifāḍah atau as-syahādah bi al-tasāmu‘ merujuk pada bentuk kesaksian tidak langsung yang bersumber dari informasi publik yang tersebar luas. Ulama mengklasifikasikannya dalam tiga tingkat validitas: (1) informasi mutawātir dan faktual yang wajib diterima meskipun tidak disaksikan langsung; (2) informasi yang menimbulkan dugaan kuat (ghalabat al-ẓann) dan telah mengakar dalam keyakinan kolektif; serta (3) informasi yang belum mencapai otoritas memadai.
Oleh karena itu, penerimaan syahādah al-istifāḍah dalam hukum acara syar‘i sangat bergantung pada sebaran dan kredibilitas informasinya, serta harus dievaluasi secara cermat dengan prinsip kehati-hatian dan objektivitas yudisial (Ibn Farḥūn 2003, Jld. 1: 295).
Agar syahādah al-istifāḍah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan, para fuqahā’ menetapkan sejumlah persyaratan yang bersifat normatif dan substansial. Pertama, kesaksian harus diberikan oleh minimal dua orang saksi yang adil (syāhidain ‘adlain), meskipun terdapat pendapat lain yang mensyaratkan empat saksi adil. Kedua, kesaksian tersebut tidak boleh menimbulkan keraguan, sebab apabila hanya segelintir orang yang mengetahui suatu peristiwa sementara komunitas luas yang sezaman tidak mengetahuinya, maka kesaksian tersebut dapat dinilai tidak valid, kecuali jika keraguannya dapat dikesampingkan secara objektif.
Ketiga, informasi yang dijadikan dasar kesaksian harus memiliki karakteristik istifāḍah, yakni telah tersebar secara luas di masyarakat dan diketahui secara umum. Keempat, saksi yang memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah sebagai bentuk penguatan tanggung jawab hukum dan integritas moral atas kesaksiannya (Ibn Farḥūn 2003, Jld. 1: 296).
Perbedaan Mazhab dalam Ruang Lingkup Penerapan Syahādah al-istifāḍah
Secara prinsipil, para fuqaha sepakat bahwa syahādah al-istifāḍah, merupakan bentuk kesaksian yang sah, meskipun para saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa yang menjadi objek kesaksian. Asas penerimaannya terletak pada tingkat kemasyhuran dan tersebarluaskan informasi, yang secara substansial menggantikan syarat penyaksian langsung. Perbedaan pendapat di antara para ulama tidak terletak pada keabsahan metodenya, melainkan pada jenis perkara apa saja yang dapat dibuktikan melalui syahādah al-istifāḍah.
Dalam mazhab Mālikī, terdapat perbedaan pandangan mengenai cakupan perkara yang dapat dibuktikan dengan metode ini. Al-Qāḍī ‘Abd al-Wahhāb berpendapat bahwa syahādah al-istifāḍah hanya dapat diterapkan pada perkara yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan status kepemilikan, seperti penetapan nasab, kematian, wakaf, dan pernikahan.
Sementara itu, Ibnu Rusyd al-Jadd mencatat adanya empat pendapat: (1) dapat diterapkan pada semua jenis perkara; (2) tidak dapat diterima sama sekali; (3) dapat diterima kecuali dalam perkara nasab, putusan pengadilan (qaḍā’), pernikahan, dan kematian; serta (4) hanya dapat diterima dalam empat perkara tersebut.
Adapun ulama seperti Ibn Syās, Ibn Ḥājib, dan mayoritas fuqaha Mālikiyah cenderung membatasi penerapannya dalam sejumlah perkara tertentu, dengan variasi antara 20 hingga 49 jenis perkara sebagaimana dirinci dalam al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah (1983, Jld. 26: 235).
Dalam perkara nasab dan kelahiran, terdapat konsensus (ijmā‘) yang diriwayatkan oleh Ibn al-Mundzir mengenai kebolehan pembuktian melalui syahādah al-istifāḍah. Adapun dalam mazhab Ḥanbalī dan sebagian Syāfi‘iyyah, diperkenankan penggunaan metode ini dalam sembilan perkara, antara lain: nikah, kepemilikan mutlak, wakaf dan penyalurannya, kematian, pembebasan budak, hubungan nasab karena pembebasan budak, perwalian, serta pelepasan jabatan publik. Namun demikian, sebagian ulama Syāfi‘iyyah lainnya mengecualikan penggunaannya dalam perkara-perkara seperti wakaf, perbudakan, dan ikatan perkawinan. Sedangkan Abū Ḥanīfah membatasi penerimaan syahādah al-istifāḍah hanya dalam tiga jenis perkara, yakni pernikahan, kematian, dan nasab (Ibn Quddamah, .1983, Jld 12: 23)
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (1989), hakim diperbolehkan memutus perkara berdasarkan syahādah al-istifāḍah, karena informasi yang tersebar luas dalam masyarakat dapat menjadi dasar pembuktian yang kuat dan objektif. Kesaksian semacam ini dipandang lebih mampu menghindari kecurangan baik dari saksi maupun hakim, dan dalam beberapa kasus bahkan memiliki kekuatan probatif yang lebih besar daripada kesaksian dua orang laki-laki yang memenuhi syarat formil dan materil.
Namun demikian, validitas kesaksian istifāḍah tetap memerlukan standar ketat, seperti keharusan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar telah tersebar luas dan diterima sebagai kebenaran kolektif, bukan sekadar rumor atau kabar simpang siur.
Syahādah al-istifāḍah dalam Praktik Yudisial
Dalam praktik peradilan, kesaksian de auditu atau syahādah al-istifāḍah lebih lazim digunakan dalam perkara voluntair (permohonan) dibandingkan perkara contentiosa (gugatan). Hal ini disebabkan karena dalam perkara gugatan, pembuktian umumnya diawali dengan alat bukti yang lebih kuat seperti kesaksian langsung dari saksi yang mengalami peristiwa. Kesaksian de auditu kemudian dapat berfungsi sebagai pelengkap atau penguat atas pembuktian yang telah diajukan sebelumnya, termasuk pengakuan atau alat bukti lainnya.
Mahkamah Agung RI telah mengakomodasi konsep syahādah al-istifāḍah, khususnya dalam perkara wakaf. Kesaksian ini dipahami sebagai keterangan dari saksi yang tidak mengalami langsung peristiwa wakaf, namun mengetahui bahwa suatu benda telah lama digunakan untuk kepentingan ibadah oleh masyarakat dan dianggap sebagai harta wakaf. Selain dalam perkara wakaf, syahādah al-istifāḍah juga diakui kekuatan pembuktiannya dalam pengesahan perkawinan (itsbāt nikāḥ).
Hal itu, ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa syahādah al-istifāḍah dapat dibenarkan dalam perkara itsbāt nikāḥ maupun ikrar wakaf yang telah lama terjadi, baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa.