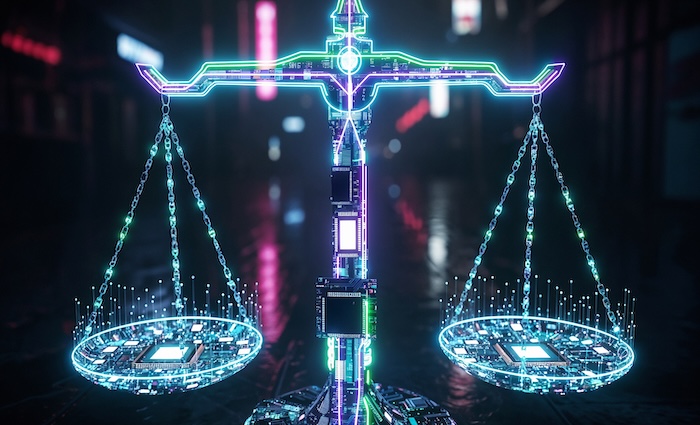Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah transformasi peradilan yang sangat fundamental. Di satu sisi, kita menyambut momentum bersejarah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026, yang membawa paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia.
Di sisi lain, revolusi teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) merambah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk ruang sidang yang selama ini identik dengan toga hitam, palu, dan tumpukan berkas perkara.
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan progresif dalam transformasi digital melalui e-Court, e-Litigation, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Direktori Putusan yang telah memberikan transparansi dan efisiensi luar biasa.
Namun, kini kita sampai pada titik kritis: sejauh mana AI boleh berperan dalam pertimbangan substansial putusan hakim? Ini bukan lagi persoalan administratif atau teknis, melainkan menyentuh jantung filosofis peradilan: keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral.
Tulisan ini berupaya mengurai dilema tersebut dari perspektif filosofis dan praktis, dengan mengintegrasikan perkembangan hukum pidana nasional terkini, pembelajaran dari praktik global, serta memberikan arahan strategis bagi ekosistem peradilan Indonesia dalam menghadapi era algoritma.
Dialektika Nurani dan Algortima: Esensi Pekerjaan Hakim
A. Natura Keputusan Yudisial: Antara Logika dan Kebenaran Hati Nurani
Pekerjaan hakim pada hakikatnya bukan sekadar operasi logika hukum yang mekanis. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini adalah amanat konstitusional yang menempatkan hakim bukan sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi), melainkan sebagai penjaga keadilan substantif yang memadukan logika hukum, hati nurani, dan kepekaan terhadap nilai-nilai sosial.
Putusan yang adil lahir dari perpaduan harmonis antara: (1) Penguasaan teknis yuridis yang presisi; (2) Pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan kultural di mana perkara terjadi; (3) Empati kemanusiaan yang melihat para pihak bukan sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki martabat; dan (4) Kebijaksanaan (wisdom) yang terakumulasi dari pengalaman mengadili ribuan kasus dan menyaksikan langsung dinamika kemanusiaan.
Dalam konteks KUHP Nasional yang akan berlaku, dimensi ini semakin krusial. Pasal 51 ; Pasal 54 dan pasal 70 KUHP Nasional mengatur inovasi pidana bersyarat dengan persyaratan khusus dan pedoman pemidanaan yang memberikan ruang diskresi lebih luas kepada hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan, kondisi personal pelaku, dan potensi rehabilitasi. Lebih jauh, Pasal 54 (2) tentang Pemaaf Hakim / Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon) memberikan kewenangan luar biasa kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.
B. Limitasi Ontologis AI: Mesin Tanpa Nurani
Kecerdasan Buatan, betapapun canggihnya, memiliki keterbatasan ontologis fundamental. AI adalah sistem komputasi yang bekerja dengan pattern recognition berbasis data historis. Large Language Models (LLM) seperti ChatGPT-4, Claude, atau Gemini memang mampu menganalisis jutaan dokumen hukum, menemukan preseden, dan bahkan menyusun draft pertimbangan hukum dalam hitungan detik. Namun, AI tidak memiliki:
- Kesadaran moral (moral consciousness) untuk membedakan "benar" dan "adil" dalam konteks unik setiap perkara;
- Empati autentik untuk merasakan penderitaan korban, penyesalan terdakwa, atau tekanan sosio-ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidana;
- Intuisi yudisial yang lahir dari pengalaman hidup dan interaksi langsung dengan kompleksitas kemanusiaan;
- Tanggung jawab moral dan accountability di hadapan Tuhan dan masyarakat atas setiap putusan yang dijatuhkan.
Lebih jauh, AI rentan terhadap bias algoritmik. Sistem AI belajar dari data masa lalu, dan jika data tersebut mengandung bias sistemik—misalnya diskriminasi berbasis ras, gender, atau kelas sosial—maka AI akan mereproduksi dan bahkan mengamplifikasi bias tersebut.
Studi ProPublica (2016) terhadap sistem COMPAS yang digunakan di pengadilan Amerika Serikat menunjukkan bahwa algoritma penilaian risiko residivisme secara sistematis memberikan skor risiko lebih tinggi kepada terdakwa kulit hitam dibandingkan kulit putih dengan latar belakang kriminal yang serupa.
Dalam konteks Indonesia, penggunaan AI tanpa filter moral dan kearifan hakim dapat menghasilkan putusan yang secara teknis "konsisten" dengan preseden statistik, namun gagal menangkap rasa keadilan lokal dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi bintang pemandu sistem hukum kita.
Pembelajaran dari Praktik Global: Loomis dan Piagam Etika Eropa
A. Kasus State v. Loomis: Batas Penggunaan AI dalam Pemidanaan
Kasus State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wisconsin 2016) menjadi landmark case yang menandai batas etis penggunaan AI dalam peradilan pidana.
Eric Loomis dihukum berdasarkan rekomendasi dari sistem COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), sebuah algoritma proprietary yang menilai risiko residivisme terdakwa. Loomis mengajukan banding dengan dalil bahwa penggunaan sistem black-box yang tidak transparan melanggar hak konstitusionalnya atas due process.
Mahkamah Agung Wisconsin memutuskan bahwa meskipun pengadilan boleh mempertimbangkan skor risiko dari AI, namun: (1) Skor tersebut tidak boleh menjadi faktor determinan dalam penjatuhan pidana; (2) Hakim wajib memahami limitasi dan potensi bias dari sistem; (3) Terdakwa berhak mendapat penjelasan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko; dan (4) Keputusan akhir tetap berada di tangan hakim sebagai pemegang tanggung jawab moral.
Putusan Loomis menegaskan prinsip fundamental: AI adalah advisory tool, bukan decision-maker. Ini sejalan dengan doktrin human-in-command yang harus menjadi pijakan dalam setiap penggunaan AI di ranah yudisial.
B. European Ethical Charter on the Use of AI in Judicial Systems
Komisi Eropa untuk Efisiensi Peradilan (CEPEJ) pada 2018 menerbitkan European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment, yang kemudian diadopsi oleh Komite Menteri Dewan Eropa. Piagam ini menetapkan lima prinsip etis fundamental:
- Prinsip Respect for Fundamental Rights: AI harus menjamin perlindungan HAM, termasuk hak atas peradilan yang adil, presumption of innocence, dan right to explanation;
- Prinsip Non-Discrimination: AI wajib dirancang dan diaudit untuk mencegah bias berbasis ras, gender, agama, atau status sosial;
- Prinsip Quality and Security: Data yang digunakan harus valid, akurat, dan aman dari manipulasi;
- Prinsip Transparency, Impartiality, and Fairness: Algoritma harus dapat dijelaskan (explainable AI) dan diaudit secara independen;
- Prinsip "Under User Control": Hakim tetap memegang kendali penuh (human-in-command). AI hanya alat bantu, bukan pengambil keputusan.
Prinsip terakhir adalah yang paling krusial. Human-in-command bukan sekadar slogan, melainkan garantsi bahwa tanggung jawab moral, akuntabilitas, dan kebijaksanaan dalam memutus keadilan tetap berada di tangan manusia yang memiliki nurani. Teknologi boleh membantu hakim menemukan hukum (rechtsvinding), tetapi tidak boleh menggantikan kebijaksanaan dalam memutus keadilan (rechtschepping).
Urgensi Regulasi AI dalam Peradilan Indonesia
A. Risiko Black Box dan Imperatif Transparansi
Ancaman terbesar dari AI dalam konteks hukum adalah sifatnya sebagai "black box”, algoritma tertutup yang prosesnya tidak dapat dijelaskan kepada publik atau pihak yang berperkara.
Bayangkan situasi di mana sistem AI merekomendasikan hukuman penjara 10 tahun untuk seorang terdakwa, namun ketika ditanya "Mengapa 10 tahun? Bagaimana sistem sampai pada angka itu?", tidak ada jawaban yang dapat diberikan secara transparan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas due process dan hak terdakwa untuk mengetahui dasar pemidanaan sebagaimana dijamin Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 4 KUHAP.
Lebih jauh, dalam era KUHP Nasional yang memberikan ruang diskresi lebih luas kepada hakim-terutama terkait pengampunan hakim / Judicial Pardon, pidana bersyarat, dan individualisasi pemidanaan—transparansi menjadi semakin krusial.
Jika hakim menggunakan AI untuk mempertimbangkan apakah seorang terdakwa layak mendapat pengampunan/ pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 (2) KUHP Nasional, maka terdakwa, penuntut umum, dan masyarakat berhak mengetahui faktor-faktor apa yang dipertimbangkan AI dan bagaimana hakim melakukan "quality control" terhadap rekomendasi tersebut.
B. Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum yang tegas tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi. Dalam konteks peradilan, data perkara seringkali mencakup informasi sangat sensitif: latar belakang ekonomi keluarga, riwayat kesehatan mental, orientasi seksual, keyakinan agama, bahkan trauma kekerasan.
Jika data ini digunakan untuk melatih sistem AI tanpa protokol keamanan yang ketat, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan menjadi sangat nyata.
Kasus kebocoran data KPU di tahun 2024 yang mengekspos informasi 200 juta pemilih menjadi pengingat keras bahwa infrastruktur digital kita masih rentan. Mahkamah Agung harus memastikan bahwa setiap sistem AI yang digunakan dalam ekosistem peradilan memenuhi standar keamanan siber tertinggi, dengan enkripsi end-to-end, audit keamanan berkala, dan mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran data.
C. Isu Keadilan Prosedural dan Akses terhadap Keadilan
Asas equality before the law mengharuskan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Namun, jika sistem peradilan bergantung pada AI yang canggih dan mahal, muncul risiko kesenjangan digital (digital divide) yang dapat memperparah ketimpangan akses keadilan.
Pencari keadilan dari daerah terpencil, masyarakat kurang mampu, atau kelompok rentan mungkin tidak memiliki kemampuan teknis atau finansial untuk memahami atau mengkritisi rekomendasi AI yang digunakan terhadap mereka.
Oleh karena itu, setiap penggunaan AI dalam proses yudisial harus disertai dengan mekanisme bantuan hukum dan edukasi publik yang memadai, memastikan bahwa teknologi tidak menjadi instrumen yang memperlebar jurang ketidakadilan, melainkan menjembataninya.
Peta Jalan Strategis Mahkamah Agung: Regulasi Sebagai Benteng Keadilan
Untuk memastikan bahwa AI menjadi sekutu bagi keadilan, bukan ancaman terhadap integritas peradilan, Mahkamah Agung perlu menyusun kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan berbasis pada prinsip-prinsip etis universal. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan:
A. Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Etika dan Tata Kelola AI dalam Peradilan
MA perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus mengatur etika dan tata kelola penggunaan AI dalam proses yudisial. PERMA ini harus memuat:
- Definisi dan Ruang Lingkup: Apa yang dimaksud dengan AI dalam konteks peradilan, jenis-jenis AI yang diperbolehkan (misalnya: legal research assistant, case management system) dan yang dilarang (misalnya: automated sentencing system);
- Prinsip Human-in-Command: Penegasan tegas bahwa hakim adalah pengambil keputusan final dan AI hanya boleh berfungsi sebagai alat bantu, bukan penentu;
- Kewajiban Transparansi: Setiap penggunaan AI dalam pertimbangan perkara wajib dicantumkan dalam putusan, termasuk nama sistem, metodologi, dan limitasinya;
- Larangan Diskriminasi: Sistem AI wajib diaudit untuk memastikan tidak mengandung bias berbasis SARA, gender, status sosial, atau faktor diskriminatif lainnya;
- Perlindungan Data: Implementasi protokol keamanan data yang ketat sesuai UU PDP, termasuk anonimisasi data perkara yang digunakan untuk training AI;
- Mekanisme Pengaduan dan Oversight: Pembentukan jalur pengaduan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh penggunaan AI, serta audit berkala oleh lembaga independen.
B. Pembentukan Unit Khusus Teknologi Peradilan dan Etika AI
MA perlu membentuk Unit Khusus yang bertanggung jawab atas governance dan oversight terhadap seluruh sistem teknologi yang digunakan dalam peradilan, khususnya AI. Unit ini harus memiliki kompetensi interdisipliner (hukum, teknologi informasi, etika, statistik) dan berfungsi sebagai:
- Quality Assurance: Melakukan pengujian dan sertifikasi terhadap setiap sistem AI sebelum diimplementasikan;
- Continuous Monitoring: Memantau kinerja sistem AI secara berkala untuk mendeteksi anomali, bias, atau penurunan akurasi;
- Training and Capacity Building: Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparatur peradilan tentang penggunaan AI yang etis;
- Research and Development: Mengembangkan sistem AI yang dirancang khusus untuk konteks hukum Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.
C. Kewajiban Audit Etis dan Sertifikasi Sistem AI
Setiap sistem AI yang akan digunakan dalam ekosistem peradilan wajib melalui audit etis yang komprehensif, meliputi: (1) Fairness Audit untuk mendeteksi bias algoritmik; (2) Transparency Audit untuk memastikan bahwa proses pengambilan kesimpulan AI dapat dijelaskan (explainable AI); (3) Security Audit untuk menjamin perlindungan data dan ketahanan terhadap serangan siber; dan (4) Compliance Audit untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Audit ini harus dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki akreditasi, dan hasilnya wajib dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas publik. Sistem yang tidak lolos audit tidak boleh digunakan dalam proses peradilan.
D. Program Literasi Digital dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Transformasi digital peradilan tidak akan berhasil tanpa peningkatan kapasitas SDM. MA perlu menyelenggarakan program pelatihan berjenjang yang mencakup:
- Tingkat Dasar: Literasi digital umum dan pemahaman tentang bagaimana AI bekerja;
- Tingkat Menengah: Kemampuan menggunakan alat-alat AI untuk legal research dan case analysis secara kritis;
- Tingkat Lanjut: Pemahaman mendalam tentang limitasi AI, bias algoritmik, dan cara melakukan quality control terhadap output AI.
Penting untuk dicatat bahwa tujuan pelatihan bukan membuat hakim menjadi programmer, melainkan memastikan mereka memiliki AI literacy yang cukup untuk dapat menggunakan teknologi secara kritis dan etis.
Keberanian Nurani di Era Algortima Seorang Hakim
A. Jangan Takut Menyimpang dari "Rata-Rata" AI
AI mungkin menyajikan analisis yang sangat logis berdasarkan ribuan putusan sebelumnya. Ia akan menghitung hukuman rata-rata untuk tindak pidana tertentu, faktor pemberat dan peringanan yang lazim, serta prediksi residivisme berdasarkan profil demografis. Semua tersaji dalam efisiensi yang memukau. Namun, di tengah hiruk pikuk data ini, hakim harus mengambil jeda.
Jika sistem AI merekomendasikan hukuman 5 tahun penjara karena itulah "median statistik" untuk kasus sejenis, namun hati nurani Yang Mulia—yang sudah terasah dengan nilai kemanusiaan, pemahaman terhadap konteks sosial-ekonomi lokal, dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki algoritma—mengatakan bahwa demi keadilan substantif, hukuman seharusnya lebih ringan (karena ada upaya rekonsiliasi yang tulus) atau lebih berat (karena ada dampak sistemik yang merusak tatanan sosial), maka putuskanlah sesuai nurani!
Keberanian hakim untuk menyimpang dari "rata-rata algoritmik" demi menegakkan rasa keadilan yang sesungguhnya adalah martabat tertinggi peradilan. Konsistensi yang paling penting bukanlah konsistensi statistik AI, melainkan konsistensi moral dalam menegakkan keadilan.
B. Gali Rasionalitas Kemanusiaan dalam Pertimbangan Putusan
Dalam setiap putusan, pastikan Yang Mulia memuat pertimbangan yang menunjukkan bahwa keputusan lahir dari proses deliberasi yang mendalam, bukan kalkulasi mekanis. Cantumkan: (1) Konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidana; (2) Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat; (3) Sikap dan remorse terdakwa; (4) Potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial; (5) Pertimbangan restorative justice jika relevan; dan (6) Nilai-nilai kearifan lokal dan living law yang hidup di masyarakat.
Jika Hakim menggunakan AI sebagai referensi, cantumkan secara eksplisit bahwa "Majelis Hakim telah mempertimbangkan analisis dari sistem [nama sistem AI], namun setelah melakukan quality control dan mempertimbangkan seluruh konteks kemanusiaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa..." Transparansi ini penting untuk akuntabilitas dan kepercayaan publik.
C. Independensi dari Tekanan Algoritmik dan Opini Publik
Dalam era media sosial dan trial by public opinion, hakim menghadapi tekanan ganda: dari rekomendasi AI yang terlihat "objektif" dan dari opini publik yang vokal. Namun, independensi yudisial adalah jantung peradilan yang fair. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.
Hakim tidak bertanggung jawab kepada algoritma atau trending topic di Twitter/X. Hakim bertanggung jawab kepada kebenaran, keadilan, Tuhan Yang Maha Esa, dan hati nurani sendiri. Jika AI dan opini publik menuntut hukuman maksimal, namun nurani Hakim mengatakan bahwa keadilan akan lebih terlayani dengan pengampunan/ pemaafan hakim (Pasal 54 (2) KUHP Nasional) atau pidana bersyarat ( Pasal 70 (1) kuhp Nasional ) dengan pembinaan intensif, maka beranilah memutuskan demikian dengan pertimbangan yang kokoh dan transparan.
Sinergi Antar Generasi Hakim: Memadukan Data dan Kearifan
Peradilan Indonesia saat ini menghadapi realitas demografis yang unik. Di satu sisi, ada hakim senior yang mengandalkan akumulasi kearifan, intuisi mendalam, dan moralitas yang dibangun dari puluhan tahun mengadili. Di sisi lain, ada hakim muda Generasi Z dan Milenial yang adalah digital natives, fasih menggunakan AI untuk efisiensi dan analisis data. Kesenjangan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan inkonsistensi dan menggerus kepercayaan publik.
A. Hakim Muda sebagai AI Translator dan Reverse Mentor
Hakim generasi muda memiliki peran strategis sebagai "penerjemah AI" (AI translator). Tugas mereka bukan hanya menggunakan AI secara teknis, tetapi menerjemahkan output AI kepada rekan senior dengan bahasa non-teknis yang mudah dipahami. Mereka harus mampu menjelaskan: "Sistem AI menyarankan X berdasarkan data Y dengan limitasi Z. Namun, ini bukan keputusan final, melainkan input untuk pertimbangan majelis."
Lebih jauh, hakim muda harus mengadopsi peran reverse mentor, di mana mereka melatih hakim senior dalam penggunaan teknologi yang etis tanpa menggantikan kearifan senior tersebut. Ini adalah bentuk kolaborasi horizontal yang saling memperkaya, bukan hierarki vertikal.
B. Hakim Senior sebagai Kompas Moral dan Quality Control
Hakim senior tidak perlu menjadi ahli coding atau memahami neural networks. Namun, mereka harus menjadi kompas moral dan penjamin kualitas (quality control) atas output AI. Pertanyaan kunci yang harus selalu diajukan: "Apakah rekomendasi AI ini adil secara kontekstual? Apakah ini sejalan dengan nilai Pancasila dan kearifan lokal? Apakah ini menghormati martabat manusia?"
Pengalaman puluhan tahun mengadili adalah filter paling ampuh terhadap bias algoritmik. Ketika AI menyarankan hukuman yang "konsisten secara statistik" namun "tidak adil secara kontekstual", hakim senior memiliki otoritas moral untuk menolaknya dengan pertimbangan yang matang.
C. Kebijakan Institusional MA: Memfasilitasi Sinergi
Mahkamah Agung perlu merancang kebijakan yang secara aktif memfasilitasi sinergi antar generasi:
- Program Mentoring Terbalik: Setiap hakim senior dipasangkan dengan hakim muda sebagai "digital mentor" dalam program terstruktur dengan target kompetensi yang jelas;
- Panel Diskusi Wajib untuk Kasus AI-Assisted: Setiap perkara yang menggunakan AI sebagai alat bantu analisis wajib didiskusikan dalam panel (majelis) yang terdiri dari perwakilan kedua generasi, memastikan bahwa logika data dan kearifan pengalaman berpadu sebelum putusan dijatuhkan;
- Knowledge Sharing Forum: Forum rutin bulanan di mana hakim dari berbagai generasi berbagi best practices dalam menggunakan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan;
- Sistem Reward yang Seimbang: Penilaian kinerja hakim harus mengapresiasi baik kemampuan teknologi maupun kearifan yudisial, tidak hanya mengukur kecepatan atau kuantitas putusan.
Isu-Isu Kekinian: Tantangan Spesifik di Era KUHP Nasional
A. Pengampunan Hakim (Rechterlijk Pardon) dan Diskresi Algoritmik
Pasal 56 KUHP Nasional memperkenalkan konsep pengampunan hakim yang memberikan kewenangan luar biasa kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Ini adalah diskresi yang sangat luas dan membutuhkan kebijaksanaan tinggi.
Muncul pertanyaan: dapatkah AI membantu hakim menentukan apakah seorang terdakwa
layak mendapat pengampunan? Jawabannya: Ya, sebagai salah satu faktor pertimbangan, tetapi dengan sangat hati-hati. AI dapat menganalisis faktor-faktor objektif seperti latar belakang terdakwa, tingkat keseriusan tindak pidana, dampak terhadap korban, dan potensi rehabilitasi. Namun, keputusan memberikan pengampunan adalah pertimbangan moral-filosofis yang hanya dapat dilakukan oleh hakim dengan nurani yang jernih.
Yang harus dihindari adalah situasi di mana hakim menjadi "corong AI" dengan menyatakan "Sistem AI merekomendasikan pengampunan, maka saya memberikan pengampunan." Ini adalah abdikasi tanggung jawab moral. Seharusnya: "Setelah mempertimbangkan analisis dari sistem pendukung keputusan, kondisi personal terdakwa, dampak sosial, dan keadilan substantif, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengampunan adalah keputusan yang paling adil dalam kasus ini karena..."
B. Pidana Bersyarat dengan Persyaratan Khusus dan Monitoring Berbasis AI
Pasal 54-55 KUHP Nasional mengatur pidana bersyarat dengan persyaratan khusus yang dapat mencakup kewajiban ganti rugi, rehabilitasi, atau pembinaan khusus. Di sinilah AI dapat berperan sangat positif dalam fase post-sentencing: sistem monitoring berbasis AI dapat membantu Bapas (Balai Pemasyarakatan) memantau kepatuhan terpidana terhadap persyaratan khusus secara real-time, memberikan early warning jika ada indikasi pelanggaran, dan mengukur efektivitas program rehabilitasi.
Namun, sekali lagi, keputusan mencabut pidana bersyarat atau memberikan kelonggaran harus tetap berada di tangan hakim, bukan otomatis oleh sistem. AI hanya menyajikan data compliance, hakim yang memutuskan dengan mempertimbangkan konteks kemanusiaan.
C. Restorative Justice dan Peran AI dalam Fasilitasi Mediasi
PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban. AI dapat berperan dalam: (1) Melakukan risk assessment untuk menentukan kasus mana yang cocok untuk restorative justice; (2) Memfasilitasi komunikasi awal antara pihak-pihak; dan (3) Memantau implementasi kesepakatan damai.
Namun, proses mediasi itu sendiri—mendengarkan penderitaan korban, melihat penyesalan pelaku, memfasilitasi rekonsiliasi yang autentik—adalah proses yang sangat manusiawi yang tidak dapat digantikan oleh AI. Teknologi dapat mendukung logistik dan administrasi, namun kebijaksanaan mediator dan sensitivitas hakim tetap menjadi kunci.
D. Pemberantasan Korupsi dan Analisis Big Data
Dalam perkara korupsi, AI dapat sangat membantu dalam menganalisis big data transaksi keuangan yang kompleks, mengidentifikasi pola beneficial ownership yang tersembunyi, dan menelusuri aliran dana lintas yurisdiksi. Kementerian Keuangan dan KPK telah menggunakan AI untuk mendeteksi anomali pajak dan transaksi mencurigakan.
Hakim yang menangani perkara korupsi perlu memanfaatkan tools ini untuk mempercepat proses pembuktian dan penelusuran aset. Namun, dalam menentukan unsur mens rea (niat jahat) dan pertanggungjawaban pidana, hakim tidak boleh sepenuhnya bergantung pada kesimpulan algoritmik. Konteks sosial, tekanan politik, dan keadaan memaksa (force majeure) adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dengan kebijaksanaan manusiawi.
Penutup: Teknologi untuk Keadilan, Bukan Sebaliknya
Kecerdasan Buatan adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Pertanyaannya bukan "apakah" kita akan menggunakan AI dalam peradilan, melainkan "bagaimana" kita menggunakannya dengan cara yang menegakkan, bukan mengkhianati, nilai-nilai fundamental peradilan: keadilan, kebijaksanaan, dan martabat manusia.
Transformasi digital peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung RI telah membawa kemajuan luar biasa dalam efisiensi dan transparansi. Namun, di tengah euforia teknologi, kita harus tetap waspada: jangan sampai dalam mengejar kecepatan, kita kehilangan kebijaksanaan; dalam mengejar konsistensi statistik, kita kehilangan keadilan substantif; dalam mengandalkan algoritma, kita melupakan nurani.
Menjelang implementasi KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, yang memberikan ruang diskresi lebih luas kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan manusiawi, momen ini adalah waktu yang tepat untuk menegaskan kembali: Hakim adalah "wakil Tuhan di muka bumi" yang memiliki tanggung jawab moral tertinggi dalam menegakkan keadilan. Teknologi adalah pelayan, bukan tuan.
Kepada Yang Mulia para Hakim di seluruh Indonesia: jadilah pelopor yang berani dan bijaksana. Gunakan teknologi dengan cerdas, namun jangan pernah menyerahkan nurani Anda kepada algoritma. Dalam setiap putusan, tanyakan pada diri sendiri: "Apakah ini adil? Apakah ini sesuai dengan hati nurani saya? Apakah saya dapat mempertanggungjawabkan keputusan ini di hadapan Tuhan, masyarakat, dan diri saya sendiri?"
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah "ya", maka ketuklah palu dengan keyakinan penuh, terlepas dari apa yang direkomendasikan AI atau apa yang dituntut opini publik. Karena keadilan sejati hanya dapat lahir dari kebeningan hati nurani yang dibantu—bukan digantikan—oleh kecerdasan buatan.
Mahkamah Agung, melalui regulasi yang tepat, pendidikan yang berkesinambungan, dan kepemimpinan yang visioner, memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa revolusi AI menjadi berkah, bukan kutukan, bagi peradilan Indonesia. Marilah kita bersama-sama mewujudkan peradilan yang modern, efisien, namun tetap berjiwa Pancasila: adil, bermartabat, dan penuh kebijaksanaan.
"Teknologi hadir untuk melayani keadilan, bukan membentuk keadilan itu sendiri."
"Nurani hakim adalah benteng terakhir keadilan yang tidak boleh dikalahkan algoritma."
Referensi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif
State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wisconsin, 2016)
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), "European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment" (2018)
Julia Angwin, et al., "Machine Bias: There's Software Used Across the Country to Predict Future Criminals. And it's Biased Against Blacks," ProPublica (2016)
Mireille Hildebrandt, "Law as Computation in the Era of Artificial Legal Intelligence," University of Toronto Law Journal (2018)
Ryan Calo, "Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap," University of Bologna Law Review (2017)
Kate Crawford, "The Hidden Biases in Big Data," Harvard Business Review (2013)