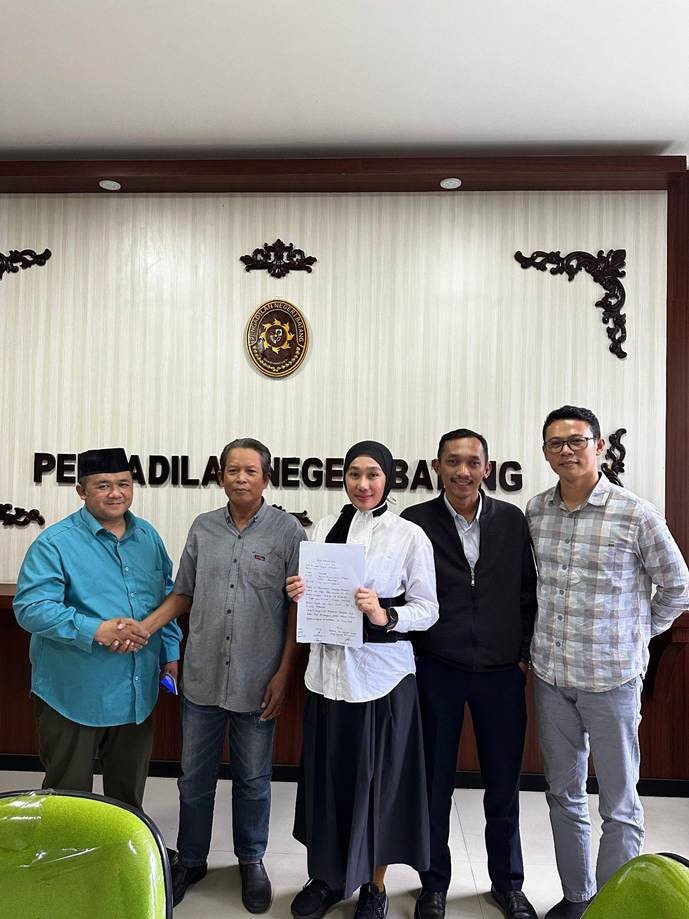Gagasan tentang mediasi dalam hukum pidana merupakan hal yang relatif baru dalam sistem hukum modern. Disebut baru karena secara historis, hukum pidana berakar pada paradigma retributif: pidana dipandang sebagai pembalasan negara terhadap pelaku yang melanggar norma hukum.
Dalam paradigma ini, negara bertindak sebagai pelaksana keadilan dengan menjatuhkan sanksi sebagai ekspresi ketidaksukaan terhadap perbuatan pidana.
Namun, seiring perkembangan pemikiran hukum, muncul pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif. Paradigma ini berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi moral pelaku.
Dalam konteks inilah, konsep mediasi penal memperoleh relevansinya. Mediasi penal menempatkan pelaku dan korban dalam posisi dialogis untuk mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan keseimbangan sosial akibat tindak pidana.
Mediasi Penal dan Keadilan Restoratif
Dalam hukum positif Indonesia, konsep yang sejalan dengan mediasi penal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) melalui mekanisme diversi.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke luar jalur pengadilan dengan pendekatan restoratif. Tujuannya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak pelaku dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban.
Mekanisme ini menjadi tonggak penting bagi perubahan orientasi sistem peradilan pidana Indonesia ke arah yang lebih restoratif. Namun, pertanyaan selanjutnya: apakah mediasi penal dimungkinkan bagi pelaku dewasa?
Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada 2026, tidak ditemukan ketentuan eksplisit tentang mediasi penal.
Ketiadaan ini wajar karena KUHP adalah hukum pidana materiil, sedangkan mediasi penal termasuk dalam ranah hukum acara pidana (formil). Maka, pengaturannya lebih tepat dimasukkan ke dalam undang-undang hukum acara pidana.
Hukum Jinayat dan Prinsip Pemaafan
Dalam hukum Islam, khususnya hukum jinayat, tindak pidana (jarimah) dibagi menjadi tiga kategori utama: hudud, qisas-diyat, dan ta‘zir.
Pembagian ini didasarkan pada sumber ketentuan dan sifat penghukuman. Hudud bersumber langsung dari Al-Qur’an dan hadis, sedangkan ta‘zir merupakan hasil ijtihad penguasa (Amir) sesuai konteks sosial.
Dari segi sifat, hudud mengandung hak Allah dan hak manusia sekaligus, sehingga pemaafan dari korban tidak dapat menghapus hukuman.
Berbeda dengan qisas dan diyat yang sepenuhnya merupakan hak manusia (huquq al-‘ibad), di mana pemaafan dari korban dapat menggugurkan hukuman qisas dan diganti dengan diyat (kompensasi).
Al-Qur’an memberi ruang pemaafan dalam perkara qisas, sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Mā’idah ayat 45, yang menekankan keutamaan memberi maaf dan menggantinya dengan kompensasi. Prinsip afw (pemaafan) dan ṣulḥ (perdamaian) inilah yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif modern.
Praktik di Dunia Islam
Dalam praktik, prinsip tersebut diterapkan di sejumlah negara Islam, seperti Arab Saudi. Dalam perkara qisas, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak langsung dieksekusi karena masih harus menunggu persetujuan Raja (Amir).
Masa ini memberi waktu bagi keluarga korban untuk mempertimbangkan pemaafan atau menerima diyat, difasilitasi oleh lembaga perdamaian lokal (Lajnat al-Iṣlāḥ) dan tokoh masyarakat.
Jika mediasi berhasil dan korban memaafkan pelaku, hukuman mati dapat dibatalkan dan diganti dengan pembayaran diyat, atau bahkan ditiadakan seluruhnya jika pemaafan diberikan tanpa syarat.
Praktik ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam modern secara nyata mengintegrasikan mekanisme sosial, keagamaan, dan administratif untuk mewujudkan keadilan restoratif.
Quo Vadis Indonesia?
Hingga kini, sistem hukum pidana Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas bagi penerapan mediasi penal. Baik KUHP maupun KUHAP tidak mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif berbasis mediasi antara pelaku dan korban.
Wacana pembaruan KUHAP memang ada, tetapi proses politik hukum dan kompleksitas reformasi peradilan membuatnya sulit terwujud dalam waktu dekat.
Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang lebih humanis semakin mendesak. Dalam konteks ini, Provinsi Aceh menempati posisi strategis.
Sebagai daerah dengan kekhususan penerapan syariat Islam, Aceh memiliki kewenangan normatif melalui Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Kedua qanun ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum substantif dan prosedural, tetapi juga ruang inovasi hukum berbasis nilai Islam.
Pembaruan terhadap qanun-qanun tersebut guna memasukkan ketentuan tentang mediasi penal merupakan langkah realistis dibanding menunggu reformasi hukum nasional. Bahkan, pengaturan mediasi penal di Aceh bisa menjadi pilot project kebijakan hukum pidana nasional.
Aceh memiliki fondasi nilai yang kuat untuk mengintegrasikan konsep mediasi penal dengan prinsip afw (pemaafan), ishlah (perdamaian), dan diyat (kompensasi).
Jika terbukti efektif menurunkan residivisme, mempercepat penyelesaian perkara, dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat, maka model ini dapat menjadi best practice bagi pembaruan hukum acara pidana nasional.
Penutup
Penerapan mediasi penal berbasis nilai Islam bukan sekadar langkah eksperimental, melainkan upaya menghidupkan kembali semangat hukum yang memulihkan, bukan menghukum.
Arah reformasi hukum pidana Indonesia seharusnya bergerak menuju sintesis antara keadilan restoratif modern dan spirit moralitas hukum Islam—keadilan yang menegakkan hukum tanpa mematikan kemanusiaan.